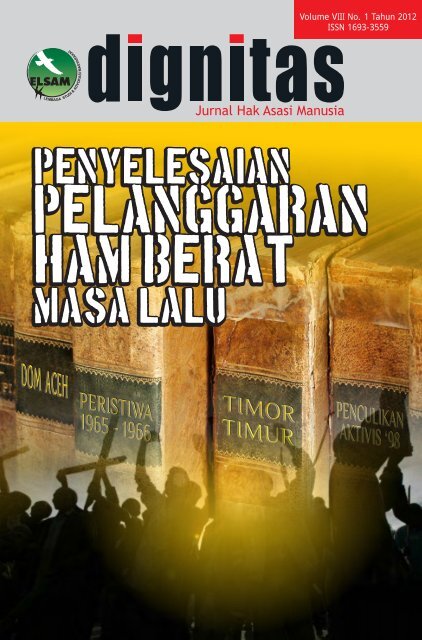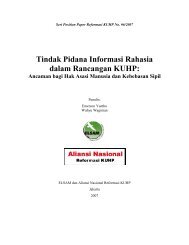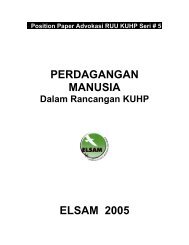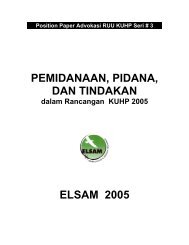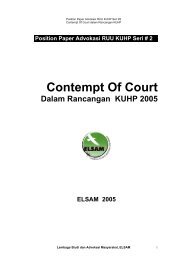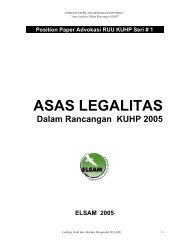RH7yFQ
RH7yFQ
RH7yFQ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
ISSN 1693-3559
dignitas<br />
Jurnal Hak Asasi Manusia<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
ISSN 1693-3559<br />
Jurnal Dignitas merupakan jurnal yang terbit dua kali setahun,<br />
setiap Juni dan Desember, dengan mengangkat isu utama mengenai<br />
hak asasi manusia. Tulisan yang diterbitkan di jurnal ini memandang<br />
hak asasi manusia secara multidisipliner. Bisa dari sudut pandang<br />
hukum, filsafat, politik, kebudayaan, sosiologi, sejarah, dan<br />
hubungan internasional.<br />
Tema yang diterbitkan diharapkan mampu memberikan kontribusi<br />
pengetahuan dan meramaikan diskursus hak asasi. Kehadiran Jurnal<br />
Dignitas ini ingin mewarnai perdebatan hak asasi yang ada.<br />
Misi Jurnal Dignitas adalah menyebarkan gagasan dan pemikiran<br />
yang dielaborasi melalui studi, baik teoretik maupun empirik,<br />
tentang permasalahan hak asasi manusia atau hukum yang<br />
berkaitan dengan hak asasi manusia.<br />
Dewan Redaksi: Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ery Seda, Ifdhal Kasim, Karlina L. Supeli,<br />
Sandra Moniaga, Soetandyo Wignjosoebroto, Todung Mulya Lubis, Yosep Adi Prasetyo;<br />
Pemimpin Redaksi: Indriaswati Dyah Saptaningrum; Redaktur Pelaksana: Widiyanto Staf<br />
Redaksi: Ikhana Indah, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyudi Djafar, Wahyu Wagiman,<br />
Zainal Abidin; Sekretaris Redaksi: E. Rini Pratsnawati Sirkulasi dan Usaha: Khumaedy<br />
Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)<br />
Alamat Redaksi: Jln. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510<br />
Telp: 021-7972662, 79192564 Fax: 021-79192519<br />
Email: office@elsam.or.id Website: www.elsam.or.id
dignitas<br />
Jurnal Hak Asasi Manusia<br />
DAFTAR ISI<br />
EDITORIAL<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
ISSN 1693-3559<br />
______ 3<br />
FOKUS<br />
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi demi Masa Lalu<br />
______ 7<br />
oleh Agung Putri Astrid<br />
______ 9<br />
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />
oleh Otto Syamsuddin Ishak ______ 25<br />
Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi<br />
oleh Budiawan ______ 41<br />
DISKURSUS ______ 49<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
di Indonesia dan Negara-Negara Lain<br />
oleh Zainal Abidin ______ 51<br />
Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu<br />
oleh Herry Sucipto dan Hajriyanto Y. Thohari ______ 75<br />
OASE ______ 87<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
oleh Stanley Adi Prasetyo ______ 89<br />
TINJAUAN ______ 115<br />
”Mengindonesiakan” Anak Timor Leste<br />
oleh Razif ______ 117<br />
KONTRIBUTOR ______ 127<br />
PEDOMAN PENULISAN ______ 129<br />
PROFIL ELSAM ______ 131
EDITORIAL<br />
Sidang Pembaca yang kami hormati!<br />
Jurnal dignitas kali ini mengetengahkan tema mengenai kabar<br />
penyelesaian kejahatan hak asasi manusia masa lalu. Tema ini secara<br />
sengaja dipilih guna mengungkapkan pelbagai analisis seputar proses<br />
penyelesaian kejahatan masa lalu di Indonesia yang bisa dikatakan<br />
stagnan.<br />
Proses kanalisasi penyelesaian tampak sangat kuat sedang<br />
berlangsung dengan modus lebih sistematis, mulai dari ketentuan<br />
normatif kebijakan yang ada, hingga faktor implementasi penyelesaian<br />
yang tiada komitmennya. Itulah Indonesia. Kita bisa lihat dari perjalanan<br />
upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.<br />
Beberapa waktu lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia<br />
(Komnas HAM) telah menyelesaikan tugasnya melakukan penyelidikan<br />
pro-justicia terhadap Peristiwa tahun 1965/1966. Hasilnya, Komnas<br />
HAM menemukan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat<br />
dengan melibatkan unit negara yang bertanggung jawab atas keamanan<br />
saat itu, yaitu Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban<br />
(Kopkamtib).<br />
Hasil penyelidikan Komnas HAM memang menerbitkan secercah<br />
harapan. Institusi ini kemudian meminta kepada Kejaksaan Agung<br />
menindaklanjuti ke tahapan penyidikan. Namun bak nyala lilin yang tibatiba<br />
padam tertiup angin, Kejaksaan Agung menyatakan hendak<br />
mengembalikan berkas penyelidikan yang disusun berdasar<br />
penyelidikan selama empat tahun itu.<br />
Lalu kita pun menjadi paham sistem kepolitikan dan hukum kita<br />
sekarang tak kunjung menyemai keadilan bagi korban. Tesis bahwa<br />
setiap negara yang telah melewati fase pemerintahan otoriter akan<br />
mengalami periode transisi tampaknya tak berlaku di Indonesia.<br />
3
Tak pernah tuntasnya penyelesaian masa lalu menjadi penanda<br />
gagalnya periodisasi yang bernada siklis itu. Kondisi Indonesia saat ini<br />
merupakan kelanjutan dari absennya 'patahan' atau batasan yang jelas<br />
antara masa kini dan masa lalu. Karena kini adalah akibat masa lalu.<br />
Asumsi yang berkembang kemudian telah terjadi pembajakan<br />
demokrasi oleh elit lama yang berganti muka menjadi penguasa baru<br />
dengan menggunakan momentum reformasi yang tak terdisain pro<br />
terhadap korban. Elit-elit lama bermetamorfosis dan melindungi<br />
kekuasaannya melalui serangkaian disain aturan hukum yang tak<br />
mencerminkan keadilan bagi korban.<br />
Prosedur hukum menjadi pertimbangan utama, yang ternyata<br />
tak berpengaruh pada perbaikan substansi keadilan. Elit lama ini<br />
ditengarai masih menguasai ranah penegakan dan proseduralisme<br />
hukum ini. Namun, tesis ini ternyata tak berhenti di sini. Ada fenomena<br />
menarik melihat perkembangan post-reformasi di Indonesia. Pegiat hak<br />
asasi manusia Agung Putri melihat dari sudut pandang lain itu.<br />
Menurutnya, Indonesia mengalami fase unik tatkala periode<br />
paska-reformasi sekarang lebih banyak diwarnai dengan dinamika<br />
interaksi korban dan pelaku secara intensif. Fenomena ini merujuk pada<br />
sejumlah peristiwa, seperti halnya, beberapa korban penculikan tahun<br />
1997/1998 memilih bergabung dengan partai politik yang dikontrol<br />
oleh jenderal yang diduga kuat terlibat dalam penculikan mereka saat itu.<br />
Demikian pula representasi korban kejahatan masa lalu yang<br />
pada akhirnya memiliki jabatan-jabatan strategis paska-reformasi dinilai<br />
gagal mengartikulasikan kepentingan kolektif korban. Mereka<br />
setidaknya memiliki kesempatan untuk mengukir sejarah dengan<br />
membuat pembatasan antara masa kini dan masa lalu.<br />
Namun ternyata kelompok korban yang memiliki kekuasaan<br />
tersebut tak mampu melakukan pembatasan itu. Mereka malah justru<br />
memilih jalan kompromi yang akhirnya keinginan pengungkapan<br />
kejahatan masa lalu pun termoderasi dalam kepentingan pragmatis.<br />
Gambaran ini persis terjadi di Aceh, seperti dianalisis oleh Otto<br />
Syamsuddin Ishak, intelektual Aceh yang lama terlibat dalam gerakan<br />
masyarakat sipil Aceh ini.<br />
Tatkala mantan para pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM)<br />
4
menguasai mayoritas kursi di parlemen lokal dan posisi gubernur/wakil<br />
gubernur, mereka memiliki kesempatan untuk mendorong kejahatan<br />
masa lalu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi<br />
(KKR) Aceh. Akan tetapi apa yang terjadi? Hingga kini KKR Aceh<br />
belum terbentuk dengan dalih ketiadaan dasar legalitasnya.<br />
Terdapat dua skema utama yang selama ini dikenal luas kerangka<br />
penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Pertama, melalui<br />
pengadilan hak asasi manusia, dan jalur kedua lewat komisi kebenaran<br />
dan rekonsiliasi. Zainal Abidin dari ELSAM menguraikan kedua<br />
mekanisme tersebut dengan becermin pada proses penyelesaian<br />
kejahatan hak asasi manusia di negara-negara lain.<br />
Indonesia mengenal dua mekanisme penyelesaian tersebut,<br />
hanya saja untuk penyelesaian melalui KKR tidak pernah terjadi. Komisi<br />
ini bahkan tak pernah ada dan dasar hukum pembentukannya dianulir<br />
oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Sementara pengadilan hak asasi<br />
manusia telah dijamin keberadaannya lewat UU No. 26 tahun 2000<br />
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<br />
Bila terkait dengan kasus sebelum UU disahkan, mekanismenya<br />
lewat pembentukan pengadilan HAM Adhoc. Untuk kasus sesudahnya<br />
lewat pengadilan HAM biasa. Untuk pembentukan Pengadilan HAM<br />
Adhoc harus ada rekomendasi dari DPR dan pembentukannya berdasar<br />
Keputusan Presiden. Bisa dibayangkan betapa berlikunya mekanisme<br />
penyelesaian kejahatan hak asasi manusia masa lalu di negara ini.<br />
Menurut Hajriyanto Thohari, wakil ketua Majelis<br />
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan segala kerumitan yang ada,<br />
pembentukan UU KKR sebagai sarana untuk penyelesaian kejahatan<br />
masa lalu perlu didorong kembali.<br />
Ada banyak kasus yang niscaya saat ini sedang ditunggu<br />
kepastian penyelesaiannya oleh para korban. Menurut Irawan Saptono<br />
(2002), dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, terdapat tiga tipologi<br />
korban yang perlu dilihat dalam menjamin keadilan mereka yang<br />
terlanggar haknya. Satu, mereka yang masuk klasifikasi korban langsung.<br />
Dua, korban tak langsung yang biasanya menderita psikis dan emosi<br />
yang berat. Dan ketiga, para aktivis yang turut diculik karena<br />
memperjuangkan pengungkapan kejahatan hak asasi manusia.<br />
5
Tulisan Budiawan mengenai narasi tiga korban tak langsung<br />
mengulas betapa passion memories-nya sangat menyentuh. Rata-rata para<br />
korban tak langsung, yang seperti para istri dari mereka yang ditangkap<br />
dengan dalih terlibat PKI tahun 1965 mengalami pergulatan batin yang<br />
cukup keras. Ada istri yang tak siap menghadapi kesendirian, ada pula<br />
yang dengan tabah dan 'menormalkan' hidupnya yang tak normal, dan<br />
lain sebagainya.<br />
Para korban tak langsung ini cenderung memiliki perasaan yang<br />
sama: mereka cemas akan kejelasan nasib suami, anak, atau sanak<br />
saudara mereka yang diculik, dihilangkan paksa, atau mereka yang<br />
mengalami pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya.<br />
Stanley Adi Prasetyo berusaha mengungkapkan perasaan yang<br />
dialami oleh aktivis-cum-seniman Wiji Thukul persis saat-saat terakhir<br />
sebelum dia dihilangkan paksa oleh Orde Baru Soeharto, di tahun 1998.<br />
Wiji Thukul mengungkapkan kegetirannya melihat situasi politik dan<br />
sosial yang berkembang saat itu lewat belasan puisinya.<br />
Menariknya, puisi-puisi Wiji Thukul ini belum pernah<br />
dipublikasikan dalam terbitan-terbitan sebelumnya. Baru di jurnal ini<br />
Stanley mengulas puisi-puisi yang dirangkainya menjadi satu rangkaian<br />
cerita yang apik. Hingga kini Wiji Thukul tak jelas keberadaannya. Tak<br />
ada pernyataan resmi dari negara mengenai penghilangan paksa yang<br />
menimpa seniman paling dicari zaman Orde Baru tersebut.<br />
Di akhir edisi ini, kami memuat sebuah resensi buku berjudul<br />
”Making Them Indonesia; Child Transfers Out of East Timor ” karangan<br />
Helena van Klinken. Resensi ditulis oleh Razif. Buku ini bercerita<br />
tentang pemindahan anak-anak Timor Leste berusia di bawah dua<br />
hingga belasan tahun ke Indonesia dengan sejumlah metode<br />
pemindahan dan motifnya.<br />
Semoga Jurnal dignitas ini dapat memperkaya bacaan dan<br />
analisis para pembaca terhadap situasi hak asasi manusia saat ini. Selamat<br />
membaca!<br />
WIDIYANTO<br />
Redaktur Pelaksana<br />
6
FOKUS
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />
demi Masa Lalu<br />
Agung Putri Astrid<br />
Abstract<br />
This article argues that the Indonesia's transition towards democracy has not been<br />
completed. It hasn't only been hijacked, but it comprises of a dynamic interaction<br />
between actors who inherit the gloomy condition of the past. Those who are held<br />
hostage by the past, who must solve the problems of the past, has blocked the path<br />
towards settlement. Indonesia comprises of the dynamics between victims and<br />
perpetrators who live side-by-side and that has created the drama of the hijacking<br />
of democracy, it is held hostage by the past. It seems that nation building must<br />
start from here, from the drama of the hijacking of democracy.<br />
Keywords: Hijacking Democracy; The Past<br />
Catatan kenangan<br />
Siang ini, di pertengahan tahun, sudah hari kesekian Jakarta tak lagi<br />
menanggung hujan. Dedaunan yang 5 jam lalu tegak kehijauan, kuning<br />
terkantuk-kantuk. Jalanan meliuk gang perkampungan Condet, panas<br />
dan lengang. Siapa rela memanggang diri di ketinggian matahari selain<br />
penjual asinan dan reparasi sepatu? Tak sampai satu kilo dari Condet<br />
arah timur adalah Lubang Buaya. Nama sebuah desa di kecamatan<br />
Halim, Jakarta Timur, yang sontak menjadi buah mulut dengan rasa<br />
seram di tahun 65. Situs penculikan 6 orang jendral dan seorang kapten<br />
pada 1 Oktober 1965 ini. Kini seperempat kawasannya berdiri museum<br />
dan monumen pancasila sakti, yang setiap tanggal 1 Oktober akan<br />
dibersihkan dari para gelandangan dan pedagang kaki lima karena<br />
presiden akan memimpin upacara militer di sana.<br />
Nun di selatan Condet, dalam jarak tempuh mikrolet M-06<br />
jurusan Kampung Melayu – Gandaria, sebuah kompleks militer pasukan<br />
khusus mencatat riwayat telah menyembunyikan sejumlah pemuda dan<br />
9
FOKUS<br />
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />
menyiksa mereka di tahun 1998 dan di antara mereka jejaknya tak<br />
berbekas hingga kini. Sementara berbalik ke arah utara, menuju<br />
kampung Melayu-Matraman-Salemba tak satupun bisa menghindar<br />
melewati situs pembakaran pertokoan Ramayana, Jatinegara Mall dalam<br />
kerusuhan Mei 1998, gedung Departemen Pertanian dalam peristiwa 27<br />
Juli 1996, dan markas PKI di Jalan Kramat 81 pada tahun 1966.<br />
Di tengah kampung ini tergelar kembali lembar kejadian demi<br />
kejadian yang sempat kubaca dan kudengar tentang kekerasan politik.<br />
Tak sedikitpun aku pernah mengalaminya. Namun dalam berbagai<br />
sebab dan cara ikut membentuk pikiran, dan cita rasa. Ada komunitas<br />
yang secara sembarangan disebut komunitas korban kekerasan oleh<br />
negara yang aroma penderitaannya belasan tahun terhirup. Jujur, tak<br />
seluruh cerita mereka kurasai sebagai ratapan dan malah sebaliknya aku<br />
lebih suka belajar dari mereka. Kadang bila gairah hilang, kita tenggelam<br />
dalam kehidupan masing-masing.<br />
Mulanya adalah seorang sahabat datang padaku meminta<br />
menulis soal politik yang berurusan dengan korban. Kupikir ini bukan<br />
saatnya. Waktuku habis bersama teman jalanan, para pencoleng, preman<br />
terminal, tukang kayu, pengupas bawang Pasar Induk, serta penganggur<br />
di kampungku, korban pemiskinan. Hitungan matematis mereka<br />
tentang kehidupan ini adalah mendapat hari ini untuk hari ini. Masa<br />
depan cuma akumulasi dari potongan-potongan keberuntungan hari ke<br />
hari. Bagaimanakah caraku mengkalkulasi biaya darah dan derita masa<br />
lalu untuk masa depan ketika kampung ini separuhnya berisi kaum<br />
serabutan?<br />
Tapi ada daya tariknya permintaan temanku itu. Aku harus<br />
menjawab pertanyaan, adakah jalan keluar bagi korban dalam politik<br />
carut-marut saat ini. Aku berhadapan dengan gagahnya kesimpulan<br />
akademik teoritisi politik yang memvonis bahwa transisi di Indonesia<br />
sudah berhenti. Dan hanya ada satu sebab, menurut mereka, sistem dan<br />
institusi demokrasi telah dibajak oleh elit dominan warisan Orde Baru<br />
maupun elit baru. Rasanya tidak ada salahnya pendapat ini. Namun<br />
dalam hati aku ingin tahu, makhluk seperti apakah yang mampu<br />
menunda terselesaikannya masa lalu sekaligus membajak demokrasi<br />
dalam satu tarikan nafas?<br />
Hari menjelang sore. Angin sore merambat menyusup jendela<br />
kamar. Kurasai hawa penantian sekalian orang akan datangnya azan<br />
10
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
maghrib. Mengikuti menit-menit penantian itu aku menjalin pikiran,<br />
ingatan dan perasaan sebisanya tentang serpih fakta kekerasan masa lalu<br />
yang beterbangan di kota Jakarta. Kekerasan puluhan tahun lalu<br />
memang tinggal debu politik. Namun debu itu menempel lengket. Sama<br />
lengketnya dengan lelehan darah membeku di seragam Letjen S Parman<br />
yang dipajang di museum Lubang Buaya. Debu itu mestinya bisa<br />
dibersihkan. Anehya, tak satupun melakukannya.<br />
Dalam tragedi politik, tak mudah bagi kita menghapus jejaknya,<br />
seberapapun jauh usaha menenggelamkannya. Tiap sudut kota, orangorangnya<br />
berelasi dengan masa lalu, baik dengan kekuasaannya maupun<br />
penghancurannya. Ingatan yang telanjur kolektif terpelihara dari<br />
generasi ke generasi, dengan cara dan tujuan yang berbeda. Tidak ada<br />
masa lalu yang benar masa lalu, meskipun masalah datang silih berhanti,<br />
orang hidup dan mati, menetap dan pindah.<br />
Kenangan Politik<br />
Akhir-akhir ini kerap terdengar lontaran ”Ah, masyarakat sekarang<br />
sudah pragmatis.” Artiya masyarakat hanya peduli pada uang, persetan<br />
dengan nilai kejujuran dan keadilan. Survai kompas bulan lalu<br />
mengamini lontaran ini dengan angka-angka hasil survai. Masyarakat<br />
Indonesia bukan agen perubahan, tetapi motor konservatisme kultural<br />
dan politik.<br />
Suasana tak ingin berubah juga diberkati oleh pandangan dari<br />
Istana Negara. Presiden berhenti bicara soal masa lalu. Kunci<br />
rekonsiliasi, menurut SBY, adalah melupakan masa lalu. Ini dilontarkan<br />
di hadapan tokoh-tokoh dunia yang malang melintang memerangi<br />
kekerasan termasuk penerima hadiah Nobel, mantan presiden Timor<br />
Leste, Jose Ramos Horta. Mengingat masa lalu sama dengan<br />
menyandera diri pada masa lalu dan berhenti menatap masa depan.<br />
Presiden SBY cukupkan dengan bersyukur bahwa di masa<br />
pemerintahannya tidak terjadi pelanggaran HAM.<br />
Pendapat ini berbalik ketika Jokowi menang pada putaran<br />
pertama sebesar 42, 60 persen dengan dana minim melawan gubernur<br />
Jakarta yang menguasai hampir semua lini kehidupan ibu kota. Setelah<br />
berdebat tanpa kata sepakat untuk menjelaskan kejutan ini, akhirnya<br />
baik ahli politik maupun supir taksi sama beranggapan bahwa Jokowi<br />
menang karena rakyat Jakarta menginginkan perubahan.<br />
11
FOKUS<br />
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />
Apakah rakyat Indonesia tak ingin berubah, pragmatis,<br />
konservatif, oportunis atau sebaliknya, progresif, emansipatoris,<br />
dinamis, sebenarnya cuma kesimpulan permukaan. Jejak kebungkaman<br />
periode Orde Baru yang menggerus heroisme jaman revolusi hingga<br />
pertengahan tahun 60an, belum lagi dijelajahi. Bagiku, menilai bahwa<br />
demokrasi berhenti berdetak karena elit politik Indonesia tidak pro<br />
rakyat, predator, benalu kekuasaan, pewaris ketamakan Orde Baru atau<br />
maling yang masuk dalam selayar mewah pemerintahan SBY sama<br />
1<br />
dengan bermimpi tentang negara republik yang tidak pernah ada.<br />
Suka tak suka jalan historis penuh luka ini yang menentukan apa<br />
yang hendak diubah dan ke arah mana perubahan itu. Tiap sentimeter<br />
perubahan itu senantiasa dihidupi oleh pengalaman traumatik bangsa.<br />
Tak seorang pun bisa memulai yang baru dengan menyingkirkan yang<br />
lama, karena yang baru lahir dari yang lama, sekalipun sama<br />
memprioritaskan periuk nasi. Bahkan setelah 15 tahun, di tengah<br />
korupsi bermilyar para politisi pasca orde baru, usaha Agung Laksono<br />
dan kawan-kawannya menobatkan Suharto sebagai pahlawan Republik<br />
gagal. Pengalaman traumatis bukan cuma milik korban tetapi suatu rasa<br />
kolektif bangsa ini.<br />
Selama berbulan-bulan menelusuri kehidupan masyarakat<br />
Afrika Selatan setelah 10 tahun berlalunya rejim apartheid tahun 2002,<br />
kutemukan betapa gaya berpolitik baru lahir justru dari pergulatan<br />
antara konservatisme lama, oportunisme baru dan sobekan sobekan<br />
luka. Semua diperebutkan, mulai dari menentukan bahasa negara, nama<br />
jalan, hingga prosedur penguasaan tanah, tender pembangunan, dan<br />
lokasi pertambangan. Ada juga yang secepat kilat menyesuaikan diri<br />
dengan hiruk pikuk bisnis pasca apartheid baik mantan polisi kulit putih<br />
2<br />
jaman Apartheid maupun pebisnis kulit hitam.<br />
1. Tesis ini secara utuh disusun oleh Vedi R. Hadiz dan Richard Robison. Analisis politik yang berkembang<br />
saat ini tidak lain hanya mengekor di belakangnya. Cukup luas diketahui bahkan dalam periode heroik<br />
revolusi Agustus 1945, begitu banyak predator, maling dan orang-orang kaya yang meloncat ke perahu<br />
gerakan kemerdekaan dan banyak lainnya yang membajak revolusi itu. Pramoedya Ananta Toer<br />
melukiskan periode ini dalam novelnya: Di Tepi Kali Bekasi, Jakarta, Lentera Dipantara, 2003 dan<br />
Larasati, Jakarta, Lentera Dipantara, 2003. Juga penting membaca buku Robert Cribb tentang periode ini,<br />
Gangster and Revolutionaries, Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution, 1945-1949, Jakarta, Equinox,<br />
2009.<br />
2.Betapapun, Afrika Selatan masih prihatin atas gagalnya sebagian besar pebisnis kulit hitam.<br />
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3262123.stm Mereka yang bertahan sedikit diantaranya adalah<br />
milyuner Patrice Tlhopane Motsepe, pembuat minuman anggur, Jabulani Ntshangase<br />
12
Metode dan praktik rekonsiliasi berkembang subur justru di<br />
negeri yang tersobek-sobek oleh rejim apartheid. Kongres ilmu politik<br />
Afrika Selatan, konperensi metodologi kesehatan masyarakat pasca<br />
apartheid maupun teologi demokrasi dan rekonsiliasi tidak lain adalah<br />
ilmu-ilmu baru di Afrika yang dibangun dari pergulatan antara masa lalu<br />
dan masa depan. Tak ada ilmu dan strategi politik yang dicangkokkan<br />
dari luar. Semua gagal.<br />
Tak diduga, pemerintah Afrika Selatan, dalam upaya<br />
memulihkan lukanya, pun perlu mencari pegangan historis pada<br />
penggagas gerakan Asia Afrika, yang susah payah ditenggelamkan oleh<br />
Orde Baru. Bulan April 2005, Bangsa Afrika Selatan memberikan<br />
bintang kehormatan kelas 1 pada Bung Karno, The Order of the Supreme<br />
3<br />
Companions of Oliver R. Tambo sebagai tokoh Asia Afrika yang telah<br />
memberikan inspirasi bagi perjuangan rakyat Afrika Selatan.<br />
Jam menunjuk pukul enam. Azan maghrib berkumandang<br />
antara masjid ke masjid sepanjang jalanan pantai Situbondo, Jawa Timur.<br />
Sejuk angin sore menyapu sisa panas siang hari. Senja yang sama<br />
menggelayuti tiap banjar di Bali oleh alunan kidung melantunkan puja<br />
puji seloka. Demikian litani ”Salam Maria” mendengung di sudut biara<br />
Susteran Canossian, Comorro, Timor Leste. Tenggelamnya matahari<br />
diberkahi umat manusia di tempat dimana luka-luka menyayat pernah<br />
4<br />
terjadi.<br />
Saat maghrib, kerap menutup episode kekerasan siang hari.<br />
Letupan peluru menembus kepala mahasiswa dalam demonstrasi tahun<br />
1998 dan 1999 di tengah kumandang azan maghrib. Kepulan asap hitam<br />
dari kantor PDI di Jalan Diponegoro 58 dan gedung-gedung di Salemba<br />
tanggal 27 juli 1996 membubung tinggi bersama senja. Ratusan warga<br />
kelurahan Koja, Tanjung Priok bersimbah darah menjelang Maghrib. Di<br />
Lampung, juga di desa Nisam, Aceh Utara, warga tidak ke surau untuk<br />
5<br />
berazan bila beredar desas-desus bahwa tentara mengepung desa.<br />
3. Oliver Reginald KaizanaTambo adalah pahlawan rakyat Afrika Selatan. Bersama Nelson Mandela dan<br />
Walter Sisulu ia mendirikan ANC (African National Congres) organ utama perjuangan pembebasan rakyat<br />
Afrika Selatan dari apartheid. Namanya diabadikan pada bandara Internasional Afrika Selatan.<br />
http://www.sahistory.org.za/people/oliver-reginald-tambo.<br />
4. Di tahun 2000an warga Situbondo panik oleh isu dukun santet dan ninja yang berujung ke pembunuhan<br />
orang-orang yang dicurigai dukun santet. Susteran Canossian menjadi tempat berlindungnya warga desa<br />
dari amukan milisi Aitarak dan Dadurus Merah Putih yang membakari desa-desa di tahun 1999. Sakralitas<br />
banjar-banjar di Bali tak hanya di segi religiusitasnya tetapi kenangan akan kekerasan tahun 1965.<br />
5. Berbagai laporan HAM dari Aceh hingga Papua menyiratkan senja sebagai ancaman. Lihat juga buku fiksi,<br />
novel karya Arafat Nur, Lampuki, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2011.<br />
13<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
FOKUS<br />
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />
Sejak drama penculikan jendral di Jumat Legi 1 Oktober 1965<br />
dan selanjutnya, turunnya matahari berarti mulainya bencana.<br />
Penangkapan dan pengambilan orang tidak kembali sejak November<br />
1965 hingga 1969 di desa-desa di Jawa, Bali, Sumatera berlangsung saat<br />
matahari merayap turun. Tiga puluh tahun kemudian, menyusul<br />
peristiwa Sabtu Pon tanggal 27 Juli pagi hari, jajaran pimpinan Angkatan<br />
Darat memaklumkan pengejaran aktivis PRD dan PDI melalui Jurnal<br />
Petang SCTV dan RCTI. Saat maghrib bagi kebanyakan orang Indonesia<br />
adalah waktu yang traumatik tetapi di saat sama diberkati.<br />
Tragedi politik tidak saja menyisakan kenangan tetapi hidup bila<br />
sinyal kekerasan memancar. Lebih lagi, oleh situasi yang tetap<br />
mengancam, yang karenanya tragedi serupa mungkin berulang, trauma<br />
itu terpelihara dengan baik. Karenanya, siapakah, pimpinan politik<br />
manakah, kekuasaan apakah, yang berani menjamin bahwa drama<br />
kekerasan tidak akan terulang kembali?<br />
Serangan kepada kelompok Ahmadiyah hanya menghidupkan<br />
sinyal lama betapa kekerasan antar masyarakat sengaja dibiarkan. Di<br />
Poso, Maluku, Sanggau, Sintang di tahun 1998, maupun Singkawang,<br />
Lombok, Bali dan pedesaan Jawa Timur di tahun 1965, polisi dan tentara<br />
berada di antara para penyerang.<br />
Tuduhan penguasa bahwa Ahmadiyah menghina Islam dan<br />
patut diusir justru menyetrum kenangan lama tentang keberingasan<br />
masyarakat membakar rumah dan membunuh mereka yang dianggap<br />
ternoda oleh komunisme, atheisme atau aliran sesat. Para penganut<br />
agama lokal seperti Kaharingan, Sunda Wiwitan, Parmalim peka dengan<br />
gerak pensucian macam ini. Warga pun masih mengenang pembantaian<br />
Haur Koneng, Jawa Barat tahun 1984. Sinyal itu berkedip-kedip<br />
sepanjang masa karena monumen-monumen hidup warga puluhan desa<br />
di Malang Selatan, Blitar, Kediri yang hampir 100% beragama Kristen<br />
atau Katolik. Mereka ini pemeluk kejawen yang 'hijrah' massal di<br />
penghujung tahun 60an untuk menyelamatkan diri dari tuduhan atheis.<br />
Dimensi kejadian yang berbagai-bagai itu membentuk trauma.<br />
Dimensi yang bukan peristiwa dan tak bisa disusun kronologinya.<br />
Menjadi tapol karena namanya tertera dalam daftar tangkap, karena<br />
pernah mengisi formulir, memberi pelajaran untuk mewaspadai semua<br />
formulir dan tetap memelihara identitas diri yang berbeda-beda.<br />
Peristiwa 65 yang cuma semalam, telah meluluh-lantakkan<br />
14
segalanya hingga berdekade kemudian. Anak istri suami tercerai-berai,<br />
hilangnya tulang punggung keluarga, dan mata pencaharian serta status<br />
sosial (Roosa, et.al, ed, 2004). Orang gerah bicara politik sekaligus takut<br />
pada agama atau etnis lain. Bila perempuan angkat bicara, tak akan<br />
mungkin serupa dengan ”satriyo piningit” melainkan wujud ”gerwani”<br />
yang artinya kasar, liar dan nakal. Bila masyarakat punya masalah, jalan<br />
keluarnya berupa obat mujarab tanpa menghiraukan problem<br />
politiknya: minum obat agar sembuh dan bukan membangun sistem<br />
kesehatan agar jangan sakit. Politik kewargaan lenyap, yang ada adalah<br />
aktor-aktor yang lolos litsus. Organisasi politik hanya ada bersama<br />
keluarnya ijin. Berkumpul lebih dari 5 orang juga ijin. Patriotisme cuma<br />
ada di benak orang yang punya rencana makar. Tidak ada hidup gotong<br />
royong dan kepemimpinan warga. Masyarakat muak pada politik<br />
sekaligus takut pada kekuasaan.<br />
Kekerasan tak semata soal kerugian psikis dan fisik. Kekerasan<br />
politik itu penuh makna sosial, bertujuan menghancurkan hubungan<br />
sosial antar individu dan individu dengan masyarakat. Yang hendak<br />
diperlihatkan adalah betapa orang bisa menjatuhkan martabat. (Hamber,<br />
2004)<br />
Politik Kenangan<br />
Masyarakat yang lumpuh kepemimpinannya, dicekam takut, disergap<br />
kenangan akan kekerasan politik masa lalu, menjalani peralihan<br />
kekuasaan yang khas. Bara api semangat menyeret penguasa lama,<br />
sejatinya ikut membakar serumah-rumahnya. Namun bayi demokrasi ini<br />
menghadapi dua soal besar: keharusan menghukum pelaku kekerasan<br />
masa lalu yang disandera oleh kebutuhan konsolidasi komponen bangsa<br />
secara demokratik. Tak ada kenyataan seindah adagium pengadilan atas<br />
kejahatan masa lalu melandasi terbangunnya masyarakat demokratik.<br />
Benar, mantan penguasa rejim otoritarian telah kehilangan<br />
legitimasinya. Tetapi konsolidasi demokrasi bukan perkara hukum<br />
apalagi moral. Dalam politik ada ribuan kemungkinan. Desakan public<br />
untuk pengadilan penghabisan bagi sang diktator, seperti di Mesir<br />
terhadap Hosni Mubarak awal Juni 2012 lalu, seharusnya membuka<br />
jendela demokrasi. Tetapi Mesir malah diguncang krisis dan lahir negara<br />
fundamentalis agama. Belum lagi Libya, Irak dan Hungaria. Pada<br />
bangsa-bangsa pasca kolonial pertaruhan gerakan demokrasi yang<br />
15<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
FOKUS<br />
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />
bertahun terdepolitisasi adalah integritas kebangsaan itu sendiri. Bung<br />
Karno ada benarnya:<br />
”perjuanganku lebih mudah dibandingkan perjuangan kalian nanti,<br />
karena sekarang aku berjuang melawan penjajah (bangsa asing), tapi<br />
akan lebih berat lagi perjuangan kalian, karena akan melawan bangsa<br />
kalian sendiri”<br />
Keinginan menghapus mimpi buruk masa lalu dan memelihara<br />
kebebasan masa kini malah membuat perhitungan dengan mantan<br />
penguasa rejim otoritarian kerap berbatas-batas. Hingga kini, tak satu<br />
ulasan tentang peralihan politik di berbagai negeri berani menyimpulkan<br />
bahwa setelah segala tindakan mengadili pimpinan diktator otoritarian,<br />
perhitungan dengan masa lalu selesai. Chile, setelah 20 tahun masih<br />
mengadili anggota junta militer. Demikian pula Argentina.<br />
Setelah 14 tahun menginterogasi mantan penguasa Orde Baru,<br />
kita justru diperhadapkan pada belantara sisa otoritarian yang tidak<br />
berujung. Reformasi 1998 melahirkan pengadilan HAM, suatu<br />
pengadilan paling menyeramkan untuk mengadili kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan dan genosida. UU No. 26/2000 memerintahkan Komisi<br />
Nasional HAM membuat laporan pro-justicia yang menjadikannya<br />
lembaga paling prestisius dengan kewenangan mengkalkulasi perbuatan<br />
setingkat pimpinan negara. Namun pengadilan HAM dihadang oleh<br />
prosedur pembuktian yang merujuk pada kitab hukum pidana buatan<br />
pemerintah colonial, yang hanya mengenal kejahatan terorganisir.<br />
Belum sampai ke ranah pengadilan, sejak pagi-pagi Kejaksaan Agung<br />
menolak Komnas HAM, baik laporannya maupun data dan faktanya.<br />
Akhirnya tak satupun pengadilan menghukum pimpinan orkestra<br />
kekerasan Orde Baru.<br />
Selain laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan, komisi<br />
penyelidik dua negara Indonesia dan Timor Leste tahun 2007, tak ada<br />
laporan yang mengungkap kebenaran. Pernyataan komandan militer,<br />
pendapat akademisi, dakwaan Jaksa hingga pertimbangan hakim sama<br />
menyebut peristiwa paling tragis di republik ini sebagai bentrokan antar<br />
kelompok (Agung Putri, 2008). Tragedi 1965 dijelaskan sebagai langkah<br />
aparat keamanan memulihkan ketertiban akibat bentrokan antara<br />
kelompok pro dan anti komunis. Pembunuhan massal Tanjung Priok<br />
1984 dijelaskan sebagai upaya aparat keamanan mempertahankan diri<br />
dari amukan massa. Kekerasan selama jajak pendapat di Timor Leste<br />
16
sebagai ekses dari upaya aparat keamanan mencegah konflik antara<br />
gerakan pro-kemerdekaan dan pro-integrasi.<br />
Prosedur yudisial begitu sulit menggugat kekerasan negara,<br />
kekerasan oleh aparatur negara terhadap warganya. Negara dalam<br />
khazanah pikiran orang Indonesia adalah bangunan moral dan politis<br />
bangsa. Negara bukan institusi hukum tetapi pencapaian historis<br />
gerakan anti kolonial. Negara yang rapuh serta merta akan<br />
menggerogoti bangsa (Latif, 2012).<br />
Tetapi lebih dari soal persepsi, kebijakan pemulihan ketertiban<br />
mau tak mau menyeret lembaga negara, Kejaksaan Agung salah satunya.<br />
Lembaga ini dalam riwayatnya menjadi lembaga pemberi pembenaran<br />
hukum bagi kekerasan. Kejaksaan Agung atas masukan-masukan dari<br />
tim psikologi, Fakultas Psikologi UI, menggolongkan warga ke dalam<br />
golongan A, B, C, yang menentukan jenis hukuman mulai dari hukuman<br />
mati, penjara seumur hidup atau pembuangan. Lembaga ini berkuasa<br />
menetapkan suatu perkara sebagai tindak pidana khusus, tindakan<br />
membahayakan keamanan negara, di bawah undang-undang subversi.<br />
Kejaksaan Agung membuat operasi berdarah di tahun 1965<br />
berlandas hukum. Di bawah kendali operasi besar pemulihan keamanan-<br />
Kopkamtib tahun 1965, Kejaksaan Agung memimpin Operasi Justisi,<br />
dengan wewenang membuang orang, mengeksekusi mati dan menguasai<br />
6<br />
seluruh tempat pembuangan tahanan politik. Ialah alat hukum yang<br />
menjalankan fungsi politik. Sekalipun kewenangannya kini diciutkan<br />
melalui revisi UU Kejaksaan dan kewenangan historisnya yaitu<br />
melarang peredaran buku dilucuti melalui keputusan Mahkamah<br />
Konstitusi tahun 2010, namun ia tetap mengabdi pada otoritarianisme,<br />
terutama meninjau dakwaan jaksa atas perkara pelanggaran HAM di<br />
7<br />
pengadilan HAM.<br />
Demikian pula dengan pengadilan. Sekalipun Mahkamah<br />
Agung telah menjadi lembaga judisial independen, pengadilan HAM<br />
6. Lembaga ini dalam satu dekade juga menjalankan perdagangan, mengantarkan panen beras dari Pulau<br />
Buru ke Pulau Ambon, atau memasok kebutuhan garam dari Jawa ke Pulau Buru. Pulau Buru adalah<br />
tempat pembuangan para simpatisan Sukarno dan PKI. Detil penggambaran hubungan antar lembaga ini<br />
lihat Pramoedya Ananta Toer, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Jakarta, Lentera, 1995.<br />
7. Elsam memantau persidangan di Pengadilan HAM ad hoc dan membuat catatan hasil pemantauan. Lihat<br />
www.elsam.or.id . Lihat juga beberapa catatan pengadilan David Cohen dalam<br />
http://ictj.org/publication/intended-fail-trials-ad-hoc-human-rights-court-jakarta<br />
17<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
FOKUS<br />
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />
enggan mempertimbangkan bukti di luar dakwaan Jaksa yang sudah<br />
minim itu, misalnya mengabaikan keterangan saksi maupun korban,<br />
untuk kejahatan luar biasa yang telah menyalahgunakan kewenangan<br />
negara. Keputusan pengadilan lebih banyak menjerat pelaku lapangan<br />
dari pada pembuat kebijakan (Cohen, 2003; Elsam, 2004).<br />
Beberapa keputusan pengadilan memang mempertimbangkan<br />
korban. Hakim mengabulkan gugatan korban untuk memperoleh<br />
kembali rumah yang diduduki militer Udayana, suatu kasus di Bali.<br />
Kemenangan memperoleh kembali tanah perkebunan yang sempat<br />
dirampas militer di daerah Blitar juga berhasil dilakukan. MA tahun 2008<br />
mengeluarkan keputusan mencabut sebagian besar peraturan dengan<br />
syarat bebas G30S. Nani Sumarni, mantan penyanyi Istana yang<br />
mendapat cap ET bertahun-tahun, berhasil memperoleh KTP seumur<br />
hidup. Namun bagai perahu mengapung di samudra rahasia masa lalu,<br />
kemenangan ini hanya kemenangan hukum ketimbang penyelesaian<br />
pelanggaran HAM.<br />
Ketika menjabat presiden, Gus Dur menjajagi jalan politik<br />
dengan menyatakan permintaan maafnya atas kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan kepada warga korban kekerasan '65.<br />
Namun langkah ini dijegal seketika oleh gelombang protes<br />
massa NU, khususnya Jawa Timur. Protes yang sama terhadap Komnas<br />
HAM ketika mengeluarkan laporan HAMnya tentang tragedi tahun<br />
1965 13 tahun kemudian.<br />
Faksi-faksi anti komunis yang menggantikan suara para jendral<br />
Orde Baru, mengancam: jangan coba-coba menyelesaikan kekerasan<br />
Orde Baru. Sementara itu Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya<br />
8<br />
tahun 2006 telah membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi<br />
dengan dalil sederhana: tiadanya kepastian hukum. Akibatnya pun<br />
sederhana, hukum menyandera jalan politik untuk mengurus masa lalu.<br />
Kegagalan ini di ujungnya adalah tindakan absurd seperti memaksa<br />
pemindahan jazad Heru Atmojo dari liang kubur Taman Makam<br />
9<br />
Kalibata.<br />
Menurut Robison dan Vedi (2004), sekalipun pilar ekonomi<br />
politik Orde Baru telah dilucuti ini tidak mematikan kiprah aktor Orde<br />
8. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah komisi yang dimaksudkan membantu pemerintah<br />
menyelesaikan kekerasan masa lalu dengan cara membongkar fakta kekerasan, memberikan pengakuan<br />
resmi atas kejadian tersebut, memberikan kompensasi pada korban dan keluarganya serta penghukuman<br />
atau pemaafan bagi pelakunya. Lihat naskah UU KKR yang telah dibatalkan. www.elsam.or.id<br />
9. Letkol AU Heru Atmodjo meninggal pada tanggal 29 Januari 2011. Ia diduga terlibat dalam gerakan 30<br />
September 1965. Ia dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa dan dijatuhi hukuman penjara.<br />
18
Baru dan jaringannya. Mereka bertahan dan menyesuaikan diri dengan<br />
sistem baru. Kekuasaan politik kembali dimonopoli dan sumber daya<br />
ekonomi dikolonisasi. Demokrasi kita sudah dibajak (Priyono, 2004).<br />
Kebertahanan kaum predator ini patut diduga menjadi penghambat<br />
penyelesaian kekerasan politik masa lalu.<br />
Namun agaknya terlalu gegabah mengatakan kegagalan<br />
menginterogasi masa lalu bersumber dari rendahnya kualitas demokrasi.<br />
Selain warisan otoritarian itu efektif bekerja di institusi-institusi<br />
peradilan, toh demokrasi yang pincang ini, demokrasi semu, demokrasi<br />
para preman, ternyata tidak bisa mengubur dosa masa lalu. Demokrasi<br />
itu sendiri tumbuh di atas lanskap politik yang dibangun melalui tragedi<br />
berdarah. Yang dihadapi , ternyata lebih dari konflik antar partai politik,<br />
antara kelompok golongan masyarakat, antara PKI dan non PKI.<br />
Di atas orkestrasi kekerasan tahun 1965, Orde Baru menyiapkan<br />
landasan ideologi, politik, ekonomi baru, dan sebesarnya coba<br />
melenyapkan pemerintahan Kabinet Gotong Royong dan revolusi<br />
Agustus dengan sebutan Orde Lama. Bukan saja mereka yang dibunuh,<br />
dibuang, dipenjara, atau yang membunuh, membuang, dan memenjara<br />
terikat oleh tragedi itu. Tetapi juga mereka, kaum intelektual, seniman,<br />
profesional, teknokrat, pengusaha, rohaniwan, diplomat, yang<br />
membangun orde. Para reformis yang berjuang meluruskan yang<br />
diselewengkan Suharto harus menjawab pertanyaan: siapa bertanggung<br />
jawab atas berdiri dan langgengnya Orde Baru?<br />
Para pemimpin negara masa reformasi tak putus rantainya<br />
dengan Orde Baru. Habibie, tak lepas dari sebutan ”anak emas<br />
Suharto”. Gus Dur tak mungkin membebaskan NU dari keterlibatan<br />
kekerasan di masa lalu yang kemudian menjadi korban intervensi Orde<br />
Baru dalam muktamar tahun 1984 (Aspinall, 2005). Megawati<br />
Sukarnoputri sejak muda tersingkir bersama dengan tergulingnya<br />
pemerintahan Soekarno. SBY terkait dengan peristiwa 27 Juli dan<br />
beberapa kekerasan di Timor Leste. Sementara itu mertua SBY, Jendral<br />
Sarwo Edi, adalah aktor penting pemulihan ketertiban paling berdarah<br />
tahun 1965 yang juga disingkirkan Soeharto.<br />
Siapapun, kaum demokrat di negeri ini, terlibat atau tidak dalam<br />
kekerasan, menjadi korban atau tidak, tetapi menyumbang<br />
pembangunan Orde Baru, berarti ikut melumat kabinet gotong royong<br />
Soekarno. Kerumitan ini terpancar dalam pendapat pemimpin NU<br />
19<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
FOKUS<br />
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />
dalam dengar pendapat dengan anggota Panitia Khusus RUU Komisi<br />
10<br />
Kebenaran dan Rekonsiliasi, DPR RI.<br />
”….Maka hendaknya kalau memang kita membuat undang-undang ini<br />
harus ditentukan terlebih dahulu niat membuat undang-undang itu,<br />
apakah kita menuju kepada rekonsiliasi ataukah kita ingin membuka<br />
kasus-kasus yang lalu itu, … Saya berpendapat bahwa kalau luka-luka<br />
yang lama itu ditelusuri, dibuka satu persatu secara nasional maka yang<br />
terjadi adalah fenomena pertikaian baru tanpa bisa dihindari. Maka yang<br />
betul adalah kita harus menutup dalam-dalam seluruh peristiwa-peristiwa<br />
yang memilukan itu kemudian kita atasi seluruh ekses-ekses yang timbul<br />
karenanya…. Hasyim Muzadi, ketua PBNU, dalam RDPU Pansus<br />
RUU KKR 2003”<br />
Pertanyaan dasarnya: bagaimana cara kita membongkar masa<br />
lalu?<br />
Keterbukaan yang digulirkan oleh sejumlah perwira militer,<br />
lebih dari suatu angin kebebasan dan kemenangan orde hak asasi, adalah<br />
11<br />
juga momentum kembalinya para politisi dan parpol tersingkir sejak<br />
masa de-sukarnoisasi 1965 hingga 1971 dan sesudahnya. Politisi NU<br />
yang bersembunyi di tubuh Golkar, menunjukkan ke NU-annya.<br />
Bahkan sejumlah tokoh Golkar justru dibesarkan oleh pemerintahan<br />
Sukarno. Bisnis keluarga Aburizal Bakri (Pohan, 2011) dan Jusuf Kalla<br />
tumbuh dari program pengusaha pribumi periode Sukarno. Sekalipun<br />
orang semacam Arifin Panigoro atau bahkan Taufik Kiemas bersikap<br />
serupa Orde Baru (Robison dan Vedi, 2004), mereka justru pendukung<br />
pemerintahan Sukarno.<br />
Partai politik baru yang lahir dari semangat reformasi, memilih<br />
melekatkan diri pada partai lama. PKB bangkit dari masa tiarap panjang<br />
NU dari politik. PDI Perjuangan mencoba mengembalikan kejayaan<br />
PNI. PAN menjadi semacam 'sayap politik' Muhamadiyah. Partai Bulan<br />
Bintang mensenyawakan diri dengan Masyumi. PDS dengan Parkindo.<br />
PKS, eksponennya dikaitkan dengan gerakan DI/ TII.<br />
Kita menyaksikan suatu transformasi korban, pelaku, saksi,<br />
pendukung, atau penyembah Orde Baru menjadi politisi pasca Orde<br />
10. Lihat teks transkripsi dengar pendapat antara pemimpin NU, KH Hasyim Muzadi dengan anggota DPR<br />
RI Komisi III, 2004.<br />
11. Perwira militer, termasuk Jendral polisi Roekmini yang mendorong keterbukaan tahun 1993 melalui<br />
forum parlemen, itu terutama didasari oleh kekuatiran peran ICMI yang semakin membesar, ketimbang<br />
komitmen pada kebebasan berekspesi. Pertentangan ideologis antara militer merah putih dan militer<br />
hijau (Aspinall, 2005).<br />
20
Baru. Mereka mendukung partai tertentu dan menjadi anggota legislatif,<br />
misalnya AM Fatwa, Beni biki, Yusron, dan Ribka Ciptaning. Mantan<br />
Tapol, tokoh perburuhan, Mochtar Pakpahan mendirikan partai buruh.<br />
Demikian pula Sri Bintang Pamungkas dengan partai nasionalnya.<br />
Setelah peristiwa 27 Juli muncul politisi antara lain Mangara Siahaan,<br />
Eros Djarot, dan Sophan Sophiaan.<br />
Perwira tinggi yang namanya tersebut dalam laporan Komnas<br />
HAM membentuk partai politik, atau mem-backing partai-partai besar.<br />
Junus Josfiah, namanya tersebut berkali-kali dalam pembunuhan<br />
wartawan Australia di Balibo 1974 menjadi pimpinan PPP. Jendral<br />
Muchdi belakangan menyusul. Mereka bahkan menjadi pelindung<br />
12<br />
pimpinan partai politik yang menjadi korban. Pemimpin tertinggi<br />
partai Gerindra, Prabowo masih memiliki soal dengan peristiwa<br />
penculikan di tahun 1998. Jendral (purn.) Wiranto yang punya soal<br />
dengan kebijakan bumi hangus di Timor Leste tahun 1999 kini<br />
memimpin partai Hanura.<br />
Transformasi ini bukan adegan 'ramai-ramai melupakan masa<br />
lalu'. Justru sebaliknya, sedang terjadi pengentalan identitas gerakan<br />
politik karena keterlibatan dalam kekerasan di masa lalu. Di kalangan<br />
korban pun, korban '65 misalnya, akan sulit melibatkan diri dalam partai<br />
Golkar, PKB atau PAN dan lebih memilih PDIP dan partai Sukarnois<br />
lainnya. Bali khususnya, perseteruan antara PNI dan PKI di tahun 65<br />
membuat korban PKI kini bisa dipastikan lebih bersimpati kepada<br />
Golkar dan Partai Demokrat. Korban Tanjung Priok berada di belakang<br />
PPP. Di Aceh, partai Aceh didukung penuh oleh korban kekerasan<br />
Orde Baru.<br />
Partai politik itu sendiri adalah korban Orde Baru, terkubur<br />
dalam fusi 3 partai, atau dibubarkan, diinterupsi, dikangkangi Golkar<br />
dan mengidap trauma yang sama. Kini pelaku politik pasca Orde Baru,<br />
korban dan pelaku, hidup bersama dalam format politik khas reformasi,<br />
yang mengikuti selera internasional (Robison dan Hadiz, 2004) dan tidak<br />
sampai membedah aktor yang mendepolitisasi masyarakat dan<br />
melumpuhkan partai politik.<br />
12. Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, ketika diusung menjadi ketua umum PDI dalam<br />
kongres Surabaya, berusaha disingkirkan. Ketika PDI Perjuangan memenangkan pemilu 1999, banyak<br />
tokoh militer yang dahulu berseberangan menjadi pelindungnya.<br />
21<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
FOKUS<br />
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />
Maka di tubuh parlemen, perbedaan dalam melihat masa lalu<br />
menjadi samar dalam bisik-bisik ketimbang debat terbuka sekalipun<br />
dibentuk panitia khusus untuk menguji kasus orang hilang, Trisakti<br />
Semanggi. Ketika salah satu anggota parlemen dari Golkar, Priyo Budi<br />
Santoso menolak Presiden menyatakan permintaan maaf terhadap<br />
korban 65, anggota DPR lain memilih diam.<br />
Sementara di kepulauan yang jauh dari bencana politik nasional,<br />
korban dan pelaku pun hidup saling bertukar luka. Di Bali, korban dan<br />
pelaku hidup dalam satu rumah besar dan menghidupi<br />
persembahyangan yang sama. Di Kupang, pelaku menjalani pengobatan<br />
supra natural untuk mengusir hantu korban yang dibunuhnya di tahun<br />
60an. Tokoh-tokoh daerah, Kepala LPM desa, penasehat perkawinan,<br />
pelukis istana, pemborong proyek perumahan punya masa lalu penuh<br />
luka (Putu Oka Sukanta, 2011). Para politisi Dayak terkemuka fasih<br />
mengurai betapa mobilisasi etnis melayu menyingkirkan mereka di sudut<br />
samping Orde Baru. Politisi Cina tak mungkin lupa akan pembantaian di<br />
Kalimantan, khususnya Sintang dan Sanggau puluhan tahun lalu.<br />
Drama pembajakan demokrasi kalaulah ada, tidak lain adalah<br />
fungsi efekif menyandera setiap pelaku politik dengan catatan masa<br />
lalunya, bukan untuk membungkam. Politik penyelesaian kekerasan<br />
masa lalu dan politik menggunakan kenangan masa lalu ganti berganti.<br />
Kenangan akan kekerasan masa lalu pada gilirannya membentuk politik<br />
masa kini. Karenanya kalaulah ini sebuah pembajakan, maka inilah<br />
pembajakan yang abadi. Kalaulah ini bagian dari pembangunan bangsa,<br />
maka demokrasi itu harus bisa mengakhiri politik penenggelaman<br />
Sukarno dan Orde Lama bersama-sama antara pelaku dan korban.<br />
Penting diingat bahwa trauma politik bukan sekumpulan<br />
simtom...trauma lebih berarti hancurnya individu dan sturktur sosial<br />
politik suatu masyarakat. Dalam pengertian ini memang penting<br />
membantu korban untuk menghadapi dampak konflik, tetapi trauma<br />
juga menuntut terjadinya transformasi masyarakat, memperbaiki relasi<br />
dan perubahan kondisi sosial. (Hamber, 2004)<br />
Dalam kata Nelson Mandela:<br />
Ketika saya melangkah keluar penjara, sudah menjadi misi saya untuk<br />
membebaskan yang ditindas maupun yang menindas. Orang bilang kita<br />
sudah mencapainya. Bagi saya belum. Sesungguhnya kita belum bebas;<br />
22
kita hanya mencapai suatu keinginan untuk menjadi bebas, hak untuk<br />
tidak ditindas. Tapi kita belum sampai di tahap akhir perjalanan hidup<br />
kita. Kita baru di tahap awal dari perjalanan yang lebih panjang dan sulit.<br />
Untuk menjadi bebas, tidak cukup hanya membuka rantai belenggunya,<br />
tetapi hidup dalam cara yang saling menghormati dan memperbesar<br />
kebebasan orang lain. Ujian yang sesungguhnya akan kesetiaan kita pada<br />
kebebasan baru dimulai (Mandela, 1995).<br />
23<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
Ikhtiar Mencuci<br />
”Karpet Martti” di Aceh<br />
Otto Syamsuddin Ishak<br />
Abstract<br />
The conflict between GAM and RI ended with the Helsinki MoU agreement on<br />
15 August 2005. The hope to deal with past human rights violations in Aceh<br />
appeared several times, but always ended in failures. This article explores the<br />
failures to deal with past human rights violations in Aceh inspite of the political<br />
change occured in the region<br />
Keywords: Aceh, Human Rights, Past Human Rights Violation<br />
Pendahuluan<br />
Harapan pertama penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Aceh<br />
muncul dalam perundingan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-RI di<br />
Helsinki (2005), tapi gagal. Harapan kedua muncul ketika pembahasan<br />
draf RUU Pemerintahan Aceh (2006), tapi gagal lagi. Harapan ketiga<br />
sempat bangkit paska pemilukada gubernur (2006) yang dimenangkan<br />
oleh golongan politik yang dahulunya pejuang, tetapi gagal juga.<br />
Paska Pemilu 2009 muncul lagi harapan ketika kursi parlemen<br />
provinsi didominasi oleh Partai Aceh (2009), tapi masih gagal juga.<br />
Harapan kelima timbul manakala kandidat gubernur/wakil gubernur<br />
dari Partai Aceh menang dalam pemilukada (2012), dan kini draft qanun<br />
KKR dijanjikan akan dibahas di parlemen provinsi Aceh. Apakah<br />
nantinya akan muncul qanun KKR sebagai instrumen untuk mencuci<br />
sebagian ”Karpet Martti” yang masih bersimbah darah?<br />
Hal yang sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada elite politik,<br />
militer, gerilyawan dan milisi—baik secara sendiri-sendiri maupun<br />
secara bersama-sama—yang berani mengatakan atau sebaliknya<br />
membantah di depan publik perihal adanya pelanggaran HAM yang<br />
terjadi selama hampir tiga dasawarsa konflik GAM-RI di Aceh. Semua<br />
25
FOKUS<br />
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />
pihak yang berkuasa saat ini bergeming untuk membahas upaya<br />
penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu Aceh itu.<br />
Tentu saja mandegnya upaya ini tidak sejalan dengan cita<br />
Republik sebagai sebuah negara hukum sebagaimana termaktub dalam<br />
Konstitusi. Sangat disayangkan karena realitas yang terjadi sekarang<br />
seakan-akan merupakan penegasian eksistensi Republik sebagai negara<br />
hukum, dan sebagai sebuah negara modern yang memiliki Konstitusi<br />
yang mencerminkan penghormatan dan kehendak penegakan HAM.<br />
Memang bila dilihat dari konteks historis, sejak berdirinya<br />
Indonesia pada 1945, Republik ini belum memiliki fondasi politik yang<br />
cukup kuat untuk mewujudkan penghormatan dan kemauan penegakan<br />
HAM sebagai sebuah realitas. Ini dibuktikan dengan amat sedikitnya<br />
proses peradilan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan. Dengan kata<br />
lain, Republik ini memiliki tradisi politik yang cukup kuat untuk<br />
mengakumulasi kejahatan kemanusiaan.<br />
Sejak Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada 1999-2002,<br />
HAM telah menjadi bagian yang integral dalam Konstitusi. Jumlah<br />
pasal-pasalnya lebih banyak dibanding pasal yang berkenaan dengan<br />
keamanan dan pertahanan. Amandemen menghasilkan pembatasan<br />
jabatan Presiden maupun Kepala Daerah. Di level pusat telah<br />
mengalami pergantian rezim penguasa paska Reformasi 1998, sedang di<br />
Aceh telah berlangsung dua kali pemilukada (2006 dan 2012), serta satu<br />
kali perubahan komposisi anggota Parlemen Aceh, yang kini dikuasai<br />
dan didominasi oleh golongan politik yang menjadi lokomotif gerakan<br />
kemerdekaan Aceh.<br />
Pertanyaan besarnya mengapa perbaikan kondisi hukum dan<br />
politik, baik di level Pusat maupun di Aceh ini, tidak kunjung memberikan<br />
kebenaran dan keadilan terhadap korban konflik Aceh? Padahal<br />
kejahatan kemanusiaan sebagai fakta sosial (yang terus bergerak menjadi<br />
fakta sejarah) tidak terbantahkan.<br />
Bukankah ikhtiar memberikan kebenaran dan keadilan pada<br />
korban dan pelaku merupakan perwujudan pernyataan diri sebagai<br />
negara hukum? Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan<br />
penuntasan kejahatan masa lalu di Aceh?<br />
Untuk menjawab persoalan di atas, tulisan ini memaparkan<br />
kembali catatan-catatan tentang perdebatan antara pihak RI dan GAM<br />
di meja perundingan di Helsinki, proses pengadopsian resolusi masalah<br />
26
pelanggaran HAM dalam UU Pemerintahan Aceh, serta ikhtiar<br />
organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mendorong adanya sebuah<br />
qanun tentang komisi kebenaran.<br />
1. Martti: ”Merumitkan Hidup”<br />
Jika merujuk pada catatan proses perundingan di Helsinki versi Hamid<br />
Awaluddin, sebenarnya tidak ada agenda untuk membahas masalah<br />
penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM selama konflik. Delegasi<br />
RI tidak memasukkannya dalam agenda perundingan secara spesifik.<br />
Delegasi RI hanya mengusulkan pembahasan terkait topik<br />
1<br />
”penghargaan pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.”<br />
Baru pada perundingan putaran kedua, Nurdin Abdul Rahman,<br />
salah seorang delegasi GAM melontarkan topik ini. Nurdin sendiri<br />
memang ditangkap pada 1990 di masa Aceh distatuskan oleh Rezim<br />
Orde Baru sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi<br />
Operasi Jaring Merah. Lalu, setelah dijatuhi hukuman 13 tahun penjara.<br />
Tetapi dengan adanya Reformasi 1998, ia bebas setelah menjalani<br />
2<br />
hukuman selama 10 tahun.<br />
Dalam perundingan Helsinki putaran kedua itu Nurdin<br />
mengatakan:<br />
”Untuk urusan hak asasi manusia dan keadilan, kita harus lakukan<br />
investigasi yang dilaksanakan oleh lembaga mandiri internasional. Saya<br />
3<br />
telah mengalami penganiayaan dalam penjara.”<br />
Pengajuan masalah pelanggaran HAM oleh Nurdin dinilai<br />
4<br />
Hamid Awaluddin sebagai sesuatu hal yang sangat personal Nurdin<br />
Abdul Rahman. Menurut Hamid Awaluddin, pengalaman Nurdin itu<br />
selalu dijadikan titik tolak pembicaraan masalah pelanggaran HAM dan<br />
permintaan untuk adanya solusi.<br />
Hamid Awaluddin, sebagai ketua delegasi RI, merespon<br />
panjang-lebar untuk persoalan HAM tersebut secara normatif, setelah<br />
diinterupsi oleh Martti Ahtisaari dengan istirahat minum teh dan kopi<br />
terlebih dahulu.<br />
1. Awaluddin, Damai Di Aceh: Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki. Jakarta: CSIS, 2008. Halaman 72.<br />
2. http://www.analisadaily.com/news/read/2012/04/18/46237/turut_membidani_mou_helsinki/<br />
3. Ibid, halaman 129.<br />
4. Ibid, halaman 111.<br />
27<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
FOKUS<br />
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />
Perkenankan saya memaparkan agenda hak smanusia. Masalah HAM<br />
ini, dunia telah menyaksikan betapa pemerintahan kita sangat serius<br />
untuk ini. Dari perspektif hukum, kita telah memiliki UU HAM dan<br />
Peradilan HAM. Sejumlah draft UU yang berkaitan dengan masalah<br />
HAM dan hak-hak sipil politik kini tengah dibahas. Dalam waktu<br />
dekat ini, dua instrument dasar HAM internasional, akan diratifikasi,<br />
yakni, Konvensi Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik serta<br />
Konvensi Internasional mengenai hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.<br />
Ini adalah tiang pancang utama HAM universal. Ini tak pernah<br />
terbayangkan sebelumnya bahwa kita menyentuh kedua pilar utama ini.<br />
Segi kelembagaan, kita punya Komnas HAM yang sangat mandiri.<br />
Peradilan HAM sudah berjalan.... Kini kita juga dalam proses<br />
pembentukan Komisi Rekonsiliasi.... Jadi, jika GAM berbicara tentang<br />
demokrasi dan HAM, maka segala penilaian negatifnya itu, memang<br />
5<br />
benar dalam konteks masa silam. Bukan sekarang ini....”<br />
Ketika anggota delegasi GAM, Bachtiar Abdullah, menanyakan<br />
bagaimana menyikapi pelanggaran HAM di masa konflik: ”Apakah kita<br />
6<br />
memandangnya hanya ke depan, bukan ke belakang?” Segera direspon<br />
oleh Martti Ahtisaari dengan memuja uraian normatif Hamid<br />
Awaluddin di atas.<br />
”Satu di antara sekian kerumitan hidup yang kita alami adalah, yang<br />
berhubungan dengan masa silam kita. Hati-hati dengan soal ini. Dengan<br />
segala respek saya pada pemerintahan sekarang, banyak sekali kemajuan<br />
yang telah dicapainya … Namun, jangan kita larut dengan kesedihan<br />
masa lalu.”<br />
”Kita tak akan mungkin memasukkan ini dalam draft tertulis sebab<br />
sangat sensitif. Ini tidak berarti kita bahwa kita hapuskan pembicaraan<br />
tentang ini. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita harus<br />
bersihkan karpet dari agenda ini. Inilah yang kita maksudkan itikad<br />
baik. Tentu saja memang selalu mengecewakan dan tidak memuaskan.<br />
Kita butuh keberanian menghadapi ini. Singkatnya, masalah HAM<br />
7<br />
adalah masalah masa depan.”<br />
5. Op Cit, halaman 131-132.<br />
6. Op Cit, halaman 133.<br />
7. Op Cit, halaman 133-134.<br />
28
Dengan pernyataannya itu, Martti Ahtisaari memang tidak<br />
hendak membersihkan ”karpet berdarah”, juga bukan hendak<br />
mengabaikannya, tapi tidak mau masuk ke dalam salah satu kerumitan<br />
hidup. Mantan Presiden Finlandia itu dengan ”berani” mengambil<br />
karpet tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak masa lalu, lalu dia<br />
berseru: ”mari kita menatap masa depan.”<br />
Hasil perundingan kemudian adalah tiga butir kesepakatan yang diatur<br />
dalam bab HAM. Berikut adalah poin-poin tentang pelanggaran HAM<br />
sepanjang hampir tiga dasawarsa konflik bersenjata itu, yang<br />
dirumuskan dalam MoU Helsinki:<br />
2.<br />
2.1.<br />
2.2.<br />
2.3.<br />
HAM dalam MoU Helsinki<br />
2. Ikhtiar Pada Konteks Nasional<br />
MoU Helsinki memberikan mandat kepada Presiden dan DPR untuk<br />
segera membuat UU baru terkait dengan Aceh dengan mengadopsi<br />
butir-butir kesepakatan Helsinki. Pengusulan dan pembahasan<br />
rancangan undang-undang untuk Aceh kemudian menjadi arena<br />
kontestasi bagi banyak individu elite politik dan pihak golongan politik.<br />
Di Aceh, kontestasi terjadi antara kekuatan masyarakat sipil,<br />
individu elite, elite politik (eksekutif dan legislatif), dan GAM. Tentu saja<br />
masing-masing memiliki agenda sendiri. Ada elite politik yang<br />
melakukan manuver individual dengan cara mengajukan revisi UU No.<br />
18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah<br />
Istimewa Aceh, lalu dia menyerahkan draf tersebut ke pihak terkait di<br />
29<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
Pemerintah RI akan mematuhi Konvenan Internasional<br />
Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan<br />
Politik dan Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.<br />
Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk<br />
Aceh.<br />
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh<br />
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas<br />
merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.
FOKUS<br />
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />
Jakarta. Demikian pula ada inisiatif dari eksekutif untuk mendahului<br />
proses drafting RUU.<br />
Hal yang menarik adalah organisasi masyarakat sipil juga<br />
mengambil inisiatif untuk menyusun draf RUU, sehingga pada satu<br />
kondisi politik tertentu muncul konsensus politik dari semua kekuatan<br />
politik di Aceh untuk melakukan reformulasi bersama yang menjadi draf<br />
RUU dari Aceh. Draf ini yang kemudian disandingkan dengan draf yang<br />
dibahas oleh DPR RI.<br />
Dalam pembahasan di DPR RI, ternyata perihal hak asasi<br />
manusia tidak menjadi topik yang krusial. Perdebatan mengenai HAM<br />
seakan tidak dianggap masalah penting ketimbang tema-tema lain yang<br />
diatur dalam RUU. Sejumlah poin penting terkait HAM yang diusulkan<br />
dalam draf RUU versi Aceh justru dihilangkan.<br />
Misalnya, perihal pelembagaan pengadilan HAM dan Komisi<br />
Kebenaran. Ketentuan mengenai rentang waktu implementasi dua<br />
usulan institusi ini dihilangkan. Sehingga ketentuan waktu pendiriannya<br />
tidak mengikat. Nasib yang sama terjadi pada usulan tentang<br />
kemungkinan keterlibatan pelapor khusus dalam investigasi kejahatan<br />
HAM. Ketentuan ini dihapus dalam RUU hasil pembahasan DPR.<br />
Berikut adalah poin-poin penting dalam draf RUU usulan Aceh<br />
yang mengalami amputasi dan koreksi ketika dibahas di DPR RI:<br />
Usulan Aceh yang Dihilangkan di DPR RI<br />
3. Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />
paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undangundang<br />
ini.<br />
4. Pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan<br />
Rekonsiliasi di Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah<br />
pengesahan undang-undang ini.<br />
5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah derivasi dari<br />
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional yang<br />
bertugas untuk merumuskan dan menentukan<br />
rekonsiliasi dan melakukan klarifikasi terhadap<br />
pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu.<br />
30<br />
Tenggang waktu<br />
dihilangkan<br />
Ayat ini<br />
dihilangkan<br />
Tugas untuk<br />
klarifikasi<br />
dihilangkan
Setidaknya ada tiga asumsi mengenai minimnya pembahasan<br />
serta penghilangan poin-poin penting tentang HAM dalam RUU<br />
Pemerintahan Aceh di DPR. Pertama, karena rumusan dalam MoU<br />
Helsinki menjamin ditutupnya persoalan pelanggaran HAM masa lalu<br />
(konflik). Kedua, masalah HAM di Aceh dianggap sebagai wacana ke<br />
depan. Ini seturut dengan pembahasan dalam perundingan Helsinki.<br />
Ketiga, minimnya pembahasan HAM dapat memberikan kenyamanan<br />
politik bagi kelompok elite penguasa dan politisi di DPR.<br />
Hal yang terakhir ini menjelaskan bahwa satu karakter transisi<br />
kekuasaan di Indonesia adalah tetap adanya kontinuitas antara penguasa<br />
terdahulu dengan yang kemudian. Kontinuitas ini menjadi salah satu<br />
kendala politik yang utama dalam penegakan HAM untuk kasus-kasus<br />
pelanggaran HAM masa lalu, karena pelanjut penyelenggara negara<br />
sekarang—baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif hingga ke pelaksana<br />
di lapangan—adalah bagian dari rezim masa lalu, baik secara struktural<br />
maupun kultural.<br />
Justru mereka memiliki kewenangan untuk menciptakan<br />
diskontinuitas antara kejahatan masa lalu dengan pelembagaan<br />
pengadilan HAM di masa kini dengan kalimat: ”Untuk memeriksa,<br />
mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia<br />
8<br />
yang terjadi sesudah Undang-Undang ini diundangkan …”<br />
Peminggiran upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di<br />
Aceh juga terjadi pada proses pembahasan RUU di DPR RI. Masalah<br />
yang dianggap krusial dibahas oleh DPR RI adalah masalah seperti<br />
31<br />
dignitas<br />
6. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di<br />
Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh<br />
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional dengan<br />
memperhatikan pertimbangan DPRA.<br />
Dalam hal tidak adanya jaminan proses investigasi yang adil<br />
dilakukan terhadap kasus-kasus kejahatan berat hak asasi<br />
manusia tertentu di wilayah, pemerintah memberi<br />
kesempatan kepada pelapor khusus (special rappourteur)<br />
dan/atau pejabat lain Pererikatan Bangsa-Bangsa untuk<br />
masuk ke wilayah Aceh.<br />
8. Cetak tebal dari penulis.<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
”memperhatikan<br />
pertimbangan<br />
DPRA”<br />
dihilangkan<br />
Perihal membuka<br />
kesempatan<br />
untuk melibatkan<br />
pelapor khusus<br />
dihilangkan
FOKUS<br />
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />
desentralisasi (penyerahan kewenangan Pusat ke Aceh) dan<br />
dekonsentrasi (pelimpahan kewenangan), persoalan implementasi<br />
syariat Islam agar tidak menjadi jalan bagi gerakan syariatisasi negara,<br />
serta masalah model demokrasi lokal, termasuk di dalamnya mekanisme<br />
9<br />
pemilihan kepala daerah dan ketentuan mengenai partai politik lokal.<br />
Koalisi organisasi masyarakat sipil yang sejak masa konflik telah<br />
mengadvokasi persoalan pelanggaran HAM menganggap tindakan<br />
politik dalam pembahasan RUU di DPR dengan mengamputasi poin<br />
penting terkait HAM sebagai tindakan ”merampas hak keadilan<br />
korban.” Mereka juga menilai tindakan politik tersebut telah ”merusak<br />
10<br />
tatanan hukum nasional yang menjamin keadilan.”<br />
Pada saat yang hampir bersamaan, pada konteks nasional,<br />
munculnya gagasan pembentuk KKR Aceh memicu kembali desakan<br />
untuk segera membentuk KKR Nasional karena keberadaannya berelasi<br />
dengan keberadaan KKR Aceh. Kaitan ini sesuai dengan rumusan RUU<br />
Aceh yang sedang dibahas oleh Pansus DPR.<br />
Sutradara Ginting, salah seorang politikus PDIP, menegaskan<br />
bahwa ”kalau KKR nasional tidak segera dibentuk, KKR di Aceh juga<br />
11<br />
tidak bisa jalan.” Oleh karena itu PDIP mendesak Presiden SBY untuk<br />
segera membentuk KKR Nasional.<br />
Pendapat lain muncul setelah Mahkamah Konstitusi mencabut<br />
UU KKR sehingga pembentukan KKR Nasional yang ditunda-tunda<br />
itu justru mendapat landasan hukum untuk tidak dibentuk. Akibatnya,<br />
muncul kecemasan terhadap kemungkinan pembentukan KKR Aceh,<br />
meski Ketua MK, Jimly Asshidiqie, mengklarifikasinya. Jimly<br />
mengatakan:<br />
”KKR NAD tidak terkait dengan UU KKR. Itu ada kaitannya dengan<br />
UU PA sendiri... Kalau mau lewat mekanisme KKR, bisa dibuat lagi UU<br />
KKR yang sesuai dengan UUD dan instrumen hukum internasional. Ini<br />
12<br />
(UU KKR lama) kok kompensasi dikaitkan dengan amnesti…”<br />
RUU Aceh pun akhirnya disahkan menjadi UU No. 11 tahun<br />
2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini memang menjamin<br />
9. Kompas, 1 April 2006.<br />
10. Siaran Pers No. 15/Siaran Pers/VII/2006, Jakarta, 4 Juli 2006. Perihal ini ada kecemasan politik dari<br />
Fraksi PDIP: ”Tidak adil jika kemudian anggota Gerakan Aceh Merdeka terbebas karena telah<br />
memperoleh amnesti, sedangkan para anggota TNI/Polri terancam diadili. Karena itu, F-PDIP<br />
mengusulkan pemberian amnesti kepada semua pihak pelaku konflik di masa lampau sebelum<br />
terbentuknya pengadilan HAM dan KKR.” Kompas, 18 Mei 2006.<br />
11. Koran Tempo, 20 Juni 2006.<br />
12. Detikcom, 8 Desember 2006. Kajian Elsam atas Keputusan MK tentang pencabutan UU KKR<br />
menyatakan, antara lain, membuka jalan bagi terbentuknya kultur impunitas di Indonesia. Elsam,<br />
”Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Konstitusional,” Seri Briefing Paper No. 01 Januari 2007.<br />
32
keberadaan KKR di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 229. Namun<br />
dicabutnya UU KKR oleh MK membuat KKR di Aceh tidak memiliki<br />
basis legalnya karena dalam Pasal 229 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh<br />
dinyatakan bahwa KKR Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari<br />
KKR Nasional.<br />
Berikut adalah ketentuan mengenai HAM—termasuk KKR<br />
Aceh—yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh:<br />
33<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
Pasal 228<br />
(1) Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara<br />
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah Undang-Undang<br />
ini diundangkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.<br />
(2) Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud<br />
pada ayat (1) memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi,<br />
dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.<br />
Pasal 229<br />
(1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini<br />
dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.<br />
(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud<br />
pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi<br />
Kebenaran dan Rekonsiliasi.<br />
(3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan<br />
peraturan perundang-undangan.<br />
(4) Dalam menyelesaikan kasus pelangggaran hak asasi manusia di Aceh,<br />
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat<br />
mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam<br />
masyarakat.<br />
Pasal 230<br />
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan,<br />
penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya<br />
penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur<br />
dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.<br />
Sumber: UU No. 11 Tahun 2006
FOKUS<br />
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />
Satu-persatu ikhtiar untuk menyelesaikan kasus-kasus<br />
pelanggaran yang terjadi semasa tiga dasawarsa konflik di Aceh pada<br />
konteks nasional mulai pudar. Poin-poin penting mengalami amputasi.<br />
UU KKR pun dicabut oleh MK yang karena pencabutan ini, maka<br />
ikhtiar pembentukan KKR di Aceh dengan sendirinya berakhir.<br />
Meski demikian gerakan masyarakat sipil dan korban<br />
pelanggaran HAM di Aceh tak tinggal diam. Mereka lalu memusatkan<br />
ikhtiarnya pada arena politik lokal di Aceh, tepatnya di DPRA dan<br />
Pemerintah Aceh hasil Pemilukada 2006 yang dimenangkan oleh<br />
pasangan GAM-SIRA—yang maju melalui jalur independen—yakni:<br />
Gubernur, Irwandi Yusuf, dan Wakil Gubernur, M. Nazar.<br />
3. Ikhtiar Pada Konteks Aceh<br />
Lalu bagaimana ikhtiar di tingkat lokal Aceh? Pada prinsipnya Gubernur<br />
Irwandi mendukung pembentukan KKR karena merupakan amanah<br />
13<br />
dari MoU Helsinki. Irwandi juga menyatakan ikhtiar yang sudah<br />
dilakukannya untuk mencari payung hukum bagi KKR Aceh, yakni<br />
dengan cara menulis surat pada Presiden SBY. Payung hukum nasional<br />
dibutuhkan karena "KKR di Aceh, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)<br />
14<br />
merupakan bagian tidak terpisahkan dari KKR." Dalam lain kata,<br />
Pemerintah Aceh bersikap akan membentuk KKR Aceh apabila ada<br />
payung hukum nasional untuk pembentukan KKR Nasional. Pada<br />
kesempatan lain, Gubernur Irwandi mengatakan:<br />
”Mengingat batas waktu yang ditetapkan UUPA telah dilewati, maka<br />
saya menyarankan kepada Presiden untuk mengupayakan percepatan<br />
pembentukan pengadilan tersebut agar tersedianya jalur hukum untuk<br />
korban-korban pelanggaran HAM di Aceh… Sebagai jalan lain, kami<br />
menyarankan agar Presiden mempertimbangkan untuk menetapkan suatu<br />
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang KKR.<br />
15<br />
Ini memang dimungkinkan karena situasinya darurat.”<br />
Ikhtiar Gubernur Irwandi tersebut dibenarkan oleh Menteri<br />
Dalam Negeri Mardiyanto bahwa surat Gubernur telah diterima dan<br />
Pemerintah sedang berkonsultasi dengan para pihak yang terkait di<br />
Jakarta.<br />
13. http://www.rakyataceh.co.nr/, rakyat aceh, 16 Februari 2007.<br />
14. Kompas, 24 Maret 2007.<br />
15. Serambi, 24 November 2007. Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, A Hamid Zein bahkan<br />
memberikan harapan yang lebih besar tentang pembentukan KKR “bahwa Rancangan Undang-Undang<br />
(RUU) KKR sudah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2008.” Serambi,<br />
26 November 2007.<br />
34
35<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
”Kami sudah menerima surat permohonan dari Gubernur (NAD)<br />
Irwandi Yusuf agar pemerintah segera mengeluarkan keputusan mengenai<br />
pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Surat itu akan<br />
16<br />
menjadi pertimbangan penyegeraan pembentukan KKR.”<br />
Perihal pembentukan KKR juga dibicarakan dalam pertemuan<br />
Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Damai Aceh, yang<br />
merupakan forum perwakilan Pemerintah Pusat yang berkantor di<br />
Aceh. Anggota FKK, Masykur, meyakinkan bahwa Pusat siap untuk<br />
membentuk KKR, dan dia justru meragukan kesiapan Pemerintah Aceh<br />
dan pihak GAM.<br />
”Dari hasil rapat tersebut memang telah kita sepakati untuk perancangan<br />
Perpu bagi pembentukan KKR di Aceh secara lebih spesifik, mengingat<br />
acuan dasar pembentukan KKR yang didasarkan pada UU No 27<br />
Tahun 2004 Tentang KKR, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.<br />
Saat ini Perpu tersebut sedang dalam proses persiapan…. Pada prinsipnya<br />
pemerintah pusat siap untuk membentuk KKR dan pengadilan HAM di<br />
Aceh, sekarang pertanyaannya adalah apakah pihak yang dulunya<br />
17<br />
bertikai siap untuk menerimanya.”<br />
Di lain pihak, ternyata rancangan qanun KKR tidak masuk<br />
dalam Program Legislasi DPRA 2007, meski sudah diamanatkan dalam<br />
MoU Helsinki dan UUPA. Sejumlah organisasi masyarakat sipil pun<br />
menyikapinya dengan mendesak Pemerintah RI untuk segera<br />
membentuk KKR di Aceh sebagai perwujudan pengakuan terhadap<br />
18<br />
kehormatan para korban dan ahli warisnya.<br />
Di tingkat bawah, gerakan masyarakat sipil sudah<br />
mensosialisasikan pembentukan KKR Aceh kepada para ulama. Aksi<br />
mereka mendapatkan dukungan dari ulama Aceh yang terhimpun dalam<br />
Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA).<br />
Dalam sebuah kesempatan, Sekretaris Jendral HUDA, Tgk<br />
Faisal Ali, mengatakan bahwa korban konflik mempertanyakan tiga poin<br />
kepada Gubernur Irwandi. Ketiga poin tersebut adalah kapan<br />
pengadilan HAM di Aceh bisa dilaksanakan, kapan Komisi Kebenaran<br />
16. Kompas, 27 November 2007.<br />
17. Serambi, 4 Oktober 2007.<br />
18. Serambi, 19 Agustus 2007.
FOKUS<br />
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />
dan Rekonsiliasi (KKR) dibentuk dan dijalankan, ketiga mengapa<br />
kinerja Badan Reintegrasi Damai-Aceh (BRA) sampai kini belum<br />
maksimal dalam menjalankan program reintegrasi untuk korban<br />
19<br />
konflik.<br />
Namun Gubernur Irwandi tak serius menanggapi keluhan para<br />
ulama. Dia hanya mengatakan agar para korban bersabar. Lalu, dia<br />
mengalihkan perbincangan dengan para korban ke persoalan kebutuhan<br />
lain yang mendesak, yakni pembentukan Komisi Komplain<br />
sebagaimana yang diamanatkan MoU Helsinki.<br />
”Ini juga belum terbentuk, padahal ini sangat penting. Karena pada waktu<br />
terjadi konflik, banyak rumah, toko, kendaraan masyarakat yang<br />
dibakar dan diambil paksa. Sampai sekarang belum ada proses<br />
penggantiannya. Dalam perjanjian damai, masalah ini harus<br />
20<br />
dilaksanakan, agar orang yang jadi korban bisa mendapat ganti rugi.”<br />
Konsekuensi logis dari sikap Gubernur Irwandi yang<br />
menggantungkan pembentukan KKR Aceh pada payung hukum<br />
nasional berdampak pada gagalnya upaya 35 anggota DPR Aceh periode<br />
2004-2009 yang menggunakan hak inisiatif mereka mengajukan draf<br />
rancangan qanun KKR untuk dibahas, menjadi gagal. Salah seorang<br />
inisiator, Muklis Mukhtar menjelaskan bahwa ”ada penjelasan dari<br />
Pemerintah Aceh yang meminta ditunda, maka semangat dari tim ini<br />
21<br />
sempat buyar.”<br />
Ketika berkunjung ke Aceh, Martti Ahtisaari mengakui masih<br />
adanya butir-butir dalam MoU Helsinki yang belum diimplementasikan,<br />
khususnya yang menyangkut pembentukan pengadilan HAM dan KKR,<br />
namun hal ini menjadi tanggungjawab Pemerintah sepenuhnya.<br />
”Adalah menjadi kewenangan polisi untuk menyelidiki dan menindak<br />
para pelakunya, sehingga jangan sampai menjadi ancaman bagi masa<br />
22<br />
depan perdamaian Aceh.”<br />
Dalam hal ini cara pandang Pemerintah Aceh (termasuk staf ahli<br />
gubernur) dan Martti Ahtisaari dalam melihat siapa pihak yang<br />
bertanggung jawab dalam pembentukan pengadilan HAM dan KKR<br />
adalah Pemerintah Pusat. Dalam bahasa staf ahli Gubernur, M Nur<br />
Rasyid, ”Pemerintah RI masih punya utang, antara lain belum<br />
19. Serambi, 7 September 2007.<br />
20. Serambi, 7 September 2007.<br />
21. Serambi, 11 Februari 2009.<br />
22. Serambi, 26 Februari 2009.<br />
36
37<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
23<br />
terbentuknya KKR.”<br />
Meskipun demikian kondisi politik di Aceh, para aktivis<br />
organisasi masyarakat sipil dan para korban tetap melakukan ikhtiar<br />
untuk pembentukan pengadilan HAM dan KKR. Harapan itu kembali<br />
muncul paska Pemilu 2009 karena Partai Aceh mendominasi kursi<br />
parlemen di provinsi. Partai ini mendapat 33 dari 69 kursi DPR Aceh.<br />
Mereka menuntut segera pembahasan dan pengesahan rancangan<br />
qanun KKR. Direktur AJMI, Hendra Budian mengatakan: ”Kepada<br />
Dewan baru agar sesegera mungkin mengesahkan Qanun KKR demi<br />
24<br />
menjawab rasa keadilan bagi korban konflik.” Gubernur Irwandi pun<br />
kian mempertegas sikap politiknya perihal ini:<br />
”Yang sangat penting untuk kita minta perubahan adalah Pasal 229<br />
tentang pembentukan KKR. Dalam UUPA disebutkan kalau<br />
pembentukan KKR Aceh harus dibentuk berdasarkan UU. Dalam<br />
penjelasan UUPA, UU yang menjadi cantolan KKR Aceh adalah UU<br />
No 27 Tahun 2004 tentang KKR nasional. Masalahnya UU KKR itu<br />
sudah dibatalkan oleh MK. Untuk menunggu UU yang baru, kita<br />
membutuhkan waktu yang lama. Kalau Aceh membentuk KKR dengan<br />
menggunakan payung hukum qanun, perdebatan hukum akan panas lagi.<br />
Alangkah sangat bijak kalau kita minta agar Pasal 229 ini direvisi,<br />
sehingga kita tidak perlu menunggu UU lagi untuk pembentukan KKR<br />
25<br />
Aceh.”<br />
4. Korban Memonumenkan Kebenaran<br />
Di tingkat bawah, masyarakat memiliki ikhtiarnya sendiri dalam<br />
mengingat pelanggaran hak asasi manusia sepanjang konflik<br />
berlangsung. Warga Pusong di Kota Lhokseumawe bersama dengan<br />
Komunitas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Aceh Utara dan<br />
Lhokseumawe (K2HAU) mengadakan ritual tahunan berupa doa<br />
bersama dan menyantuni anak yatim dalam mengenang tragedi<br />
penyiksaan di Gedung KNPI, pada 9 Januari 1999. Dalam peristiwa ini<br />
lima warga sipil meninggal, 23 luka berat dan 21 luka ringan. Mereka juga<br />
mendesak Pemerintah di Jakarta dan Gubernur Aceh untuk membentuk<br />
pengadilan HAM dan KKR sesuai amanat MoU Helsinki.<br />
23. Serambi, 28 Agustus 2009.<br />
24. Serambi, 1 Oktober 2009.<br />
25. Materi disampaikan pada diskusi politik dengan tema: Menjaring Aspirasi Rakyat Aceh dalam Revisi<br />
UUPA, bertempat di Anjong Mon Mata Banda Aceh tanggal 21 April 2010 yang dilaksanakan DPP Partai<br />
Rakyat Aceh (PRA).
FOKUS<br />
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />
Berbagai organisasi masyarakat sipil, masyarakat dan keluarga<br />
korban tragedi Simpang KKA yang terjadi pada 3 Mei 1999 di Aceh<br />
Utara juga mengkonstruksi ritual peringatan atas tragedi tersebut. Selain<br />
26<br />
peringatan tahunan, mereka juga mendirikan monumen dengan grafiti:<br />
�Pemerintahan Aceh dan Pusat harus mengambil langkahlangkah<br />
kongkrit misalnya dengan membentuk tim-tim<br />
pencari fakta terhadap kasus masa lalu di Aceh untuk adanya<br />
sebuah pendomentasian kasus secara menyeluruh di Aceh,<br />
pemerintahan Aceh segera membentuk Qanun KKR Aceh.<br />
�Pemerintahan di tingkat Nasional harus segera mengesahkan<br />
undang-undang KKR Nasional yang sudah dicabut.<br />
�Pembentukan pengadilan HAM untuk Aceh menjadi<br />
bahagian dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM Aceh,<br />
mekanisme pengadilan HAM dan KKR saling berhubungan<br />
dalam proses pemberian rasa keadilan bagi korban.<br />
Demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat dan korban serta ahli<br />
warisnya di Jamboe Keupok, Bakongan, Aceh Selatan. Mereka<br />
mendirikan sebuah monumen untuk mengenang 16 warga sipil yang<br />
menjadi korban massal. Saburan, salah seorang anak korban,<br />
mengatakan:<br />
”Negara melakukan kejahatan, kami tidak ingin melupakan. Apalagi<br />
sampai sekarang keadilan dan tanggung jawab negara belum terwujud…<br />
Tugu ini penting sebagai bukti sejarah. Setidaknya menjadi pengobat hati<br />
27<br />
kami para korban dan kami tetap menuntut hak.”<br />
Di Banda Aceh, Keluarga korban penghilangan paksa se-Aceh<br />
(Kagundah) meminta agar Pemerintah Aceh membentuk qanun KKR.<br />
Hasil Kongres, menurut sekretaris jenderal Kagundah, Rukaiyah:<br />
”Orang-orang yang hilang semasa konflik itu merupakan tulang punggung<br />
bagi keluarga. Sekarang mereka tidak ada lagi, sehingga para keluarga<br />
korban kesulitan memenuhi nafkahnya… Ini harus ditunjukkan sebagai<br />
wujud kepedulian pemerintah untuk mendukung keberlangsungan<br />
28<br />
perdamaian yang berkeadilan di Aceh.”<br />
26. http://atjehlink.com/tragedi-simpang-kka-keadilan-bukan-sebatas-tugu/<br />
27. VHRmedia, 28 Oktober 2011.<br />
28. Waspada Online, 15 October 2009.<br />
38
39<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
Penutup<br />
Berkaca pada kasus Aceh, penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia<br />
memang sudah menjadi satu hal yang kusut. Instrumen-instrumen<br />
hukum yang tersedia—apalagi dengan dibatalkannya UU KKR—tidak<br />
mampu menerobos stagnasi ini. Bahkan, bukan para korban dan ahli<br />
warisnya saja yang semakin sukar untuk memperoleh kebenaran sebagai<br />
haknya, akan tetapi Presiden SBY pun tidak memiliki mekanisme yang<br />
legal ketika dia hendak meminta maaf kepada para korban. Ini suatu<br />
kondisi yang berlaku secara nasional, sementara pelanggaran HAM terus<br />
terjadi dan akumulatif, sebagaimana yang terjadi di Papua (konflik<br />
vertikal) dan kasus-kasus sengketa pertanahan (konflik horizontal).<br />
Untuk konteks Aceh, penyelesaian pelanggaran di masa konflik<br />
dapat dilihat sebagai arena politik di mana terjadi kontestasi antara<br />
persekongkolan elite berhadapan dengan para korban bersama<br />
organisasi masyarakat sipil. Sejak di meja perundingan Helsinki, masalah<br />
kejahatan masa lalu telah dimasukkan dalam laci perundingan oleh<br />
Martti Ahtisaari, dengan persetujuan pihak GAM dan RI. Hal ini lantas<br />
dilegalkan oleh Pansus RUU Pemerintahan Aceh. Apalagi, tidak lama<br />
kemudian MK membatalkan UU KKR. Kondisinya, pengadilan HAM<br />
belum dibentuk dan UU KKR—sebagai tempat sandaran hukum<br />
nasional bagi pembentukan KKR Aceh menurut pandangan elite politik<br />
Aceh dan Jakarta—dicabut.<br />
Namun, para korban dan OMS terus berikhtiar untuk adanya<br />
pembahasan dan pengesahan terhadap draf rancangan Qanun KKR<br />
yang sudah lama mereka formulasikan. Terakhir, dalam konteks<br />
Pemilukada 2012, ada negosiasi politik antara anggota parlemen dari<br />
Partai Aceh dan para pihak untuk membahas draf tersebut sebagai hak<br />
inisiatif DPRA, yang mana hal ini tidak terlepas dari janji politik saat<br />
pemilukada. Namun, korban dan OMS hendaknya tetap bersikap<br />
waspada dan kritis terhadap kemungkinan tindakan politik mereka di<br />
parlemen Aceh untuk mengorientasikan KKR sesuai dengan<br />
kepentingannya sebagai salah satu pihak yang potensial sebagai pelaku<br />
pelanggaran ham.<br />
Meskipun demikian, sebenarnya cukup penting untuk terus<br />
memperluas ikhtiar para korban dalam memonumenkan pelanggaran<br />
HAM, misalnya para korban dan OMS membentuk sebuah komisi<br />
historis, yang merupakan setengah perwujudan dari komisi kebenaran
FOKUS<br />
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />
yang sedang diperjuangkan tersebut. Korban dan OMS harus<br />
meneruskan pencarian bentuk komisi kebenaran yang tidak tergantung<br />
pada kebijakan politik pemerintah dan tidak terjangkau oleh intervensi<br />
golongan politik mana pun.<br />
Satu hikmah yang penting untuk disadari bahwa perundingan di<br />
Helsinki–dari perspektif HAM—merupakan negosiasi politik di antara<br />
para pihak yang sama-sama potensial sebagai pelaku pelanggaran HAM,<br />
yang difasilitasi oleh pihak yang memiliki sikap politik untuk<br />
memasukkan ”karpet Martti” ke dalam gudang sejarah masa lalu.<br />
Memang dari sudut politik bernegara, harapan menjadi pupus; tetapi<br />
ikhtiar para korban sendiri harus terus dipupuk dan dilanjutkan karena<br />
suatu waktu kebenaran diyakini akan terbit, dan sejarah akan<br />
mencatatnya.<br />
40
Kekerasan Politik Massal dan<br />
1<br />
Kultur Patriarkhi<br />
Budiawan<br />
Abstract<br />
Every mass political violence always brings deep trauma in various layers of<br />
victims. Direct victims were very likely to experience shock when they faced<br />
situation that has completely changed or situation that they never imagined before.<br />
This article seeks to explain the different lived experiences of the three wives of<br />
the former political prisoners of the '1965 Tragedy' when their husbands were<br />
released from prison.<br />
Keywords: Political Violence, Victims<br />
Perang atau kekerasan politik massal hampir senantiasa menciptakan<br />
janda-janda dan anak-anak yatim piatu, entah untuk selamanya atau<br />
untuk sementara. Sebab, kebanyakan korban langsung dari kekerasan<br />
itu, entah dibunuh atau dipenjarakan, adalah laki-laki dewasa, yang<br />
notabene suami atau ayah. Begitu pula dengan tragedi 1965-66, di mana,<br />
menurut perkiraan kasar yang paling sering dilontarkan orang, sekitar<br />
setengah juta anggota atau simpatisan PKI (dan ormas-ormasnya), atau<br />
mereka yang sekadar dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI,<br />
dibunuh dalam periode waktu antara akhir 1965 hingga pertengahan<br />
1966. Sementara lebih dari satu juta anggota atau mereka yang dituduh<br />
sebagai anggota PKI (atau ormas-ormasnya) dipenjarakan tanpa proses<br />
pengadilan sama sekali.<br />
Jika sebagian besar mereka yang dibunuh atau dipenjarakan<br />
adalah laki-laki dewasa, yang kebanyakan di antaranya adalah suami atau<br />
1. Tulisan ini merupakan versi Indonesia yang lebih ringkas dari bab saya yang berjudul ”Living with the Spectre<br />
of the Past: Traumatic Experiences among wives of former political prisoners of the '1965 Event' in Indonesia”, dalam<br />
Roxana Waterson and Kwok Kian Woon (eds.), Contestation of Memory in Southeast Asia (Singapore:<br />
Singapore University Press, 2012); hal. 270 – 291.<br />
41
FOKUS<br />
Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi<br />
ayah, maka bisa dibayangkan berapa anak yang kemudian menjadi yatim,<br />
dan berapa istri yang kemudian menjadi janda. Dalam masyarakat di<br />
mana laki-laki umumnya berperan sebagai satu-satunya pencari nafkah<br />
dalam keluarga, maka dalam situasi semacam itu bisa dibayangkan<br />
bagaimana para istri yang kemudian menjadi janda (entah karena<br />
suaminya dibunuh atau dipenjarakan) harus berjuang untuk<br />
mempertahankan hidup dirinya dan anak-anaknya.<br />
Kisah dalam tulisan ini bersumber dari penuturan orang-orang<br />
yang cukup dekat dengan istri-istri mantan tahanan politik dan karena itu<br />
tahu banyak pengalaman hidup mereka. Kisah mereka itu menarik untuk<br />
diperbincangkan bukan hanya untuk memahami seberapa jauh tragedi<br />
1965-66 telah menciptakan berlapis-lapis korban, tetapi juga untuk<br />
memahami bagaimana kultur patriarkhi telah membentuk beragam<br />
memori di kalangan perempuan yang terkena dampak tidak langsung<br />
dari tragedi tersebut. Beragam memori itu termanifestasikan dalam<br />
berbagai respons terhadap situasi masa kini, situasi di mana menuturkan<br />
penderitaan masa lalu secara publik telah menjadi sesuatu yang mungkin,<br />
walau terkadang bukannya tanpa resiko.<br />
Berikut ini pengalaman tiga istri mantan tahanan politik (tapol)<br />
yang mengalami jalan hidup yang berbeda dalam bertahan hidup, bukan<br />
hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial. Untuk memudahkan<br />
penuturan, ketiga istri itu saya sebut Bu Surti, Bu Siti, dan Bu Sri.<br />
Kisah Bu Surti<br />
Bu Surti adalah istri seorang tentara berpangkat rendah. Suaminya<br />
ditahan selama empat belas tahun karena menjadi bagian dari resimen<br />
yang dianggap mendukung Gerakan 30 September pimpinan Letkol.<br />
Untung Samsuri. Ketika suaminya mulai ditahan, dia harus menghidupi<br />
dirinya dan kedua anaknya yang masing-masing putra berusia enam<br />
tahun dan putri berusia empat tahun.<br />
Pada mulanya Bu Surti bekerja sebagai buruh pada industri<br />
rumahan yang memproduksi tepung beras. Dia harus bekerja dari subuh<br />
hingga petang, sementara kedua anaknya dia tinggal di rumah dan dijaga<br />
oleh tetangga yang masih ada hubungan kerabat dengannya. Selama<br />
sepuluh tahun dia menjalani kerutinan hidup seperti itu. Begitulah dia<br />
dan kedua anaknya bisa bertahan hidup. Bahkan lebih dari itu, dia<br />
mampu menyekolahkan anak sulungnya ke sekolah menengah atas,<br />
42
sementara anak keduanya ke sekolah menengah pertama.<br />
Tetapi dalam bayangannya, problem biaya pendidikan pasti akan<br />
menghadang kelak ketika anak sulungnya lulus sekolah menengah atas<br />
dan hendak melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk mengantisipasi hal<br />
itu, alih-alih terus-menerus menjadi buruh, Bu Surti mulai merintis<br />
usaha sendiri. Dengan modalnya yang kecil plus pinjaman lunak dari<br />
bekas majikannya, dia pun membuka usaha pembuatan tepung beras<br />
sendiri. Usahanya ini ternyata berkembang. Dari semula mempekerjakan<br />
tiga orang, tiga tahun kemudian dia mempekerjakan sepuluh orang. Dan<br />
dengan bisnisnya yang berkembang ini dia pun tidak kesulitan<br />
membiayai pendidikan anak sulungnya ke perguruan tinggi, dan anak<br />
keduanya ke sekolah menengah atas.<br />
Pada tahun 1979 suami Bu Surti dilepas dari rumah tahanan.<br />
Istilah ”dibebaskan” sebenarnya jelas tidak tepat, sebab para mantan<br />
tapol 'Peristiwa 1965' itu senantiasa diawasi gerak-geriknya oleh aparat<br />
keamanan, serta sangat terbatas ruang gerak mereka. Pelepasan ini tentu<br />
merupakan hal yang membahagiakan Bu Surti dan kedua anaknya.<br />
Mereka kini kembali utuh sebagai sebuah keluarga.<br />
Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama.<br />
Keberhasilan Bu Surti dalam berjuang mempertahankan hidup dan<br />
bahkan sukses merintis usaha sendiri ternyata tidak disambut dengan<br />
kebanggaan oleh suaminya, tetapi malah dipandang sebagai<br />
pengambilalihan atas otoritasnya sebagai kepala keluarga. Dalam situasi<br />
di mana ekonomi keluarga bertumpu pada usaha istrinya, dia merasa<br />
kehilangan wibawa sebagai kepala keluarga. Dia merasa tidak mampu<br />
meraih kembali wibawa masa lalu, masa sebelum dia di-tapol-kan, di<br />
mana dia bisa dan biasa memerintah istrinya seperti halnya<br />
komandannya memerintah dirinya. Pendek kata, wibawa dirinya sebagai<br />
kepala keluarga dia taruh lebih penting daripada keberhasilan istri dan<br />
kedua anaknya dalam berjuang menyambung hidup.<br />
Dalam situasi di mana suaminya tak sanggup menatap realitas<br />
yang telah berubah, hubungan Bu Surti dengan suaminya semakin sering<br />
diwarnai ketegangan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk hidup<br />
secara terpisah, tetapi tidak bercerai. Suaminya hidup bersama putranya,<br />
sementara Bu Surti bersama putrinya.<br />
Bagi Bu Surti, pengalaman pahit yang mengendap dalam<br />
ingatannya bukanlah saat-saat dimana dia harus bekerja keras selama<br />
43<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
FOKUS<br />
Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi<br />
bertahun-tahun untuk mempertahankan hidup dirinya dan kedua<br />
anaknya, tetapi saat suaminya tidak mampu melihat realitas yang telah<br />
berubah. Ingatan atas sikap dan perilaku suaminya selepas dari penjara<br />
itu senantiasa dia coba simpan untuk dirinya. Sebab, setiap kali ingatan<br />
itu muncul, dia tak kuasa menahan kekecewaannya yang mendalam<br />
terhadap suaminya. Dalam kekecewaan semacam itu, dia pun bertanyatanya<br />
apakah setiap suami selalu ingin menang sendiri, seperti suaminya<br />
itu.<br />
Kisah Bu Siti<br />
Bu Siti adalah istri seorang guru sekolah menengah atas. Dia mempunyai<br />
dua anak, yang masing-masing putra berusia tiga setengah tahun dan<br />
putri berusia satu setengah tahun ketika suaminya mulai ditahan pada<br />
akhir Oktober 1965. Pada mulanya dia adalah seorang ibu rumah tangga.<br />
Tetapi ketika suaminya mulai dipenjara, dengan modal pinjaman dari<br />
orang tuanya dia mencoba membuka warung kelontong di bagian teras<br />
rumahnya. Usaha itu dia kerjakan sambil mengasuh kedua anaknya yang<br />
masih balita.<br />
Pada suatu hari ada seorang polisi datang hendak membeli<br />
sesuatu di warung kelontong Bu Siti. Pada mulanya dia hanya hendak<br />
membeli sesuatu. Tetapi ketika Pak Polisi itu tahu bahwa suami pemilik<br />
warung kelontong tersebut tengah menjadi tahanan politik, dia pun<br />
bersimpati. Bermula dari rasa simpati, polisi itu pun mulai menaruh hati.<br />
Semenjak itu Pak Polisi tersebut semakin sering berbelanja di warung<br />
kelontong Bu Siti. Dalam perkembangan selanjutnya, dia datang bukan<br />
untuk membeli sesuatu, tetapi sekedar bertandang untuk mengobrol<br />
kesana-kemari.<br />
Bu Siti bukannya tidak tahu kalau Pak Polisi tersebut telah jatuh<br />
hati kepadanya. Tetapi, dalam situasi di mana dia tidak tahu, dan tak<br />
seorang pun tahu sampai kapan suaminya akan berada di tahanan, dia<br />
pun bingung. Di satu sisi dia memang mendambakan seorang laki-laki<br />
yang selain bisa membantu upaya untuk bertahan hidup juga bisa<br />
menciptakan rasa aman bagi dirinya dan kedua anaknya yang masih<br />
balita, sementara di hadapannya telah ada seorang laki-laki yang<br />
menawarkan diri sebagai pengganti suaminya.<br />
Di sisi lain, Bu Siti tahu kalau suaminya masih hidup. Hanya saja<br />
dia tidak tahu sampai kapan suaminya akan berada di tahanan. Dalam<br />
44
situasi penuh kebimbangan itu dia hamil. Tanpa seizin suaminya yang<br />
masih berada di tahanan, Bu Siti membiarkan Pak Polisi itu hidup<br />
bersama dirinya dan kedua anaknya, tanpa ikatan perkawinan dengan<br />
dirinya.<br />
Menjelang akhir 1969 tersiar kabar akan terjadi pelepasan besarbesaran<br />
para tapol yang termasuk kategori golongan C. Bu Siti pun<br />
bertanya-tanya apakah suaminya termasuk yang akan segera dilepaskan.<br />
Ternyata betul. Dia mendapat informasi dari kerabat suaminya bahwa<br />
suaminya akan dilepaskan pada akhir 1969. Lalu Bu Siti meminta<br />
pengertian kepada Pak Polisi itu agar pergi meninggalkan dirinya dan<br />
ketiga anaknya—termasuk anak hasil hubungan tidak sah<br />
dengannya—karena suaminya akan segera pulang.<br />
Ketika suaminya pulang, Pak Polisi itu memang telah pergi.<br />
Tetapi kini suami Bu Siti mendapati tiga anak di rumahnya, di mana anak<br />
ketiga itu bukan hasil hubungan antara dirinya dengan istrinya. Suami Bu<br />
Siti tidak terkejut akan hal itu. Sebab, sewaktu masih di tahanan dia sudah<br />
mendengar kabar tentang perselingkuhan istrinya dari tetangga yang<br />
sering dititipi kiriman makanan untuk dirinya. Mendengar kabar tak<br />
sedap itu, suami Bu Siti langsung menderita depresi berat, bahkan dia<br />
hampir—dalam istilah di kalangan para tapol—terkena ”PA” atau<br />
pikiran abnormal.<br />
Suami Bu Siti waktu itu disadarkan oleh teman-temannya<br />
sesama tapol bahwa apa yang terjadi dengan keluarga di rumah sungguh<br />
berada di luar kendali mereka. Bahkan apa yang terjadi pada mereka pun<br />
juga tidak berada dalam kendali mereka. Semuanya itu harus diterima<br />
sebagai kenyataan. Dan kini, selepas dari penjara, dia langsung<br />
menghadapi kenyataan tersebut.<br />
Suami Bu Siti sebenarnya rela menghadapi kenyataan istrinya<br />
telah berselingkuh sewaktu dia di penjara, dan dari hasil perselingkuhan<br />
itu lahir seorang anak. Dia memaafkan perbuatan istrinya walau istrinya<br />
tidak pernah meminta maaf. Tetapi masalahnya, istrinya bukan hanya<br />
tidak pernah meminta maaf, melainkan malah menyalahkan dirinya. Bu<br />
Siti mengatakan bahwa dia telah berselingkuh dan kemudian<br />
membuahkan seorang anak adalah akibat suaminya ditahan, dan<br />
penahanan dirinya karena dia ikut-ikutan berpolitik. Dengan kata lain,<br />
bagi Bu Siti, sumber segala kenyataan pahit itu adalah 'politik'.<br />
Itu sebabnya semenjak suaminya dilepas dari tahanan, Bu Siti<br />
45<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
FOKUS<br />
Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi<br />
selalu mengontrol segala hal yang dibaca, didengar, ditonton dan<br />
dibicarakan oleh suaminya. Tindakan ini dilakukan Bu Siti agar sang<br />
suami tidak mengikuti perkembangan situasi politik. Suaminya dilarang<br />
membaca surat kabar, dilarang mendengarkan atau menonton siaran<br />
berita radio maupun televisi. Begitu pula suaminya juga dia kontrol agar<br />
jangan terlalu sering bertemu dan berbicara dengan kakak iparnya, yang<br />
sejak kecil selalu menjadi panutan suaminya sampai dalam soal ideologi<br />
politik. (Kakak iparnya itu juga ditahan dan dilepaskan pada akhir 1969).<br />
Pendek kata, Bu Siti mengendalikan hampir segala gerak langkah<br />
suaminya, sesuatu yang tidak terjadi sebelum suaminya ditahan.<br />
Tetangga dan kerabat dekatnya bukannya tidak melihat adanya<br />
perubahan relasi komunikasi antara Bu Siti dan suaminya. Dengan sinis<br />
mereka melihat hal itu sebagai upaya Bu Siti menutupi kesalahannya. Bu<br />
Siti bukannya tidak sadar akan sinisme mereka itu. Hal itu tampak dalam<br />
sikap tertutup terhadap tetangga dan kerabat dekatnya. Kalau toh ada<br />
komunikasi, biasanya komunikasi itu penuh kepuraan-puraan atau<br />
sekadar basa-basi. Bu Siti hingga kini cenderung mengurung diri.<br />
Suaminya pun terkurung dalam pengurungan diri istrinya itu.<br />
Kisah Bu Sri<br />
Sama dengan Bu Surti dan Bu Siti, Bu Sri adalah seorang ibu rumah<br />
tangga sebelum suaminya ditahan. Dia memiliki empat anak, yang terdiri<br />
dari dua putri dan dua putra. Ketika suaminya masuk penjara pada akhir<br />
Oktober 1965, anaknya yang sulung berusia tujuh tahun, sedangkan<br />
yang bungsu setengah tahun.<br />
Berbeda dari pengalaman hidup Bu Surti dan Bu Siti,<br />
pengalaman hidup Bu Sri sewaktu ditinggal suaminya di penjara relatif<br />
tidak berliku-liku. Untuk menyambung hidup dirinya dan keempat<br />
anaknya dia sepenuhnya ditopang oleh orang tuanya dan mertuanya.<br />
Dua putrinya dia titipkan di rumah mertuanya, sedangkan dia bersama<br />
kedua putranya tinggal bersama orang tuanya. Selain menyandarkan<br />
pada uang pensiun ayahnya, Bu Sri juga bersandar pada hasil kerja<br />
ibunya, yang mulai membuka usaha jual beli pakaian bekas semenjak<br />
ketempatan anak dan kedua cucunya. Bu Sri sendiri sepenuhnya<br />
mengurusi kedua putranya yang masih balita.<br />
Setelah suaminya dilepas dari penjara pada akhir 1969, Bu Sri<br />
dan keempat anaknya serta suaminya kembali hidup bersama. Mereka<br />
46
tinggal di rumah mertua Bu Sri. Mereka hidup bertani, dan menjalani<br />
taraf hidup yang serba pas-pasan, sampai akhirnya suami Bu Sri<br />
mendapatkan pekerjaan di Jakarta kembali pada profesi semula, yaitu<br />
guru.<br />
Kisah hidup Bu Sri barangkali yang paling lazim terjadi di<br />
kalangan para istri mantan tapol. Artinya, kemampuan untuk bertahan<br />
hidup sewaktu suami di penjara sangat bergantung pada topangan<br />
ekonomi orang tua atau kerabat dekat, bahkan sampai pada masalah<br />
tempat tinggal. Boleh jadi kondisi semacam inilah yang membuat orang<br />
seperti Bu Sri tidak perlu 'terjatuh' pada situasi seperti yang dialami Bu<br />
Siti, dan juga terhindar dari pengalaman seperti yang dialami Bu Surti.<br />
Korban Tidak Langsung dan Kultur Patriarkhi<br />
Para istri tapol seperti dituturkan di atas jelas bukan korban langsung dari<br />
kekerasan politik massal 1965-66. Mereka sendiri tidak pernah<br />
diinterogasi dan dipenjara. Mereka juga tidak mengalami ancaman fisik<br />
dari pihak manapun. Namun, akibat yang mereka (dan anak-anak<br />
mereka) alami sebagai dampak dari ditahannya suami mereka jelas tidak<br />
bisa diremehkan. Masalah yang langsung menghadang mereka jelas<br />
adalah problem berjuang untuk menyambung hidup.<br />
Namun seperti terlihat dalam kasus Bu Surti, keberhasilan dalam<br />
berjuang untuk survival ternyata tidak mendapat apresiasi sama sekali<br />
dari suaminya. Keberhasilan istri untuk survival dipandang sebagai<br />
ancaman buat wibawa suami. Dan itulah momen yang traumatis bagi<br />
istri, karena kemudian dia kehilangan rasa hormat kepada suami, bahkan<br />
mungkin juga rasa hormat kepada laki-laki.<br />
Keberhasilan seorang istri untuk bertahan hidup seperti lumer<br />
dan nyaris tak berarti ketika bertabrakan dengan tembok kultur<br />
patriarkhi. Padahal, dengan keberhasilan itu sebenarnya yang dituntut<br />
adalah kesetaraan, bukan pembalikan relasi kuasa antara suami dan istri.<br />
Dalam kasus Bu Siti, tampak bahwa bayangan bagaimana masyarakat<br />
nyaris tidak menyisakan ruang untuk memahami 'perselingkuhannya'<br />
telah membuat Bu Siti menempatkan suaminya, orang terdekatnya,<br />
sebagai sasaran pemberontakannya terhadap kultur patriarkhi. Ongkos<br />
yang harus dia bayar adalah isolasi yang dilakukan lingkungan<br />
terdekatnya atas dirinya.<br />
Sedangkan dalam kasus Bu Sri, boleh dikatakan tidak ada<br />
47<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
FOKUS<br />
Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi<br />
pengalaman traumatis dengan suami maupun lingkungan tetangga serta<br />
kerabatnya, karena sejak awal dia tetap patuh berada dalam kultur<br />
patriarkhi.<br />
Ketiga kasus di atas membentuk politik memori yang berbeda.<br />
Bagi Bu Surti, ingatan yang kelam dan karena itu menjadi beban<br />
bukanlah saat-saat dia harus bekerja keras menghidupi diri dan kedua<br />
anaknya, tetapi justru saat-saat sesudah suaminya dilepas dari tahanan.<br />
Bagi Bu Siti, momen yang kelam bukanlah ketika dia harus<br />
bekerja sendirian sembari mengasuh kedua anaknya yang masih balita,<br />
tetapi ketika perselingkuhannya dengan orang lain telah membuahkan<br />
seorang anak, persis ketika mulai terdengar kabar akan adanya pelepasan<br />
para tapol secara besar-besaran pada akhir 1969. Di situ dia dihadapkan<br />
pada situasi serba tidak pasti, sementara melalui cibiran, masyarakat telah<br />
menghukumnya. Ketika suaminya pulang, dia tabrak tembok kultur<br />
patriarkhi itu dengan menjadikan suaminya sebagai sasaran antaranya.<br />
Tetapi, justru karena itu masyarakat semakin menghukumnya, dengan<br />
cara mengisolasinya dalam pergaulan sosial.<br />
Pada kasus Bu Sri yang sejak awal berada dalam posisi submisif<br />
pada kultur patriarkhi, perjalanan hidupnya relatif tidak berliku. Tidak<br />
seperti Bu Surti dan Bu Siti, bagi Bu Sri tidak ada pengalaman masa lalu<br />
yang harus dia taruh di bawah karpet. Masa lalu suami sebagai tapol<br />
bukanlah sebuah aib dalam keluarga. Bahkan karena dia tidak 'terjatuh'<br />
pada pengalaman seperti yang terjadi pada Bu Siti itu merupakan sesuatu<br />
yang membanggakannya. Tanpa disadari, dengan sikap semacam ini dia<br />
sebetulnya telah turut merepoduksi 'moralitas' dalam kultur patriarkhi.<br />
Dengan ketiga kisah di atas tampak bahwa kekerasan politik<br />
massal yang terjadi dalam masyarakat dengan kultur patriarkhi yang<br />
kental menjadikan perempuan sebagai korban tidak langsung yang efek<br />
traumatisnya mungkin lebih panjang daripada laki-laki yang menjadi<br />
korban langsung. Hal ini antara lain tampak pada sikap tidak peduli di<br />
kalangan para istri mantan tapol terhadap perubahan politik semenjak<br />
Suharto jatuh, di mana para mantan tapol kini dimungkinkan untuk<br />
mengartikulasikan memori mereka secara publik. Bila sebagian mantan<br />
tapol perempuan (apalagi laki-laki) telah menuturkan penderitaan<br />
mereka melalui memoar-memoar atau otobiografi, para istri mantan<br />
tapol seperti Bu Surti, apalagi Bu Siti, terus hidup bersama pengalamanpengalaman<br />
traumatis itu.<br />
48
DISKURSUS
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran<br />
HAM Berat di Indonesia dan<br />
*)<br />
Negara-negara Lain<br />
Zainal Abidin<br />
Abstract<br />
A number of countries have succeeded in dealing with their past gross human<br />
rights violations by using various methods that were crystallized in two models:<br />
through court and the establishment of truth commission. A method was picked<br />
based on the political context of each country. But in Indonesia, the two options<br />
are on threshold of failure.<br />
Keywords: Human Rights Tribunal, Truth Commission, Gross Violence of<br />
Human Rights<br />
A. Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia<br />
Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia<br />
sebenarnya sudah sangat jelas berdasarkan sejumlah instrumen hukum<br />
yang telah dibentuk, di antaranya berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000<br />
tentang Pengadilan HAM. Penyelesaian tersebut, pada intinya berpijak<br />
pada dua mekanisme, yakni terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di<br />
masa lalu melalui mekanisme penghukuman pengadilan HAM adhoc<br />
dan melalui mekanisme KKR, sedangkan pelanggaran HAM berat yang<br />
terjadi setelah pembentukan UU Pengadilan HAM, dilakukan melalui<br />
1<br />
Pengadilan HAM.<br />
Sejarah pembentukan kedua mekanisme penyelesaian tersebut<br />
* Sebagian besar dalam tulisan ini juga dimuat dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Edisi 11 Volume 1 Tahun<br />
2012 yang diterbitkan oleh Dirjen HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia<br />
1. Pembedaan ini merujuk pada Pasal 4, Pasal 43 dan Pasal 47 UU No. 26/2000. Pasal 43 menyebut<br />
pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum adanya UU No. 26/2000 dilakukan dengan Pengadilan<br />
HAM ad hoc, dan Pasal 47 menyebutkan menyebut pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum<br />
adanya UU No. 26/2000 tidak tertutup kemungkinan dapat diselesaikan melalui KKR.<br />
51
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
berlangsung panjang dan berliku. Gagasan pembentukan KKR<br />
misalnya, sebagai salah satu mekanisme untuk memper-<br />
tanggungjawabkan pelanggaran HAM masa lalu, telah muncul sejak<br />
2<br />
reformasi mulai bergulir tahun 1998. Pembentukan KKR mendapatkan<br />
basis legalnya dan menunjukkan komitmen negara yang kuat untuk<br />
menyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, ketika Majelis<br />
Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR No. V<br />
Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan. Ketetapan<br />
tersebut menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM masa lalu, dan<br />
menyatakan bahwa di masa lalu telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan<br />
dan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu diungkap demi<br />
menegakkan kebenaran. Ketetapan tersebut juga merekomendasikan<br />
3<br />
untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional.<br />
”Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai<br />
lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan<br />
dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan<br />
kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan<br />
pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan<br />
ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan<br />
melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai<br />
bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat<br />
dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf,<br />
perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain<br />
yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa<br />
4<br />
dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.”<br />
UU Pengadilan HAM mengatur mekanisme pengadilan untuk<br />
memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam<br />
pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan<br />
5<br />
terhadap kemanusiaan. Terhadap kejahatan-kejahatan yang masuk<br />
kategori pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000,<br />
6<br />
dilakukan melalui pengadilan HAM ad hoc.<br />
2 Munculnya gagasan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman negara lain misalnya di Afrika Selatan dan<br />
sejumlah negara di Amerika Latin. Lihat Progress Report, ”Pembentukan Komisi Kebenaran dan<br />
Rekonsiliasi” ELSAM, 27 Januari 2006.<br />
3. Lihat Ketetapan MPR No. V/2000.<br />
4. Ketetapan MPR No. V/2000, Hal. 8.<br />
5. Lihat pasal 7, 8 dan 9 UU No. 26/2000. Untuk melengkapi landasan hukum pengadilan HAM, pada tahun<br />
2002, pemerintah menerbitkan 2 Peraturan Pemerintah (PP); 1) PP No. 2/2002 tentang Tata Cara<br />
Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM yang Berat dan PP No. 3/2002 tentang<br />
Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.<br />
6. Lihat pasal 43 UU No. 26/2000.<br />
52
UU juga menyebut bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi<br />
sebelum berlakunya UU ini tidak menutup kemungkinan<br />
7<br />
penyelesaiannya dilakukan oleh KKR yang dibentuk melalui UU.<br />
Berdasarkan UU tersebut, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap<br />
8<br />
kemanusiaan, yang termasuk dalam ”the most serious crimes” dan<br />
merupakan kejahatan internasional, akan dapat diadili di Pengadilan<br />
Indonesia.<br />
Komitmen adanya pengadilan HAM dan KKR juga dijanjikan<br />
dibentuk di Papua. Melalui UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi<br />
Khusus Papua, negara berjanji kepada rakyat Papua tentang<br />
pertanggungjawaban berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua<br />
melalui dua instrumen yaitu Pengadilan HAM dan KKR. UU tersebut<br />
menyatakan KKR dilakukan untuk ”melakukan klarifikasi sejarah dan<br />
merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi” dalam<br />
9<br />
rangka menjaga persatuan bangsa.<br />
Pada tahun 2004, terbentuk UU No. 27 tahun 2004 tentang<br />
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang mengatur tentang<br />
pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu, mekanisme<br />
10<br />
penyelesaian di luar pengadilan dan rehabilitasi kepada korban.<br />
Namun, selama tahun 2004-2006 pembentukannya sangat lambat, dan<br />
11<br />
Pemerintah hanya berhasil melakukan proses seleksi anggota KKR.<br />
Pada tahun 2006, komitmen untuk penyelesaian pelanggaran<br />
HAM masa lalu juga dinyatakan dalam konteks pelanggaran HAM berat<br />
di Aceh. UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,<br />
memandatkan adanya pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di<br />
12<br />
Aceh.<br />
Pada tahun 2006 pula, terbentuk UU No. 13 tahun 2006 tentang<br />
Perlindungan Saksi dan Korban, yang dapat dikatakan sebagai regulasi<br />
7. Lihat pasal 47 UU No. 26/2000.<br />
8. Istilah ”the most serious crimes ” merujuk pada istilah yang dinyatakan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998.<br />
Sebagai catatan, penjelasan pasal 7 UU No. 26/2000 menyatakan ”Kejahatan genosida dan kejahatan<br />
terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan Rome Statute of The Intemational Criminal Court”<br />
(Pasal 6 dan Pasal 7).<br />
9. Lihat Pasal 44 UU No. 21/2001.<br />
10. DPR dan Pemerintah pada saat itu, setelah melalui perdebatan yang panjang selama kurang lebih 16<br />
bulan, akhirnya mengesahkan RUU KKR menjadi UU, meski disadari adanya kelemahan dalam<br />
pengaturannya. Sejumlah organisasi masyarakat sipil memandang ada kelemahan dalam UU KKR, yakni<br />
kurang sesuai dengan prinsip-prinsip berdasarkan hukum HAM internasional.<br />
11. Lihat Progress Report, ”Pandangan Elsam atas Pembentukan KKR Terlambat Dua Tahun; Penundaan<br />
Pembentukan KKR: Pengingkaran atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di<br />
Masa Lalu”, ELSAM, 2006.<br />
12. Lihat pasal 228 dan 229 UU No.11/2006.<br />
53<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
yang memperkuat mekanisme Pengadilan HAM. UU tersebut mengatur<br />
tentang perlindungan saksi dan korban yang lebih baik, dan memberikan<br />
penguatan pengaturan tentang kompensasi dan restitusi, termasuk hal<br />
atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial kepada korban<br />
13<br />
pelanggaran HAM berat. UU tersebut juga memandatkan<br />
pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<br />
Namun, pada tahun 2006 pula, MK membatalkan UU No. 27<br />
Tahun 2004 tentang KKR, karena dianggap bertentangan dengan<br />
Konstitusi, hukum HAM internasional dan hukum humaniter<br />
internasional. MK kemudian merekomendasikan untuk membentuk<br />
UU KKR baru sesuai dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang<br />
berlaku secara universal, serta mendorong negara untuk melakukan<br />
15<br />
rekonsiliasi melalui kebijakan politik.<br />
”Dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan<br />
hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup<br />
upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya<br />
rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain<br />
dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum<br />
(undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM<br />
yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi<br />
melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara<br />
16<br />
umum.”<br />
Dari kerangka hukum sebagaimana disebutkan di atas, konsep<br />
dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat telah jelas dan<br />
masih menggunakan dua mekanisme, yaitu melalui jalur pengadilan dan<br />
KKR. MK, meski membatalkan UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR,<br />
tetap merekomendasikan pembentukan UU KKR baru dan melalukan<br />
rekonsilasi.<br />
Justru pada tataran implementasi kedua mekanisme tersebut<br />
yang mengalami hambatan dan stagnasi hingga saat ini. Dari sisi<br />
penyelesaian melalui pengadilan, tercatat hanya dua kasus yang telah<br />
dibawa ke pengadilan HAM adhoc, yakni perkara pelanggaran HAM<br />
13. Lihat pasal 5 dan pasal 7 UU No. 13/2006. Kemudian juga muncul PP No. 44/2008 tentang Pemberian<br />
Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.<br />
14. Lihat Pasal 11-27 dan Pasal 45 UU No. 13/2006.<br />
15. Lebih lengkap tentang argumen MK dan respon ELSAM atas keputusan tersebut bisa dilihat di Briefing<br />
Paper, ”Making Human Rights A Constitutional Rights, A Critique of Constitutional Court's Decision on the Judicial<br />
Review of the Truth and Reconciliation Commission Act and Its Implication for Settling Past Human Rights Abuses”,<br />
ELSAM, 2007.<br />
16. Lihat Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, hal. 131.<br />
54<br />
14
erat Timor-Timur pada tahun 1999 dan Tanjung Priok tahun 1984, dan<br />
sebuah Pengadilan HAM untuk kasus Abepura tahun 2000.<br />
Dalam ketiga pengadilan tersebut, sebagaimana disebutkan<br />
pada bagian atas, proses pengadilan bisa dikatakan gagal menghadirkan<br />
keadilan. Justru sejumlah inisiatif korban dan masyarakat sipil melalui<br />
17<br />
jalur pengadilan maupun upaya lainnya yang lebih maju.<br />
Demikian pula dengan berbagai penyelidikan yang telah<br />
dilakukan oleh Komnas HAM, diantaranya Kasus Trisaksi, Semanggi I<br />
dan II, Kasus Talangsari 1989, dan Kasus Penghilangan Paska 1997-<br />
1998 yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung<br />
dan Presiden. Sejumlah argumen dari Kejaksaan Agung untuk tidak<br />
menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM diantaranya untuk<br />
pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 belum ada<br />
rekomendasi dari DPR dan masih ada berbagai hal yang harus dilengkapi<br />
18<br />
oleh Komnas HAM.<br />
Namun, alasan-alasan Kejaksaan Agung tidak konsisten.<br />
Misalnya, dalam perkara Penghilangan Paksa Tahun 1997-1998 yang<br />
telah mendapatkan rekomendasi DPR untuk membentuk Pengadilan<br />
HAM adhoc tidak dilaksanakan hingga saat ini. Padahal, pada 28 Oktober<br />
2009, DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk<br />
19<br />
Pengadilan HAM adhoc untuk kasus Penghilangan Paksa 1997-1998.<br />
Presiden juga hingga kini belum menerbitkan keputusan untuk adanya<br />
20<br />
pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa tersebut.<br />
B. Pelanggaran HAM yang Berat: Pengalaman Internasional dan<br />
Berbagai Negara<br />
Banyak negara telah melakukan penyelesaian kejahatan masa lalunya<br />
dengan metode yang bermacam-macam. Negara-negara tersebut<br />
cenderung pada mulanya dipimpin oleh rezim pemerintahan yang<br />
17. Lihat catatan Elsam, ”Pemetaan Singkat Kebijakan Reparasi dan Implementasinya di Indonesia”, 3<br />
Oktober 2011. Lihat juga, Zainal Abidin, ”Jalan Berliku Meraih Keadilan”, Bulletin Asasi, Elsam, edisi<br />
Januari-Februari 2012. Dokumen dapat diakses di www.elsam.or.id<br />
19. Mengenai perdebatan tentang Pembentukan Pengadilan HAM dapat dilihat dalam Jurnal Dignitas,<br />
”HAM dan Realitas Transisional”, Elsam, 2011.<br />
20. Terdapat 4 rekomendasi dari DPR yaitu yaitu pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk menangani<br />
kasus orang hilang, memberikan kompensasi kepada keluarga korban, pencarian 13 orang hilang yang<br />
belum ditemukan dan ratifikasi Konvensi HAM PBB tentang penghilangan orang secara paksa. Lihat<br />
juga Kertas Posisi Keadilan Transisional, ”Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: Berlanjutnya<br />
Penyangkalan Negara atas Hak-Hak Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara<br />
Paksa Periode 1997-1998”, Elsam, 17 Februari 2011. Lihat juga ASASI, ”Penghilangan Paksa 1997-1998:<br />
Rekomendasi Tanpa Atensi, Edisi November-Desember 2011. Dokumen dapat diakses di<br />
www.elsam.or.id<br />
55<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
otoriter yang sangat kuat mengontrol kekuasaan. Dengan latar belakang<br />
politik yang beragam, pola penyelesaian kejahatan masa lalu negaranegara<br />
tersebut juga berbeda-beda. Di bawah ini merupakan pola<br />
implementasi penyelesaian kejahatan masa lalu yang telah dilakukan oleh<br />
negara-negara lain:<br />
1. Praktik Penghukuman Melalui Pengadilan<br />
Sejarah penghukuman terhadap terjadinya berbagai kejahatan serius<br />
telah berlangsung lama. Sejumlah pengadilan Internasional telah digelar,<br />
disamping berbagai pengadilan untuk kejahatan-kejahatan serius yang<br />
dilakukan dalam tingkat domestik. Di antara yang pertama adalah<br />
Pengadilan Leipzig tahun 1921, untuk mengadili para penjahat perang<br />
Jerman pada perang dunia pertama, yang dilakukan oleh Mahkamah<br />
21<br />
Agung Jerman berdasarkan Perjajian Versailles.<br />
Kemudian, praktik proses penghukuman terhadap para pelaku<br />
kejahatan-kejahatan yang serius tersebut berlanjut, di antaranya<br />
sejumlah pengadilan yang terkenal, yakni; pengadilan kejahatan<br />
internasional setelah perang dunia, yaitu ”International Military Tribunal ”<br />
(IMT) atau dikenal sebagai ”Nuremberg Tribunal” pada tahun 1945 dan<br />
”International Military Tribunal for the Far East (IMTFE)” atau dikenal<br />
22<br />
sebagai ”Tokyo Tribunal” pada 1946. Pengadilan Nurenberg mengadili<br />
24 para pimpinan Nazi yang didakwa dengan; turut serta dalam suatu<br />
perencanaan atau konspirasi untuk melaksanakan kejahatan terhadap<br />
perdamaian (crime against peace), merencanakan, memprakarsai, dan<br />
mengadakan peperangan agresi militer dan ataupun kejahatan lainnya<br />
terhadap perdamaian, melakukan kejahatan perang (war crime) dan<br />
kejahatan kemanusiaan. Sementara Pengadilan Tokyo mendakwa 28<br />
orang yang kebanyakan terdiri dari pejabat militer dan pemerintahan<br />
Jepang dengan dakwaan terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan<br />
23<br />
terhadap kemanusiaan.<br />
Kemudian setelah usai perang dingin, menghadapi kekejaman<br />
21. Tobias Lock dan Julia Riem, ”Judging Nurenberg: The Laws, The Rallies, The Trial”, Dokumen dapat diakses di<br />
http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol06No12/PDF_Vol_06_No_12_1819-1832_v<br />
Developments_LockRiem.pdf<br />
22. Pembentukan IMT didasarkan pada insiatif sekutu yang memenangkan perang untuk mengadili para<br />
pemimpin Nazi-Jerman, baik sipil maupun militer, sebagai penjahat perang dengan terlebih dahulu<br />
dituangkan dalam London Agreement tanggal 8 Agustus 1945. Sedangkan IMTFE dibentuk berdasarkan<br />
Proklamasi Panglima Tertinggi Tentara Sekutu Jenderal Douglas MacArthur pada 1946.<br />
23. http://cnd.org/mirror/nanjing/NMTT.html<br />
56
yang terjadi di Bekas Negara Yugoslavia dan Rwanda dibentuk<br />
Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia atau<br />
”the International Criminal Tribunal for fomer Yugoslavia (ICTY)” dan atau<br />
Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda ”the International<br />
24<br />
Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)”.<br />
ICTR merupakan pengadilan bentukan PBB untuk mengadili<br />
para pelaku kejahatan perang yang terjadi selama konflik Balkan pada<br />
tahun 1990an. Pengadilan ini telah mendakwa lebih dari 160 pelaku,<br />
termasuk kepala negara, perdana menteri, pimpinan militer, pejabat<br />
pemerintah, dan lainnya dengan tuduhan atas tindakan pembunhan,<br />
penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, perusakan properti dan<br />
25<br />
kejahatan-kejahatan lainnya sebagainya diatur dalam Statuta ICTY.<br />
Sementara ICTR, yang juga merupakan pengadilan bentukan PBB, yang<br />
berlokasi di Aruza Tanzania, mengadili para pelaku kejahatan genosida,<br />
kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum<br />
humaniter internasional lainnya atas peristiwa yang terjadi di Rwanda<br />
26<br />
pada tahun 1994, dan telah mendakwa sekitar 72 pelaku.<br />
Pada tahun 1998, masyarakat Internasional sepakat membentuk<br />
Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang<br />
27<br />
didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998. Semangat pembentukan<br />
ICC sebagaimana disebutkan dalam Statuta Roma 1998 diantaranya<br />
untuk memerangi impunitas dan bahwa kejahatan genosida, kejahatan<br />
terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagai<br />
”the most serious crimes of concern to the international community as a whole”.<br />
Statuta Roma mengatur kewenangan untuk mengadili<br />
kejahatan-kejahatan paling serius (the most serious crimes), yaitu kejahatan<br />
genosida (the crime of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes<br />
against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (the<br />
28<br />
crime of aggression). Berbeda dengan pengadilan internasional<br />
sebelumnya yang bersifat ad hoc, Mahkamah Pidana Internasional<br />
29<br />
merupakan pengadilan yang permanen.<br />
24. Kedua pengadilan ini juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kedua pengadilan<br />
dibentuk oleh lembaga yang sama, yaitu Dewan Keamanan PBB melalui sebuah resolusi. ICTR dibentuk<br />
berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.955, tanggal 8 November 1994 .<br />
25. http://www.icty.org/sid/3.<br />
26. http://www.unictr.org/AboutICTR/GeneralInformation/tabid/101/Default.aspx<br />
27. Statuta ini diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 negara yang berpartisipasi dalam ”United Nations<br />
Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court” di kota Roma,<br />
Italia<br />
28. Pasal 5 Statuta Roma 1998.<br />
29. Pasal 3(1) Statuta Roma.<br />
57<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
Sejak pendiriannya, ICC setidaknya telah memeriksa 16 kasus<br />
atas tujuh peristiwa yang terjadi di Uganda, Kenya, Kongo, Sudan,<br />
Afrika Tengah, Libya, dan Pantai Gading. Terdakwa pertama yang<br />
dijatuhi hukuman oleh ICC adalah Thomas Lubanga Dyilo dari Kongo,<br />
yang didakwa melakukan kejahatan perang, dimana dia diduga<br />
memerintahkan anak buahnya melakukan pelanggaran HAM yang<br />
massif, termasuk kekejaman etnis, pembunuhan, penyiksaan,<br />
pemerkosaan, mutilasi dan memaksa anak-anak untuk menjadi tentara.<br />
Lubaga Dyilo akhirnya dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dengan<br />
terbuktinya melakukan pemaksaan kepada anak-anak untuk menjadi<br />
30<br />
tentara.<br />
Pengalaman sejumlah pengadilan tersebut telah jelas<br />
memberikan pesan bahwa para pelaku kejahatan-kejahatan serius harus<br />
dibawa ke pengadilan dan diadili. Sejumlah instrumen HAM<br />
internasional telah dibentuk untuk memastikan adanya penghukuman<br />
bagi para pelaku kejahatan-kejahatan serius. Pelanggaran hak asasi<br />
manusia yang berat, misalnya genosida dan penyiksaan, juga telah diakui<br />
sebagai ”jus cogens” atau ”peremptory norms” yang karenanya pelaku<br />
kejahatan tersebut merupakan adalah musuh semua umat manusia (hostis<br />
humanis generis) dan penuntutan terhadap para pelakunya merupakan<br />
31<br />
kewajiban seluruh umat manusia (obligatio erga omnes).<br />
Hal ini juga berarti bahwa untuk kejahatan-kejahatan serius tidak<br />
diperkenankan adanya amnesti. Sejumlah dokumen PBB menyebutkan<br />
secara tegas bahwa amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku<br />
32<br />
pelanggaran HAM berat. Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB<br />
tahun 2004, dalam Point 3 menegaskan sebagai berikut:<br />
”…amnesties should not be granted to those who commit violations of<br />
human rights and international humanitarian law that constitute crimes,<br />
30. http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/<br />
31.Lihat ”Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity”<br />
(E/CN.4/2005/102/Add.1 08 Februari 2005).<br />
32. Lihat General Comment 20 Pasal 7 [Kovenan Hak Sipil dan Politik] menyatakan bahwa "that some States<br />
have granted amnesty in respect of acts of torture. Amnesties are generally incompatible with the duty of the States to<br />
investigate such acts” (General Comment 20 concerning Article 7, replaces General Comment 7 concerning Prohibition of<br />
Torture and Cruel Treatment or Punishment); lihat juga Laporan Sekjen PBB mengenai pembentukan<br />
Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone S/200/915), 4 Oktober 2000 dalam paragraph 22-24, Laporan<br />
Sekjen PBB tentang The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, (S/2004/616),<br />
23 Agustus 2004, Independent Study on Best Practices, Including Recommendations, to Assist States In Strengthening<br />
Their Domestic Capacity to Combat All Aspects Of Impunity (E/CN.4/2004/88).<br />
58
urges States to take action in accordance with their obligations under<br />
international law and welcomes the lifting, waiving, or nullification of<br />
33<br />
amnesties and other immunities”.<br />
Kewajiban untuk melakukan penghukuman ini, yang tertuang<br />
dalam sejumlah instrumen HAM internasional, juga yurisdiksi<br />
internasional, yaitu berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tertentu,<br />
mewajibkan untuk dituntut di dalam negeri, maupun memberikan<br />
kemungkinan pelaku pelanggaran tersebut dapat diproses di pengadilan<br />
di luar negeri. Hal ini misalnya dalam Konvensi Pencegahan dan<br />
Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (The Convention on the<br />
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), yang memberikan<br />
kewajiban utama untuk penuntutan pelaku kepada negara dimana<br />
pelanggaran terjadi, tetapi juga menentukan bahwa pengadilan lainnya,<br />
34<br />
termasuk pengadilan internasional, memiliki yurisdiksi.<br />
35<br />
Demikian juga dengan Konvensi Anti Penyiksaan, yang<br />
menentukan adanya yurisdiksi internasional atas kejahatan penyiksaan<br />
yang lebih luas dan spesifik. Menurut Konvensi ini, negara-negara<br />
mempunyai kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili seorang<br />
yang diduga melakukan tindakan penyiksaan.<br />
Di Amerika Serikat, sebuah produk hukum yang disebutkan<br />
sebagai Alien Tort Claims Act (1789) memberikan peluang untuk<br />
kesalahan atas kejahatan apapun yang ”melanggar the law of nations”<br />
dapat disidangkan di pengadilan federal perdata Amerika Serikat.<br />
Demikian juga, Torture Victim Protection Act (1992) memungkinkan warga<br />
negara Amerika Serikat dan keluarganya yang menjadi korban<br />
penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh<br />
pejabat di negara lain, dapat disidangkan di Amerika Serikat.<br />
Di Inggris, sebuah ketentuan yang dikeluarkan tahun 1988<br />
memberikan kewenangan yurisdiksi ekstra-teritorial pada pengadilan<br />
pidana untuk menyidangkan pelaku penyiksaan dari negara mana pun<br />
yang dilakukan kepada korban dari negara mana pun dan tidak<br />
tergantung di mana penyiksaan dilakukan. Negara-negara lain yang<br />
sudah pernah mengajukan permohonan ekstradisi atau sudah pernah<br />
33. (Resolution : 2004/72, Impunity, E/CN.4/RES/2004/72), 21 April 2004.<br />
34. Kemungkinan ini telah diakui berdasarkan beberapa keputusan hukum pengadilan Amerika Serikat<br />
(kasus Demjanjuk), Israel (kasus Eichmann) dan House of Lords di Inggris (kasus Pinochet).<br />
35. Lengkapnya The International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or<br />
Punishment.<br />
59<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
menghukum pelaku pelanggaran HAM seperti ini termasuk Spanyol,<br />
Belanda, Jerman, Perancis dan Italia.<br />
Sejumlah model pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang<br />
terjadi terus mengalami perkembangan, yang dapat dilakukan dalam<br />
berbagai bentuk pertanggungjawaban dan proses penuntutan melalui<br />
pengadilan baik dalam level internasional, regional, maupun domestik.<br />
a. Pengadilan Nasional-Internasional (hybrid)<br />
Pada tahun 2002 sebuah pengadilan khusus (special court) yang<br />
bersifat hibrida (nasional dan internasional) dibentuk di Sierra<br />
Leone atas dukungan PBB untuk melengkapi kerja Komisi<br />
Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yurisdiksi pengadilan ini<br />
mencakup kejahatan perang, kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan, dan kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur<br />
dalam hukum internasional, dan akan mengadili orang-orang<br />
yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran hukum<br />
internasional dan hukum Sierra Leone yang dilakukan di<br />
36<br />
wilayah Sierra Leone, sejak 30 November 1996. Jaksa<br />
penuntut dan Hakim dalam pengadilan ini ditunjuk oleh PBB<br />
dan dari Sierra Leone, yang dalam pemilihannya dilakukan<br />
37<br />
melalui konsultasi antara PBB dan Pemerintah Sierra Leone.<br />
Sejumlah pelaku kejahatan telah diadili, diantaranya tiga<br />
komandan Revolutionary United Front (RUF), Issa Hassan Sesay,<br />
Morris Kallon and Augustine Gbao atas dakwaan melakukan<br />
kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan (crimes against humanity) atas peranan mereka<br />
dalam perang sipil yang berakhir tahun 1999. Issa dijatuhi<br />
pidana 52 tahun atas 16 dakwaan, Kallon dijatuhi pidana 39<br />
38<br />
tahun, dan Gbao mendapatkan hukuman 25 tahun.<br />
Di Kamboja, PBB dan Pemerintah Kamboja menyepakati<br />
pembentukan pengadilan pada bulan Oktober tahun 2004.<br />
Pengadilan tersebut akan menjadi mekanisme untuk<br />
mengadili para pemimpin rezim Khmer Merah dan ”mereka<br />
yang paling bertanggung jawab” atas tindakan kejahatan<br />
kemanusiaan.<br />
36. http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/605?OpenDocument.<br />
37. http://www.sc-sl.org/<br />
38. http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=10517<br />
60
Sebagaimana dengan pengadilan khusus Sierra Leone, ”Khmer<br />
Rouge Tribunal ” juga akan beranggotakan hakim dari Kamboja<br />
dan dari luar negeri. Kasus pertama yang disidangkan adalah<br />
terdakwa mantan anggota senior Khmer Merah, Kaing Guek<br />
Eav yang dikenal sebagai Duch. Di persidangan Duch terbukti<br />
bersalah terlibat dalam pembunuhan dan penyiksaan serta<br />
kejahatan terhadap kemanusiaan sewaktu memimpin penjara<br />
Tuol Sleng, tempat terjadinya penyiksaan yang dilakukan<br />
rezim ultra komunis yang dituduh menyebabkan 1,7 juta<br />
orang tewas tahun 1975-1979, dan merupakan salah satu<br />
tragedi terburuk pada abad ke-20. Duch kemudian dihukum<br />
35 tahun penjara dan pada tingkat banding Duch dijatuhi<br />
39<br />
pidana penjara seumur hidup.<br />
b. Inter-American Human Right Court<br />
Pengadilan Inter-Amerika memiliki dua jurisdiksi: mengadili<br />
(adjudicatory jurisdiction) dan memberikan opini hukum (advisory<br />
jurisdiction). Dalam kapasitasnya mengadili kasus, maka hanya<br />
dua jenis pihak yang berhak untuk mengajukan kasus<br />
mengenai interpretasi dan implementasi isi Konvensi: Komisi<br />
HAM Inter-Amerika dan negara pihak dari Konvensi tersebut.<br />
Namun Komisi HAM hanya boleh mengajukan kasus bila<br />
semua prosedur Komisi yang dinyatakan dalam Konvensi<br />
HAM Inter-Amerika Pasal 48-50 (termasuk dengan<br />
mengusahakan penyelesaian domestik) telah dilakukan.<br />
Peranan Pengadilan Inter-Amerika dalam pengembangan<br />
konsep-konsep HAM sangat berarti dalam masa-masa transisi<br />
banyak negara di wilayah Amerika Latin. Salah satu<br />
peranannya adalah dalam pengentasan impunitas, dimana baik<br />
pengadilan tersebut dan Komisi Pengadilan HAM secara<br />
konsisten menyatakan bahwa penerapan undang-udang<br />
amnesti kepada kasus-kasus pelanggaran serius HAM tidak<br />
sesuai dengan Konvensi HAM Amerika.<br />
Misalnya, sebuah kasus yang terjadi di El-Savador dimana<br />
tentara membunuh enam pastur Jesuit dan dua orang<br />
39. http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/03/khmer-rouge-duch-sentence-cambodian.<br />
61<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
perempuan. Pengadilan menyatakan bahwa UU Amnesti<br />
tahun 1993 El-Savador melanggar kewajiban negara itu dalam<br />
Konvensi HAM Amerika, sehingga negara El-Savador harus<br />
menyidik dan mengadili mereka yang bertanggung jawab.<br />
Pengadilan HAM Inter-Amerika menekankan bahwa Komisi<br />
Kebenaran, walaupun memiliki peranan relevan, tidak boleh<br />
dianggap sebagai pengganti yang memadai dari proses<br />
pengadilan sebagai metode pencapaian kebenaran. Komisi<br />
kebenaran bukan didirikan dengan presumsi bahwa tidak akan<br />
ada pengadilan setelahnya, namun harusnya menjadi suatu<br />
langkah untuk mengetahui kebenaran dan pada akhirnya<br />
40<br />
memastikan keadilan akan ditegakkan.<br />
c. Pengadilan Pidana Domestik<br />
Pada bulan April tahun 2004, sebuah pengadilan di Belanda<br />
menjatuhkan hukum 30 tahun penjara kepada bekas kolonel<br />
dari Republik Demokratik Congo, Sebastian Nzapali, atas<br />
keterlibatannya dalam kejahatan perang, khususnya<br />
penyiksaan seorang tahanan yang berada dalam<br />
perlindungannya pada tahun 1996. Perkara ini dapat<br />
disidangkan di Belanda berdasarkan Konvensi Anti<br />
Penyiksaan, di mana pengadilan domesik negara yang telah<br />
meratifikasi konvensi tersebut (dan optional protocols-nya), boleh<br />
mengusut orang yang dicurigai melakukan beberapa jenis<br />
41<br />
pelanggaran HAM di negara lain.<br />
Tahun 2004 lalu merupakan tahun pertama perkara<br />
pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri yang disidangkan<br />
di Inggris. Pada bulan Oktober, perkara seorang komandan<br />
Perang Afghanistan, Faryadi Sarwar Zardad, yang dituduh<br />
berkonspirasi dalam penyiksaan dan penyanderaan antara<br />
tahun 1991 dan tahun 1996 dibuka di Pengadilan Pidana Pusat<br />
Old Bailey di London. Zardad berpindah ke Inggris pada 1998<br />
dan setelah tinggal beberapa waktu, kemudian ditangkap.<br />
42<br />
Zardad akhirnya dijatuhi pidana 20 tahun penjara.<br />
40.Laporan No. 136/99 (El Salvador), paragraf. 229-230. Lihat juga http://www.cidh.oas.org<br />
/annualrep/99eng/Merits/ElSalvador10.488.htm<br />
41.http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=36&level1=15248&level2=&level3=&textid=39989<br />
42.http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4695353.stm, lihat juga http://www.guardian.co.uk/uk<br />
/2005/jul/19/afghanistan.world<br />
62
Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia berhasil menangkap<br />
mantan anggota senior kelompok milisi yang bertanggung<br />
jawab atas genosida di Rwanda pada tahun 1994. Ephrem<br />
Nkezabera ditangkap berdasarkan UU Kejahatan Perang yang<br />
memungkinkan pengadilan Belgia untuk mengadili mereka<br />
43<br />
yang dituduh sebagai ”genocidaire” di luar negara tersebut.<br />
Saat ini sejumlah negara di Amerika Latin juga melakukan<br />
proses penghukuman kepada para pelaku pelanggaran HAM<br />
yang terjadi di masa lalu. Pada Oktober 2011, Mahkamah<br />
Agung Argentina menghukum Alfredo Astiz, mantan tentara<br />
Agrentina, dengan penjara seumur hidup atas kejahatan<br />
terhadap kemanusiaan selama masa ”Dirty War”. Artiz terbukti<br />
ikut serta dalam penculikan dan pembunuhan terhadap suster<br />
Alice Demon dan Leonie Duquet, dan juga Azucena Villaflor,<br />
seorang pendiri ”the Mothers of Plaza de Mayo”, sebuah<br />
kelompok yang meminta adanya penyelidikan untuk kasus-<br />
44<br />
kasus penghilangan paksa.<br />
Pada Juli 2012, mantan pimpinan militer Argentina, Jorge<br />
Videla dan Reynaldo Bignone dijatuhi hukuman masingmasing<br />
50 tahun dan 15 tahun penjara atas kejahatan<br />
melakukan pencurian bayi dan anak-anak dari tahanan politik,<br />
dimana ketika itu setidaknya 400 bayi telah diambil dari orang<br />
45<br />
tua mereka ketika dipenjara.<br />
d. Gugatan Perdata<br />
Mekanisme gugatan perdata, yang sering dilakukan dengan<br />
menuntut pejabat negara untuk memperoleh ganti rugi,<br />
kompensasi dan rehabilitasi. Gugatan ini dilakukan biasanya<br />
sebagai jalan terakhir ketika proses penuntutan dan<br />
penghukuman dihalang-halangi. Hal ini misalnya terjadi di<br />
43. http://www.trial-ch.org/en/ressources/trial-watch/trial-watch/profils/profile/627<br />
/action/show/controller/Profile.html<br />
44. http://www.independent.co.uk/news/world/americas/argentina-finally-serves-justice-on-the-angelof-death-2376896.html.<br />
45. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-18731349<br />
63<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
Uruguay tahun 1990, dimana beberapa anggota keluarga orang<br />
yang dibunuh dan dihilangkan paksa memperoleh ganti rugi<br />
dari negara berdasarkan keputusan pengadilan perdata.<br />
Di tingkat internasional, gugatan perdata juga bisa diajukan di<br />
berbagai negara, misalnya seperti Alien Tort Claims Act di<br />
Amerika Serikat yang memungkinkan permohonan untuk<br />
ganti-rugi dapat diajukan kepada pengadilan federal negara<br />
tersebut. Kendati tindakan kejahatan dilakukan di luar negeri,<br />
para pelaku tetap bisa diadili di Amerika Serikat sepanjang<br />
tergugat memiliki kontak dengan Amerika Serikat. Sejumlah<br />
gugatan dengan prosedur ini misalnya, gugatan yang diajukan<br />
oleh Center for Justice and Accountability di San Fransisco atas<br />
nama keluarga Uskup Agung Romero, yang dibunuh oleh<br />
militer di El Salvador pada tahun 1980.<br />
Setelah hampir 25 tahun sejak pembunuhan Romero, sama<br />
sekali belum ada upaya oleh pemerintah El Salvador untuk<br />
menyelesaikan pembunuhan tokoh HAM ini. Pengadilan<br />
Federal Fresno, California, memutuskan bahwa salah satu<br />
orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut<br />
adalah seorang pensiunan kapten angkatan udara, Alvaro<br />
Saravia, yang telah tinggal di Amerika Serikat selama hampir<br />
20 tahun. Saravia diperintahkan untuk membayar USD 10 juta<br />
46<br />
sebagai ganti rugi kepada keluarga Uskup Agung Romero.<br />
Juga gugatan korban rezim bekas Presiden Filipina, Ferdinand<br />
Marcos. Meskipun Marcos, yang sudah pindah ke A.S. dan<br />
tinggal di Hawaii, meninggal selama proses gugatan ini berlalu,<br />
pengadilan tetap memerintahkan 'estate' Marcos untuk<br />
membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar USD 150<br />
47<br />
juta.<br />
e. Permintaan Ekstradisi<br />
Penahanan bekas diktator Chile, Jendral Pinochet, ditahan di<br />
46. http://www.cja.org/article.php?list=type&type=77<br />
47. Sandra Collver, ”Bringing Human Rights Abuses to Justice in U.S. Courts: Carrying Forward the Legacy of the<br />
Nurenberg Trial”. Dokumen dapat diakses di: http://www.cardozolawreview.com/content/27-<br />
4/COLIVER.WEBSITE.pdf<br />
64
Inggris pada bulan Oktober 1998 berdasarkan surat perintah<br />
internasional yang dikeluarkan oleh hakim Spanyol, Baltasar<br />
Garzon, yang meminta Pinochet diekstradisi ke Spanyol<br />
berdasarkan beberapa tuduhan penyiksaan warga negara<br />
Spanyol. Pinochet ditahan di Inggris selama 16 bulan, namun<br />
akhirnya permintaan ekstradisi ditolak dan Pinochet diijinkan<br />
balik ke Chile.<br />
Spanyol juga menerima tuntutan Yayasan Rigoberta Menchu<br />
yang ditujukan kepada bekas diktator Guatemala, Jendral<br />
Efrain Rios Mott, atas tuduhan melakukan pelanggaran<br />
kejahatan kemanusiaan, dengan catatan hanya kasus yang<br />
melibatkan warga negara Spanyol sebagai korban yang dapat<br />
48<br />
diproses.<br />
Argentina telah menjadi sasaran gugatan berdasarkan<br />
yurisdiksi internasional, dan persidangan in absentia yang<br />
pernah dilakukan di Perancis, Spanyol, Itali dan Jerman. Pada<br />
Juli 2003, Spanyol meminta 46 petinggi militer diekstradisi atas<br />
49<br />
tuduhan penyiksaan dan genosida dan pada tahun 2007<br />
Spanyol juga meminta Argentina untuk mengekstradisi 40<br />
orang, termasuk mantan Presiden Agentina, yang didakwa<br />
melakukan genosida, terrorisme and penyiksaan selama masa<br />
50<br />
kediktatoran tahun 1976 dan 1983.<br />
Pada Maret 2004, giliran Pemerintah Jerman meminta bekas<br />
Presiden Argentina, Jorge Videla, untuk diekstradisi bersama<br />
dengan dua petinggi militer lain, yaitu Emilio Massera dan<br />
Buillermo Suarez Mason yang semuanya dituduh ikut terlibat<br />
dalam pembunuhan tiga mahasiswa Jerman pada tahun 1976<br />
51<br />
dan 1977.<br />
2. Komisi Kebenaran<br />
Sejak awal tahun 1980-an muncul mekanisme baru untuk menghadapi<br />
48. http://www.guardian.co.uk/world/1998/oct/18/pinochet.chile.<br />
49. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3052333.stm<br />
50. http://english.peopledaily.com.cn/200702/10/eng20070210_349129.html<br />
51. http://www.dw.de/dw/article/0,,1128473,00.html<br />
65<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
dan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang secara umum<br />
disebut sebagai komisi kebenaran. Di Argentina, pada 16 Desember<br />
1983 dibentuk Komisi Nasional untuk Menyelidiki Kasus-kasus<br />
Penghilangan Paksa melalui Keputusan Presiden Raul Alfosin.<br />
Kemudian berlanjut pada pembentukan komisi kebenaran di berbagai<br />
negara lainnya, di antaranya Uganda, Chile, Chad, El Salvador, dan Haiti,<br />
dan Afrika Selatan, Guatemala, Nigeria, Sierra Leone, Timor Lesta, dan<br />
52<br />
lainnya.<br />
Sejak tahun 1978-2007, setidaknya lebih dari 32 Komisi<br />
Kebenaran terbentuk di 28 negara dengan berbagai format dan<br />
53<br />
mandatnya. Pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika<br />
Selatan, sebagai mekanisme pengungkapan kebenaran 'non-judial' atas<br />
berbagai pelanggaran HAM yang massif telah mendapatkan perhatian<br />
54<br />
dunia.<br />
Pembentukan Komisi Kebenaran di berbagai negara, sangat<br />
tergantung konteks pelanggaran masa lalu serta konteks masa transisi<br />
masing-masing negara tersebut, namun secara umum Komisi<br />
Kebenaran dapat dinyatakan sebagai:<br />
”Sebuah institusi non-yudisial yang bersifat sementara yang didirikan oleh<br />
sebuah institusi resmi untuk menyelidiki pola pelanggaran HAM berat<br />
yang dilakukan selama kurun waktu tertentu pada masa lalu. Tujuan<br />
dibentuknya institusi ini adalah untuk menerbitkan sebuah laporan<br />
terbuka, termasuk data-data tentang korban,beberapa butir rekomendasi<br />
55<br />
menuju pencapaian keadilan dan rekonsiliasi.”<br />
Komisi Kebenaran dibentuk untuk menghadapi warisan<br />
pelanggaran masa lalu dan mencapai rekonsiliasi nasional yang bersifat<br />
partisipatori dan mendalam, dan bukan untuk menghindari akuntabilitas<br />
pelanggaran maupun proses pengadilan. Pengalaman berbagai negara<br />
menunjukkan bahwa komisi kebenaran pada umumnya dibentuk karena<br />
adanya proses transisi dari pemerintahan otoriter menuju sebuah<br />
pemerintahan demokratis, atau dibentuk dalam upaya mempertahankan<br />
perdamaian usai terjadinya perang sipil atau pemberontakan bersenjata.<br />
52. Pricilla B. Hayner, ”Unspeakable Truth: Facing the Challenge of Truth Commission”, Routledge, 2002. Telah<br />
diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh ELSAM dengan judul, ”Kebenaran Tak Terbahasakan:<br />
Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan, 2005.<br />
53. http://www.amnesty.org/en/international-justice/issues/truth-commissions<br />
54. Pricillia B. Hayner, ”Truth Commission: A Schemic Overview”, International Review of the Red Cross, Vol. 88, Juni<br />
2006.<br />
55. Dan Bronkhorst, 'Truth Commissions and Transitional Justice: A Shrot Guide' Amnesty Internasional Netherlands<br />
Document, September 2003, www.amnesty.nl/downloads/truthcommission_guide.doc<br />
66
Proses pembentukan Komisi Kebenaran dapat dilakukan berdasarkan<br />
keputusan presiden atau undang-undang di tingkat nasional, maupun<br />
sebagai kesepakatan perdamaian yang didukung ditingkat internasional,<br />
misalnya oleh PBB.<br />
Lahirnya komisi kebenaran tidak dimaksudkan untuk<br />
menggantikan fungsi peradilan dalam pencarian keadilan dan<br />
akuntabilitas, melainkan dimaksudkan untuk melengkapi segala aspek<br />
penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu termasuk pencarian keadilan,<br />
penegakan hukum, pengungkapan kebenaran, perubahan hukum dan<br />
institusi, pemulihan, rekonsiliasi, pematahan budaya impunitas dan lain<br />
sebagainya.<br />
Komisi kebenaran meskipun mandatnya dipengaruhi konteks<br />
pelanggaran dan bentuk akuntabilitas yang diharapkan, pendirian suatu<br />
komisi kebenaran harus berdasar kepada norma dan prinsip-prinsip<br />
sebagaimana yang dituangkan dalam hukum HAM internasional.<br />
Artinya, Komisi kebenaran (dan rekonsiliasi) merupakan salah satu<br />
mekanisme yang melengkapi proses akuntabilitas kejahatan pelanggaran<br />
HAM yang berat.<br />
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa Komisi<br />
Kebenaran didasari oleh pentingnya melakukan catatan yang akurat atas<br />
pengalaman masa lalu (historical record of past abuses) yang berguna untuk<br />
mencegah terjadinya peristiwa yang sama terulang. Kemudian, fungsi<br />
penting adanya proses ini untuk mendorong adanya pengakuan resmi<br />
atas pelanggaran HAM yang terjadi, dan negara secara publik mengakui<br />
kesalahan atas terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu.<br />
Selain itu, catatan tentang pelanggaran HAM yang terjadi akan<br />
mampu merekomendasikan berbagai langkah-langkah penting untuk<br />
adanya akuntabilitas, pemulihan kepada korban, dan rekomendasi<br />
perbaikan institusi dan adanya kebijakan untuk memastikan pelanggaran<br />
serupa tidak terulang. Tersedianya catatan yang akurat dari praktek masa<br />
lalu juga akan mempermudah penegakan akuntabilitas oleh negara.<br />
Berbeda dengan mekanisme pengadilan, proses dalam komisi<br />
kebenaran memberikan ruang yang penting bagi para korban untuk<br />
mengungkapkan ceritanya, dengan demikian dapat mengungkap apa<br />
yang sesungguhnya terjadi di masa lalu. Pengungkapan kebenaran, yang<br />
mendasarkan pada suara korban akan berkontribusi pada proses<br />
penyembuhan sosial (social healing), dan mendorong terjadinya<br />
67<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
perdamaian yang nyata di tingkat komunitas masyarakat.<br />
Pengalaman berbagai komisi kebenaran yang ada, setidaknya ada<br />
empat hal pokok; pertama, perumusan mandat Komisi Kebenaran tidak<br />
baku, namun secara hukum, biasanya ada mandat khusus Komisi dan<br />
batasan yang jelas. Kedua, komisi yang dibentuk mengharuskan<br />
tersedianya struktur, komposisi dan keanggotaan yang menjamin<br />
tercapainya mandat. Ketiga, adanya mekanisme kerja komisi yang jelas,<br />
terkait dengan dengan persoalanpersoalan seperti jenis investigasi yang<br />
harus dilakukan, apakah pengambilan pernyataan harus dilakukan<br />
secara rahasia (confidential) atau terbuka, bagaimana mekanisme kerja<br />
komisi dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta,<br />
di luar komisi. Perumusan juga menjaga dipergunakannya prinsipprinsip<br />
”the rights to know the truth”, ”the rights to justice”, dan ”the rights to<br />
reparation” yang menjamin akuntabilitas kerja komisi dalam<br />
56<br />
pengungkapan kebenaran. Keempat, adanya laporan Komisi yang<br />
menunjukkan hasil kerja komisi kebenaran yang lebih lengkap dari<br />
peristiwa masa lalu yang diungkapkan.<br />
Berbagai negara yang melakukan proses pengungkapan<br />
kebenaran di antaranya: Argentina, dengan membentuk ”Comisión<br />
Nacional para la Investigación sobre la Desaparición de Personas”/ CONADEP<br />
(Komisi Nasional untuk Orang Hilang Argentina) yang menghasilkan<br />
laporan akhir berjudul ”Nunca Mas: Informe de la Comision Nacional sobre la<br />
Desaparicion de Personas”. Laporan yang mencakup 8.961 kasus<br />
penghilangan paksa, dan termasuk konteks politik, akar masalah, bentuk<br />
kekerasan, modus operandi dan latar belakang pelaku, nama orang<br />
hilang yang dicatat, kesimpulan dan rekomendasi untuk ke depan,<br />
termasuk perkara yang pantas diteruskan dan diproses di pengadilan.<br />
Nama individu yang terlibat dalam pelanggaran disebutkan dalam<br />
laporan akhir dengan catatan belum tentu bisa disebutkan sebagai<br />
57<br />
merekalah yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.<br />
Di Chile, membentuk Komisi Nasional untuk Kebenaran dan<br />
Rekonsiliasi Chile yang menghasilkan laporan akhir yang sering<br />
disebutkan sebagai 'Rettig Report' diajukan ke parlemen pada Februari<br />
1991. Laporan diterbitkan dalam bentuk dua jilid yang dibagi empat<br />
bagian utama dengan 1.800 halaman. Laporan ini berdasarkan 2.920<br />
perkara yang diselidikinya dan memuatkan informasi tentang konteks<br />
sejarah, tanggungjawab institusional, ringkasan 2.279 kasus<br />
56. ELSAM, Kertas Posisi RUU Kebenaran dan Rekonsiliasi, 2004.<br />
57. Nunca Mas: the Report of the Argentine National Commision on the Dissapearance, Farrar Straus Giroux dan Index<br />
on Cencorship, 1986.<br />
68
pembunuhan dan orang hilang dan berbagai bentuk rekomendasi.<br />
Ketika melakukan presentasi laporan kepada negara, Presiden Alywin<br />
meminta maaf kepada korban dan keluarganya atas nama negara dan<br />
mengirim laporan tersebut kepada setiap keluarga korban pelanggaran<br />
58<br />
HAM.<br />
Di El Salvador, dibentuk Komisi Kebenaran El Salvador<br />
diberikan tugas untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang dilakukan<br />
dua belah pihak dalam dua belas tahun perang sipil antara 1980-1992,<br />
menghasilkan laporan akhir 'De la Locura a la Esperanza ' (From Madness to<br />
Hope). Laporan diajukan ke Pemerintah (Presiden El Salvador) dan<br />
Sekretaris-Jendral PBB pada 15 Maret 1993 dan diterbitkan sebagai<br />
dokumen PBB dalam bentuk tiga jilid sekitar 200 halaman. Walaupun<br />
Komisi Kebenaran selama masa kerjanya menerima dan melakukan<br />
penyelidikan sekitar 22.000 kasus pelanggaran HAM, laporan sendiri<br />
hanya sebutkan 32 kasus secara detail yang dianggap mewakili dan<br />
menunjukkan jenis dan pola pelanggaran selama 12 tahun perang sipil El<br />
Salvador. Laporan disusun dengan menyebutkan kronologis dan analisis<br />
pola pelanggaran yang kemudian dibagi berdasarkan pelaku<br />
pelanggaran, yaitu negara atau pihak FMLN (Frente Farabundo Martí para<br />
la Liberación Naciona) atau Front Pembebasan Nasional Farabundo Marti,<br />
59<br />
dimana pelaku terbesar adalah negara.<br />
Di Guatemala, dibentuk Komisi Klarifikasi Sejarah Guatemala<br />
yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan dan<br />
penghilangan paksa yang terjadi selama 36 tahun konflik bersenjata di<br />
Guatemala. Laporan akhir diajukan ke Presiden dan PBB dengan judul<br />
'Ingatan Sunyi.' Laporan sekitar 3.000 halaman ini didasarkan sekitar<br />
8.000 pengakuan atau testimoni pelanggaran yang memuat 80 kasus<br />
secara terperinci yang dilampirkan dengan ringkasan 8.000 kasus<br />
tersebut. Menurut laporan, sekitar 200.000 orang meninggal akibat 36<br />
tahun konflik bersenjata Guatemala. Nama pelaku tidak disebutkan,<br />
namun dengan melakukan analisis konteks pelanggaran yang cukup<br />
mendalam, dengan melakukan analisis tentang penyebab dan akar<br />
konflik bersenjata, strategi dan mekanisme kekerasan serta dampak dan<br />
60<br />
akibatnya.<br />
58. Pricilla B. Hayner, ”Kebenaran Tak Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran,<br />
Kenyataan dan Harapan, Elsam, 2005. Hal. 63-68.<br />
59. Lihat Laporan Komisi Kebenaran El Salvador ”From Madness to Hope”, dokumen dapat diakses di<br />
http://www.usip.org/files/file/ElSalvador-Report.pdf , lihat juga Pricilla B. Hayner, ”Kebenaran Tak<br />
Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan, Elsam, 2005.<br />
Hal. 69-72.<br />
60. Pricilla B. Hayner, ”Kebenaran Tak Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran,<br />
Kenyataan dan Harapan, Elsam, 2005. Hal. 81-86.<br />
69<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
Kemudian di Afrika Selatan, dibentuk Komisi Kebenaran dan<br />
Rekonsiliasi Afrika Selatan yang mempunyai mandat untuk melakukan<br />
analisis dan memberi penjelasan tentang penyebab, sifat dan meluasnya<br />
pelanggaran HAM berat, termasuk mengidentifikasi pelaku pelanggaran<br />
tersebut, baik individu maupun organisasi. Laporan akhir kerja komisi<br />
ini yang secara singkat disebutkan sebagai 'Final Report ' diajukan ke<br />
Presiden Nelson Mandela. Laporan akhir berdasarkan pengakuan dari<br />
23.000 korban dan saksi, dimana 2.000 kesaksian dilakukan di forum<br />
dengar pendapat yang terbuka untuk publik, dengan melakukan analisis<br />
Apartheid sebagai kejahatan kemanusiaan, analisis khusus tentang<br />
peranan negara dan metode dan jenis pelanggaran, pelanggaran HAM<br />
dari perspektif korban, dan analisis tentang konteks sosial pelanggaran<br />
dan keterlibatan institusional. Laporan Akhir oleh KKR memberikan<br />
61<br />
sekitar 250 butir rekomendasi.<br />
Sejumlah negara lainnya, yang membentuk Komisi juga telah<br />
menyelesaian dan menyusun laporan akhir, diantaranya Sierra Leone<br />
dengan laporan ”Witness to Truth: Final Report of the Truth and Reconciliation<br />
of Sierra Leone” tahun (2005), Peru dengan Laporan ”Informe Final de la<br />
Comision de la Verdad y Reconciliation” tahun (2003), Timor Leste dengan<br />
Laporan berjudul ”Chega” tahun 2006, dan lain-lain.<br />
Kehadiran komisi kebenaran, sebagaimana disebutkan di atas,<br />
berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, yakni: a)<br />
memberikan sumbangan terhadap proses transisi ke arah demokrasi<br />
dengan melakukan catatan imparsial tentang masa lalu, b) memberikan<br />
ruang resmi bagi korban untuk mengungkapkan kebenaran dan<br />
menuntut kompensasi, rehabilitasi dan pemulihan, c) memberikan<br />
rekomendasi menuju perubahan institusi dan perubahan hukum guna<br />
pencegahan terulangnya pelanggaran pada masa depan (non-recurrence<br />
principle), dan d) menentukan siapa yang bertanggungjawab dan<br />
memberikan saran untuk memperoleh akuntabilitas dan menghapuskan<br />
impunitas.<br />
61. Rekomendasi-rekomendasi tersebut difokuskan terhadap beberapa masalah pokok, yakni; a) pencegahan<br />
pelanggaran terulang, b) akuntabilitas, c) pemulihan dan rehabilitasi, d) organisasi, administrasi dan<br />
manajemen, d) lembaga pemasyarakatan, e) komunitas agama, f) dunia usaha, g) hukum dan yudisial, h)<br />
aparat keamanan, i) sektor kesehatan, j) media Massa, k) arsip bahan-bahan KKR, l) pembasmian<br />
dokumen, m) gerakan kemerdekaan, dan n) hak asasi manusiaa Internasional. Lihat Laporan Akhir KKR<br />
Afrika Selatan. Dokumen dapat diakses di http://www.justice.gov.za/trc/report/index.htm.<br />
70
Komisi Kebenaran pada akhirnya diharapkan akan dapat<br />
mendukung adanya tanggungjawab dan akuntabilitas Negara,<br />
memastikan pelanggaran tidak terulang, mengembalikan hak korban,<br />
mendorong adanya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik, dan pada<br />
akhirnya juga mendorong proses demokratisasi. Komisi Kebenaran<br />
dengan laporan akhirnya, saat ini terbukti mendorong proses-proses<br />
yang diharapkan tersebut, bahkan meski dalam jangka panjang,<br />
mendorong terus berlangsungnya proses penghukuman kepada para<br />
pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu, yang saat ini misalnya sedang<br />
berlangsung di sejumlah negara Amerika Latin, seperti Guatemala,<br />
Kolombia, El Salvador dan Argentina.<br />
Pada Januari 2012, Presiden El Salvador Mauricio Funes secara<br />
resmi meminta maaf atas pembantaian ribuan warga yang dilakukan<br />
militer pada tahun 1981 silam, dimana lebih dari 1.000 warga desa tewas<br />
62<br />
selama perang sipil 1980-1992. Di Guatemala, pada Januari 2012,<br />
mantan diktator Efraín Ríos Montt diadili atas tuduhan terlibat dalam<br />
genosida selama 17 bulan pemerintahannya antara tahun 1982-1983. Di<br />
Kolombia Presiden Juan Manuel Santos, meminta maaf atas peran<br />
negara dalam pembantaian sekitar 50 anggota sayap paramiliter di El<br />
Tigre selama serangan terhadap gerilyawan sayap kiri tahun 1999.<br />
Di Argentina, Pemerintah dan Pengadilan sedang menguji<br />
warisan kekejaman selama ”Perang Kotor”, yang pada bulan Oktober<br />
2011, Mahkamah Agung Argentina menghukum Alfredo Astiz, mantan<br />
tentara Argentina, dengan penjara seumur hidup atas kejahatan terhadap<br />
63<br />
kemanusiaan, dan pada Juli 2012, mantan pimpinan militer Argentina,<br />
Jorge Videla dan Reynaldo Bignone dijatuhi hukuman masing-masing<br />
64<br />
50 tahun dan 15 tahun penjara.<br />
C. Penutup<br />
Berbagai pengalaman bagaimana dunia internasional dan negara-negara<br />
lain menghadapi kekejaman dan pelanggaran HAM berat masa lalu,<br />
menunjukkan sekarang ini tidak ada tempat aman (no save haven) bagi para<br />
pelaku ”the most serious crimes”, di antaranya kejahatan genosida dan<br />
kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dalam hukum Indonesia dikenal<br />
sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat. Pengalaman berbagai<br />
praktik penghukuman, baik di tingkat domestik maupun internasional,<br />
62.http://news.detik.com/read/2012/01/17/125232/1817633/1148/presiden-el-salv ador-minta-maafatas-pembantaian-ribuan-warganya.63.http://www.independent.co.uk/news/world/americas/argentina-finally-serves-justice-on-the-angelof-death-2376896.html.<br />
64.http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-18731349<br />
71<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
telah memberikan cukup banyak fakta bahwa para pelaku pelanggaran<br />
HAM berat tidak mudah lagi lepas dari tuntutan pertanggungjawaban.<br />
Berbagai instrumen hukum internasional telah dibentuk untuk<br />
memastikan bahwa ada penghukuman bagi para pelaku dan semakin<br />
memastikan tidak mentolerir adanya amnesti dimasa depan.<br />
Pengalaman pembentukan komisi kebenaran (dan rekonsiliasi)<br />
juga membuktikan bahwa komisi ini mempunyai kontribusi besar<br />
terhadap pertanggungjawaban berbagai tindak kejahatan dan<br />
pelanggaran HAM. Meski adanya komisi kebenaran tidak semua<br />
berhasil, contoh-contoh terbaik telah dihadirkan dan memberikan<br />
sumbangan penting bagi perkembangan negara-negara tersebut dalam<br />
menjamin perlindungan HAM, memastikan terpenuhinya hak-hak<br />
korban, berjalannya demokrasi dan terjaganya perdamaian. Negaranegara<br />
yang gagal memahami masa lalunya, menolak kekejaman yang<br />
telah terjadi, dan tidak belajar dari pengalaman tersebut, berpotensi<br />
mengulangi kesalahan yang sama.<br />
Dalam konteks Indonesia, komitmen negara untuk<br />
menyelesaian dan bertanggungjawab atas pelanggaran HAM masa lalu<br />
saat ini berada dalam ujian. Komitmen yang dituangkan dalam berbagai<br />
produk hukum, yang bukan hanya komitmen secara nasional tetapi<br />
secara khusus juga dinyatakan kepada masyarakat Papua dan Aceh,<br />
seolah menemui jalan buntu. Indonesia telah menguji pertanggungjawaban<br />
atas pelanggaran HAM berat melalui pengadilan, juga<br />
”setengah jalan” dalam berupaya membentuk Komisi Kebenaran dan<br />
Rekonsiliasi, yang sayangnya saat ini justru mandek. Padahal, tuntutan<br />
atas adanya pertanggungjawaban dengan mengungkapan kebenaran,<br />
menegakkan keadilan dan hukum atas berbagai peristiwa pelanggaran<br />
HAM berat terus bergaung. Dampak lebih jauh, ketiadaan pembelajaran<br />
atas praktik yang salah di masa lalu, menyebabkan terus direproduksinya<br />
kekerasan, praktik diskriminasi, dan berbagai pelanggaran HAM<br />
lainnya, yang menghambatnya berjalannya proses demokratisasi.<br />
Merefleksikan berbagai pengalaman bagaimana negara-negara<br />
lain mengadapi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi, dan dikaitkan<br />
dengan konteks penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Indonesia<br />
saat ini, belum terlambat bagi Indonesia untuk konsisten<br />
mengimplementasikan agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa<br />
lalu, mencegah supaya tidak terulang, dan bagaimana menghadapi<br />
72
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
pelanggaran HAM yang terjadi di masa depan. Pengalaman berbagai<br />
negara dalam menghadapi pelanggaran HAM yang berat, menujukkan<br />
bahwa adanya banyak jalan untuk pertanggungjawaban. Indonesia,<br />
dalam konteks saat ini, akan memulai dari mana?<br />
73
Penanganan Pelanggaran<br />
HAM Berat Masa Lalu<br />
Herry Sucipto dan Hajriyanto Y. Thohari<br />
Abstract<br />
Every country in transition from authoritarianism to democracy such as Indonesia<br />
usually encountered problems when they tried to solve past gross human rights<br />
violations. Limited instruments and the encompassing political legacy often become<br />
serious problems. This article offers insights and recommendations from a political<br />
perspective on how to deal with past gross human rights violations.<br />
Keywords: Transition to Democracy, Human Rights<br />
Pendahuluan<br />
Kesulitan menuju era demokratis sangat beralasan. Pertama, ketika<br />
berkuasa, rezim otoritarian secara sistemik membangun sistem politik<br />
yang di satu pihak mengukuhkan kekuasaan yang amat terpusat, dan di<br />
pihak lain mengeliminasikan kontrol yang berasal dari luar sistem. Tidak<br />
ada balancing of power dalam menjalankan jalannya pemerintahan.<br />
Kedua, meski pada awalnya rezim otoritarian cenderung<br />
menekankan penggunaan kekerasan untuk melumpuhkan oposisi,<br />
dalam perkembangannya rezim semacam ini juga menggunakan dasardasar<br />
moral dan intelektual untuk memenangkan dukungan publik yang<br />
lebih luas. Jadi, tidak hanya dominasi, tetapi juga hegemoni. Melalui<br />
hegemonilah dukungan moral dan intelektual terhadap rezim otoritarian<br />
digalang. Akibatnya, rezim transisi sering harus berjuang untuk<br />
mengubah orientasi, paradigma dan berbagai bentuk kepercayaan<br />
tentang, misalnya, bagaimana kekuasaan seharusnya dikelola, bagaimana<br />
individu seharusnya memposisikan dirinya terhadap kekuasaan.<br />
Ketiga, rezim transisi selalu dihadapkan pada dua posisi waktu<br />
yang sering bertolak belakang dalam gagasan dasarnya: masa depan yang<br />
lebih baik dan masa lalu yang penuh keburukan. Sementara terdapat<br />
75
DISKURSUS<br />
Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu<br />
kebutuhan untuk melakukan konsolidasi kelembagaan yang diperlukan<br />
bagi hadirnya sebuah pengelolaan kekuasaan yang demokratis, terdapat<br />
desakan untuk menemukan cara tentang bagaimana warisan rezim<br />
otoritarian itu hendak diselesaikan.<br />
Salah satu warisan terburuk yang dihasilkan oleh rezim<br />
sebelumnya yang melekat pada sistem adalah kejahatan terhadap hakhak<br />
asasi manusia (HAM). Sementara konsolidasi kelembagaan masih<br />
diupayakan (yang seringkali memang sungguh tidak mudah itu), terdapat<br />
tuntutan yang menggunung untuk segera membawa pelaku kejahatan<br />
HAM.<br />
Masa Lalu, Kini, dan Mendatang: Mencari Solusi Terbaik<br />
Seperti disinggung dalam pengantar, rezim-rezim masa lalu pasti<br />
mewariskan banyak masalah, termasuk pelanggaran HAM di sana-sini.<br />
Rezim Orde Lama mewariskan setumpuk masalah hukum dan politik,<br />
serta pelanggaran kepada pemerintahan Orde Baru. Demikian halnya<br />
pemerintahan Orde Baru mewariskan puluhan kasus hukum dan<br />
pelanggaran HAM kepada pemerintahan era reformasi.<br />
Tentu semua itu harus tetap menjadi tanggungjawab kita,<br />
sebagai generasi berikutnya yang menjadi pelanjut pembangunan bangsa<br />
saat ini, untuk menyelesaikan berbagai warisan persoalan semaksimal<br />
mungkin. Pastilah penyelesaian tidak ada yang sempurna alias<br />
memuaskan semua pihak. Namun demikian, sebagai tanggungjawab<br />
sejarah, ikhtiar itu harus terus dilakukan.<br />
Dalam penyelesaian terhadap masa lalu, terdapat empat pola<br />
yang lazimnya dapat dipilih. Sebagai sebuah spektrum keempat opsi itu<br />
bergerak dari (1) ”never to forget, never to forgive” (tidak melupakan dan tidak<br />
memaafkan, yang berarti ”adili dan hukum”); dan (2) ”never to forget but to<br />
forgive” (tidak melupakan tetapi kemudian memaafkan, yang berarti ”adili<br />
dan kemudian ampuni”); sampai dengan (3) ”to forget but never to forgive”<br />
(melupakan tetapi tidak pernah memaafkan, yang artinya tidak ada<br />
pengadilan tetapi akan dikutuk selamanya); dan (4) ”to forget and to forgive”<br />
(melupakan dan memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan dan<br />
dilupakan begitu saja).<br />
Jerman, setelah runtuhnya pemerintahan fasis di bawah Hitler,<br />
dengan bantuan negara-negara sekutu, menerapkan pola pertama.<br />
Sebaliknya, Spanyol memilih pola keempat segera setelah jatuhnya<br />
76
diktaktor Franco di era 1970-an. Korea Selatan, sementara itu,<br />
menerapkan pola kedua pada kasus kedua mantan presidennya.<br />
Afrika Selatan memilih pola kedua dengan penekanan lebih pada<br />
pendekatan disclossure melalui ”Truth and Reconcilliation Commission”<br />
(Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sering disingkat<br />
dengan istilah ”KKR”) daripada pengadilan. Sedangkan pola ”to forget but<br />
never to forgive” pada dasarnya dapat ditemukan pada cara masyarakat<br />
Eropa melihat Inquisition yang dilakukan pada penganut ajaran Protestan<br />
di Eropa selama abad pertengahan.<br />
Beberapa negara yang mencoba berikhtiar menyelesaikan masa<br />
lalunya itu dapat dibilang berhasil, tentu dengan berbagai<br />
konsekuensinya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Solusi ideal<br />
seperti apa yang dapat kita ambil? Apakah dengan menempuh salah satu<br />
pola di atas, ataukan dengan kombinasi dari keempat model tersebut,<br />
ataukah dengan cara yang sama sekali baru, dengan pengkondisian<br />
Indonesia saat ini?<br />
Sejak awal reformasi, keinginan untuk memunculkan landasan<br />
bersama untuk menuju Indonesia masa depan yang lebih bermartabat<br />
sangat kuat. Kita mengokohkan dalam UUD 1945 bahwa negara<br />
Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) pada<br />
Perubahan Ketiga. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah jika<br />
kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar: supremasi hukum (supremacy<br />
of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan<br />
penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum<br />
(due process of law).<br />
Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan<br />
terlihat ciri-cirinya, yaitu adanya (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi<br />
manusia; (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan (3)<br />
legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara<br />
maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui<br />
hukum. Bahkan kemudian juga dikenal adanya Pengadilan Tata Usaha<br />
Negara (PTUN).<br />
Dalam konteks penegakan hukum, khususnya masalah<br />
pelanggaran HAM berat masa lalu, harus diakui, sampai saat ini<br />
Indonesia belum pernah mengalami atau menjalankan proses<br />
penyelesaian masalah tersebut. Ikhtiar menuju arah itu pernah<br />
dilakukan, yakni dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No<br />
77<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu<br />
V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.<br />
Ketapan MPR ini melihat bahwa dalam sejarah perjalanan negara<br />
Indonesia telah terjadi konflik vertikal dan horizontal antar berbagai<br />
elemen masyarakat, pertentangan ideologi, kemiskinan struktural,<br />
kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan lain-lainnya. Maka diperlukan<br />
kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan<br />
persatuan dan kesatuan nasional melalui rekonsiliasi nasional.<br />
Ketetapan MPR tersebut mengamanatkan kepada DPR dan<br />
Presiden untuk membentuk UU tentang komisi kebenaran dan<br />
rekonsiliasi nasional. Maka kemudian lahirlah Undang-Undang No. 27<br />
Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU<br />
ini juga merujuk UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,<br />
selain tentu saja juga mendasarkan pada landasan yang lebih kuat di<br />
atasnya, yakni Pasal 28 UUD 1945. Sayangnya, UU KKR terhenti<br />
sebelum dilaksanakan karena diajukan judicial review oleh masyarakat ke<br />
Mahkamah Konstitusi (MK), yang akhirnya judicial review tersebut<br />
dikabulkan oleh MK pada tahun 2006 dimana UU ini dibatalkan<br />
sepenuhnya oleh MK.<br />
Di antara argumen pembatalan UU KKR tersebut adalah karena<br />
undang-undang ini dipandang mengandung beberapa kelemahan, antara<br />
lain: dalam Pasal 24 yang berbunyi: ”Dalam hal komisi telah menerima<br />
pengaduan atau laporan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang disertai<br />
permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti,<br />
Komisi wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90<br />
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.”<br />
Bisa dibayangkan hanya dalam waktu sangat singkat tersebut<br />
apakah mungkin Komisi dapat menyelesaikan suatu kasus yang berat<br />
yang misalnya melibatkan suatu institusi besar? Tentunya sangat berat<br />
bagi Komisi untuk melakukan penyelidikan hanya dalam waktu yang<br />
sangat singkat tersebut.<br />
Kemudian kita bisa melihat juga pada Pasal 27 yang berbunyi:<br />
”Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat<br />
diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.” Nah ini berarti jika<br />
pelaku tidak diberikan amnesti baik oleh Presiden dan DPR atau pelaku<br />
tidak teridentifikasi atau mungkin tidak dimaafkan oleh korban, maka<br />
dia tidak mendapat kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud<br />
UU tersebut.<br />
78
Selain itu, Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi: ”Pelaksanaan pemberian<br />
kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus<br />
dilaksanakan oleh Pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun<br />
terhitung sejak tanggal keputusan Komisi ditetapkan.” Dari pasal ini bisa<br />
dibayangkan pemberian kompensasi dan rehabilitasi ini bisa saja ditunda<br />
selama tiga tahun dengan sistem perhitungan yang tidak jelas sehingga<br />
korban akan semakin menderita.<br />
Selain itu, harus diakui pula adanya kelemahan substansi hukum<br />
HAM disebabkan oleh: ketidaksigapan dan kecermatan DPR dan<br />
Pemerintah saat pembahasan RUU; konfigurasi politik demokratis di<br />
Parlemen hasil Pemilu 1999 yang didukung pula oleh elemen-eleman<br />
demokrasi di luar Parlemen tidak dengan sendirinya melahirkan produkproduk<br />
hukum yang responsif secara substansial; masih eksisnya<br />
kekuatan pendukung pemerintahan masa lalu, sekalipun konfigurasi<br />
politik formal di DPR didominasi oleh kekuatan reformasi; penyelesaian<br />
pelanggaran HAM masa lalu tidak pernah menjadi keinginan murni<br />
pemerintah, tetapi sebagai respon terhadap desakan dalam negeri dan<br />
dunia internasional.<br />
Kini keinginan penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa<br />
lalu dan sekarang muncul melalui upaya konstitusional dalam bentuk<br />
pengajuan RUU.<br />
Urgensi KKR<br />
Pembentukan KKR sebagaimana pengalaman banyak negara, tentu saja<br />
berada dalam konteks transisi pemerintahan, yaitu dari pemerintahan<br />
otoriter menuju pemerintahan demokratis. Dalam transisi demikian,<br />
mencuat pertanyaan mengenai sikap dan tanggung jawab (responsibility)<br />
negara terhadap kejahatan kemanusian oleh rezim sebelumnya.<br />
Menurut Mary Albon, pertanyaan ini mengandung dua isu<br />
penting, yaitu: pengakuan (acknowledgement) dan pertanggungjawaban<br />
(accountability). Pengakuan mengandung dua pilihan: ”mengingat” atau<br />
”melupakan”. Akuntabilitas menghadapkan kita pada pilihan antara<br />
melakukan ”prosekusi” atau ”memaafkan”. Persoalannya, mengutip<br />
Hannah Arendt (1958), bagaimana kita bisa memaafkan apa yang tak<br />
dapat dihukum? ”Men are not able to forgive what they cannot punish ” (kita tak<br />
bisa mengampuni apa yang tak dapat kita hukum). Demikian juga,<br />
bagaimana kita bisa melupakan apa yang tak pernah dibuka untuk kita<br />
79<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu<br />
ingat bersama?<br />
Dalam kontroversi tersebut signifikansi pembentukan KKR<br />
bukan sekadar alternatif Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, tetapi<br />
juga sebagai kawan seiring. Ia merupakan upaya kunci yang kental<br />
menggunakan perspektif hak asasi manusia dan paradigma humanis<br />
yang mengedepankan kepentingan para korban di satu sisi dan<br />
menyelamatkan kehidupan masyarakat umum di sisi lain. Ia merupakan<br />
wahana untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dan reparatif di<br />
satu sisi dan konstruktif di sisi lain.<br />
Ia mengimplikasikan konsep keadilan yang keluar dari pakem<br />
klasik khas Aristotelian (keadilan komutatif/kontraktual, distributif,<br />
korektif, dan punitif) dan pakem Rawlsian-Habermasian yang<br />
menumbuhkan keadilan di atas kesetaraan (justice as fairness) yang hanya<br />
dapat diterapkan dalam situasi normal yang makin jauh panggang dari<br />
api kini. Ia memperkenalkan konsep keadilan progresif yang<br />
mengedepankan penghukuman kejahatan (keadilan kriminal),<br />
pembongkaran sejarah (keadilan historis), pengutamaan dan<br />
penghormatan terhadap korban (keadilan reparatoris), pembenahan<br />
serta pembersihan sistem penyelenggaraan negara (keadilan<br />
administratif), dan perombakan konstitusi (keadilan konstitusional)<br />
yang ditegakkan di atas prinsip rule of law, kedaulatan rakyat atau<br />
legitimasi demokratis yang mengedepankan hukum, dan bukan sekadar<br />
ruled by law, kedaulatan hukum yang belum tentu demokratis.<br />
Dengan gambaran signifikansi keberadaan KKR di atas<br />
sungguh sebuah kekeliruan bila ada anggapan bahwa pembentukan<br />
komisi ini hanya memperbanyak daftar komisi di negeri ini. Keliru pula<br />
bila ada kecurigaan bahwa ia hanya sebuah usaha parsial dan mengadaada.<br />
Lebih keliru lagi bila ada sinisme ia hanya memperpanjang rantai<br />
impunitas atau sebaliknya hanya akan menyeret dan memadati penjara<br />
dengan semua orang bersalah di masa lalu.<br />
Mengikuti Luc Huyse (1995), truth is both retribution and deterrence,<br />
kebenaran selalu bermakna sebagai dera penghukum dan penggentar.<br />
Selain itu, dalam spektrum retribusi-rekonsiliasi, responsibilitas atau<br />
sikap ideal yang kita ambil adalah selective punishment, model yang<br />
mengedepankan penagihan tanggung jawab formal atau legal secara<br />
selektif. Oleh karena itu, tipe transisi kita adalah replacement<br />
(penggantian) yang diinisiasi rakyat sendiri, yang cocok dengan model<br />
80
selektif ini.<br />
Adanya lembaga yang akan mengurus dan memproses masalah<br />
pelanggaran HAM masa lalu dan kini maupun mendatang, tetap<br />
diperlukan. Untuk itulah, pada 2009, parlemen (DPR) pernah<br />
merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan<br />
HAM ad hoc guna menyelesaikan kasus penculikan dan penghilangan<br />
paksa tahun 1997-1998. DPR bahkan sempat pula berkirim surat<br />
meminta Presiden agar menindaklanjuti rekomendasi tersebut.<br />
Namun rupanya surat DPR tidak memperoleh tanggapan resmi.<br />
Yang muncul justru tanggapan Menteri Hukum dan HAM waktu itu,<br />
Patrialis Akbar, melalui media massa, yang mengatakan bahwa, bila<br />
membongkar siapa yang bertanggung jawab atas kasus penghilangan<br />
paksa tersebut, tindakan ini akan menimbulkan kegaduhan politik.<br />
Dalam Pasal 43 Ayat (3) UU No 26 Tahun 2000 jelas disebut<br />
bahwa Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan<br />
peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Kewenangan untuk<br />
mengusulkan ini dipunyai oleh DPR dengan pertimbangan bahwa selain<br />
sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPR juga dinilai sebagai<br />
representasi rakyat Indonesia. Benar bahwa sebagai sebuah kata,<br />
rekomendasi berarti saran atau usul. Sebagai usul, ia dapat diterima<br />
secara penuh, sebagian, atau ditolak seluruhnya. Namun dalam konteks<br />
relasi antara DPR dan Presiden, bila rekomendasi DPR diabaikan oleh<br />
Presiden tanpa ada penjelasan apa pun, hal ini mengindikasikan<br />
kurangnya wibawa DPR, yang seharusnya sebagai pengawas Presiden<br />
dan representasi rakyat Indonesia, di hadapan Presiden.<br />
Sementara itu, bila Jaksa Agung serius memerankan fungsinya<br />
sebagai aparat penegak hukum, dan benar bahwa belum terbentuknya<br />
Pengadilan HAM ad hoc merupakan kendala bagi institusinya untuk<br />
menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM, tentunya<br />
rekomendasi dari DPR ini akan dilihatnya sebagai peluang, khususnya<br />
untuk melangsungkan penyidikan dan penyelesaian peristiwa<br />
penghilangan paksa 1997-1998. Bila benar begitu, tentunya Jaksa Agung<br />
aktif menunjukkan dukungannya bagi pelaksanaan rekomendasi DPR<br />
tersebut. Namun nyatanya tidak seperti itu.<br />
Masalah Rumit<br />
Di Indonesia, ada banyak masalah pelanggaran HAM, berat maupun<br />
81<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu<br />
ringan. Beberapa kasus berikut adalah pelanggaran berat HAM, seperti:<br />
pelanggaran HAM dalam Peristiwa G30S, Tanjung Priok, Warsidi<br />
Lampung. Kasus dugaan pelanggaran HAM berat Trisakti Semanggi I,<br />
II, Penculikan Paksa Aktivis Tahun 1997/1998, kasus Talangsari (di<br />
Lampung), kasus Wasior, Wamena (di Papua) yang telah selesai diselidiki<br />
oleh Komnas HAM selalu terganjal oleh berbagai kepentingan politis<br />
tertentu.<br />
Sekarang pola-pola kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah<br />
merupakan indikasi awal terjadinya pelanggaran HAM serius. Indikasi<br />
tersebut ditemukan berdasarkan pantauan Komnas HAM dalam<br />
beberapa kasus kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah akhir-akhir ini.<br />
Selain itu, ada pula dimensi pelanggaran yang sifatnya lintas<br />
negara, dalam hal ini apa yang pernah terjadi di Timor Timur (ketika<br />
masih dalam bagian dari NKRI). Di sana disinyalir kuat telah terjadi<br />
pelanggaran HAM dan kekerasan lainnya. Setelah merdeka dan menjadi<br />
negara sendiri, hasil referendum dengan nama Negara Timor Leste (TL),<br />
pemerintah kedua negara telah bersepakat membentuk Komisi<br />
Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk menyelesaikan masalah<br />
pelanggaran yang pernah terjadi di masa lalu itu.<br />
Dalam perkembangannya, KKP merekomendasikan<br />
pembentukan Komisi Nasional untuk Orang Hilang. Dalam sebuah<br />
wawancara aktivis Kontras Usman Hamid dengan Direktur HAM dan<br />
Kemanusiaan Kemenlu, Muhammad Anshor, disebutkan, bahwa komisi<br />
ini juga akan ditugaskan untuk mengidentifikasi semua anak Timor<br />
Leste yang terpisah dari orang tua mereka dan untuk memberi tahu<br />
keluarga-keluarga mereka mengenai keberadaan anak-anak tersebut.<br />
Muhammad Ridha Saleh dari Komnas HAM, dalam sebuah<br />
wawancara menegaskan, terdapat tiga hal mengenai penanganan kasus<br />
orang-orang hilang oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Leste.<br />
Pertama, berkaitan dengan orang hilang. Kedua, pembayaran pensiunan<br />
orang-orang Timor Leste yang pernah bekerja saat menjadi warga<br />
negara Indonesia. Ketiga, kerjasama bidang pendidikan. Dalam<br />
pertemuan dan kunjungan Komnas HAM, banyak suara dari korban<br />
yang terus mempertanyakannya. Ini orang hilang, bukan penghilangan<br />
paksa (disappearances). Sayangnya, rekomendasi soal penanganan orang<br />
hilang itu tak berjalan/tidak dilaksanakan. Ridha mengatakan, tak ada<br />
82
ekomendasi politik DPR untuk melaksanakan, tak ada gugus tugas dari<br />
Pemerintah.<br />
Untuk itulah, dalam konteks ini, hemat saya, perlu kiranya politic<br />
will DPR dan Pemerintah untuk menuntaskan masalah tersebut, sebagai<br />
upaya dan bentuk keseriusan Indonesia membangun kerjasama yang<br />
baik dengan Pemerintah Timor Leste, seperti yang telah disepakati<br />
bersama. Jika masalah ini tidak cepat terselesaikan, maka akan menjadi<br />
ganjalan serius bagi hubungan kedua negara, sekaligus preseden buruk<br />
tentang penanganan pelanggaran HAM masa lalu.<br />
Masalahnya adalah, akan muncul sedikitnya dua masalah serius<br />
ketika ikhtiar penanganan pelanggaran HAM masa lalu, kini, dan<br />
mendatang, yakni berkaitan dengan batasan waktu terjadinya<br />
pelanggaran di masa lalu, serta masalah tarik-menarik kepentingan<br />
politik.<br />
Yang pertama, harus jelas dulu dan disepakati batasan waktu<br />
terjadinya pelanggaran, apakah sejak era Orde Lama, ataukah era Orde<br />
Baru, ataukah sejak era Reformasi, atau bahkan sejak masa penjajahan<br />
Belanda dan Jepang. Beragam pendapat pasti akan muncul, misalnya<br />
anak-anak korban G-30S, akan menuntut haknya diproses atas<br />
pelanggaran orangtuanya, lalu korban kekerasan seksual tentara Jepang<br />
(Jugun Ianfu) terhadap kaum wanita Indonesia, lalu bagaimana dengan<br />
yang terjadi terhadap ulama HAMKA misalnya, yang dipenjara dan<br />
disiksa, tanpa proses hukum, demikian halnya Sjafrudddin<br />
Prawiranegara, keluarganya mungkin juga akan menuntut. Yang masih<br />
hidup, dipenjara tanpa proses hukum, dan masih banyak lagi lainnya.<br />
Mereka semua boleh tidak meminta Pemerintah untuk memproses,<br />
misalnya. Jadi akan banyak kepentingan yang lebih bersifat individual.<br />
Yang kedua, tarik-menarik kepentingan politik sudah tentu sulit<br />
dihindari karena banyaknya kepentingan korban dan juga kepentingan<br />
Pemerintah di dalamnya. Partai-partai politik tentu saja tidak akan<br />
tinggal diam jika ternyata ada kadernya misalnya, diduga terlibat<br />
pelanggaran, padahal ketika pelanggaran itu terjadi, kader tersebut<br />
masih berdinas aktif di institusi pemerintah maupun militer. Sudah<br />
tentu, mereka bertindak dengan prosedur yang ada, dan atas nama<br />
institusi, bukan pribadi. Ini akan menjadi akan menjadi pelik. Ini harus<br />
menjadi catatan kita semua, karena dari sini pula akan menjadi efek<br />
berantai dalam proses penyelesaian.<br />
83<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu<br />
Kesimpulan<br />
Pada prinsipnya, masalah penanganan pelanggaran HAM masa lalu, kini<br />
dan mendatang, selain harus ada payung hukum yang jelas dan tegas,<br />
juga harus ada kemauan politik yang kuat segenap elemen, terutama<br />
kalangan pemerintah, parlemen, parpol, dan kekuatan masyarakat sipil.<br />
Sebenarnya momentum penanganan pelanggaran HAM masa<br />
lalu momentumnya adalah di awal-awal reformasi, atau katakanlah era<br />
Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden<br />
Megawati Sukarnoputri. Namun sayang momentum itu dilewatkan<br />
begitu saja. Ibarat baja yang pada masa itu sedang mencair maka dengan<br />
lewatnya momentum tersebut besi baja telah mengeras kembali dan<br />
hilanglah momentum yang sangat strategis tersebut.<br />
Sekarang, tentunya gagasan dan spirit yang terkandung dalam<br />
KKR itu harus tetap ada dan terus diupayakan untuk dilaksanakan.<br />
Namun dengan catatan bahwa upaya ini harus didukung dengan<br />
kemauan kuat oleh semua pihak sebagaimana tersebut di atas untuk<br />
menyelesaikannya dengan memproses pelanggaran-pelanggaran yang<br />
terjadi terlepas dari apakah nanti dimaafkan atau dihukum, kesemuanya<br />
diserahkan pada proses yang yang nanti akan berjalan dan berlaku.<br />
Semua harus dilakukan dengan pasti dan ketegasan yang cukup.<br />
Kalau bunyinya dimaafkan tentu harus diterima, kalau harus dihukum<br />
juga harus dilaksanakan. Inilah model yang dapat kita lakukan. Untuk<br />
melakukan itu, perlu juga kita berani keluar dari jebakan-jebakan<br />
dogmatis.<br />
Setelah itu semua dilakukan, kita mesti tutup buku, dan<br />
membuka lembaran baru agar semua bisa diselesaikan dengan baik.<br />
Tanpa itu, sulit rasanya mencari jalan keluar, dan ke depan akan terus<br />
menerus terjadi perdebatan mengenai penanganan pelanggaran di masa<br />
lalu tanpa ada titik temu dan penyelesaian.<br />
Dalam konteks dan perspektif ini maka perlu dirintis kembali<br />
upaya legislasinya dengan berpedoman pada Ketetapan MPR No<br />
V/MPR/2000 yang dinyatakan sebagai masih berlaku. Apalagi menurut<br />
UU No. 12 tahun 2011, Ketetapan MPR kembali masuk dalam tata urut<br />
peraturan perundangan sehingga Tap MPR menjadi sumber hukum<br />
formal.<br />
Kita perlu merintis kembali pembentukan UU tentang Komisi<br />
Kebenaran dan Rekonsiliasi yang lebih baik dengan mengoreksi dan<br />
84
menyempurnakan kelemahan-kelemahan dalam UU No. 27 Tahun 2004<br />
tentang KKR yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi untuk<br />
menjadi payung pelaksanaan rekonsiliasi nasional. Sebagai bangsa yang<br />
besar kita yakin dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, betapa pun<br />
rumit dan beratnya.<br />
Bahan Rujukan:<br />
Ketetapan MPR RI No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan<br />
dan Kesatuan Nasional.<br />
Putusan MK Nomor 020/PUU-IV/2006.<br />
UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi<br />
(KKR).<br />
UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.<br />
Sudah kehilangan Momentum', Kompas, 4 November 2006.<br />
Korban penculikan Menuntut', Kompas 17 Maret 2005.<br />
MK Batalkan UU KKR , Cermin Buruknya Legislasi DPR, Kompaas 8<br />
Des 2006.<br />
'Seleksi Anggota KKR Dihentikan' Kompas 19 Desember 2006.<br />
Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia<br />
(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum<br />
Universitas Indonesia, 2003).<br />
Ketetapan Mejelis Permusyarakatan Rakyat No.V/MPR/2000 tentang<br />
Pemantapan Persatuan Nasional.<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 'Komisi Kebenaran dan<br />
Rekonsiliasi: Pengalaman beberapa Negara' www.elsam.or.id<br />
Victor Hansen, Ghraib: Time for The United States to Adopt A<br />
Standard of Command Responsibililty Towards<br />
Its Own, Gonzaga Law Review, 2006 2007.<br />
Jared Olanoff, Holding A Head of State Liable for War Crimes:<br />
Command Responsibility and The Milosevic.<br />
Trial, Suffolk Transnational Law Reivew, Summer 2004.<br />
Ilias Bantekas, Principles of Direst and Superior Responsibility in<br />
International Humanitarian Law, Manchester University Press,<br />
Manchester, UK, 2002.<br />
Daniel. S, Makalah seminar Pembangunan Hukum Nasional, Denpasar<br />
(Juli, 2003).<br />
85<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
DISKURSUS<br />
Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu<br />
Wawancara Usman Hamid dengan Kemlu, 10 Maret 2012.<br />
Wawancara Usman Hamid dengan Ridha Saleh, Komnas HAM, 2 April<br />
2012.<br />
”Nasir Djamil: Kita Tunggu Jawaban Presiden”, Serambi Indonesia,<br />
Kamis 29<br />
September 2011.<br />
”Menteri HAM: Usut Orang Hilang, Politik Gaduh,” Vivanews, Rabu,<br />
12 Mei 2010.<br />
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. I, Jakarta,<br />
2003.<br />
Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH, MCJ, Dari Pengadilan Militer<br />
Internasional<br />
Nuremberg ke Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia, PT. Tata Nusa<br />
2003.<br />
86
OASE
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
Stanley Adi Prasetyo<br />
Abstract<br />
Wiji Thukul is the most wanted artist-cum-activist by the New Order regime. He<br />
was abducted by the New Order regime and up till now his whereabout is<br />
unknown. As a poet, his works were feared by the rulers at that time. This article<br />
discusses Wiji Thukul's description in his unreleased poems about his own<br />
conditions just before he was forcefully dissapeared.<br />
Keywords: Abduction; Authoritarian Regime; Human Rights Violation<br />
Orang memanggilnya Wiji Thukul, nama yang dalam bahasa Jawa berarti<br />
”biji tumbuh”. Pemilik nama lengkap Wiji Widodo ini lahir di Kampung<br />
Sorogenen, Jebres, Solo, pada 24 Agustus 1963. Penampilannya sangat<br />
sederhana, tak sebagaimana seniman pada umumnya yang kerap<br />
berpenampilan ”sok seniman”. Malah penampilannya lebih sering<br />
terlihat ”kampungan” dalam arti tampil alamiah sebagai orang kampung.<br />
Suatu hari pada 1984, Wiji Thukul membaca puisi di kampus tempat saya<br />
kuliah, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Setelah<br />
selesai, dia kemudian berdiskusi dengan gaya santai, duduk dengan kaki<br />
sebelah diangkat sambil makan singkong rebus dan menyeruput kopi.<br />
Ya, itulah dia, Wiji Thukul yang pertama kali saya kenal melalui seorang<br />
budayawan asal Solo yang lebih suka dipanggil sebagai pekerja seni,<br />
Halim HD, sekitar 1983.<br />
Thukul besar dari lingkungan keluarga kelas bawah. Bapaknya<br />
penarik becak, sebagaimana mayoritas profesi para tetangga di tempat<br />
tinggalnya. Pendidikan formal Thukul adalah Sekolah Menengah<br />
Karawitan Indonesia (SMKI) Solo Jurusan Tari, tapi tak pernah<br />
ditamatkannya. Pada 1982 dia drop out dan memilih bekerja mencari uang<br />
buat membantu bapaknya. Dia pernah berjualan koran di Semarang, jadi<br />
89
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
buruh plitur di kampungnya, calo karcis bioskop, dan jadi pengamen<br />
puisi. Pernah juga dia bekerja jadi wartawan, meski hanya tiga bulan.<br />
Belakangan Thukul jadi penyair terkenal yang puisi-puisinya<br />
kerap dibaca oleh para aktivis mahasiswa pada 1980an. Dia mulai<br />
menulis puisi sejak SD, dan tertarik pada dunia teater ketika duduk di<br />
bangku SMP. Bersama kelompok Teater Jagat, dia pernah mengamen<br />
puisi keluar-masuk kampung dan kota.<br />
Meski hidupnya pas-pasan, Thukul mampu menyelenggarakan<br />
kegiatan teater dan melukis dengan anak-anak kampung Kalangan,<br />
tempat dia dan keluarganya tinggal. Pada pertengahan 1980an Thukul<br />
kerap diundang mengamen masuk ke kampus-kampus, baik di Jawa<br />
Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, maupun Jakarta. Pengalaman bergaul<br />
dengan para aktivis inilah membuat Thukul kian kritis dalam berpikir.<br />
Wiji Thukul pun menyadari pentingnya sebuah organisasi sebagai alat<br />
perjuangan.<br />
Thukul aktif terlibat dalam sejumlah aksi solidaritas terhadap<br />
para petani dan buruh. Pada 1992 dia ikut demonstrasi memprotes<br />
pencemaran lingkungan oleh pabrik tekstil PT. Sariwarna Asli Solo. Pada<br />
1994, saat terjadi aksi petani di Ngawi, Jawa Timur, Thukul memimpin<br />
massa dan melakukan orasi. Dalam aksi ini dia ditangkap serta dipukuli<br />
sejumlah aparat militer.<br />
Setahun berikutnya, saat ikut aksi aksi demo 15.000 karyawan<br />
PT. Sritex yang didukung oleh Pusat Perjuangan Buruh Indonesia<br />
(PPBI) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk demokrasi (SMID),<br />
Thukul dipukuli dengan popor senjata dan kepalanya dibenturkan ke<br />
mobil oleh aparat keamanan yang mengakibatkan mata kirinya buta. Dia<br />
mengalami cedera mata kanan karena dibenturkan mobil oleh aparat<br />
yang kemudian menangkapnya.<br />
Pada 1994 Thukul bersama seniman progresif seperti Semsar<br />
Siahaan dan Moelyono mendirikan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat<br />
(Jakker). Thukul menjadi ketuanya. Jakker sendiri membangun jaringan<br />
kesenian dengan melibatkan sejumlah seniman progresif dan<br />
1<br />
kerakyatan di berbagai daerah.<br />
Pada April 1996 Thukul hadir dalam kongres pertama<br />
1. Penjelasan mengenai sepak terjang Wiji Thukul secara lengkap bisa dibaca pada Wilson, ”Wiji Thukul:<br />
Hanya Ada Satu Kata: Hilang” dalam Wilson (editor), Kebenaran Akan Terus Hidup: Catatan-Catatan<br />
Tentang Wiji Thukul, Ikohi dan Yappika, Jakarta, 2007.<br />
90
pembentukan PRD di Kaliurang, Yogyakarta. Dalam kongres tersebut<br />
PRD mengambil keputusan penting di mana Jakker bersama Solidaritas<br />
Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan<br />
Buruh Indonesia (PPBI) dan beberapa organisasi lain secara resmi<br />
menyatakan berafiliasi secara organisasi dan Politik dengan PRD.<br />
Pada 22 Juli 1996 Thukul ikut hadir dalam pendeklarasian Partai<br />
Rakyat Demokratik (PRD) di Ruang Adam Malik di Gedung Yayasan<br />
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI), Jakarta. Pada<br />
kesempatan ini dia membacakan sebuah puisinya yang terkenal berjudul<br />
”Peringatan”. Ia juga dinyatakan terpilih terpilih menjadi Ketua Bidang<br />
Pengembangan Kebudayaan PRD, selain memimpin Jaringan Kerja<br />
(JaKer) Kebudayaan bersama dengan Semsar Siahaan. Keterlibatan Wiji<br />
Thukul dalam PRD ini jelas adalah sebuah pilihan politik.<br />
Sejak dideklarasikan, PRD selalu mendapat sorotan dari pihak<br />
aparat keamanan, termasuk kalangan intelijen. Nama PRD disebutsebut<br />
sebagai dalang beberapa aksi petani maupun buruh. Nama PRD<br />
kembali disebut-sebut saat terjadi peristiwa penyerbuan kantor PDI<br />
yang dikuasai oleh pengikut Megawati Sukarnoputri secara paksa oleh<br />
kelompok pendukung PDI Suryadi yang didukung preman dan<br />
2<br />
kelompok aparat tak berseragam. Peristiwa itu disebut sebagai Peristiwa<br />
2. Soeharto dan pembantu militernya merekayasa Kongres PDI di Medan dan mendudukkan kembali<br />
Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Rekayasa pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan Megawati<br />
itu dilawan pendukung Megawati dengan menggelar mimbar bebas di Kantor DPP PDI. Aktivitas berupa<br />
mimbar bebas yang menghadirkan sejumlah tokoh kritis dan aktivis penentang Orde Baru, telah mampu<br />
membangkitkan kesadaran kritis rakyat atas perilaku politik Orde Baru. Sehingga ketika terjadi<br />
pengambilalihan secara paksa, perlawanan dari rakyat pun terjadi. Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen<br />
Syarwan Hamid dalam penjelasannya kepada perwakilan negara asing di Departemen Luar Negeri pada 5<br />
Agustus 1996 menegaskan bahwa Peristiwa 27 Juli 1996 merupakan upaya sekelompok orang untuk<br />
menghidupkan kembali faham komunis di Indonesia. Upaya untuk menghidupkan kembali komunisme<br />
itu dilakukan dengan menggunakan konflik internal di tubuh Partai Demokrasi Indonesia sebagai "kuda<br />
troya". Penggunaan PDI sebagai "kuda troya" adalah karena PDI menyimpan konflik internal yang dapat<br />
dieksploitasi dan diprovokasi. Status PDI sebagai lembaga politik formal mengakibatkan kelompokkelompok<br />
yang bermain politik praktis tak dicurigai.<br />
Di antara kelompok ekstrem itu adalah PRD dengan berbagai faksinya yang dapat disamakan dengan PKI.<br />
Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung menuding mimbar bebas yang digelar di halaman Kantor DPP<br />
PDI adalah embrio makar terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Sebelumnya, tanggal 19 Juli 1996,<br />
Soeharto memanggil sejumlah pembantu militernya untuk membahas mimbar bebas tersebut. Soeharto<br />
mengingatkan agar pembantu militer mewaspadai makar. Lihat harian Kompas 14 Juli 2003. Analisis<br />
mendalam mengenai Peristiwa 27 Juli 1996 bisa dilihat pada Lukas Luwarso (penyunting), Peristiwa 27<br />
Juli, ISAI, Jakarta, 1997.<br />
91<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
3<br />
27 Juli 1996, ada pula yang menamakannya sebagai Peristiwa Kudatuli.<br />
Indikasi akan dijadikannya PRD sebagai pihak yang<br />
bertanggungjawab sebetulnya tampak dari penyataan Presiden Soeharto<br />
yang mengeluarkan pernyataan di depan para wartawan bahwa semua<br />
pihak harus mewaspadai aktivitas yang terjadi di depan kantor PDI di<br />
Jalan Diponegoro, Jakarta. ”Awas, ada banyak setan gundul di sana,”<br />
4<br />
ucap Presiden Soeharto. Dan ketika peristiwa terjadi dan masyarakat<br />
yang marah atas penyerangan pada dini hari 27 Juli 1996 tersebut dan<br />
melakukan penyerangan kepada sejumlah gedung pemerintah dan<br />
kendaraan berplat nomor merah, Kasospol TNI Mayjen TNI Syarwan<br />
Hamid menyatakan kepada media massa bahwa dalang kerusuhan yang<br />
5<br />
terjadi di Jakarta tak lain adalah anak-anak PRD.<br />
Hari-hari setelah Kudatuli aksi perburuan pun dimulai. Semua<br />
aktivis PRD termasuk berbagai organisasi yang berafiliasi pada PRD<br />
seperti SMID, Jaker, dan lain-lain diburu dan ditangkapi. Termasuk salah<br />
satunya adalah Wiji Thukul.<br />
3. Kudatuli. adalah akronim dari Kerusuhan 27 Juli. Sebutan ini pertama kali digunakan oleh tabloid Swadesi<br />
dan kemudian digunakan secara luas oleh berbagai media massa. Sebutan yang lain adalah Peristiwa Sabtu<br />
Kelabu yang merujuk pada hari saat terjadinya peristiwa ini yaitu hari Sabtu, kata "kelabu" untuk<br />
menggambarkan "suasana gelap" yang melanda panggung perpolitikan Indonesia saat itu. Peristiwa 27<br />
Juli 1996 ini menimbulkan kerugian material berupa 56 gedung dan 197 mobil rusak dan terbakar,<br />
sehingga menurut Gubernur Soejadi Soedirdja, total kerugian mencapai Rp.100 miliar. Dalam peristiwa<br />
ini 200 orang ditangkap. Menurut laporan Komisi Nasional Hak-Hak Azasi Manusia, ada tiga unsur<br />
penyebab kerusuhan yang terlibat, yakni unsur pendukung PDI kelompok Soerjadi dan Megawati, unsur<br />
pemerintah/aparat keamanan, dan masyarakat.<br />
4. Harian Terbit, 26 Juli 1996.<br />
5. Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditandatangani Ketua Munawir Sjadzali dan<br />
Sekjen Baharuddin Lopa tentang Peristiwa 27 Juli menyebut sebanyak 5 orang meninggal dunia, 149<br />
orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi<br />
sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi<br />
Manusia menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen<br />
Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel<br />
Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono<br />
memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya. Dokumen tersebut<br />
juga menyebutkan aksi penyerbuan adalah garapan Markas Besar ABRI c.q. Badan Intelijen ABRI<br />
bersama Alex Widya S. Diduga, Kasdam Jaya menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya, yaitu Brigade<br />
Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengamanan Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. Tri Tamtomo untuk melakukan<br />
penyerbuan. Seperti tercatat di dokumen itu, rekaman video peristiwa itu menampilkan pasukan Batalion<br />
Infanteri 201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar seolah-olah massa PDI pro-Kongres Medan.<br />
Fakta serupa terungkap dalam dokumen Paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di<br />
Komisi I dan II DPR RI, 26 Juni 2000. Lihat: Laporan Penyelidikan Komnas HAM tentang Peristiwa 27<br />
Juli 1996. Pengadilan Koneksitas yang digelar pada era Presiden Megawati hanya mampu membuktikan<br />
seorang buruh bernama Jonathan Marpaung yang terbukti mengerahkan massa dan melempar batu ke<br />
Kantor PDI. Ia dihukum dua bulan sepuluh hari, sementara dua perwira militer yang diadili, Kol CZI Budi<br />
Purnama (mantan Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya) dan Letnan Satu (Inf) Suharto (mantan<br />
Komandan Kompi C Detasemen Intel Kodam Jaya) divonis bebas.<br />
92
Wiji Thukul mengungsi meninggalkan rumah tak lama setelah<br />
namanya disebut-sebut di madia massa, termasuk sejumlah televisi.<br />
Berikut ini adalah sejumlah puisi, yang lebih merupakan catatan<br />
pribadinya saat ia pergi bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain.<br />
Puisi ini ditulis langsung oleh Wiji Thukul selama persembunyian di<br />
Jakarta dan sekitarnya. Pada masa ini saya bertemu dengan Wiji Thukul<br />
beberapa kali. Saya mendapatkan kumpulan puisi ini saat-saat terakhir<br />
kali sebelum dia memutuskan untuk pindah ke luar kota, mengingat<br />
Jakarta dinilainya sudah tidak aman.<br />
”Tolong ini kamu pegang. Siapa tahu suatu saat ada gunanya,”<br />
ujar Wiji Thukul. Kumpulan puisi ini total berjumlah 27 buah puisi yang<br />
sebagian besar belum ada judulnya. Ditulis dengan pensil di atas kertas<br />
surat putih bergaris sebanyak 13 halaman bolak-balik. Bila dilihat kisah<br />
di balik puisi, tampaknya tulisan ini dibuat setelah sang penulis<br />
menempuh perjalanan Solo, Salatiga, dan Jakarta dengan menumpang<br />
truk dan berpindah-pindah bus. Sebagian tulisan diberi catatan tanggal<br />
penulisan, sebagian tidak. Namun dari catatan yang ada bisa<br />
diperkirakan bahwa puisi ini ditulis antara tanggal 10 sampai 15 Agustus<br />
1996.<br />
Puisi berikut bercerita tentang pelarian Wiji Thukul<br />
meninggalkan kota kelahirannya, Solo. Alasan Wiji Thukul untuk pergi<br />
mengungsi dari kota Solo tak lain karena namanya disebut-sebut dalam<br />
televisi oleh seorang jendral.<br />
Para jendral marah-marah<br />
Pagi itu kemarahannya disiarkan oleh televisi. Tapi aku tidur. Istriku yang<br />
menonton. Istriku kaget. Sebab seorang letnan jendral menyeret-nyeret namaku.<br />
Dengan tergopoh-gopoh selimutku ditarik-tariknya, Dengan mata masih lengket<br />
aku bertanya: mengapa? Hanya beberapa patah kata ke luar dari mulutnya:<br />
”Namamu di televisi .....” Kalimat itu terus dia ulang seperti otomatis.<br />
Aku tidur lagi dan ketika bangun wajah jendral itu sudah lenyap dari televisi.<br />
Karena acara sudah diganti.<br />
Aku lalu mandi. Aku hanya ganti baju. Celananya tidak. Aku memang lebih<br />
sering ganti baju ketimbang celana.<br />
Setelah menjemur handuk aku ke dapur. Seperti biasa mertuaku yang setahun lalu<br />
93<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
ditinggal mati suaminya itu, telah meletakkan gelas berisi teh manis. Seperti<br />
biasanya ia meletakkan di sudut meja kayu panjang itu, dalam posisi yang gampang<br />
diambil.<br />
Istriku sudah mandi pula. Ketika berpapasan denganku kembali kalimat itu<br />
meluncur. ”Namamu di televisi....” ternyata istriku jauh lebih cepat mengendus<br />
bagaimana kekejaman kemanusiaan itu dari pada aku.<br />
Rupanya Thukul memilih meninggalkan Solo dengan<br />
menumpang sebuah kendaraan truk. Menumpang truk barangkali<br />
adalah pilihan sadarnya menghindari masuk kota atau terminal di mana<br />
kemungkinan dia akan diketemukan oleh aparat yang mencari-carinya.<br />
aku diburu pemerintahku sendiri<br />
layaknya aku ini<br />
penderita penyakit berbahaya<br />
aku sekarang buron<br />
tapi jadi buron pemerintah yang lalim<br />
bukanlah cacat<br />
pun seandainya aku dijebloskan<br />
ke dalam penjaranya<br />
aku sekarang terlentang<br />
di belakang bak truk<br />
yang melaju kencang<br />
berbantal tas<br />
dan punggung tangan<br />
kuhisap dalam-dalam<br />
segarnya udara malam<br />
langit amat jernih<br />
oleh jutaan bintang<br />
sungguh<br />
baru malam ini<br />
begitu merdeka paru-paruku<br />
94
malam sangat jernih<br />
sejernih pikiranku<br />
walau penguasa hendak mengeruhkan<br />
tapi siapa mampu mengusik<br />
ketenangan bintang-bintang?<br />
Dari urutan catatan yang bisa dilacak dari puisi-puisi yang<br />
ditulisnya, rupanya Salatiga jadi tujuan kota terdekat yang dipilih Thukul<br />
ketika ia memutuskan meninggalkan kota Solo. Dia ke kota dingin yang<br />
berjarak tempuh sekitar sejam dengan roda empat ini dalam keadaan<br />
kedinginan dan kelaparan. Seharian dia bersembunyi di Solo setelah<br />
meninggalkan rumah.<br />
Rupanya sesampai di Salatiga, Thukul memilih untuk mampir ke<br />
rumah seorang dosen yang dikenalnya dengan baik di kawasan Kemiri<br />
Candi, di pinggiran kota di belakang kampus Universitas Kristen Satya<br />
Wacana. Orang itu tak lain adalah pasangan Dr Arief Budiman dan Leila<br />
Ch. Budiman. Hal ini bisa dikenali dari puisi yang diberinya judul ”Buat<br />
L.Ch & A.B”. Wiji Thukul yang menggambarkan kelelahan fisik dan<br />
kelelahan psikis yang dialaminya.<br />
Buat L.Ch & A.B.<br />
darahku mengalir hangat lagi<br />
setelah puluhan jam sendi<br />
sendi tulangku beku<br />
kurang gerak<br />
badanku panas lagi<br />
setelah nasi sepiring<br />
sambel kecap dan telur goreng<br />
tandas bersama tegukan air<br />
dari bibir gelas keramik yang kau ulurkan dengan senyum<br />
manismu<br />
kebisuan berhari-hari<br />
kita pecahkan pagi itu<br />
dengan salam tangan<br />
95<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
pertanyaan<br />
dan kabar-kabar hangat<br />
pagi itu<br />
budimu menjadi api<br />
tapi aku harus pergi lagi<br />
mungkin tahun depan<br />
atau entah kapan<br />
akan kuketuk lagi<br />
daun pintumu<br />
bukan sebagai buron<br />
Dari Jawa Tengah rupanya Thukul terus bergerak dan sampai di<br />
Jakarta. Ia rupanya ditampung di sebuah rumah di pinggiran Jakarta<br />
milik sepasang aktivis yang baru saja menikah. Thukul menulis puisi<br />
yang diberinya judul ”Kado untuk Pengantin Baru” sebagai berikut.<br />
Kado untuk Pengantin Baru<br />
pengantin baru<br />
ini ada kado untukmu<br />
seorang penyair<br />
yang diburu-buru<br />
maaf aku mengganggu<br />
malam bulan madumu<br />
aku minta kamar satu<br />
untuk membaringkan badanku<br />
pengantin baru<br />
ini datang lagi tamu<br />
seorang penyair<br />
yang dikejar-kejar serdadu<br />
memang tak ada kenikmatan<br />
di negri tanpa kemerdekaan<br />
selamanya tak akan ada kemerdekaan<br />
jika berbeda pendapat menjadi hantu<br />
96
pengantin baru<br />
ini ada kado untukmu<br />
seorang penyair yang dikejar-kejar serdadu<br />
Dalam pelarian, Thukul melalui komunikasi dengan sejumlah<br />
teman-temannya sempat mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di<br />
rumahnya yang rupanya telah didatangi sejumlah aparat. Dia menulis<br />
beberapa puisi berikut.<br />
kuterima kabar dari kampung<br />
rumahku kalian geledah<br />
buku-bukuku kalian jarah<br />
tapi aku ucapkan banyak terima kasih<br />
karena kalian telah memperkenalkan sendiri<br />
pada anak-anakku<br />
kalian telah mengajari anak-anakku<br />
membentuk makna kata penindasan<br />
sejak dini<br />
ini tak diajarkan di sekolahan<br />
tapi rejim sekarang ini<br />
memperkenalkan kepada semua kita<br />
setiap hari di mana-mana<br />
sambil nenteng-nenteng senapan<br />
kekejaman kalian<br />
adalah buku pelajaran<br />
yang tak pernah ditulis!<br />
Thukul juga menulis sebuah puisi khusus buat anaknya dalam<br />
6<br />
situasi dia sebagai buron pemerintahan Orde Baru. Berikut puisi itu:<br />
Wani,<br />
bapakmu harus pergi<br />
kalau teman-temanmu tanya<br />
kenapa bapakmu dicari-cari polisi<br />
jawab saja:<br />
97<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
6. Menikah dengan Dyah Sujirah alias Sipon rekannya satu teater pada tanggal 23 Oktober 1988 dan<br />
dikaruniai dua orang anak, yaitu Fitri Nganthi Wani dan Fajar Merah. Foto kopi naskah puisi ini pernah<br />
saya berikan kepada seorang wartawan bawah tanah yang kemudian dimuatnya dalam majalah SiaR dan<br />
kemudian dikutip oleh terbitan bawah tanah yang dikelola aktivis PRD yaitu media Pembebasan dan<br />
kemudian dimuat dalam jurnal Indonesia, terbitan Universitas Cornell, Amerika.
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
”karena bapakku orang berani”<br />
kalau nanti ibu didatangi polisi lagi<br />
menangislah sekuatmu<br />
biar tetangga kanan kiri datang<br />
dan mengira ada pencuri<br />
masuk rumah kita<br />
Bagi Thukul arti sebuah persahabatan sejati baru bisa dirasakan<br />
saat datang cobaan. Meski banyak orang merasakan penindasan<br />
sebagaimana yang dirasakannya, juga rakyat pada umumnya, namun<br />
dalam situasi yang menghimpit tak semua teman berani menemuinya.<br />
Thukul menulis sebuah puisi yang berjudul ”Pepatah Buron”.<br />
Pepatah Buron<br />
penindasan adalah guru paling jujur<br />
bagi yang mengalami<br />
lihatlah tindakan penguasa<br />
bukan retorika bukan pidatonya<br />
kawan sejati adalah kawan yang masih berani<br />
tertawa bersama<br />
walau dalam kepungan bahaya<br />
Situasi pelarian tak mengecilkan semangat juang Thukul.<br />
Sikapnya tetap teguh dan kritis pada kekuasaan. Pada beberapa<br />
kesempatan dia menulis kegeramannya pada penguasa. Berikut puisi<br />
yang ditulisnya.<br />
kekuasaan yang sewenang-wenang<br />
membuat rakyat selalu berjaga-jaga<br />
dan tak bisa tidur tenang<br />
sampai mereka sendiri lupa<br />
batas usianya tiba<br />
dan dalam diamnya<br />
rakyat ternyata bekerja<br />
menyiapkan liang kuburnya<br />
98
lalu mereka bersorak<br />
ini kami siapkan untukmu tiran!<br />
penguasa yang lalim<br />
ketika mati tak ditangisi rakyatnya<br />
sungguh memilukan<br />
kematian yang disyukuri dengan tepuk tangan<br />
Thukul juga menulis sebuah puisi lain tentang penguasa. Ia yakin<br />
bahwa penguasa lalim tak bisa membungkam suara rakyat.<br />
ujung rambut ujung kuku<br />
gendang telinga<br />
dan selaput bola mataku<br />
tidak mungkin lupakan kamu<br />
bilur di punggung<br />
nyeri di tulang<br />
berhari-hari<br />
darah di helai rambut ujung kuku<br />
dendang telinga<br />
dan selaput bola mataku<br />
telah mengotori namamu<br />
nyeri di tulang<br />
berhari-hari<br />
bilur di punggung<br />
karena sabetan<br />
telah mencoreng namamu<br />
kau tak kan bisa mencuci namamu<br />
sekalipun 1000 mobil pemadam kebakaran<br />
kau kerahkan<br />
kau tak kan bisa mencuci tanganmu<br />
sekalipun 1000 pengeras suara<br />
melipatgandakan pidatomu<br />
suara rakyat adalah suara Tuhan<br />
dan kalian tak bisa membungkam Tuhan<br />
99<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
sekalipun kalian memiliki 1.000.000 gudang peluru<br />
Dalam pelarian, Thukul terus mengikuti pemberitaan media<br />
massa. Dia membaca koran dan melihat televisi. Dia menemukan<br />
kenyataan bahwa pemberitaan media massa lebih banyak<br />
mempraktikkan jurnalisme omongan. Bukan jurnalisme yang<br />
memberitakan realitas penderitaan rakyat. Semua kebohongan yang<br />
diucapkan penguasa dikutip mentah-mentah oleh media massa. Thukul<br />
mencemaskan bahwa bukan tak mungkin yang akan muncul adalah<br />
nasionalisme model jaman Nazi di Jerman.<br />
Jakarta simpang siur<br />
ormas-ormas tiarap<br />
tiap dengar berita<br />
pasti ada aktivis ditangkap<br />
telepon-telepon disadap<br />
koran-koran disumbat<br />
rakyat was-was dan pengap<br />
diam-diam orang cari informasi<br />
dari radio luar negeri<br />
jangan percaya<br />
pada berita mass media cetak<br />
dan elektronika asing!<br />
Penguasa berteriak-teriak setiap hari<br />
Nasionalismenya mirip Nazi<br />
Thukul juga menulis beberapa kata, tidak dalam bentuk puisi,<br />
tapi lebih merupakan rangkaian kata-kata terpilih. Kata-kata ini lebih<br />
merupakan perasaan Thukul saat membaca, mendengar dan memirsa<br />
tayangan televisi.<br />
berhari-hari – ratusan jam – ratusan kilometer – puluhan kota – bis – colt – truk –<br />
angkutan – asap rokok – uap sampah – tengik wc – knalpot terminal – embun<br />
subuh – baca koran – omongan penguasa – nonton tivi – omongan penipu – presiden<br />
marah-marah – jendral-jendral marah-marah – intelektual bayaran ikut-ikutan –<br />
100
sekretariat organisasi aktivis diobrak-abrik – penculikan – penggrebegan –<br />
pengejaran – pembenaran dibikin kemudian – semua benar karena semua diam<br />
Thukul juga merasa bahwa usia kekuasaan tak akan lama lagi.<br />
Baginya usia penguasa pasti ada batasnya, demikian pula dengan<br />
pemerintahan yang otoriter. Pada akhirnya, Thukul yakin, rakyat pasti<br />
akan menang.<br />
apa penguasa kira<br />
rakyat hidup di hari ini saja<br />
apa penguasa kira<br />
ingatan bisa dikubur<br />
dan dibendung dengan moncong tank<br />
apa penguasa kira<br />
selamanya ia berkuasa<br />
tidak!<br />
tuntutan kita akan lebih panjang umur<br />
ketimbang usia penguasa<br />
derita rakyat selalu lebih tua<br />
walau penguasa baru naik<br />
mengganti penguasa lama<br />
umur derita rakyat<br />
panjangnya sepanjang umur peradaban<br />
umur penguasa mana<br />
pernah melebihi tuanya umur batu akik<br />
yang dimuntahkan ledakan gunung berapi?<br />
ingatan rakyat serupa bangunan candi<br />
kekejaman penguasa setiap jaman<br />
terbaca di setiap sudut dan sisi<br />
yang menjulang tinggi<br />
Thukul yakin bahwa keyakinan dirinya, juga keyakinan mayoritas rakyat,<br />
101<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
tak bisa diubah meskipun penguasa menggunakan cara-cara represif<br />
kepada rakyatnya.<br />
ketika datang malam<br />
aku menjadi gelap<br />
ketika pagi datang<br />
aku menjadi terang<br />
aku rakyatmu<br />
hidup di delapan penjuru<br />
kau tak bisa menangkapku<br />
karena kau tak mengenalku<br />
kau tak bisa mendengarkan aku<br />
karena kau terus berbicara<br />
berbicara dan berbicara<br />
dengan mulut senapan<br />
pembantaian- pembantaian<br />
dan pembantaian<br />
mayat-mayat bergelimpangan<br />
mayat-mayat disembunyikan<br />
kau tak bisa menguburkan aku<br />
kau tak bisa menyembuhkan lukaku<br />
karena kau tak kenal aku<br />
karena kau terus berbicara<br />
berbicara dan berbicara<br />
dengan tembakan dan ancaman<br />
dan penjara<br />
Meski terus bergerak dengan cara berpindah-pindah untuk<br />
menghindari pencarian dan penangkapan, Thukul merasa dirinya<br />
nyaman dan sama sekali tak cemas. Dirinya merasa waras sepenuhnya.<br />
Berikut puisi yang menggambarkan hal ini.<br />
102
habis cemasku<br />
kau gilas<br />
habis takutku<br />
kau tindas<br />
kini padaku tinggal tenaga<br />
mendidih!<br />
segala telah kau rampas<br />
kau paksa aku tetap bodoh<br />
miskin dan nelan ampas<br />
kini padaku tinggal tenaga<br />
mengepal-ngepal<br />
di jalan-jalan<br />
habis cemasku<br />
kau gilas<br />
habis takutku<br />
kau tindas<br />
aku masih tetap waras!<br />
Hal ini berbeda dengan penguasa yang menurut Thukul sedang<br />
risau. Pergolakan yang sedang terjadi Thukul anggap telah menggoyang<br />
kursi kedudukan sang penguasa. Si penguasa digambarkannya dalam<br />
puisi berikut.<br />
ayo kita tebakan!<br />
dia raja<br />
tapi tanpa mahkota<br />
punya pabrik punya istana<br />
coba tebak siapa dia?<br />
dia adalah aku!<br />
dia kaya<br />
keluarganya punya saham di mana-mana<br />
tapi negaranya rangking tiga<br />
103<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
paling korup di dunia<br />
coba tebak siapa dia?<br />
dia adalah aku!<br />
dia tua<br />
tapi ingin tetap berkuasa<br />
tak boleh ada calon lain<br />
selain dia<br />
kalau marah<br />
mengarahkan angkatan bersenjata<br />
rakyat kecil yang tak bersalah ditembak jidatnya<br />
coba tebak siapa dia?<br />
dia adalah aku!<br />
dia sakti<br />
tapi pasti mati<br />
meski seakan tak bisa mati<br />
coba tebak siapa dia?<br />
dia adalah aku!<br />
siapa aku?<br />
aku adalah diktator<br />
yang tak bisa tidur nyenyak!<br />
Thukul yakin bahwa penguasa tak mungkin menyembunyikan<br />
bau busuk dari rekayasa di balik Peristiwa 27 Juli 1996. Meski sejumlah<br />
jendral menyangkal keterlibatan Pemerintah di balik peristiwa tersebut<br />
dan menuding sejumlah aktivis yang mendalangi, Thukul yakin bahwa<br />
rakyat sudah cerdas. Rakyat tak bisa ditipu lagi dengan berbagai pidato<br />
dan kebohongan. Berikut puisi yang ditulis Thukul.<br />
ujung rambut ujung kuku<br />
gendang telinga<br />
dan selaput bola mataku<br />
tidak mungkin lupakan kamu<br />
bilur di punggung<br />
104
nyeri di tulang<br />
berhari-hari<br />
darah di helai rambut ujung kuku<br />
dendang telinga<br />
dan selaput bola mataku<br />
telah mengotori namamu<br />
nyeri di tulang<br />
berhari-hari<br />
bilur di punggung<br />
karena sabetan<br />
telah mencoreng namamu<br />
kau tak kan bisa mencuci namamu<br />
sekalipun 1000 mobil pemadam kebakaran<br />
kau kerahkan<br />
kau tak kan bisa mencuci tanganmu<br />
sekalipun 1000 pengeras suara<br />
melipatgandakan pidatomu<br />
suara rakyat adalah suara Tuhan<br />
dan kalian tak bisa membungkam Tuhan<br />
sekalipun kalian memiliki 1.000.000 gudang peluru<br />
Bagi Thukul, selama pelarian, faktor cuaca dinilai menjadi faktor<br />
yang menguntungkan dirinya. Orang-orang yang mencarinya akan<br />
kesulitan melakukan pekerjaannya saat malam tiba. Apalagi bila air<br />
mengucur dari langit dengan derasnya. Cuaca yang buruk dan kegelapan<br />
malam yang pekat adalah selimut bagi persembunyian Thukul. Hujan<br />
juga sepertinya memberikan harapan akan munculnya perubahan.<br />
hujan malam ini turun<br />
untuk melindungiku<br />
intel-intel yang bergaji kecil<br />
105<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
pasti jengkel dengan yang memerintahmu<br />
hujan malam ini turun<br />
untuk melindungiku<br />
agar aku bisa istirahat<br />
agar tenagaku pulih<br />
setelah berhari-hari lelah<br />
agar aku tetap segar<br />
dan menang<br />
hujan malam ini turun<br />
untuk melindungiku<br />
bunyi kodok dan desir angin<br />
membikin pelupuk mataku membesar<br />
aku ngantuk dan ingin tidur<br />
biarlah para serdadu di ibukota<br />
berjaga-jaga dengan senapan M-16nya<br />
biarlah penguasa sibuk sendiri<br />
dengan ketakutannya<br />
karena telah mereka taruh sendiri<br />
bom waktu di mana-mana<br />
mereka menciptakan musuh<br />
dan menembaknya sendiri<br />
mereka menciptakan kerusuhan<br />
demi mengamankannya sendiri<br />
hujan malam ini turun<br />
untuk melindungiku<br />
malam yang gelap ini untukku<br />
malam yang gelap ini selimutku<br />
106
selamat tidur tanah airku<br />
selamat tidur anak-istriku<br />
saatnya akan tiba<br />
akan tiba<br />
bagi merdeka<br />
untuk semua<br />
Thukul merasa dirinya, sebagaimana para aktivis pro-demokrasi<br />
lainnya, harus mampu bertahan, bernafas panjang. Thukul mengajak<br />
rekan-rekannya untuk tidak kalut menghadapi keadaan dan terus<br />
berjuang menghadapi berbagai cobaan yang saat itu datang mendera<br />
mereka.<br />
bernafas panjanglah<br />
jangan ditelan kalut<br />
bernafas panjanglah<br />
jangan dimakan takut<br />
bernafas panjanglah<br />
jangan berlarut-larut<br />
bernafas panjanglah<br />
jangan surut<br />
bernafas panjanglah<br />
walau gelap<br />
bernafas panjanglah<br />
walau pengap<br />
bernafas panjanglah kau, bernafas panjanglah para korban<br />
bernafas panjanglah aku<br />
bernafas panjanglah kalian<br />
bernafas panjanglah semua<br />
bernafas panjanglah<br />
melihat tank-tank dikerahkan<br />
bernafas panjanglah<br />
melihat tentara mondar-mandir<br />
berselendang M-16<br />
107<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
bernafas panjanglah<br />
mendengar para aktivis ditangkapi<br />
bernafas panjanglah<br />
para kambing hitam yang diadili<br />
bernafas panjanglah<br />
dengan pemutar-balikan ini<br />
mereka ingin sejarah dibaca bersih<br />
bagaimana mungkin<br />
jika mereka menulis dengan sobekan daging<br />
laras senapan<br />
dan kubangan darah<br />
baca kembali semuanya<br />
dan bernafas panjanglah<br />
bernafas panjanglah akal<br />
bernafas panjanglah hati<br />
bangun<br />
dan bernafas panjanglah!<br />
Dalam persembunyian yang dilakukannya, Thukul sangat<br />
berdisiplin menjaga diri. Dia sadar bahwa ada banyak orang mengintai<br />
tempat-tempat yang dicurigai. Dia hanya bangun membuka kran air dan<br />
menggunakan toilet saat tuan rumah ada di rumah. Dia tak menyalakan<br />
lampu meski hari telah gelap. Dia lebih memilih menunggu sang pemilik<br />
rumah pulang. Dia diam dalam sunyi. Karena itulah Thukul sangat peka<br />
dengan keadaan sekelilingnya.<br />
di ruang ini yang bernafas cuma aku<br />
cecak dan serangga<br />
air menetes rutin dari kran ke bak mandi<br />
semakin dekat aku dengan detak jantungku<br />
dingin ubin, lubang kunci, pintu tertutup, kurang cahaya<br />
108
kini bagian hidupku sehari-hari<br />
di sini bergema puisi<br />
di antara garis lurus tembok<br />
lengkung meja kursi<br />
dan rumah sepi<br />
puisi yang ditajamkan<br />
pukulan dan aniaya<br />
tangan besi penguasa<br />
Bulan-bulan Agustus minggu kedua, di sekitar tempat Thukul<br />
bersembunyi ia hanya bisa mengamati situasi di luar rumah dengan cara<br />
mengintip melalui lubang kunci. Dia menyaksikan berbagai aktivitas<br />
masyarakat dalam rangka menyambut peringatan Kemerdekaan 17<br />
Agustus.<br />
bulan agustus sudah tiba<br />
penduduk ramai-ramai pasang bendera<br />
tapi aku hanya lihat yang di seberang rumah saja<br />
kuintip dari lubang kunci<br />
sebab aku dikejar-kejar penguasa<br />
sudah puluhan hari aku tak melihat angkasa<br />
kehidupan di sekelilingku kusimak<br />
dari datak-deru dan tawanya<br />
aku tak bisa lihat wujud dan wajahnya<br />
aku ditahan bukan dipenjara<br />
aku disel bukan dibui<br />
sebab kehidupan sehari-hari<br />
adalah penjara nyata<br />
rakyat negeri ini<br />
Thukul juga membaca berita dari koran yang dibawa pulang oleh<br />
teman yang rumahnya diinapinya. Dia juga merasakan di mana-mana<br />
109<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
banyak orang tengah menyambut suasana peringatan kemerdekaan.<br />
Namun Thukul mempertanyaan makna kemerdekaan yang<br />
sesungguhnya. Berikut puisi yang ditulisnya.<br />
sebuah bank<br />
memasang iklan<br />
ukuran setengah halaman koran, teriaknya:<br />
Dirgahayu Republik Indonesia 51 th<br />
dengan huruf kapital<br />
iklan itu juga memekik-mekik:<br />
MERDEKA MERDEKA MERDEKA<br />
sementara itu ratusan aktivis<br />
di daerah dan di ibukota ditangkapi<br />
sebuah iklan<br />
ukuran setengah halaman koran<br />
menggusur kenyataan yang sewenang-wenang<br />
yang seharusnya diberitakan<br />
MERDEKA MERDEKA MERDEKA<br />
siapa yang merdeka?<br />
Kebosanan selama berhari-hari bersembunyi dalam sunyi<br />
dengan membatasi gerak-gerik diri, membuat Thukul merasa bahwa<br />
meski dia berada di sebuah rumah, namun sesungguhnya dia ibarat<br />
berada di penjara. Sebuah hal yang kontras dengan suasana di luar<br />
rumah, di mana ada sejumlah orang tengah berlatih berbaris untuk<br />
upacara 17 Agustusan.<br />
di atas rumah ada burung<br />
ku tahu dari kicaunya<br />
di luar rumah ada orang<br />
kutangkap lagi dari cakap<br />
dan langkah kakinya<br />
110
ini rumah biasa<br />
tak beda penjara<br />
tadi pagi kubaca di koran<br />
kabar penangkapan-penangkapan<br />
tapi sore ini<br />
ku dengar di jalan<br />
orang latihan baris-berbaris<br />
untuk merayakan hari kemerdekaan<br />
Dari balik kain gorden rumah persembunyian, Thukul<br />
tampaknya berkesempatan mencuri-curi lesempatan untuk mengintip<br />
pemandangan di luar rumah. Ia menyaksikan pemandangan indah di<br />
pagi hari. Indahnya sebuah pagi, tapi menurut Thukul akan lebih indah<br />
lagi bila negeri ini terbebas dari ganasnya kuasa tirani. Berikut sebuah<br />
puisi berjudul ”Bagi Siapa Kalian Memetik Panenan”.<br />
Bagi Siapa Kalian Memetik Panenan<br />
pagi dingin<br />
udara masih mengandung embun<br />
bukit-bukit di kejauhan<br />
disaput arak-arakan halimun<br />
matahari terbnit<br />
sempurna bulat merah setampah di langit<br />
batang-batang pohon besar dan cabang-cabangnya<br />
seperti ratusan penari<br />
yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi<br />
kususuri keheningan ini<br />
sendiri<br />
jilatan matahari<br />
segarnya udara pagi<br />
alangkah indah negri ini<br />
andai lepas dari masa ganas tirani<br />
111<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
Di balik rasa percaya diri akan keamanan yang melingkupinya,<br />
Thukul sepertinya merasa kesepian. Ia juga merasa bahwa ia harus<br />
bergegas berpindah dan tak bisa berlama-lama di tempat<br />
”penampungan” saat itu. Meski ia merasa nyaman dengan kesunyian<br />
yang melingkupinya, ia lebih memilih menghindari penangkapan.<br />
Berikut puisi yang ditulisnya.<br />
nonstop 24 jam<br />
yang berkuasa di sini<br />
adalah cahaya<br />
saban pagi ia membuat garis-garis lurus<br />
di sekitar jendela<br />
gambar motif gorden tampak jelas<br />
coklat hitam dan putihnya<br />
lalu pada sore hari<br />
ia mengubah warna langit-langit<br />
sudut-sudut tembok<br />
bidang ubin dan susunan benda-benda<br />
yang ada di dalamnya<br />
dan bila malam tiba<br />
telapak kakiku diberinya mata<br />
demikian pula punggung tangan<br />
dan jari-jarinya<br />
saat aku terbaring<br />
serasa yang ada<br />
cuma desir angin<br />
detak jantung<br />
tulang-tulang<br />
dan hembusan nafasku saja<br />
tapi aku harus pergi<br />
dari kesunyian ini<br />
sebelum penguasa merenggut<br />
aku dan damai ini<br />
112
Wiji Thukul memang kemudian memutuskan pergi dari tempat<br />
persembunyian, tempat menuliskan semua puisinya ini. Dia terus<br />
berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Setelah Peristiwa 27 Juli 1996<br />
hingga 1998, sejumlah aktivis ditangkap, diculik dan hilang, termasuk<br />
Thukul. Sejumlah orang masih melihatnya di Jakarta pada April 1998.<br />
Thukul masuk daftar orang hilang sejak tahun 2000. Keluarganya<br />
7<br />
melaporkan hilang pada April 2000, sampai saat ini keberadaannya<br />
masih tetap misteri.<br />
Hingga sekarang Widji Thukul tidak diketahui nasibnya, apakah<br />
ia sudah meninggal atau berada di suatu tempat. Puisi dan karyakaryanya<br />
masih dibaca orang. Pada Agustus 2009, DPR menyetujui<br />
rekomendasi Pansus DPR tentang penghilangan orang secara paksa<br />
untuk meminta Presiden RI agar segera mengeluarkan Keppres<br />
pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc. DPR juga setuju dengan<br />
permintaan Komnas HAM agar Kepolisian Republik Indonesia segera<br />
mencari dan menemukan Wiji Thukul beserta 12 orang lain yang<br />
dinyatakan hilang, dalam keadaan hidup ataupun mati.<br />
113<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
7. Hilangnya Wiji Thukul pada sekitar Maret 1998 menurut KontraS diduga kuat berkaitan dengan aktivitas<br />
yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Saat itu bertepatan dengan peningkatan operasi represif yang<br />
dilakukan oleh rezim Orde Baru dalam upaya pembersihan aktivitas politik yang berlawanan dengan Orde<br />
Baru. Operasi pembersihan tersebut hampir merata dilakukan diseluruh wilayah Indonesia. Kita mencatat<br />
dalam berbagai operasi, rezim Orde Baru juga melakukan penculikan terhadap para aktivis (22 orang)<br />
yang hingga saat ini 13 orang belum kembali. Lihat: Siaran Pers KontraS No: 7/SP-KONTRAS/II/2000<br />
tentang Hilangnya Wiji Thukul.
TINJAUAN
”Mengindonesiakan”<br />
Anak Timor Leste<br />
Razif<br />
Judul : Making Them<br />
Indonesians: Child<br />
Transfers out of East<br />
Timor<br />
Penulis : Helene van Klinken<br />
Penerbit : Victoria: Monash<br />
University, 2012<br />
Kolasi : 252 hal<br />
ISBN : 9781876924072<br />
Sejak abad ke-20 dan memasuki 21 setiap peperangan dan konflik<br />
bersenjata yang terjadi di muka bumi senantiasa melibatkan anak.<br />
Sepanjang Perang Dunia II, menurut sejarawan Peter Stearns, paling<br />
tidak satu setengah juta anak hilang dan mati terbunuh. Di Eropa dan<br />
Asia, anak-anak yang dilibatkan dalam perang tersebut adalah anak-anak<br />
1<br />
dari keturunan Yahudi.<br />
Militer Nazi sebagai dalang pembunuhan anak terbesar<br />
sepanjang Perang Dunia II berkeyakinan bahwa anak-anak Yahudi perlu<br />
dibunuh agar di masa depan keturunan mereka dapat dihambat.<br />
Kejahatan yang sama terjadi di Argentina selama periode ”Dirty War”<br />
1976-1983. Anak dan bayi yang diduga keturunan aktivis gerakan kiri<br />
diculik oleh penguasa militer Argentina dengan maksud untuk dididik<br />
1. Peter Stearns menegaskan bahwa peperangan atau konflik yang melibatkan anak-anak dengan tujuan<br />
untuk menaklukkan orang tuanya. Lihat, Peter. N. Stearns. Childhood in World History. (New York:<br />
Routledge, 2011), hlm. 147.<br />
117
TINJAUAN<br />
”Mengindonesiakan” Anak Timor Leste<br />
dan diurus tentara supaya ketika dewasa tidak seperti orang tuanya yang<br />
radikal dan pembangkang.<br />
Tak hanya berlangsung di negara yang mengalami peperangan,<br />
tampaknya metode serupa dilakukan oleh negara-negara yang memiliki<br />
kompleksitas isu etnis, seperti Australia. Di Negeri Kanguru itu pada<br />
paruh abad 20 terjadi pengambil-alihan anak-anak bumiputera aborigin<br />
Australia oleh orang-orang kulit putih. Tujuan pengambilan paksa ini<br />
agar anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang 'superior', dan<br />
dijauhkan dari keterbelakangan kebudayaan orang tuanya.<br />
Pemerintahan Orde Baru Soeharto pernah melakukan kebijakan<br />
migrasi paksa terhadap anak tatkala menginvasi Timor Leste. Sepanjang<br />
masa invasi sejak 1976 hingga 1999 berlangsung pemindahan anak<br />
Timor Leste ke Indonesia. Pemindahan anak Timor Leste itu dianggap<br />
sebagai bagian dari proyek kebudayaan yang dilakukan oleh rezim Orde<br />
Baru untuk membuat mereka Indonesia. Buku yang disusun oleh<br />
Helene Van Klinken berjudul Making Them Indonesians ini menceritakan<br />
pengambilan paksa anak-anak Timor Leste ke Indonesia itu.<br />
Pesan kuat buku ini tergambar melalui kulit muka buku berupa<br />
foto Presiden Soeharto dan Nyonya Tien Soeharto beserta anak-anak<br />
Timor Leste yang sedang berkunjung ke Istana Presiden di Jalan<br />
Cendana, Jakarta Pusat. Anak-anak Timor Leste itu dianggap sebagai<br />
”anak presiden”. Mereka disekolahkan dan diurus dengan tanggungan<br />
biaya oleh Yayasan Dharmais milik keluarga Soeharto.<br />
Pada tahun 1986 diperkirakan jumlah anak Timor Leste yang<br />
dibawa ke Indonesia mencapai 40.000 orang lebih (hlm. xxvi). Hasil<br />
perhitungan itu merupakan jumlah besar.<br />
Buku ini sejatinya merupakan disertasi Helen di Universitas<br />
Queensland, Brisbane, Australia. Penyusunannya menggunakan<br />
pendekatan sejarah lisan. Melalui metode tersebut Helen berupaya<br />
merekonstruksi proses pemindahan anak-anak Timor Leste ke<br />
Indonesia.<br />
Sejarah Pengambilan Anak Timor Leste<br />
Penelitian Helen berangkat dari digelarnya Komisi Penerimaan,<br />
Kebenaran dan Rekonsialiasi Timor Leste (CAVR) tahun 2003. Dia<br />
melakukan serangkaian wawancara baik dengan korban yakni yang<br />
waktu lampau masih anak-anak maupun dengan pelaku—perwira<br />
118
tentara, pegawai negeri, rumah yatim piatu, pengurus gereja, masjid, dan<br />
yayasan Islam. Awalnya anak-anak yang dipindahkan ke Indonesia<br />
adalah anak yatim piatu dari kalangan Apodeti dan UDT.<br />
Pemindahan anak-anak Timor Leste ke Indonesia berlangsung<br />
secara sistematis, dan tentu pemindahan tersebut melibatkan negara.<br />
Kenapa negara begitu berkepentingan untuk memindahkan anak Timor<br />
Leste ke Indonesia? Juga, institusi-institusi apa saja yang terlibat?<br />
Di Timor Leste pada masa Portugis telah berdiri sebuah rumah<br />
yatim piatu. Pada awal pendudukan Indonesia mulai 1976-1977 rumah<br />
yatim piatu itu diurus oleh pasukan Brawijaya. Pada paruh 1977 tentara<br />
menyerahkan pengelolaannya pada Dinas Sosial. Penyerahan itu<br />
bersamaan dengan diproklamasikannya Timor-Timur sebagai provinsi<br />
ke-27 Indonesia.<br />
Pada tahun yang sama berdiri Yayasan Dharmais di bawah<br />
kendali keluarga Soeharto. Yayasan ini dipersiapkan untuk menyambut<br />
20 anak Timor-Timur yang dipindahkan ke Jawa Tengah. Mereka<br />
ditampung di S.T. Thomas, Semarang. Biaya sekolah, makan, seragam<br />
dan lain-lain dibiayai oleh Yayasan Dharmais. Namun, terungkap dari<br />
wawancara Helen bahwa banyak komponen biaya yang tidak dibayarkan<br />
oleh Yayasan Dharmais.<br />
Institusi lain yang terlibat dalam pemindahan anak Timor Leste<br />
adalah Kinderdof yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Organisasi ini<br />
mempunyai jaringan internasional dalam mengurus anak-anak yatim<br />
piatu. Awalnya, Kinderdof diperuntukkan bagi keluarga Apodeti dan<br />
UDT Kepanjangannya? saja. Kinderdof menggunakan perawat khusus<br />
untuk mengurus anak-anak. Itu sebabnya ia dianggap sebagai tempat<br />
penampungan anak kelas satu. Tempat ini dilengkapi pula dengan<br />
pendidikan sekolah.<br />
Institusi lain yang terlibat adalah Panti Penyantunan Anak<br />
Taruna Negara (PPATN). PPATN berlokasi di Bandung dijalankan oleh<br />
Departemen Sosial. Pemindahan anak Timor Leste diperankan pula<br />
oleh misi Islam untuk memperluas pengaruhnya di ruang teritorial<br />
provinsi baru itu. Masuknya Islam ke Timor-Timur bermula dari tentara.<br />
Banyak anggota militer baik perwira maupun prajurit menjadi anggota<br />
Rawatan Rohani Islam.<br />
Keterlibatan tentara dalam islamisasi pada masa awal invasi<br />
Indonesia di Timor-Timur, melempangkan jalan bagi Dewan Dakwah<br />
119<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
TINJAUAN<br />
”Mengindonesiakan” Anak Timor Leste<br />
Islamiyah Indonesia (DDII) untuk mengembangkan sayap di sana.<br />
Mereka membangun sekolah Islam dan langgar. Akan tetapi islamisasi<br />
oleh DDII tidak berlangsung mulus. Terjadi perlawanan terhadap<br />
pembangunan sarana ibadah tersebut yang membuat DDII<br />
memutuskan untuk mengirim anak-anak Timor-Timur ke Indonesia<br />
untuk dididik.<br />
Pada 1982, DDII mendirikan Yayasan Kesejahteraan Islam<br />
Nasrullah (Yakin), organisasi yang kelak menyebarkan anak-anak Timor<br />
Leste ke pesantren-pesantren di Jawa Barat dan Sulawesi. Dalam<br />
pengiriman anak itu, Yakin dibantu oleh militer, Departemen Agama,<br />
dan keluarga Arab Timor-Timur berdomisili di kampung Alor, Dili<br />
Barat. Motivasi Yakin mengirim anak-anak itu ke Indonesia agar setelah<br />
mereka selesai pendidikan sekolah pesantren dapat menjadi guru dan<br />
pendakwah di Timor Leste.<br />
Proses Pemindahan Anak dari Timor Leste ke Indonesia<br />
Bagaimana proses pengambilan anak-anak itu terjadi? Dalam<br />
menjelaskan proses pemindahan anak-anak Timor Leste, terdapat<br />
empat sasaran kelompok anak yang dipindahkan ke Indonesia. Ini<br />
persepsi Helene sebagaimana ditulis di buku? Atau opini pribadi?<br />
Pertama, anak-anak di wilayah pertempuran tahun 1976-1978<br />
saat tentara Indonesia melakukan operasi pengepungan dan<br />
pemusnahan di basis-basis perlawanan Timor Leste. Operasi militer<br />
Indonesia awal-awal masa invasi itu banyak menelan korban perempuan<br />
dan anak-anak. Mereka terpaksa turun dari pegunungan menyerah.<br />
Mereka kelaparan dan kekurangan obat-obatan.<br />
Banyak anak-anak itu kemudian dibawa ke Indonesia ketika<br />
prajurit pulang kampung. Mereka dititipkan terlebih dulu di rumah<br />
yatim-piatu Seroja. Dalam situasi seperti ini anak-anak itu dianggap telah<br />
yatim piatu dan hidup dalam kemiskinan.<br />
Kedua, anak-anak yang berada di kamp-kamp penahanan yang<br />
tinggal bersama orang tua atau dengan walinya—biasanya paman—dan<br />
orang dewasa lainnya. Anak-anak itu hidup miskin dan kekurangan<br />
makanan. Biasanya tentara memberikan makanan dan pakaian. Ketika<br />
tentara habis masa tugasnya, anak-anak itu dibawa ke Indonesia.<br />
Ketiga, anak-anak yang menjadi Tenaga Bantuan Operasi<br />
(TBO). Biasanya anak-anak yang menjadi TBO berumur 8-13 tahun.<br />
120
Pekerjaan mereka membawa barang-barang, alat-alat dan juga mengisi<br />
amunisi senjata saat melakukan pertempuran dengan gerakan<br />
perlawanan.<br />
Anak-anak yang dipekerjakan sebagai TBO tidak mendapatkan<br />
upah. Mereka seperti budak. Mereka hanya mendapatkan makan.<br />
Padahal dalam prosedur ketentaraan, anak-anak TBO harus<br />
dikembalikan lagi ke orang tua dan bersekolah. Tujuan para perwira<br />
tentara membawa anak-anak bekas TBO agar mereka dapat dididik<br />
untuk menjadi Indones yang pro-integrasi.<br />
Keempat, anak-anak pejuang gerilyawan dari Falintil menjadi<br />
sasaran tentara untuk dibawa ke Indonesia. Di kalangan elit tentara<br />
Indonesia ada imajinasi untuk menaklukkan musuh, keturunannya perlu<br />
dipurifikasi. Tentara memilih anak-anak berkulit bersih bersinar yang<br />
dibawa ke Indonesia, seperti kepercayaaan kolonialis Eropa awal abad 20<br />
yang membawa anak-anak mestizo dari musuh yang dijajah.<br />
Motivasi Pemindahan<br />
Motivasi tentara membawa anak-anak Timor Leste ke Indonesia sangat<br />
beragam. Namun bila ditelisik motivasi utamanya bertujuan untuk<br />
menaklukkan perjuangan orang tua mereka yang anti-integrasi. Anakanak<br />
Timor Leste itu diperadabkan dan menjadi patuh.<br />
Selain itu, pemindahan anak oleh tentara ke Indonesia dapat juga<br />
dilihat sebagai bentuk penyanderaan. Tentara Indonesia berpikir jika<br />
anak-anak Timor Leste disandera maka pejuang Timor Leste mau<br />
berintegrasi dengan Indonesia.<br />
Hampir seluruh anak yang dibawa ke Indonesia baik oleh tentara<br />
maupun lembaga pemerintah Orde Baru dipaksa menghapus identitas<br />
ke ”timorlesteannya”. Rata-rata orang tua angkat yang notabene orang<br />
Indonesia menyembunyikan fakta bahwa anak itu berasal dari Timor<br />
Leste. Misalkan saja, anak yang diangkat dipaksa menganut agama orang<br />
tua angkat dan mengganti namanya menjadi berbau ”Indonesia”.<br />
Tentara-tentara Indonesia jarang yang menepati janji untuk<br />
mengembalikan anak ke orang tua atau wali setelah tamat sekolah. Dari<br />
tindakan ini terlihat jika tentara menjadikan pengambilan anak dari pihak<br />
lawan sebagai bagian dari strategi perang.<br />
Rezim Orde Baru menganggap pemindahan anak Timor Leste<br />
merupakan simbol integrasi. Negara berkepentingan untuk mengubah<br />
121<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
TINJAUAN<br />
”Mengindonesiakan” Anak Timor Leste<br />
kebudayaan dan identitas anak itu. Mereka sehari-hari menggunakan<br />
bahasa daerah Jawa, jika tinggal di Jawa Tengah, dan berbahasa Sunda<br />
bila tinggal di Jawa Barat. Mereka berbicara di depan kelas atau<br />
berdiskusi dengan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan<br />
Indonesia. Intinya mereka bersekolah di Indonesia dipaksa untuk<br />
menjadi orang Indonesia.<br />
Dalam penyusunan buku ini Helen menggunakan dokumendokumen<br />
terkait dari Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja<br />
dan lain-lain. Menurut penelitian Helen, anak-anak Timor Leste yang<br />
dibawa ke Indonesia berumur antara 2 hingga 10 tahun, dan ada yang<br />
berumur belasan tahun. Anak di bawah umur 10 tahun digemari untuk<br />
dibawa oleh pelaku karena mudah dipengaruhi.<br />
Penutup<br />
Tanpa disadari tindakan rezim Orde Baru mendukung pemindahan anak<br />
adalah melanggar salah satu poin Convention Genocide (pemusnahan) PBB<br />
tahun 1951. Anak-anak adalah sumber penting untuk menyambung<br />
nilai-nilai kebudayaan dari suatu kelompok bangsa. Asumsinya bila<br />
anak-anak dalam satu periode perjalanan bangsa banyak hilang, maka<br />
bangsa itu mengalami hambatan dalam perkembangan.<br />
Anak-anak yang dibawa baik oleh individu maupun institusi<br />
yang didukung negara tidak memperhatikan faktor kejiwaan atau<br />
psikologis anak-anak itu. Banyak orang tua mati terbunuh atau dianiaya<br />
disaksikan oleh anak-anak itu. Faktor yang mencekam itu berada dalam<br />
benak anak tanpa pernah diperhatikan oleh pihak pelaku.<br />
Memasuki tahun 2003 Pemerintah Indonesia mengumumkan<br />
penghapusan status pengungsi bagi warga Timor Leste. Pengumuman<br />
itu mempunyai arti anak-anak yang dibawa mempunyai kesempatan<br />
untuk bisa bergabung kembali ke Timor Leste. Mereka yang diambil<br />
paksa masa itu sekarang sudah dewasa. Ada yang kembali ke Timor<br />
Leste, ada yang tidak.<br />
Salah satu anak yang menjadi korban tersebut adalah Biliki.<br />
Perempuan ini telah menikah dengan seorang tentara di Jakarta dan<br />
mempunyai tiga orang anak. Biliki berkesempatan untuk kembali<br />
sementara ke Dili saat memberikan kesaksian di CAVR. Anak korban<br />
pengambilan lainnya adalah Petrus Kanisius. Beda dengan Biliki, Petrus<br />
menyatakan pulang ke Timor Leste. Sekarang ini dia telah diangkat<br />
122
menjadi kepala sekolah SMA di Dili.<br />
Hampir rata-rata anak-anak itu telah dipisahkan dari ranah<br />
kebudayaan mereka selama 18 tahun dan bahkan lebih dari itu. Mereka<br />
sudah tidak memahami bahasa, dan adat istiadat. Anak-anak yang<br />
kembali harus mengikuti upacara adat karena mereka dianggap telah<br />
mati.<br />
Namun, banyak anak-anak yang belum kembali atau tidak bisa<br />
kembali karena telah kawin-mawin di Indonesia. Sejarah sosial<br />
pemindahan anak-anak Timor Leste sebuah cerita yang unik. Narasi itu<br />
belum banyak diketahui oleh publik di Indonesia dan Timor Leste.<br />
Untuk memperluas penyebaran kisah itu buku ini perlu diterjemahkan<br />
ke dalam kedua bahasa: Indonesia dan Tetun, Timor Leste.<br />
123<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
KONTRIBUTOR
KONTRIBUTOR<br />
Razif<br />
Sejarahwan, aktif di Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), mempunyai<br />
kepedulian pada sejarah hubungan kerja dan juga masalah ingatan sosial.<br />
Saat ini ia sedang menyelesaikan penelitian bersama ELSAM tentang<br />
pola penghilangan paksa di Indonesia.<br />
Agung Putri Astrid<br />
Pekerja HAM, anggota Perkumpulan dan mantan Direktur Eksekutif<br />
ELSAM, koordinator ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus<br />
(AIPMC). Putri juga penggagas sekaligus penggerak Pertemuan Korban<br />
Orde Baru, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Relawan Penggerak<br />
Jakarta Baru (RPJB), dan alumnus Institute of Social Studies (ISS), Den<br />
Haag, Belanda.<br />
Budiawan<br />
Staf pengajar Program Studi Kajian Budaya dan Media, Sekolah<br />
Pascasarjana UGM. Ia memperoleh gelar PhD di bidang Kajian Asia<br />
Tenggara, National University of Singapore, 2003. Aktif menulis opini<br />
tentang masa lalu dan pelanggaran hak asasi manusia.<br />
Stanley Adi Prasetyo<br />
Menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM periode 2007-2012, aktif<br />
dalam gerakan sosial sejak di bangku kuliah di Universitas Satya Wacana<br />
Salatiga pada awal 1980an. Terlibat pula dalam sejumlah organisasiorganisasi<br />
yang bergerak dalam isu hak asasi manusia, seperti ELSAM,<br />
Demos, dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI).<br />
Herry Sucipto<br />
Staf Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI<br />
Hajriyanto Y. Thohari<br />
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Periode 2009-<br />
2012, terpilih sebagai Anggota DPR dari daerah pemilihan IV Jawa<br />
Tengah.<br />
127
Zainal Abidin<br />
Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),<br />
alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), dan terlibat<br />
dalam advokasi ICC bersama sejumlah aktivis hak asasi manusia lain.<br />
Otto Syamsuddin Ishak<br />
Terlahir di Yogyakarta tahun 1959, meraih doktor di bidang sosiologi<br />
dari Universitas Indonesia (2011) dengan judul disertasi, Aceh Pasca<br />
Konflik: Arena Kontestasi 3 Varian Nasionalisme. Gelar master di<br />
bidang sosiologi dan sarjana geografi diraih dari Universitas Gadjah<br />
Mada (1995 dan 1987). Sejak 1989 tercatat sebagai dosen pada<br />
Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh.<br />
128
PEDOMAN PENULISAN JURNAL<br />
Redaksi Jurnal Dignitas menerima kiriman tulisan dengan pedoman<br />
sebagai berikut:<br />
�Jurnal ini mengutamakan penulisan artikel dengan gaya bahasa yang<br />
sederhana, mudah dicerna, dan tidak rumit. Ini diterapkan agar<br />
tulisan dapat dipahami oleh kalangan yang lebih luas, tidak cuma<br />
kalangan hukum saja.<br />
�Audiens jurnal ini mencakup juga masyarakat nonhukum yang<br />
memiliki perhatian luas tentang hukum dan dinamikanya. Hukum<br />
mengandung kosakata yang khusus, kaku, mungkin juga tertutup,<br />
yang hanya dimengerti oleh kalangan hukum saja. Kata-kata seperti<br />
retroaktif, susah dimengerti oleh masyarakat nonhukum. Sehingga<br />
kata-kata yang sekiranya rumit dimengerti masyarakat nonhukum<br />
perlu diberi penjelasannya supaya mudah dipahami.<br />
�Tiap kosakata asing diusahakan dicari padanannya dalam bahasa<br />
Indonesia, kecuali untuk jurnal edisi bahasa Inggris. Contoh: by<br />
ommission, maka diganti atau ditambahi keterangan pembiaran.<br />
Namun, jika tak ada, atau susah menemukannya dalam bahasa<br />
Indonesia, tak masalah.<br />
�Pada dasarnya, jurnal ini semi akademis. Tak terlalu ketat dalam<br />
penggunaan metodologi maupun pemakaian kosakata ilmiah.<br />
Penulisannya naratif, diawali dengan abstraksi tulisan. Tulisan harus<br />
fokus pada masalah tanpa melebarkan pembahasan.<br />
�Panjang tulisan semua rubrik, FOKUS, DISKURSUS, OASE sekitar<br />
20.000-23.000 karakter, kecuali TINJAUAN. Sedang untuk rubrik<br />
TINJAUAN mengulas buku atau kumpulan buku, film, karya sastra,<br />
pertunjukan kesenian, panjangnya antara 10.000 – 13.000 karakter.<br />
- Kami menerima tulisan dengan sumber catatan kaki atau<br />
footnote, bukan catatan akhir atau endnote dan catatan<br />
perut.<br />
- Contoh catatan kaki untuk sumber buku:<br />
Yando Zakaria, Abih Tandeh, Cetakan Pertama,<br />
(Jakarta: Elsam, 2000), halaman 143.<br />
- Contoh catatan kaki untuk sumber kolom, makalah, atau<br />
kumpulan tulisan:<br />
129
- Moh. Mahfud MD, ”Komisi Yudisial dalam Mozaik<br />
Ketatanegaraan Kita”, dikutip dalam Bunga Rampai Komisi<br />
Yudisial dan Reformasi Peradilan, (Jakarta: Komisi Yudisial,<br />
2007), hal 7.<br />
�Tulisan disertai daftar pustaka dengan format, sebagai contoh:<br />
- Daniel Dhakidae. Cendekiawan dalam Kekuasaan Negara<br />
Orde Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.<br />
�Kami menggunakan pedoman penulisan yang lazim digunakan<br />
pelbagai jurnal atau majalah. Penyebutan nama surat kabar, majalah,<br />
judul buku, atau media terbitan lainnya dicetak miring. Misal, Majalah<br />
Time dijatuhi denda Rp 1 trilyun oleh Mahkamah Agung atas kasus<br />
gugatan Suharto.<br />
�Sedang untuk judul artikel diberi tanda kutip [”….”]. Seperti contoh:<br />
Pengadilan, menurut Satjipto Rahardjo dalam tulisannya berjudul<br />
”Pengadilan Sang Pemenang”, tak akan pernah berhenti menjadi<br />
institut perang antara keangkaramurkaan dan kebaikan-keadilan.<br />
Kirimkan naskah Anda dalam bentuk softcopy dikirimkan ke alamat email<br />
office@elsam.or.id dengan melampirkan biodata. Redaksi menyediakan<br />
honorarium yang pantas untuk tulisan yang dimuat.<br />
130
PROFIL ELSAM<br />
(LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT)<br />
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and<br />
Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan,<br />
berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta.<br />
Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan,<br />
memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi<br />
manusia pada umumnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi<br />
UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan<br />
Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah<br />
membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui<br />
pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi<br />
manusia (HAM).<br />
VISI<br />
Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis,<br />
berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.<br />
MISI<br />
Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang<br />
memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak<br />
ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.<br />
KEGIATAN UTAMA:<br />
1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;<br />
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;<br />
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan<br />
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia<br />
PROGRAM KERJA:<br />
1. Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Rangka<br />
Mewujudkan Demokrasi dan Sistem Hukum yang Berkeadilan.<br />
2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme<br />
Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai<br />
Bentuknya.<br />
3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan<br />
Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas dan<br />
Akuntabilitas Lembaga.<br />
131
Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAM<br />
Badan Pengurus:<br />
Ketua: Sandra Moniaga, SH<br />
Wakil Ketua: Ifdhal Kasim, SH<br />
Sekretaris: Roichatul Aswidah, S.Sos, MA<br />
Bendahara I : Ir. Suraiya Kamaruzzaman, MA<br />
Bendahara II : Abdul Haris Semendawai, SH, LLM<br />
Anggota Perkumpulan:<br />
Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; Dra. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir.<br />
Agustinus Rumansara, M.Sc.; Francisia Sika Ery Seda; Hadimulyo; Lies Marcoes, MA;<br />
Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; Maria Hartiningsih; E. Rini<br />
Pratsnawati; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos; Toegiran S.Pd;<br />
Herlambang Perdana SH, MA.; Ir. Yosep Adi Prasetyo<br />
Pelaksana Harian:<br />
Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, SH. LLM<br />
Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan dan Plt Kepala Divisi Advokasi<br />
Hukum: Wahyu Wagiman SH.<br />
Deputi Direktur Pengembangan sumber daya HAM ( PSDHAM) dan Plt Kepala Divisi<br />
Monitoring Kebijakan dan Pengembangan Jaringan: Zainal Abidin, SH<br />
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, SE<br />
Kepala Divisi Kampanye dan Kerjasama Internasional:<br />
Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi: Triana Dyah, SS<br />
Staf Pelaksana Program bidang Advokasi Hukum:<br />
Ikhana Indah Barnasaputri,SH; Andi Muttaqien, SH<br />
Staf Senior Pelaksana Program Bidang Monitoring Kebijakan & Pengembangan Jaringan:<br />
E. Rini Pratsnawati<br />
Staf Pelaksana Program bidang Monitoring Kebijakan & Pengembangan Jaringan:<br />
Wahyudi Djafar, SH<br />
Staf Pelaksana Program bidang Informasi dan Dokumentasi:<br />
Paijo, Sukadi, Ari Yurino<br />
Staf Keuangan:<br />
Rina Erayanti (Pjs.); Elisabet Maria Sagala, SE<br />
Kasir:<br />
Maria Ririhena, SE<br />
Sekretaris:<br />
Yohanna Kuncup Yanuar Prastiwi, SS<br />
Kepala bagian umum:<br />
Khumaedy<br />
Staf bagian rumah tangga:<br />
Siti Mariatul Qibtiyah; Kosim<br />
Staf bagian transportasi:<br />
Ahmad Muzani<br />
Staf bagian keamanan:<br />
Elly F. Pangemanan<br />
Alamat:<br />
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA<br />
Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Fax.: (+62 21) 7919 2519<br />
Email: office@elsam.or.id; Website: www.elsam.or.id<br />
132
FOKUS<br />
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi demi Masa Lalu<br />
oleh Agung Putri Astrid<br />
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />
oleh Otto Syamsuddin Ishak<br />
Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi<br />
oleh Budiawan<br />
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia<br />
dan Negara-negara Lain<br />
oleh Zainal Abidin<br />
Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu<br />
oleh Herry Sucipto dan Hajriyanto Y. Thohari<br />
OASE<br />
Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />
oleh Stanley Adi Prasetyo<br />
TINJAUAN<br />
”Mengindonesiakan” Anak Timor Leste<br />
oleh Razif