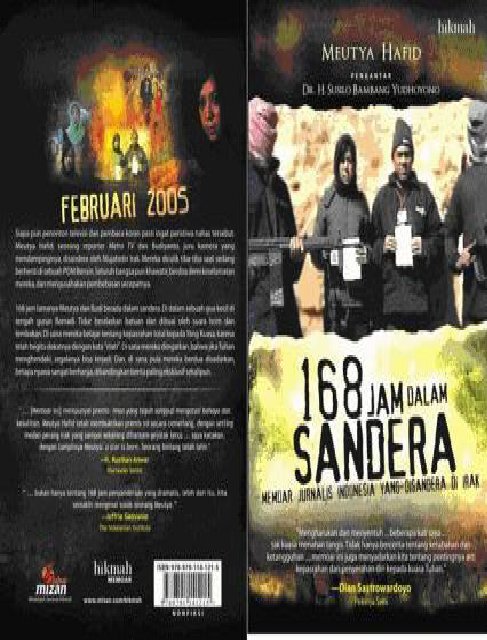You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FEBRUARI 2005<br />
Siapa pun penonton televisi dan pembaca koran pasti ingat peristiwa<br />
nahas tersebut. Meutya Hafid, seorang reporter Metro TV dan Budiyanto.<br />
juru kamera yang mendampinginya, disandera oleh Mujahidin Irak. Mereka<br />
diculik tiba-tiba saat sedang berhemidi sebuah POM Ben sin. Seluruh<br />
bangsa pun khawatir.berdoademi keselamatan mereka, dan<br />
mengusahakan pembebasan secepatnya.<br />
168 jam lamanya Meutya dan Budi berada dalam sandera. Di dalam
sebuah gua kecil di tengah gurun Ramadi. Tidur beralaskan batuan dan<br />
dibuai oleh suara bom dan tembakan. Di sana mereka belajar tentang<br />
kepasrahan total kepada Yang Kuasa, karena telah begitu dekatnya<br />
dengan kata "mau". Di sana mereka diingatkan, bahwa jika Tuhan<br />
menghendaki, segalanya bisa terjadi. Dan, di sana pula mereka berdua<br />
disadarkan, betapa nyawa sangat berharga.dibandingkan berita pating<br />
eksklusif sekalipun.<br />
"... (Memoar ini] mempunyai premis: iman yang teguh sanggup<br />
mengatasi bahaya dan kesulitan. Meutya Halid telah membuktikan premis<br />
int secara cemerlang, dengan setting medan perang Irak yang sampai<br />
sekarang dihantam gejolak terus ... saya katakan, dengan tampilnya<br />
Meutya: a star is born. Seorang bintang telah lahir." —H. Roslhan Anwar<br />
Wartawan Sonlot<br />
" ... bukan hanya tentang 168 )am penyanderaan yang dramatis, lebih<br />
dan Itu. kita semakin mengenal sosok seorang Meutya." —Jeffrie<br />
Geovante<br />
The Tnooficilan Inti «u t o<br />
N O N F I K S<br />
Meutya Hafid<br />
PENGANTAR<br />
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono<br />
168 JAM DALAM<br />
SANDERA<br />
¦<br />
MEMOAR JURNALIS INDONESIA VAN6-DISANDERA 01 IRAK<br />
tak kuasa ketangguhai<br />
n menyentuh ... beberapa kali saya idak hanya bercerita tentang<br />
ketabahan dan uga menyadarkan kita tentang pentingnya ari<br />
kepasrahan dan penyerahan diri kepada kuasa Tuhan."<br />
—Dian Sastrowardoyo<br />
Pekerja Seni<br />
"Buku Ini berisi kegigihan seorang reporter, komit men kepada<br />
profesi, serta keberanian dan keteguhan sikap. Saya seboga pimpinan<br />
Metro TV. yang idah mengupayakan keselamatan Meutya dan Budiyanto.<br />
ber bangga had dengan terbitnya buku ini* —Surya Paloh Pemimpin<br />
Umum Media Group<br />
" _ sangat menarik, berisi pengalaman pahit yang langka, dilukis oleh<br />
gejolak hati anak manusia yang mengalaminya Melalui memoar ini sekali<br />
lagi terbukti bahwa perbedaan dapat dipertemukan oleh kemanusiaan<br />
dan bahwa setelah, bahkan bersama, kesulitan ada kemudahan.' -Prof.<br />
Dr. M. Quralsh Shihab Oaektur Pusat Studi Jakarta<br />
'..dengan keyakinan yang teguh kepada Allah. Swt. komitmen yang<br />
utuh pada profesinya, serta ketegaran dalam tekanan dan musibah<br />
kehidupan, seorang Meutya Hafrd akhirnya lolos dan Mus dari kelompok<br />
ktny Al-Mvjohidinr<br />
Prof Or. M.Amien Rail<br />
Guru Sesar Ilmu PoMk Ur-wruin G*d>ah Mada, Yogyakarta<br />
'Dalam buku kecil ini penulis mengisahkan pengalamannya selama<br />
ditahan oleh Mujahidin kak. Mereka adalah tentara Alah yang<br />
perjuangannya semata mala membela Islam dan kaum Mu\lim . Karena
tujuan perjuangannya semata-mata mencari ncha Allah, bukan<br />
kemewahan dun*, maka dalam melaksanakan lugas suci ini mereka<br />
dibimbing oieh syariat islam sehingga berakhlak mulia-'<br />
—Uitai Abu Bakar Ba'asyir<br />
Ketua Mujahian inde-wua<br />
'Pengalaman Meutya, perempuan yang tegar dan penuh tawakal<br />
dalam menghadapi mu srbah. selama tujuh hari di bawah penyanderaan,<br />
sangat bermanfaat untuk menyadarkan kru. betapa kekerasan atas nama<br />
agama tidak dapat dibenarkan walau diakukan aus dafch melawan<br />
kelaliman."<br />
—Prof. Dr. M. Din Syamsuddin<br />
¦etua Umum PP Muhammadiyah<br />
'Dengan buku Ini terbukti kebenaran ungkapan (iodo yang (xi lu<br />
dirofcurr fcrcuoft tttakuStm mi sendi».*<br />
—KH. Abdurrahman Wahid<br />
Wjn:*! "iiuj u-rum Ctf Mindliiul d Jmj<br />
"Sangat menggugah dan informatif, memberi gambaran kepada<br />
setiap orang yang beken* ataupun yang tertarik pada dunia jurnalistik<br />
mengenai suka duka dan lika liku di dalamnya."<br />
-Nicholas Saputra<br />
•WrlaSenl<br />
Pujian untuk 168 Jam dalam Sandera<br />
"Saya pujikan memoar Meutya Hafid, 168 Jam dalam Sandera agar<br />
dibaca oleh wartawan,khususnya reporter televisi, radio, surat kabar, dan<br />
majalah. Gaya bertutur yang kencang, percakapan salam batin<br />
(monologue inteheur) yang dikaitkan dengan pengamatan cermat alam<br />
panca indera, pelaporan yang tanpa takut dan prasangka, penerapan kilas<br />
balik, ketegangan, konflik, solusi saat ringan (takut sama tikus), penguras<br />
air mata atau tearjerker (ketika diberitahu tentang tayangan televisi [di<br />
Indonesia] lalu menangis), doa yang pasrah, kearifan yang tampak jelas,<br />
semua itu ada dalam arus dan alur cerita. Meminjam analisis dramaturgi,<br />
168 Jam dalam Sandera mempunyai premis iman yang teguh sanggup<br />
mengatasi bahaya dan kesulitan, Meutya Hafid telah membuktikan premis<br />
ini secara cemerlang, dengan setting medan perang Irak yang sampai<br />
sekarang dihantam gejolak terus. Dan, mengutip judul film aktris tenar<br />
tahun 1940-an, Janet Gaynor, saya katakan dengan tampilnya Meutya: a<br />
star is born. Seorang bintang telah lahir."<br />
-H. Rosihan Anwar Wartawan Senior<br />
"Mengharukan dan menyentuh ... beberapa kali saya terpaksa<br />
berhenti membaca karena tak kuasa menahan tangis. Tidak hanya<br />
bercerita tentang ketabahan dan ketangguhan penulis dalam menghadapi<br />
cobaan berat, memoar ini juga menyadarkan pentingnya arti kepasrahan<br />
dan penyerahan diri kepada kuasa Tuhan."<br />
-Dian Sastrowardoyo<br />
Pekerja Seni<br />
"Sangat menggugah dan informatif, memberi gambaran kepada<br />
setiap orang yang bekerja ataupun yang tertarik pada dunia jurnalistik<br />
mengenai suka duka dan lika liku di dalamnya."<br />
-Nicholas Saputra<br />
Pekerja Seni
"Bukan saja para jurnalis, tetapi kita semua anak bangsa dapat<br />
memahami serta menghayati bagaimana dengan keyakinan yang teguh<br />
kepada Allah Swt., komitmen yang utuh pada profesinya, serta ketegaran<br />
dalam tekanan dan musibah kehidupan, seorang Meutya Hafid akhirnya<br />
lolos dan lulus dari kelompok Jaisy Al-Mujahidin, yang demikian<br />
menegangkan dan menguras perhatian kita semua."<br />
-Prof. Dr. M. Amien Rais<br />
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada,<br />
Yogyakarta<br />
"Pengalaman Meutya, perempuan yang tegar dan penuh tawakal<br />
dalam menghadapi musibah, selama<br />
tujuh hari di bawah penyanderaan, sangat bermanfaat untuk<br />
menyadarkan kita, betapa kekerasan atas nama agama tidak dapat<br />
dibenarkan walau dilakukan atas dalih melawan kelaliman."<br />
-Prof. Dr. M. Din Syamsutfdin Ketua Umum PP Muhammadiyah<br />
"Dalam buku kecil ini penulis mengisahkan pengalamannya selama<br />
ditahan oleh Mujahidin Irak. Mereka adalah tentara Allah yang<br />
perjuangannya semata-mata membela Islam dan kaum Muslim. Karena<br />
tujuan perjuangannya semata-mata mencari ridha Allah, bukan<br />
kemewahan dunia, maka dalam melaksanakan tugas suci ini mereka<br />
dibimbing oleh syariat Islam sehingga berakhlak mulia. Oleh karena itu<br />
penulis sebagai seorang wanita ketika ditahan oleh mujahidin Irak<br />
diperlakukan dengan sopan, sebagaimana keterangan penulis dalam<br />
buku ini.Pengalaman penulis ini adalah merupakan pelajaran bagi<br />
penulisan khususnya dan bagi umat Islam umumnya bahwa: (1) Allah<br />
akan selalu menguji iman dengan berbagai macam ujian yang tidak<br />
menyenangkan sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Baqarah: ISS,<br />
'Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit<br />
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan<br />
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,' (2) Allah<br />
menunjukkan bahwa mujahidin yang membela dien-Nya di dalam<br />
perjuangannya harus dilandasi oleh niat ikhlas dan akhlak mulia."<br />
-Ustaz Abu Bakar Ba'asyir<br />
Ketua Majelis Mujahidin Indonesia<br />
"Memoar yang sangat menarik, berisi pengalaman pahit yang langka,<br />
dilukis oleh gejolak hati anak manusia yang mengalaminya. Melalui<br />
memoar ini sekali lagi terbukti bahwa perbedaan dapat dipertemukan oleh<br />
kemanusiaan dan bahkan bersama kesulitan ada kemudahan."<br />
-Prof. Dr. M. Quraish Shihab Direktur Pusat Studi Al-Quran Jakarta<br />
"Dengan buku ini, terbukti kebenaran ungkapan tiada yang perlu<br />
ditakuti kecuali ketakutan itu sendiri."<br />
-KH. Abdurrahman Wahid Mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama<br />
"Buku ini berisi kegigihan seorang reporter, komitmen kepada profesi,<br />
serta keberanian dan keteguhan sikap. Saya sebagai pemimpin Metro TV,<br />
yang telah mengupayakan keselamatan Meutya dan Budi-yanto,<br />
berbangga hati dengan terbitnya buku ini."<br />
-Surya Paloh Pimpinan Media Group<br />
168 Jam DALAM SANDERA<br />
hikmah<br />
MEMOAR
adalah salah satu lini produk Penerbit Hikmah yang menyajikan<br />
kisah-kisah nyata dan biografi menakjubkan, mengejutkan, sekaligus<br />
menginspirasi dan mencerahkan<br />
168 Jam DALAM SANDERA<br />
MEMOAR JURNALIS INDONESIA YANG DISANDERA DI IRAK<br />
— Meutya Hafid —<br />
hikmah<br />
168 JAM DALAM SANDERA<br />
Memoar Jurnalis Indonesia yang Disandera di Irak<br />
Karya Meutya Hafid<br />
Copyright © Meutya Hafid, 2007 Penulis Pendamping: Mauluddin<br />
Anwar, A. Latief Siregar, Ninok Laksono Penyunting: Hermawan Aksan<br />
Penyelaras aksara: Emi Kusmiati Pewajah sampul: Windu Tampan<br />
Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika) Anggota IKAPI Jin. Puri Mutiara<br />
Raya No. 72 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 Telp. 021-75915762,<br />
Fax. 021-75915759 E-mail: hikmahku@cbn.net.id,<br />
hikmah_publisher@yahoo.com http ://www .mizan .co m/hikmah<br />
ISBN: 978-979-114-121-5<br />
Cetakan I, September 2007<br />
Didistribusikan oleh Mizan Media Utama (MMU) Jin. Cinambo<br />
(Cisaranten Wetan) No. 146 Ujungberung, Bandung 40294 Telp.: (022)<br />
7815500 (hunting) Faks.: (022) 7802288 E-mail: mi?<br />
anmu@bdg.centrin.net.id<br />
JAKARTA; (021) 7661724, 7661725, MAKASSAR: (0411) 871369,<br />
SURABAYA: (031) 60050079, (031) 8286195, MEDAN: (061) 820469<br />
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA<br />
Kata Pengantar Oleh<br />
Dr. H. Susilo Barnbang Yudhoyono<br />
SAYA menyambut baik penerbitan buku "168 Jam dalam Sandera"<br />
oleh Meutya Hafid yang menceritakan pengalamannya sewaktu disandera<br />
di Irak.<br />
Saya sendiri tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Masih segar<br />
dalam ingatan saya ketika pada tanggal 19 Februari 2005 saya<br />
dibangunkan oleh ajudan yang mengatakan ada telepon dari staf khusus<br />
Dino Patti Djalal. Pada waktu itu, saya langsung merasa pasti ada hal<br />
yang sangat mendesak, karena tidak biasanya saya dibangunkan di<br />
tengah malam. Dino menyampaikan perkembangan terakhir yang cukup<br />
memprihatinkan mengenai situasi penyanderaan<br />
Meutya Hafid dan Budiyanto di Irak. Dari laporan intelijen,<br />
sebagian besar korban penculikan di Irak berakhir tragis, dan tidak banyak<br />
yang kembali dengan selamat, itu pun biasanya setelah proses<br />
perundingan yang rumit dan memakan waktu lama. Sementara itu, kita<br />
menghadapi masalah bahwa jaringan informasi dan relasi kita di Irak<br />
sangat minim,karena KBRI di Bagdad sudah dikosongkan sejak perang<br />
Irak dan yang tinggal hanyalah satu orang staf lokal warga Irak, bernama<br />
Walid Gatag.<br />
Setelah mempertimbangkan beberapa opsi, saya segera<br />
memutuskan untuk membuat pernyataan melalui televisi malam itu juga.<br />
Kru TV segera dipanggil untuk merekam himbauan saya kepada pihak<br />
penculik yang kemudian disiarkan di televisi internasional, terutama Al
Jazeera, Himbauan tersebut pada intinya menegaskan bahwa Meutya dan<br />
Budiyanto adalah wartawan Indonesia yang berada di Irak untuk<br />
menjalankan tugas jurnalistik mereka tanpa maksud politis, dan mereka<br />
sedang meliput kondisi rakyat Irak untuk dilaporkan ke pemirsa di<br />
Indonesia. Saya mengetuk hati nurani para penculik untuk segera<br />
membebaskan Meutya dan Budiyanto agar keduanya bisa pulang ke<br />
pelukan keluarga mereka di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan<br />
nasib mereka.<br />
Selama beberapa hari setelah peristiwa penculikan tersebut<br />
pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia terfokus pada penyanderaan<br />
ini.Segala upaya kita lakukan untuk mencari informasi, mencoba<br />
melakukan kontak dengan penculik, dan mengirim pesan<br />
kepada kelompok penyandera. Selama masa penungguan yang<br />
tegang itu, saya tetap optimis bahwa penyanderaan akan berakhir dengan<br />
baik, karena Indonesia bukan pihak yang terlibat dalam konflik Irak.<br />
Karena itulah, kita semua lega ketika akhirnya, setelah 168 jam,<br />
penyandera membebaskan Meutya dan Budiyanto, yang kemudian<br />
ditemukan dalam keadaan selamat. Saya juga gembira karena<br />
setelannya,Meutya dan Budiyanto mengatakan bahwa mereka<br />
diperlakukan dengan baik.<br />
Buku ini menceritakan secara rinci pengalaman dan pandangan<br />
Meutya menjadi sandera di negeri orang, dalam lingkungan yang sangat<br />
asing bagi mereka, jauh dari tanah air. Kebanyakan kita melihat konflik<br />
berdarah di Irak dari layar televisi atau membacanya di Koran, namun<br />
Meutya dan Budianto menyaksikan dan merasakannya sendiri dari bilik<br />
salah satu kelompok bersenjata di Irak. Meutya berinteraksi dengan<br />
mereka, menatap mata mereka, mendengar amarah mereka, melihat cara<br />
hidup mereka, dan Alhamdulillah kemudian berhasil keluar dengan<br />
selamat dari penyanderaan.<br />
Pengalaman Meutya dan Budiyanto tersebut penting untuk diketahui<br />
komunitas wartawan, terutama mereka yang seringkali berada dalam<br />
situasi konflik yang penuh risiko. Hal-hal yang diceritakan Meutya di sini<br />
jugabermanfaat pula bagi aparat dan yang sehari-hari bergelut dengan<br />
kasus-kasus penyanderaan.<br />
Saya ucapkan selamat bagi Meutya yang telah<br />
tegar dalam menghadapi cobaan yang sangat berat dan sanggup<br />
menuangkannya dalam sebuah tulisan yang menggugah. Dengan<br />
pengalaman yang sangat langka ini, saya yakin Meutya dan Budiyanto<br />
akan terus berkarya memperkaya khasanah jurnalisme Indonesia dan<br />
menjadi tauladan bagi wartawan Indonesia.<br />
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono<br />
Ucapan Terima Kasih<br />
TIDAK terasa sudah lebih dari dua tahun sejak detik-detik<br />
menegangkan itu terjadi. Selama itu pula saya kembali tenggelam dalam<br />
hiruk pikuk kesibukan seharihari sebagai seorang wartawan. Sesekali,<br />
sebelum memejamkan mata untuk tidur, ba yang-bayang akan peristiwa<br />
tersebut menyeruak alam pikir. Saya teringat saat berdoa di dalam gua<br />
penyekapan, memohon semoga Tuhan mengembalikan saya ke tanah<br />
air, agar saya dapat berbagi cerita tentang pengalaman ini. Ketika itulah<br />
terbit niat awal saya, untuk mewujudkan janji tersebut dalam bentuk buku,
sebelum perlahan memori kian pupus.<br />
Perhatian dan ucapan simpati dari masyarakat yang masih saya<br />
terima hingga saat ini menyadarkan, bahwa kisah ini bukan hanya milik<br />
saya seorang diri.Saya tidak mungkin dapat melewati cobaan ini dengan<br />
baik tanpa dukungan yang begitu besar, tidak hanya dari keluarga namun<br />
dari saudara setanah air. Adapun pembelajaran ataupun manfaat yang<br />
saya petik dari kejadian ini sudah selayaknya juga menjadi sesutau yang<br />
dimiliki bersama. Dengan dorongan dan bantuan dari beberapa rekan<br />
saya coba untuk menulis, dengan segala keterbatasan saya.<br />
Buku ini juga saya tulis untuk perjuangan warga Irak. Juga untuk<br />
mereka yang menyandera saya, Jaish Al Mujahideen, sebagai<br />
pemenuhan janji seorang wartawan untuk memberitakan yang<br />
berimbang. Sesuai permintaan Rois ketika membebaskan saya dan<br />
Budiyanto, "Tolong ceritakan [kejadian selama penyanderaan ini] apa<br />
adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangkan." Harapan besar saya,<br />
semoga keadaan di Irak membaik dan warga Irak diberi petunjuk-Nya atas<br />
cara perjuangan yang terbaik.<br />
Buku ini saya dedikasikan untuk profesi saya, yang senantiasa<br />
membawa beribu warna dalam hidup saya. Semoga menjadi semangat<br />
bagi teman-teman seprofesi, dan Anda yang ingin bergabung dalam<br />
profesi ini. Juga untuk rekan seprofesi yang gugur dalam peliputan, demi<br />
menyampaikan informasi. Semoga bangsa ini dapat lebih menghargai<br />
dan menyadari, betapa dua menit paket berita televisi ataupun satu kolom<br />
tulisan di koran, terkadang risikonya nyawa.<br />
168 jam dalam penyanderaan juga menyadarkan saya, bahwa untuk<br />
meliput dalam daerah konflik ternyata butuh tak sekadar keahlian dan<br />
keberanian, tetapi juga wisdom, kedewasaan untuk menilai kapan harus<br />
maju terus, kapan harus berhenti. Berhenti bukan hanya untuk diri kita,<br />
tetapi juga untuk orang-orang yang mencintai dan menunggu kepulangan<br />
kita. Saya persembahkan buku ini kepada keluarga; mama, Metty Hafid;<br />
kakak, Fitriana dan Iss Savitri, serta kakak ipar, Kemal Massi, dukungan<br />
dan doa mereka tak pernah putus. Terima<br />
kasih atas kesabaran menghadapi cobaan, ketabahan dalam<br />
mengorbankan waktu, perasaan, emosi, dan air mata. Untuk kakak saya,<br />
(Aim.) Farid Fitrah Syawal, dan tentunya untuk ayah, (Aim.) DR. Anwar<br />
Hafid, Ph.D., sebagai sumber ketabahan dan sumber inspirasi saya<br />
dalam bekerja keras. Saya bersyukur kepada Allah atas karunia cinta-Nya<br />
yang begitu besar, yang saya rasakan melalui dukungan dan simpati<br />
begitu banyak orang di negeri ini.<br />
Terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Vudhoyono dan<br />
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pemimpin Umum Media Group Surya Paloh,<br />
Departemen Luar Negeri dan instansi pemerintah lainnya, Badan Intelijen<br />
Nasional, atas upaya yang mereka lakukan untuk mengembalikan saya ke<br />
tanah air. Terima kasih kepada seluruh organisasi media dan asosiasi<br />
jurnalis, lokal maupun internasional, yang turut menekan penculik untuk<br />
membebaskan saya.<br />
Terima kasih kepada sahabat dan rekan kerja yang senantiasa<br />
menyayangi saya, dalam setiap langkah, guru-guru pendidik, dan juga<br />
Anda yang telah turut mendoakan untuk keselamatan saya dan Budiyanto.<br />
Terima kasih untuk waktu, untuk perhatian, untuk air mata yang begitu
tulus, yang telah tercurahkan, yang telah memudahkan langkah saya<br />
kembali ke dalam pelukan orang-orang tercinta, kepada bangsa tercinta.<br />
Saya mungkin tidak dapat membalas lebih dari persembahan buku<br />
ini, semoga Allah Swt. membalas kebaikan kalian, saudara sebangsa,<br />
dengan beribu kali lipat kebaikan yang telah kalian berikan bagi saya<br />
dan Budiyanto. Amin<br />
Allahumma Inni as aluka ridhaaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon<br />
rida-Mu dan surga-Mu. Amin.[]<br />
Isi Buku<br />
Kata Pengantar oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono ~ 11 Ucapan<br />
Terima kasih ~ 15 Bab 1.<br />
Jangan Berontak,, Jangan Bergerak! ~ 21 Bab 2.<br />
Aku Benar-Benar Diculik ~ 27 Bab 3.<br />
Gua Terpencil di Tengah Gurun ~ 43 Bab 4.<br />
Selamat Jalan, Budi ~ 71 Bab 5.<br />
Memelihara Harapan ~ 93 Bab 6.<br />
Harapan yang Pupus ~ 105 Bab 7.<br />
Hilangnya kesabaran ~ 123 Bab 8.<br />
Kabar Pembebasan ~ 135<br />
Bab 9.<br />
Pembebasan yang berliku ~ 157<br />
Bab 10. Tegang Tiada Akhir ~ 171<br />
Bab 11. Aku Pulang ~ 195<br />
Bab 12. Kapan Harus Berhenti? ~ 211 Lampiran ~ 227<br />
Pergolakan Sebuah Ruang Redaksi oleh Don Bosco Selamun ~ 229<br />
Failure is not an Option oleh Dr. R.M.Marty M.Natalegawa ~ 267 Tentang<br />
Penulis ~ 283<br />
Bab l<br />
Jangan Berontak, Jangan Bergerak!<br />
SELASA, 15 Februari 2DD5 "Bangun, Mut! Bangun!"<br />
Aku kaget mendengar teriakan Budiyanto. Lebih kaget lagi ketika tas<br />
yang kupakai sebagai bantal tidur pun terenggut dari bawah kepalaku.<br />
Kenapa Budi menarik tasku? "Bangun, Mut! Bangun!" teriaknya lagi.<br />
Aku bangkit duduk.<br />
Apa gerangan yang sedang terjadi? Otakku belum bekerja seratus<br />
persen. Namun, bisa kurasakan nada kepanikan dalam lengkingan suara<br />
Budi. Budi adalah lelaki Jawa dan setahuku tutur katanya halus. Tak<br />
pernah dia meninggikan suara kepadaku seperti itu.<br />
Belum sempat aku bertanya, Budi kembali berteriak, "Paspor, Mut!<br />
Paspor...!"<br />
Paspor? Kenapa ada yang meminta paspor? Pada hal, rasanya aku<br />
sudah lama tertidur sejak melintas perbatasan.<br />
Tetapi, tanganku refleks merogoh tas mencari paspor.<br />
"Cepat, Mut! Cepat!" Lagi-lagi Budi berteriak, kali ini lebih keras.<br />
Mungkin karena panik, tanganku sulit sekali menemukan paspor. Ku<br />
aduk-aduk isi tas. Mataku yang belum awas benar mencoba memandang<br />
sekeliling.<br />
Rupanya kami berada di sebuah POM bensin. Posisi mobil GMC yang<br />
kutumpangi seperti tengah mengisi bensin. Mataku menangkap tiga<br />
sosok lelaki mengepung mobil kami. Wajah mereka tertutup kain serban
yang biasa disebut kafiyeh. Hanya mata mereka yang kelihatan. Aku yakin<br />
mereka warga Irak.<br />
Budi, yang duduk di jok depan, memutar badannya ke arahku yang<br />
duduk di jok tengah. Pasti dia tak sabar menungguku mencari paspor<br />
tanpa hasil. Di sebelah kiri Budi, kursi pengemudi tampak kosong. Ke<br />
mana Ibrahim?<br />
Namun,perhatianku tersedot oleh suara orang menghardik dalam<br />
bahasa Arab. Mata orang itu me-melototiku.<br />
"Paspor!" Hanya itu yang bisa kupahami dari rentetan kata-kata Arab<br />
yang mencerocos dari mulutnya.<br />
Aku semakin bingung, tetapi aku yakin pasti ada yang tidak beres.<br />
Bukan hanya satu, kini tiga lelaki itu Jangan Berontak, Jangan Bergerak!<br />
memaksaku dengan tatapan menikam dan tidak sabar. Ketika kutemukan<br />
pasporku, salah seorang dari mereka langsung menyambarnya.<br />
Pada saat bersamaan, Ibrahim muncul entah dari mana. Rautnya<br />
panik dan pucat.<br />
"Sahafi.1 Sahaft! Muslim.' Andonesi.'" Setengah berteriak, Ibrahim<br />
menjelaskan kepada tiga lelaki itu bahwa kami wartawan Muslim dari<br />
Indonesia.<br />
Namun, ketiga lelaki itu tak memedulikan berondongan penjelasan<br />
Ibrahim. Malah mereka membalas dengan rentetan pernyataan yang<br />
terdengar lebih sengit. Wajah Ibrahim semakin pucat. Pasti posisinya tak<br />
berdaya.<br />
Pintu mobil dibuka. Tubuh Ibrahim yang tinggi besar didorong paksa<br />
ke arahku. Lalu, seorang lelaki memaksa masuk dari samping Ibrahim,<br />
dan melompat ke kursi paling belakang. Tangannya menenteng senjata<br />
laras panjang jenis AK. Dia mengarahkan moncong senjata buatan Uni<br />
Soviet itu padaku sambil berteriak dalam bahasa Arab. Sepertinya dia<br />
mengatakan, "Jangan berontak, jangan bergerak!"<br />
Lelaki kedua menerjang masuk dari pintu kanan jok depan, memepet<br />
tubuh Budi. Dan, lelaki ketiga masuk dari pintu depan kiri, melemparkan<br />
tubuhnya di belakang kemudi. Dia membalik ke arah Ibrahim dan merebut<br />
kunci mobil dari tangannya. Kasar dan beringas. Tubuh Budi pun<br />
didorongnya ke jok tengah sehingga posisinya kini terjepit tubuhku dan<br />
Ibrahim.<br />
Mesin dihidupkan, dan dengan entakan kuat, mobil pun melesat<br />
sangat kencang.Sekelebatan aku melihat beberapa orang di POM bensin<br />
hanya melongo tanpa mampu menolong.<br />
Mobil melaju kencang di jalan yang agak lengang, membuat barangbarang<br />
bawaan kami, termasuk kamera video, handycam, tripod, laptop,<br />
dan lain-lain perangkat liputan kami, terguncang-guncang. Semuanya<br />
terjadi begitu cepat. Aku berharap ini hanya bagian dari mimpi tidurku.<br />
Kakiku serasa melayang,tubuhku seakan-akan tak lagi menempel di<br />
kursi.<br />
Mimpikah? Bukan!<br />
Walau perasaanku sulit menerima, otakku yang sudah terjaga terusmenerus<br />
meyakinkan, "Ini kenyataan, Mut, bukan mimpi!" Akhirnya, aku<br />
pasrah. "Inilah akhir hidupmu."<br />
Di tengah kepasrahanku, Ibrahim mencoba lagi menjelaskan bahwa<br />
kami wartawan Muslim dari Indonesia. Namun ketiga orang ini, dengan
tubuh ter guncang-guncang karena laju mobil tak keruan, tidak kalah<br />
sengit menjelaskan dalam bahasa Arab, entah apa. Suasana semakin<br />
tegang. Lagi-lagi usaha Ibrahim sia-sia belaka. Ini membuatku tidak mau<br />
lagi menghiraukan perdebatan mereka. Percuma. Kalau memang harus<br />
mati saat ini, aku mau mati dalam keadaan baik.<br />
Tanganku menggapai tas, merogoh buku Yasin 40 hari meninggalnya<br />
ayahku yang hari ini belum genap satu tahun wafat. Mungkin hari ini aku<br />
akan menyusulmu, Ayah.<br />
Lelaki di belakangku menodongkan senjata AK ke tubuhku. Mungkin<br />
dia menyangka aku merogoh tas untuk mengambil pistol atau senjata<br />
pembela diri. Nyaliku semakin ciut.<br />
Namun tiba-tiba Ibrahim berteriak, "Quran! Quran!" Telunjuknya<br />
mengarah ke buku Yasin di tanganku.<br />
Aku sendiri sadar betul bahwa dalam situasi ini tak ada yang bisa<br />
kulakukan kecuali berdoa. Tak kupedulikan lagi mereka yang terus<br />
menatapku. Kubuka buku dan kubaca Surat Yasin dalam hati. Tak<br />
kusangka, ketidakacuhanku rupanya membuat mereka melunak. Salah<br />
satu lelaki di jok depan menoleh dan berbicara padaku dengan nada<br />
suara yang lebih lembut.Ibrahim menerjemahkan,"Kami bukan pencuri.<br />
Kami Muslim. Kami tidak akan melukaimu." Benarkah? Mungkin bisa<br />
membaca rona kesangsian di wajahku, Ibrahim menambahkan, "Mereka<br />
adalah Mujahidin." Mujahidin? Apa urusannya dengan kami?<br />
Kuberanikan diri menatap lelaki yang tadi berbicara padaku. Sorot<br />
matanya kini tampak lebih lembut, bersahabat. Dari balik lilitan kafiyeh-nya<br />
yang melorot, sepertinya aku melihat senyuman yang tertahan di bibirnya.<br />
Dia menganggukkan kepala seolah-olah membenarkan Ibrahim. Entah<br />
kenapa aku menjadi yakin kembali. Mungkin Tuhan masih memberiku<br />
kesempatan hidup.<br />
Mataku memandang ke luar ketika iring-iringan tentara Amerika<br />
Serikat berpapasan dengan mobil kami.Iring-iringan yang sangat panjang.<br />
Puluhan tank, jip humvee, kendaraan antitank, dipenuhi tentara. Ketiga<br />
penangkap kami tampaknya tak menyangka bakal berpapasan dengan<br />
rombongan besar tentara Amerika. Wajah mereka kelihatan menegang.<br />
Terdengar kokangan senjata AK di belakangku. Ya Tuhan, kami akan<br />
diberondong puluhan tentara Amerika jika tiga /elaki ini nekat. Tiba-tiba,<br />
sopir membanting setir ke sebelah kanan, membuat posisi<br />
mobil terlempar dari ruas jalan. Untunglah gerakan itu tak membuat<br />
rombongan tentara curiga. Di depan dan belakang mobil kami memang<br />
banyak kendaraan lain yang juga memberikan jalan bagi iring-iringan<br />
serdadu itu.<br />
Setelah iring-iringan serdadu lewat, ketiga penangkap kami<br />
berdiskusi setengah berbisik. Sesaat kemudian, mereka menutup mata<br />
Ibrahim dengan kafiyeh. Punggung Ibrahim didorong sehingga posisi<br />
tubuhnya membungkuk. Lalu, giliran mata Budiyanto dililit. Dia juga<br />
dipaksa merunduk. Mungkin mereka khawatir kami akan berteriak<br />
meminta tolong saban berpapasan dengan kendaraan lain.<br />
Aku memandang ke arah lelaki di jok depan. Matanya seperti<br />
meyakinkan bahwa mereka tak akan mencelakaiku. Sempat kulirik jam<br />
tanganku, pukul 4 sore Waktu Indonesia Barat. Pukul 12 siang waktu Irak.<br />
Lalu, tiba-tiba mataku pun ditutup. Lelaki bersenjata di belakangku
melilitkan kafiyeh-nya. Kencang sekali, membuatku sulit bernapas.<br />
Tangannya menekan punggungku, memaksa tubuhku merunduk. Hanya<br />
deru mesin mobil yang kini kudengar, bersahutan dengan suara<br />
jantungku yang semakin kencang berdegup.<br />
Dunia kini benar-benar gelap.<br />
Inikah perjalanan menuju kematian?[]<br />
Bab 2<br />
Aku Benar-Benar Diculik<br />
HARI itu, Senin, 31 Januari 2DD5, aku agak terlambat tiba di kantor. Ini<br />
hari pertamaku muncul lagi di studio Metro TV Kedoya, Jakarta Barat,<br />
setelah dua pekan bertugas di Aceh, tepatnya di Meulaboh. Sepulang dari<br />
Aceh, aku sempatkan pergi ke Makassar, untuk menuntaskan urusan<br />
pensiunan almarhum ayah yang terbengkalai. Dan pagi itu, karena<br />
keberangkatan pesawatku dari Makassar tertunda, agak molor juga<br />
kedatanganku di Bandara Soekano-Hatta. Kemacetan Jakarta di awal<br />
pekan semakin menghambat kehadiranku di Kedoya.<br />
Suasana kantor ekstra sibuk. Sisa bencana tsunami yang<br />
meluluhlantakkan Aceh, 26 Desember 20 04, masih menjadi berita yang<br />
dinanti pemirsa. Dan, Metro TV adalah stasiun terdepan yang<br />
menayangkan informasi pasca bencana tsunami dari berbagai pelosok<br />
Aceh dan Nias. Lebih separuh kru redaksi Metro TV saat itu seperti pindah<br />
kantor ke berbagai daerah di Aceh yang diterjang tsunami: Banda Aceh,<br />
Meulaboh, Galang, dan Lhokseumawe. Itu berarti kurang 50 persen SDM<br />
yang tertinggal di<br />
kantor pusat harus bekerja ekstra keras. Tentu saja termasuk anchor<br />
(penyiar berita atau presenter) sepertiku, yang harus siap menjalani<br />
jadwal siaran panjang dalam sehari karena banyaknya program khusus<br />
tambahan selain program reguler yang ditayangkan. Kantor biasa<br />
menyebutnya "siaga satu".<br />
Setelah menyampaikan rangkaian informasi mengenai bencana<br />
tsunami di studio, aku mampir ke ruang redaksi, yang menjadi jantung<br />
sebuah media berita. Di sinilah semua berita diolah, dari bahan mentah<br />
menjadi materi siap tayang.Di ruang ini pula kebijakan-kebijakan penting<br />
redaksi dibahas. Juga, kalau tidak ingin ketinggalan isu dan rumpian<br />
aktual, wajib hukumnya menyambangi ruangan ini.<br />
"Horee, Meutya sudah balik. Mana oleh-oleh nya?"<br />
"Wah, kulitmu lebih manis, nih."<br />
Begitulah candaan teman-teman di redaksi menyambut rekan yang<br />
baru pulang tugas cukup lama di luar kota. Sepulang dari Aceh, kulit<br />
mukaku memang kersang terbakar. Maklumlah, selama di Aceh aku kerap<br />
masuk ke daerah terisolasi. Teunom dan PhangHa di Kabupaten Aceh<br />
Jaya, misalnya, luluh lantak sehingga tidak ada satu pun pohon rindang<br />
atau bangunan untukku berlindung dari sengatan matahari pantai yang<br />
terik. Saling canda masih berlanjut ketika lamat-lamat kudengar dari ruang<br />
Koordinator Liputan (Korlip), perbincangan soal kru yang akan mendapat<br />
tugas ke Irak. Ruangan Korlip adalah satu bagian kecil dari ruang redaksi<br />
yang lebih sibuk karena dari sanalah<br />
semua gerakan pasukan peliput alias reporter dan kontributor<br />
dikomandokan.Aku coba mencuri dengar sambil melanjutkan obrolan
dengan teman-teman. Kupikir, memang tidak berlebihan jika Metro TV<br />
mengirim tim untuk meliput pemilu Irak. Warga Irak tengah merayakan<br />
pesta demokrasi pertama setelah Saddam Hussein, pemimpin Irak<br />
selama hampir 24 tahun, jatuh. Juga, mengingat pemberitaan Metro TV<br />
mengenai Irak sebelumnya cukup intens, baik sebelum, selama, maupun<br />
setelah invasi pasukan Amerika Serikat dan sekutunya.<br />
Dari ruangan kecil itu, kudengar namaku juga disebut-sebut. Rasa<br />
ingin tahu membuatku tak berpikir dua kali langsung menerobos ke ruang<br />
korlip. Beberapa koordinator liputan tengah berembuk. Kulihat juga<br />
Budiyanto, koordinator juru kamera Metro TV yang beberapa kali ditugasi<br />
bersamaku. Penugasan kami terakhir adalah November 2004, meliput<br />
amnesti atau pengampunan yang diberikan pemerintah Malaysia kepada<br />
para tenaga kerja ilegal, termasuk dari Indonesia. Peliputan kami selama<br />
hampir satu bulan di Malaysia itu dinilai cukup sukses oleh Metro TV.<br />
"Lah, ini kebetulan ada Meutya, dia kan mahir berbahasa Inggris," ujar<br />
Budiyanto dengan logat Jawanya yang medok, sambil tersenyum ke<br />
arahku.<br />
"Ada apa sih, Mas, kok seru sekali ngobrolnya?" tanyaku.<br />
Selain Budiyanto, ada juga Dadi R. Sumaat-madja, Wakil Kepala<br />
Peliputan, dan Irfan Maulana, Koordinator Liputan.<br />
"Ada rencana penugasan ke Irak. Kalau jadi, harus berangkat<br />
secepatnya, biar tidak kehilangan momentum," kata Budiyanto. Dia<br />
menjelaskan, kalau tidak pergi segera, lebih baik rencana penugasan<br />
dibatalkan saja.<br />
"Apa saja yang perlu disiapkan, Bud? Kita tidak punya banyak waktu.<br />
Bagaimana dengan visa?" tanya Dadi.<br />
Budiyanto memang sudah dua kali meliput di Irak. Pertama, ketika<br />
sebelum invasi militer Amerika Serikat, dan kedua sesaat setelah<br />
Saddam jatuh.<br />
"Setahu saya, dua tahun lalu kita bisa minta visa on arrival ke<br />
Yordania. Paling tidak, masuk dulu ke Yordan. Urusan visa Irak kita<br />
pikirkan nanti. Yang penting berangkat dulu." Budiyanto menegaskan<br />
kemungkinan untuk mengejar waktu. Yordania merupakan negara<br />
tetangga Irak yang berbatasan langsung dan terbilang aman.<br />
Aku memilih tidak banyak bicara.<br />
"Baik, kita akan segera rapat soal jadi tidaknya berangkat, dan siapa<br />
yang akan ditugaskan. Kita masih tunggu Don." Dadi menyebut nama Don<br />
Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi Metro TV.<br />
Keluar dari ruangan kecil itu, aku tersenyum. Asyik juga kalau aku<br />
yang dipilih. Tetapi, kutepis pikiran itu karena aku tak mau berharap<br />
banyak. Lagi pula, aku belum cukup istirahat sejak kembali dari Meulaboh.<br />
Bayangan kehancuran Kota Meulaboh, bau kematian, dan sosok Yundha,<br />
bocah berusia empat tahun yang kehilangan ayah ibunya, masih melekat<br />
dalam ingatanku. Hampir setiap sore sepulang<br />
liputan di sana, aku bermain bersama Yundha. Kebetulan kami<br />
sama-sama mengungsi di Kompi C, satu-satunya markas TNI di<br />
Meulaboh yang lolos dari terjangan tsunami. Aku ingat betul mimik muka<br />
Yundha, senyumnya yang tertahan, dan sorot matanya yang kosong tetapi<br />
masih sanggup membelalak senang ketika disodori susu kotak dari<br />
bantuan kemanusiaan.
Aku melenggang ke ruang presenter. Di sini biasanya aku dan temanteman<br />
presenter mendiskusikan beragam topik, mulai dari pemberitaan<br />
yang tengah aktual, urusan jadwal siaran, hingga resto ran-restoran enak<br />
dan murah sekitar kawasan Kedoya, yang akan jadi sasaran makan siang<br />
kami berikutnya.Koordinator Presenter, Usi Karundeng,sibuk memelototi<br />
jadwal siaran presenter. Raut mukanya agak muram hari itu. Segera<br />
kutebak artinya: akan ada seorang presenter yang mendapat tugas "ke<br />
luar"ke luar kota atau ke luar negeri sehingga dia harus merombak ulang<br />
jadwal yang sudah puluhan kali dirombaknya.Menyadari<br />
kedatanganku,Usi membalik ke arahku.<br />
"Nah, ini Meutya. Kamu siap-siap berangkat ke Irak, yah."<br />
"Ke Irak, Mbak? Ada apa?" Aku pura-pura tidak tahu agar dia<br />
memberikan penjelasan lebih terperinci.<br />
"Kan lagi pemilu, Muti. Kita sudah terlambat, kamu harus segera<br />
berangkat."<br />
"Segera? Kapan?" Raut mukaku sedikit memprotes penugasan<br />
dadakan itu, tetapi tak bisa kututupi,<br />
semangatku muncul seketika.<br />
"Ehm, mungkin malam ini. Tetapi, kamu koordinasi sama Korlip, yah,"<br />
jawab Usi.<br />
"Hah, malam ini? Berapa lama, Mbak?" Walau bersemangat, aku<br />
terkejut harus berangkat malam itu juga. Padahal, waktu sudah<br />
menunjukkan pukul 1 siang. Otakku langsung berhitung: perjalanan ke<br />
rumahku saja di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, paling cepat satu<br />
jam. Belum lagi mengepak baju dan perlengkapan liputan. Ini berarti aku<br />
hanya bisa meluangkan maksimum dua jam untuk mempersiapkan<br />
segala materi yang berhubungan dengan Irak.<br />
"Satu minggu, Muti. Tetapi, kamu siap-siaplah untuk dua minggu."<br />
Senyuman Usi mengingatkanku pada penugasan di Aceh yang<br />
rencananya hanya satu minggu, tetapi kenyataannya molor hingga dua<br />
minggu.<br />
"Ini Irak, lho, Mbak. Harus pasti, satu atau dua minggu?" Aku<br />
memikirkan berapa banyak pakaian yang harus kubawa karena siapa tahu<br />
tidak ada laundry di hotel Irak yang masih porak-poranda.<br />
"Oke, Mut, gini aja deh. Kamu segera pastikan semuanya sama<br />
Claudius dan Dadi," Usi menyebutkan nama Kepala Divisi Peliputan Metro<br />
TV, Claudius Boekan, dan wakilnya, Dadi R. Suraatmadja.Kibasan<br />
tangannya mengisyaratkan agar aku segera pergi ke ruang redaksi.<br />
Belum sampai kakiku di ruang redaksi, telepon selulerku berdering.<br />
Nama "Dadi RS" tertera di layar telepon.<br />
"Siang, Mut. Rapat memutuskan kamu yang kita pilih berangkat ke Irak<br />
bersama Budiyanto. Sekretariat Redaksi sekarang sedang<br />
mengusahakan tiket untuk berangkat malam ini juga."<br />
"Mas, ini Irak, lho. Bukan Bogor. Apa harus berangkat malam ini juga?<br />
Tidak bisa besok?"<br />
"Tidak bisa, Mut. Proses pemilu sudah berjalan. Maaf, tetapi kita harus<br />
mengejar waktu. O ya, satu hal lagi. Saya cuma mau sampaikan bahwa<br />
kamu kita pilih dengan pertimbangan peliputan kamu di Aceh<br />
menunjukkan kamu tough, energi kamu seperti tiada habisnya, dan lobi<br />
kamu bagus. Harapan kita, di Irak kamu bisa melakukan hal yang sama."
Ucapan Dadi membuatku terdiam. Haruskah kuterima sebagai pujian,<br />
atau malah beban berat? Kantor berharap peliputan di Irak harus lebih<br />
baik, atau paling tidak sebanding dengan peliputanku di Aceh. Padahal,<br />
medannya sangat berbeda.<br />
"Oke, Mas," jawabku pendek. Ucapan Dadi tadi membuatku kesulitan<br />
merangkai kata-kata lain.<br />
Di ruang Koordinator Liputan, aku berdiskusi untuk mematangkan<br />
target dan strategi peliputan di Irak bersama Claudius, Dadi, dan Irfan.<br />
Budiyanto, camera person yang ditugasi menyertaiku, sibuk<br />
mempersiapkan peralatan di ruang camstore. Claudius dan Dadi<br />
menegaskan, satu yang harus terpenuhi dari penugasanku: menjawab<br />
keingintahuan masyarakat Indonesia tentang pemilu bebas pertama di<br />
Irak setelah Saddam Hussein tumbang.<br />
Keingintahuan masyarakat! Tugas seorang jurnalis untuk<br />
memenuhinya. Itulah kalimat kunci<br />
yang menggerakkanku untuk melangkah tanpa ragu ke medan tersulit<br />
sekalipun. Itu pula yang membuatku menerima penugasan ini dengan<br />
senang hati. Keyakinan dan rasa percaya diriku memuncak saat itu.<br />
Ucapan Dadi di telepon pun kuanggap sebagai tantangan yang harus<br />
kupenuhi. Ini awal yang baik. Dilengkapi dengan persiapan dan strategi<br />
peliputan yang matang, termasuk meminta tim riset redaksi untuk<br />
mencarikan segala informasi menyangkut Irak, tentu semuanya akan<br />
berjalan lancar dan baik -baik saja.<br />
* * *<br />
LANCAR dan baik-baik saja? Sungguh, peristiwa yang kini kualami,<br />
jangankan terbahas dalam diskusi kami di Kedoya, terlintas di benakku<br />
pun tidak pernah.<br />
Mobil GMC yang membawa kami tiba-tiba berhenti. Entah di mana aku<br />
sekarang. Mataku masih tertutup kafiyeh. Sepanjang perjalanan tadi,<br />
sambil berdoa kucoba mengikuti gerakan mobil. Kuhitung berapa kali<br />
mobil belok kanan, berapa kali belok kiri. Tetapi akhirnya, aku menyerah.<br />
Aku tak mampu menghitung lagi. Sebab, sang sopir cukup cerdas,<br />
melajukan kendaraan kami dengan zig-zag. Padahal yang kukenal,<br />
jalanan di Irak jarang yang berkelok-kelok seperti itu.<br />
Lagi pula, konsentrasiku buyar karena kaki kananku mulai kram dan<br />
terasa sangat sakit. Pasti karena sepanjang perjalanan posisi tubuhku<br />
merunduk<br />
sehingga harus banyak bertumpu pada kaki yang tertekuk.<br />
Sesekali kudengar rintihan Budi. Pasti dia pun sangat tersiksa. Aku sudah<br />
membayangkan banyak risiko yang akan dihadapi dalam peliputan di Irak.<br />
Tetapi, penderitaan seperti ini tak pernah terlintas!<br />
Mesin mobil dimatikan. Aku tak kuat lagi menahan kram yang luar<br />
biasa di kaki. Tetapi, aku masih bisa merasakan jemari tangan melucuti<br />
ikatan kafiyeh di kepalaku. Pasti tangan lelaki di belakangku. Meskipun<br />
belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan cahaya terang setelah<br />
sekian lama terbenam dalam gelap, mataku bisa melihat letak jarum jam<br />
tanganku. Itulah yang pertama kali kulakukan setelah mataku terlepas dari<br />
lilitan kafiyeh. Pukul 6 sore WIB. Berarti persis dua jam kami menempuh<br />
perjalanan dengan mata tertutup. Percuma aku menerka di mana posisi<br />
keberadaan kami kini.
Pukul 6 sore WIB!<br />
Mestinya saat ini aku menyampaikan laporan untuk Metro Hari Ini.<br />
Kantor memang mengharuskanku muncul di layar melaporkan hasil<br />
liputan Irak setidaknya satu kali sehari, pada program Metro Hari Ini (MHI).<br />
Untuk program yang tayang pada prime time ini, beberapa kali aku<br />
melaporkan secara live dari studio Associated Press Television Nets-work<br />
(APTN) di Bagdad.<br />
Biasanya, menjelang pukul 6 sore WIB, produser MHI sibuk<br />
meneleponku untuk memastikan materi apa saja yang akan kulaporkan.<br />
Sesungguhnya<br />
kemunculanku di layar tidak hanya mewartakan kondisi terkini Irak<br />
kepada pemirsa di Indonesia. Tampilanku juga sekaligus meyakinkan<br />
pada keluarga dan kerabatku bahwa aku baik-baik saja. Dan sore ini, aku<br />
tidak muncul menyapa mereka.<br />
Tahukah mereka bahwa aku tengah menghadapi masalah? Tahukah<br />
mereka saat ini hidupku di ujung tanduk?<br />
Mesin mobil telah dimatikan, tetapi para penculik belum<br />
membolehkan kami turun. Posisiku pun masih merunduk, tak berani<br />
memandang ke luar.Dua lelaki yang duduk di jok depan sudah turun. Aku<br />
bisa mendengar percakapan mereka, seperti tengah membahas dan<br />
mempersiapkan sesuatu. Apa yang akan mereka /akukan pada kami?<br />
Siapa yang dapat menolongku? Budi dan Ibrahim sama tak berdayanya<br />
denganku. Moncong senjata milik lelaki di jok belakang masih mengarah<br />
ke kepala kami.<br />
Kami tak mampu berbuat apa-apa. Mengharapkan bantuan datang<br />
dari luar rasanya mustahil.Aku menyesal tak mengontak Muhammad<br />
Nasser, guide kami di Bagdad, untuk mengabarkan bahwa kami akan<br />
kembali ke Bagdad. Mister Wail, sopir kami di Bagdad, juga pasti tak bakal<br />
menunggu, dan tak akan bertanya-tanya kenapa kami belum juga tiba di<br />
sana karena aku tak mengabarinya. Jadi, siapa yang bakal menyadari<br />
kami menghilang? Satu-satunya harapan adalah kantorku di Kedoya.<br />
Hanya mereka yang tahu persis posisi terakhir kami.<br />
Tetapi, tahukah mereka apa yang tengah kualami?<br />
Aku yakin tidak. Sebab, korlip dan produser di Kedoya sudah tahu<br />
bahwa sore ini aku tidak akan muncul di layar. Bukan karena aku tengah<br />
"menghadapi masalah" ini, melainkan karena mereka sudah kukabari<br />
bahwa aku tengah dalam perjalanan darat dari Amman, Ibu Kota Yordania,<br />
ke Bagdad. Ya, pukul 2.30 dini hari, aku dan Budiyanto bertolak dari<br />
Amman dengan menyewa mobil GMC milik Ibrahim. Sekitar pukul 7 pagi,<br />
kami tiba di perbatasan Yoda nia-Irak. Ini kali kedua kami memasuki Irak<br />
melalui perbatasan ini. Dua belas hari sebelumnya, kami juga menembus<br />
Irak melalui perbatasan yang sama.<br />
Seperti yang sudah kuduga, persoalan di pos imigrasi cukup rumit.<br />
Alasannya sama dengan ketika kami masuk sebelumnya, yakni ada travel<br />
ban untuk warga negara Indonesia, yang dilarang pergi ke Irak karena<br />
pemerintah tidak menjamin keselamatan mereka setelah kedutaan<br />
Indonesia untuk Irak ditarik sejak invasi tahun 2003.<br />
Namun, persoalan kali ini lebih rumit karena kepala imigrasi<br />
mempertanyakan alasan kami masuk kembali ke Irak dalam waktu<br />
singkat. Meski begitu, dia tetap ramah menyambut kami yang sudah
dikenalnya 12 hari lalu, dengan menyuguhkan chai, teh khas Irak, di<br />
ruangannya. Setelah memaklumi penjelasanku kenapa kembali ke<br />
Bagdad, dia pun menandatangani surat izin, bertepatan dengan ketika<br />
chai di gelas kecil itu sudah habis kuseruput.<br />
Perjalanan berlanjut dari perbatasan menuju Bagdad. Biasanya, tak<br />
jauh dari perbatasan, sinyal GSM akan hilang. Karenanya kusempatkan<br />
mengirim<br />
pesan singkat, SMS, kepada keluarga dan teman-teman. Sudah<br />
menjadi kebiasaanku setiap meliput di daerah konflik, memohon maaf<br />
dan doa kepada kerabat terdekat. Aku secara khusus menelepon mamaku.<br />
"Halo Mama, ini baru masuk perbatasan Irak menuju Bagdad.<br />
Paling lama lima jam lagi sampai. Nanti dikabari lagi kalau sudah di<br />
Bagdad, insya Allah."<br />
Ke nomor ponsel Koordinator Liputan, kukabar-kan posisi kami saat<br />
itu, dan perkiraan tiba di Bagdad sore hari Waktu Indonesia Barat. Kutulis<br />
pula bahwa selama perjalanan, kemungkinan banyak daerah tak bersinyal<br />
bakal kulewati sehingga akan sulit mereka menghubungi kami. Setelah<br />
mengirimkan semua SMS itu, aku merasa lebih siap masuk kembali ke<br />
Irak. Kurebahkan kepala pada tas di sampingku sebagai bantal. Aku<br />
memang paling mudah tidur di perjalanan walau dalam suasana tegang<br />
sekalipun. Sebelum lelap, sempat kuberharap, ketika membuka mata<br />
nanti, kami sudah tiba di Bagdad.<br />
Ternyata harapan itu tak kesampaian. Teriakan Budi dan entakan<br />
tangannya pada tasku membuatku kaget. Lalu, peristiwa demi peristiwa<br />
yang tak pernah kubayangkan itu terjadi dalam sekejap, bermula di POM<br />
bensin. Tiga lelaki menghardik meminta paspor, memaksa masuk ke<br />
dalam mobil, menodongkan moncong senjata AK, menutup mata kami,<br />
dan melarikan mobil kami entah ke mana.<br />
Sebelum mata kami ditutup, Ibrahim menjelaskan bahwa tiga lelaki<br />
ini adalah anggota Mujahidin. Setahuku, itulah kelompok gerilyawan yang<br />
dijuluki<br />
pemerintah Amerika Serikat sebagai pemberontak, dan biasa<br />
meledakkan kawasan-kawasan tertentu di Irak, terutama Bagdad, dengan<br />
bom mobil. Baru beberapa hari lalu, aku meliput peristiwa ledakan bom<br />
mobil di Bagdad. Dan kini, aku bersama kelompok pelakunya?<br />
Mungkinkah mereka akan menggunakan mobil ini untuk bom bunuh diri,<br />
lengkap dengan kami di dalamnya? Rasanya tak mungkin bom bunuh diri<br />
dilakukan beramai-ramai. Setidaknya, yang kutahu, belum pernah terjadi.<br />
Otakku terus bekerja ketika mataku hanya bisa melihat kegelapan.<br />
Boleh jadi mereka hanyalah para perampok yang dikenal di Irak sebagai<br />
Ali Baba, yang menculik orang asing demi uang. Mereka melakukannya<br />
karena tak lagi memiliki pekerjaan, akibat po rak-porandanya ekonomi Irak<br />
pasca-invasi. Tetapi, kenapa kami harus dibawa ke sebuah tempat entah<br />
di mana? Kenapa mereka tak mengambil saja uang dan barang bawaan<br />
kami, lalu membiarkan kami pergi? Mungkinkah mereka kelompok<br />
perlawanan anti-Amerika Serikat dan sekutunya, yang biasa menculik<br />
orang asing di Irak, dan memenggal leher sanderanya kalau tuntutan<br />
mereka tak dipenuhi? Aku akan mati dipenggal?<br />
* * *<br />
RASA sakit dan kejang di kakiku belum pulih. Kulirik Budiyanto.
Wajahnya meringis. Pasti dia juga merasakan kejang dan sakit luar biasa<br />
di kakinya yang tertekuk dan menahan beban tubuhnya selama<br />
dua jam.<br />
Lelaki di belakangku memberikan isyarat dengan senjata yang<br />
digerakkan kedua tangannya, meminta kami turun dari mobil yang<br />
pintunya telah terbuka. Wajahnya yang tak lagi tertutup kafiyeh sangat tidak<br />
bersahabat, berbeda sekali dengan lelaki yang tadi duduk di jok depan.<br />
Tertatih kakiku menjejak tanah. Bukan tanah ternyata, melainkan pasir.<br />
Kulihat butiran-butirannya seperti kebanyakan pasir pantai yang biasa<br />
kunikmati selagi liburan, hanya bentuknya lebih besar-besar dan kasar.<br />
Namun, ketika mataku menyapu sekeliling, aku terpana. Kamu tidak<br />
sedang menikmati iiburan di pantai, Meutya! Ini gurun!<br />
Ya, ini gurun pasir. Ke arah mana pun mata memandang, hanya<br />
lautan pasir kelabu yang tampak. Tidak ada rumah, pepohonan, tidak juga<br />
makhluk hidup lain, kecuali kami berenam. Mengapa kami dibawa ke sini?<br />
Kalaupun benar kami diculik, setahuku dari tayangan-tayangan televisi<br />
dan dari berbagai pemberitaan yang pernah kubaca, para sandera<br />
biasanya ditempatkan di dalam rumah atau di gedung terbengkalai, bukan<br />
di gurun pasir seperti ini.<br />
Keringat mengucur dari dahiku.Sekujur tubuhku juga mulai basah.<br />
Padahal, sebenarnya,cuaca siang hari saat Irak memasuki akhir musim<br />
dingin sama sekali tidak menyengat. Namun, rasa takutku mendorong<br />
keringat dingin itu keluar melalui pori-pori kulit. Apakah tiga lelaki ini akan<br />
mendirikan tenda tempat kami terteduh?<br />
Ternyata tidak. Mataku menumbuk sebuah gua<br />
kecil yang letaknya agak menjorok ke bawah. Aku benar-benar diculik!<br />
Aku disandera!<br />
Aku makin yakin kami bakal disekap dalam gua ketika tiga lelaki itu<br />
masuk ke gua tersebut. Sepertinya mereka tidak khawatir membiarkan<br />
kami di luar. Lagi pula, akan lari ke mana kami karena, sejauh mata<br />
memandang, yang tampak hanya gurun pasir. Gurun kelabu yang<br />
kekuningan karena tersiram cahaya matahari. Melarikan diri malah bisa<br />
mati konyol.<br />
Toh, meskipun rasa takut tak bisa kutepis, otakku terus meyakinkan<br />
diriku untuk tetap tenang. Dalam kondisi seperti ini, aku tidak boleh salah<br />
langkah. Jangan mengumbar emosi, lawanlah dengan diplomasi!<br />
Kulirik layar ponsel. Tidak ada sinyal. Meskipun sudah kuduga<br />
sebelumnya, aku tetap berharap sinyal ponselku muncul, tetapi satu titik<br />
pun tak apa. Aku ingin mengirim SMS ke Kedoya: "Kami Diculik!" Aku juga<br />
ingin meminta mamaku mendoakan kesela-matanku. Tentu saja aku tak<br />
bakal mengabarinya bahwa aku diculik. Aku tak ingin membuatnya<br />
bersedih. Aku hanya ingin minta doa. Itu saja.<br />
Dua jam aku, Budi, dan Ibrahim hanya bisa diam. Padahal, biasanya<br />
kami tak pernah berhenti mengoceh hingga rasa kantuk mendera.<br />
Terutama Budi, selalu saja ada kisah lucu yang meluncur dari mulutnya.<br />
Tetapi dalam suasana mencekam seperti ini, kami memilih tak bicara.<br />
Lagi pula, kami khawatir para penculik akan salah mengerti jika aku dan<br />
Budi berbicara dalam bahasa Indonesia. Dengan Ibrahim, aku juga tak<br />
bicara. Aku yakin tiga lelaki itu tak<br />
mengerti bahasa Inggris, bahasa sehari-hariku dengan Ibrahim.
Namun, ketika tiga lelaki itu masuk ke gua, aku mencuri kesempatan<br />
untuk bertanya kepada Ibrahim, "Di mana kita?"<br />
Setelah melirik ke dalam gua dan merasa aman, Ibrahim<br />
menjelaskan, "POM bensin tempat kita diciduk tadi adalah Ramadi, tetapi<br />
sekarang entah di mana. Mungkin antara Ramadi dan Fallujah."<br />
Mendengar penjelasannya, tubuhku semakin lemas. Kalau dugaan<br />
Ibrahim benar, berarti kami berada tepat di zona pertempuran antara<br />
gerilyawan Irak dan tentara koalisi. Aku langsung teringat riset yang<br />
kukumpulkan bersama tim Metro TV sebelum berangkat. Ramadi dan<br />
Fallujah adalah basis perlawanan kelompok gerilyawan, yang masuk<br />
dalam wilayah segitiga Sunni setelah Bagdad. Hampir seluruh warga di<br />
wilayah ini antipendudukan.Dua wilayah ini digempur habis-habisan<br />
tentara koalisi ketika menginvasi Irak tahun 2003. Tak mengherankan<br />
kalau gerakan perlawanan tumbuh subur di sini. Pertempuran masih<br />
kerap meletus, tak peduli siang atau malam.<br />
Ya Allah, apakah mereka menjadikan kami sebagai tameng?<br />
Jika pertempuran pecah, tubuhku akan jadi sasaran empuk<br />
berondongan peluru dari dua sisi berlawanan. []<br />
Bab 3<br />
Gua Terpencil di Tengah Gurun<br />
AKU masih tak bisa memercayai peristiwa yang tengah kami jalani.<br />
Bukan untuk menjalani ini aku jauh-jauh datang ke Irak. Dua belas hari<br />
lalu, tanggal 3 Februari, aku dan Budi bertolak dari Amman ke Bagdad<br />
bersama Ibrahim, melalui rute yang sama. Tak ada masalah di<br />
perjalanan. Ibrahim memang harus menyiapkan uang recehan untuk<br />
diberikan kepada orang-orang yang kerap menghentikan mobil kami<br />
sepanjang perjalanan.<br />
"Ini salah satu akibat buruk invasi," kata Ibrahim menjelaskan<br />
fenomena baru itu.<br />
Aku maklum. Toh di Jakarta juga banyak "polisi cepe" di<br />
persimpangan jalan, padahal tidak sedang mengalami darurat perang.<br />
Di Bagdad, kami menyewa dua kamar di hotel yang tidak terlalu<br />
besar, Coral Palace. Wartawan asing umumnya lebih memilih Hotel<br />
Palestine, yang berada di kawasan green zone atau zona hijau. Kawasan<br />
ini dianggap lebih aman karena dijaga ketat pasukan pendudukan. Tetapi,<br />
sebenarnya tidak bisa dibilang aman benar. Sebab,ternyata serangan<br />
bom bunuh diri oleh gerilyawan Irak justru lebih sering<br />
diarahkan ke kawasan yang konsentrasi pasukan pendudukannya<br />
tinggi, seperti green zone. Itu juga salah satu alasan kenapa kami memilih<br />
tinggal di Coral Palace, yang terletak di kawasan red zone atau zona<br />
merah. Di hotel ini pula, Budi menginap ketika pertama kali meliput Irak<br />
saat invasi baru berlangsung dua tahun lalu.<br />
Kami menyewa Muhammad Nasser, yang sebelumnya juga<br />
membantu Budi sebagai penerjemah, sekaligus guide untuk menembus<br />
akses ke kelompok Sunni. Nasser adalah seorang Muslim Sunni Irak. Dia<br />
selalu mencoba menjelaskan secara objektif berbagai informasi tentang<br />
Irak. Tetapi, dia tak bisa menyembunyikan keberpihakannya kepada<br />
mantan Presiden Saddam Hussein. Dalam kondisi tak menentu di Irak,<br />
Nasser paham betul risiko yang mengancamnya sebagai guide wartawan<br />
asing.
"Tapi saya harus menghidupi keluarga," kata Nasser, yang juga sopir<br />
KBRI di Bagdad.<br />
Dia memang kehilangan pekerjaan setelah kantor Kedutaan<br />
Indonesia ditutup pasca-invasi. Kami membayar Nasser 80 dolar Amerika<br />
per hari. Angka yang lumayan besar sebenarnya jika dalam kondisi damai.<br />
Untuk kendaraan liputan, kami menyewa mobil seorang lelaki tua yang<br />
mengerti bahasa Inggris dan biasa kami panggil Mister Wail. Entah apa<br />
merek sedan tua berwarna abu-abu milik Mister Wail karena bagian<br />
tulisan mereknya sudah dipereteli. Harga sewanya 50 dolar per hari,<br />
termasuk bensin.<br />
Selama meliput, aku merasakan suasana mencekam di Bagdad.<br />
Kota ini tampak seperti kota tua<br />
yang terbengkalai. Jalan-jalannya sebenarnya lebar dan sangat baik<br />
kualitasnya, tetapi sayang di beberapa ruas jalan utama kadang tampak<br />
lubang besar bekas serangan roket atau bom.Jembatan-jembatan layang<br />
yang tidak terkena serangan masih terlihat kukuh. Rambu-rambu lalu<br />
lintas penunjuk jalan terpampang sangat besar dan bagus.<br />
Dibandingkan dengan Jakarta, langit Bagdad sesungguhnya tampak<br />
begitu biru dan indah, tidak ada polusi, tidak ada asap. Walau hati tertekan<br />
dengan kondisi kota, setidaknya kami bisa menghirup udara bersih dan<br />
sejuk.<br />
Tidak banyak orang berlalu-lalang kalau tidak ada kepentingan yang<br />
mendesak. Jarang sekali ada yang keluar sekadar untuk "jalan-jalan"<br />
sore. Kebanyakan orang memilih untuk tinggal di rumah agar lebih aman.<br />
Pernah sore hari, aku dan Budi mencoba mampir di sebuah kedai kopi di<br />
daerah pusat kota, sayangnya pemilik kafe hanya mau membuka toko dari<br />
pagi sampai usai makan siang. Dia tidak berani buka sampai sore, kami<br />
pun terpaksa kecewa. Banyak lagi toko lain yang seperti itu. Walau tetap<br />
buka, mereka membatasi diri dengan waktu dan melihat situasi. Kalau<br />
merasa tidak aman, mereka akan tutup semau mereka.<br />
Gerakan perlawanan secara sporadis terhadap pasukan koalisi<br />
masih membara. Pelaksanaan pemilu juga menambah ketegangan itu.<br />
Maklumlah, selama ratusan tahun, kelompok Sunni, yang jumlahnya<br />
hanya 30 persen, memegang kendali kekuasaan politik. Kini, dengan<br />
pemilu demokratis pertama, diyakini<br />
dominasi mereka akan rontok oleh kelompok Syiah yang jumlahnya<br />
mencapai 60 persen di Irak.<br />
Meliput di Irak juga selalu diwarnai kejutan. Pengalaman hari<br />
pertama, misalnya,membuatku tersentak. Lewat tengah hari waktu itu.<br />
Kami tengah menuju Hotel Al-Rasyid, tempat Komisi Pemilihan umum<br />
Irak bermarkas, ketika tiba-tiba mobil kami dihentikan dan dikepung kirakira<br />
sepuluh orang berjaket hitam. Raut wajah mereka penuh amarah, dan<br />
tangan kanan mereka menodongkan pistol. Mereka berteriak dalam<br />
bahasa Arab, memaksa kami keluar dari mobil. Salah seorang dari<br />
mereka yang bertubuh jangkung mengunci leher Budi dengan tangan<br />
kanannya dan menekankan pistol ke pinggang Budi dengan tangan<br />
kirinya. Budi digiring entah ke mana. Aku bergegas mencoba<br />
menyusulnya, tetapi seorang dari mereka menghentikan langkahku<br />
dengan tangan kanan yang terus mengarahkan moncong pistol.<br />
"Jangan khawatir, mereka tidak akan membunuh Budi. Hanya
memeriksa," kata Mister Wail. Kenapa harus menodongkan pistol?<br />
Kira-kira dua puluh menit kemudian,Budi dikembalikan. Rupanya,<br />
kami tidak sengaja melewati salah satu pos rahasia pasukan koalisi.<br />
Ketika mobil kami melintas, Budi tengah mengambil gambar suasana<br />
jalanan dari dalam mobil. Menakjubkan! Berarti mereka memonitor gerakgerik<br />
setiap pengendara yang melintas. Padahal, jarak antara pos rahasia<br />
dan jalan raya cukup jauh, dan mobil kami sedang melaju.<br />
"Mereka curiga kalian mata-mata," kata Mister Wail, menjelaskan<br />
kenapa Budi diperiksa.<br />
Menurut Budi, dia diperiksa di pos tersebut. Letaknya masuk gang<br />
sehingga cukup tersembunyi. Luas bangunan dari beton itu hanya 1x1<br />
meter, dan tingginya tiga meter. Oleh orang-orang Irak tak berseragam itu,<br />
Budi diinterogasi dan diminta memutar gambar yang telah dia rekam<br />
sepanjang hari itu. Mereka ingin memastikan tidak ada gambar pos di<br />
kamera kami.Menurut Budi, wajah mereka tampak kesal karena ada<br />
adegan pasukan sipil Irak turun dari mobil jip yang terekam kamera.<br />
Mereka memanggil serdadu Amerika, yang juga meminta rekaman<br />
tersebut diputar ulang. Mereka minta adegan itu dihapus.<br />
"Selama kuputar ulang, ujung senjata laras panjang AK-47 tak pernah<br />
lepas dari leherku. Blendes, untung nggak ada gambar pos yang<br />
terekam." Budi masih mencoba bercanda, padahal ketegangan belum<br />
sirna dari wajahnya.<br />
Setelah itu, pada hari yang sama, terjadi pengalaman serupa. Saat itu<br />
Budi sedang memasang tripod di pembatas jalan utama kota, dekat<br />
Kedutaan Amerika Serikat. Kami ingin merekam suasana Bagdad yang<br />
porak-poranda. Ketika Budi baru saja menempatkan kamera di atas<br />
tripod, terdengar teriakan menghardik dari arah kedutaan. Kali ini da-nlam<br />
bahasa Inggris.<br />
"Stop shooting! Stop shooting!" Dua senjata laras panjang mengarah<br />
ke tubuh kami.<br />
Apa lagi ini? Dari kejauhan, kulihat tangan<br />
Nasser dan Mister Wail memberi isyarat agar kami segera kembali ke<br />
mobil.<br />
Namun, kudengar teriakan lain: "Don't move!"<br />
Komandan jaga kedutaan berlari ke arah kami. Dia kemudian<br />
meminta Budi memutar ulang rekaman gambar. Rupanya dia tak<br />
memercayai penjelasanku bahwa kami tak mengambil gambar kedutaan.<br />
Kali ini sikapnya lebih sopan ketimbang sepuluh lelaki Irak tak<br />
berseragam tadi. Dia pun meminta maaf sebelum mempersilakan kami<br />
berlalu.<br />
Baru beberapa jam di Irak, dua kali aku ditodong senjata! Bagaimana<br />
dengan warga Irak yang sudah menjalani kepahitan akibat invasi selama<br />
hampir dua tahun? Tak mengherankan kalau Nasser sering mengeluh<br />
hidup tertekan.<br />
Pengalaman itu membuat kami harus lebih hati-hati. Tetapi, tentu<br />
saja sikap itu menyiksa Budi. Dia tak bisa bebas merekam gambar.<br />
Bagaimana mau merekam gambar, baru memasang tripod saja sudah<br />
dibidik senjata.Padahal, gambar adalah modal utama laporan televisi.<br />
Budi mengaku liputan di Irak kali ini jauh lebih sulit dibandingkan tahun<br />
2003. Saat itu, wartawan masih bisa memetakan zona tempur atau
attlefield, dan masih ada wilayah yang aman.<br />
Betul kata Budi. Saat ini semua wilayah adalah zona tempur.<br />
Gerilyawan dapat meledakkan bom di mana saja. Tentara koalisi juga<br />
bisa melepas tembakan di mana saja karena merasa terancam.<br />
Itulah alasan kenapa pengamanan di kawasan zona hijau sangat<br />
ketat dan merepotkan. Itu kualami ketika membuat kartu identitas<br />
wartawan atau<br />
ID card khusus yang dikeluarkan seksi penerangan tentara koalisi,<br />
pada hari kedua liputan kami. ID ini penting kami miliki guna<br />
mempermudah masuk ke kawasan yang dijaga pasukan pendudukan.<br />
Tanda pengenal wartawan ini dikeluarkan di Hotel Al-Rasyid, Markas<br />
Komando Pasukan Koalisi. Untuk memasuki markas ini, seseorang<br />
harus melewati tujuh atau delapan lapis pos jaga. Aku tak ingat secara<br />
tepat. Di bagian paling luar, ada pos yang dijaga tentara dan polisi Irak. Di<br />
lapis-lapis berikutnya, pos dijaga pasukan koalisi dari negara-negara Asia<br />
yang mengirimkan tentaranya, seperti Korea Selatan dan Jepang. Barulah<br />
di lapis terdalam, kulihat pos dijaga tentara kulit putih.<br />
Pemeriksaan di setiap pos pun berbeda-beda. Ada pos pemeriksaan<br />
tas dan tubuh. Perempuan sepertiku akan digeledah oleh petugas<br />
perempuan. Pemeriksaan berlangsung cermat, bahkan kotak kosmetikku<br />
pun dibuka satu per satu. Ada juga pos yang pemeriksaannya dibantu<br />
anjing pelacak. Tas yang kami bawa diletakkan di lantai dan diendus<br />
anjing selama beberapa saat. Di pos lainnya, dilakukan tes tingkat<br />
keasaman, menggunakan kertas lakmus untuk mengukur Ph yang<br />
dimasukkan ke tas kami. Ada juga pos pemeriksaan alat elektronik.<br />
Telepon seluler dibuka, baterai dan casingnya dipisahkan. Adapun<br />
telepon berkamera harus ditinggal di pos dan diambil kembali ketika<br />
pulang. Budi menjalani pemeriksaan yang lebih rumit karena harus<br />
melepas baterai kamera. Benda ini memang kerap dicurigai sebagai<br />
pemicu bom.<br />
Perjalanan dari satu pos ke pos lainnya ber belok-belok, dengan<br />
tumpukan karung pasir di kiri— kanan setinggi dua meter. Di atas pos-pos<br />
jaga itu tampak tentara pengintai. Untuk lolos melalui semua tes ini<br />
dibutuhkan waktu setengah jam. Barulah kami tiba di pintu utama gedung<br />
yang dulu lebih dikenal sebagai Hotel Al-Rasyid.<br />
Namun, dengan kartu identitas khusus pun, keselamatan kami<br />
belumlah terjamin. Dulu, sebelum invasi, Presiden Saddam Hussein<br />
masih melindungi keselamatan wartawan asing. Tentunya untuk<br />
kepentingan propagandanya ke dunia internasional. Sesaat setelah<br />
invasi, pasukan koalisi juga menjaga keselamatan wartawan, dengan<br />
alasan yang sama. Tetapi kini, tidak ada lagi yang punya kepentingan<br />
melindungi wartawan. Bahkan,keadaan berbalik: kehadiran wartawan<br />
tidak diinginkan.<br />
Akibatnya, kami harus mencari jalan keluar di tengah serba<br />
keterkekangan ini.Kantor sudah memberikan kepercayaan penuh. Jauhjauh<br />
ke Irak percuma kaiau liputannya asal-asalan! Lagi pula, ini<br />
penugasan yang mahal. Di luar tiket dan akomodasi peliputanku, biaya<br />
lain yang cukup besar adalah pengiriman gambar melalui satelit atau<br />
feeding. Sekali mengirim gambar berdurasi 10 menit saja biayanya 800<br />
dolar. Padahal, feeding dilakukan minimal satu kali sehari.
Budi tak kehilangan akal. Dia mengambil gambar dari balkon kamar<br />
hotel pada malam hari. Cara ini tentu berisiko karena sepanjang jam<br />
malam setiap hotel dan gedung disorot lampu besar dari tanktank<br />
tentara koalisi. Kalau tindakan Budi ketahuan, dia bisa ditembak.<br />
Sebab, posisi Budi yang memanggul kamera di bahu kanannya ketika<br />
merekam gambar mirip dengan gerakgerik kelompok perlawanan yang<br />
tengah melontarkan roket jenis RPG (Rocket Propelled Grenades). Jika<br />
kamera ditempatkan di atas tripod pun kerap dicurigai sebagai alat<br />
pelontar roket.<br />
Cara lain adalah dengan lebih memfokuskan peliputan di daerah<br />
zona merah karena di sana lebih sedikit tentara koalisi yang berpatroli.<br />
Aku pun bisa bebas mewawancarai warga Irak. Memang berisiko karena<br />
di kawasan inilah bermukim kelompok-kelom pok garis keras dan antiinvasi.<br />
Tetapi, itulah risiko yang harus dihadapi.<br />
Kalau takut risiko, pergi saja dari Irak!<br />
Hari-hari berikutnya, aku menjadi terbiasa dengan rutinitas Bagdad.<br />
Ledakan bom menjadi menu harian dan letusan senjata lebih sering lagi.<br />
Belum lagi listrik yang dimatikan pada malam hari sehingga aku harus<br />
tidur di tengah kegelapan dan di antara bunyi desingan peluru.<br />
Suatu hari, aku dan Budi menonton tayangan televisi tentang<br />
pembunuhan seorang reporter televisi Al-Hurra, stasiun televisi lokal yang<br />
dikabarkan didanai Amerika. Dia diberondong gerilyawan ketika tengah<br />
tidur di kediamannya di Bagdad.<br />
"Tenang aja, Mut, biarpun ada puluhan ribu peluru berdesing di<br />
sekitar kita, kalau nama kita ng gak tertera di situ, ya kita nggak kena." Aku<br />
tertawa mendengar ucapan Budi dalam logat Jawanya<br />
yang kental. Padahal, Budi tidak sedang guyon sebab kulihat<br />
mimiknya sangat serius. Kupikir, benar juga ucapannya. Sebagai orang<br />
beragama, aku harus percaya takdir.<br />
* * *<br />
SEBENARNYA, tiga hari lalu, kami telah menyelesaikan liputan di Irak.<br />
Kami sudah melaksanakan tugas kami meliput pemilu di Irak. Kami<br />
meliput tingkat partisipasi masyarakat Irak dalam pemilu, yang ternyata<br />
cukup tinggi, di atas 60 persen, walau memang di daerah segitiga Sunni,<br />
termasuk Ramadi, banyak TPS yang kosong karena ada serangan-sera<br />
ngan ataupun ancaman ledakan bom. Untuk melihat transparansi<br />
pelaksanaan pemilu, kami rajin menyambangi kantor Komisi Pemilihan<br />
Umum Irak. Hampir setiap hari ada konferensi pers untuk mengumumkan<br />
sudah sejauh mana penghitungan suara dilakukan. Sayang, proses<br />
penghitungan dilakukan sangat tertutup, tidak seperti di Indonesia, kita<br />
bisa melihat penghitungan suara di TPS-TPS. Alasannya, demi keamanan<br />
para penghitung suara (menghindari mereka dari sabotase yang<br />
dilakukan pihak-pihak yang tidak menghendaki pemilu karena<br />
menganggap pemilu adalah hasil rekayasa Amerika). Walhasil,<br />
penghitungan suara tidak transparan dan jurnalis tidak bisa betul-betul<br />
yakin penghitungan suara dilakukan secara jurdil atau tidak.<br />
Sayangnya, ketika itu pengumuman hasil pemilu tertunda-tunda<br />
terus.Tenggat waktu seminggu pun<br />
lewat.<br />
Selama menunggu hasil pemilu diumumkan, aku dan Budi meliput
sisi-sisi lain dari Irak. Kami merekam sebanyak mungkin suasana Kota<br />
Bagdad. Sembari meliput itulah, aku memerhatikan betapa<br />
menyedihkannya Bagdad. Ibu kota negeri yang dulu disebut negeri seribu<br />
satu malam ini kini penuh kehancuran, berantakan, dan mencekam.<br />
Jalan-jalan kota dipenuhi tank-tank militer. Hampir di setiap sudut<br />
dijumpai tentara dengan senjata siap meletus. Gedung-gedung hancur.<br />
Museum Irak yang berisi karya-karya peninggalan sastra Islam/Timur<br />
Tengah juga hancur dan banyak karya berharga itu hilang. Kawat-kawat<br />
berduri dan tumpukan karung pasir bertebaran di jalan-jalan utama kota.<br />
Orang-orang, baik berpakaian seragam maupun preman, dengan santai<br />
berjalan memanggul senjata laras panjang. Dan yang lebih menyedihkan,<br />
orang Irak, yang dulu kabarnya terkenal ramah dan sangat menghormati<br />
tamu, kini lebih banyak yang ketakutan melihat orang asing. Tatapan<br />
mereka awalnya selalu curiga dan tidak bersahabat, barulah setelah kami<br />
bicara baik-baik mereka biasanya melunak. Banyak warga yang tidak mau<br />
bicara melihat kami membawa kamera. Mereka tidak banyak yang berani<br />
berbicara di depan kamera jika kami minta wawancara.<br />
Trauma dan ketakutan, itulah yang membayangi Kota Bagdad.<br />
Liputan kami juga mencakup kehidupan sehari-hari warga Bagdad.<br />
Kami meliput suasana di pasar Syahdun. Keramaian pasar bisa dijadikan<br />
tolok ukur<br />
pergerakan ekonomi.Di sebuah pasar di Kota Bagdad terlihat hanya<br />
beberapa toko yang buka. Menurut para pedagang, selama menunggu<br />
hasil pemilu diumumkan, masyarakat lebih banyak yang memilih tidak<br />
keluar rumah akibat khawatir dengan aksi-aksi perlawanan dari kelompok<br />
penentang pemilu. Jadi, pasar terlihat sepi, penjual juga tidak bergairah.<br />
Tiga hari setelah menyelesaikan tugas meliput itulah, kami berada di<br />
perbatasan Irak-Yordania, menuju Amman. Di perbatasan itu, kami harus<br />
menunggu untuk mendapatkan visa on arrival baru sebagai izin masuk ke<br />
Yordania. Kedutaan Yordania memang hanya memberikan visa model ini<br />
untuk sekali masuk, dan itu sudah kami gunakan ketika masuk dari<br />
Indonesia.<br />
Di perbatasan, hanya ada satu komputer yang dapat digunakan. Sial,<br />
sistem online keimigrasiannya sedang hang. Kami terpaksa menunggu<br />
tujuh jam hingga komputer tersambung kembali dengan kantor imigrasi di<br />
Amman. Meski siang hari, embusan angin serasa seperti ujung-ujung<br />
jarum dingin yang menembus hingga tulang. Chai, teh hangat khas Irak,<br />
tak mampu mengadang rasa dingin yang membekukan tubuhku. Di luar<br />
kantor imigrasi, butiran-butiran salju berjatuhan seperti kerikil putih yang<br />
ditaburkan dari langit.<br />
Telepon seluler dalam tasku berbunyi tanda SM S masuk. Dari nomor<br />
Koordinator Liputan di Kedoya.<br />
"Maaf Mut, Bud, rapat redaksi memutuskan kalian membatalkan<br />
pulang ke Amman dan tetap di Irak untuk meliput peringatan Asyura, 10<br />
Muharram<br />
mendatang. Dadi RS."<br />
Kami terkejut membacanya. Aku dan Budi hanya bisa saling pandang.<br />
Kembali ke Irak? Posisi kami telah keluar dari perbatasan Irak, tetapi<br />
belum lolos dari imigrasi perbatasan Yordania karena terganjal masalah<br />
visa. Untuk kembali ke Irak, kami harus mengurus visa di Kedutaan Irak di
Amman. Sebab, visa masuk Irak pun hanya berlaku sekali. Mereka pikir<br />
kembali ke Irak segampang membalik telapak tangani Setidaknya butuh<br />
waktu dua hari untuk memperoleh lagi visa Irak.<br />
Apa mau dikata. Ini perintah.<br />
Dan sebenarnya,aku juga berharap bisa meliput Asyura, peristiwa<br />
kematian cucu Nabi Muhammad Saw., Hussein bin Ali, yang diperingati<br />
kaum Syiah secara besar-besaran di Kota Karbala. Pada masa Saddam<br />
Hussein berkuasa, peringatan itu dibatasi. Tetapi setelah invasi, kaum<br />
Syiah dari luar Irak pun berdatangan.<br />
Esok paginya, kami mengurus visa di Kedutaan Irak di Amman.<br />
Tentu saja pejabat kedutaan yang lebih sepekan lalu kami temui<br />
terkejut.<br />
"Kenapa baru kemarin keluar dari Irak kini mau masuk lagi?"<br />
Berbagai alasan kami ajukan, termasuk soal janji wawancara dengan<br />
sejumlah tokoh pemenang pemilu yang belum sempat dipenuhi. Rencana<br />
peliputan Asyura sengaja kami rahasiakan. Kami tak ingin alasan ini<br />
justru menghambat pemberian visa.<br />
Maklum, selama dua tahun peringatan besar-besar an Asyura, selalu<br />
terjadi peristiwa kekerasan yang disinyalir dilakukan kelompok Sunni.<br />
Walaupun terlihat enggan, pejabat kedutaan itu akhirnya meminta<br />
kami kembali esok paginya untuk mengambil paspor dan visa.<br />
Selama sehari menunggu itulah, aku dan Budi berdiskusi panjang<br />
soal rencana masuk kembali ke Irak. Jujur, perasaanku menjelang<br />
keberangkatan kedua ini jauh berbeda dengan kali pertama. Ada<br />
keraguan yang terus menggelayut. Mungkin karena secara fisik mulai<br />
lelah. Tetapi, faktor psikis lebih banyak berperan. Beberapa hari berada di<br />
Bagdad yang tak menentu memang membuat kami tertekan. Wajar saja<br />
jika banyak warga Irak, terutama para perempuan, yang kabarnya kini<br />
selalu mengonsumsi obat penenang. Berat rasanya bagiku harus<br />
mengulang semua pemandangan itu.<br />
Bahasan pertama diskusi kami adalah apakah kami siap atau tidak<br />
masuk kembali ke Irak. Aku dan Budi sepakat, semua keputusan ada di<br />
tangan kami.<br />
"Jakarta boleh menugaskan, tetapi dalam kondisi begini, kita di<br />
lapanganlah yang memutuskan," kataku meyakinkan Budi.<br />
Peliputan Asyura di Kota Karbala bukan hal mudah. Karbala, yang<br />
dihuni mayoritas kaum Syiah, berjarak dua jam perjalanan dari Bagdad.<br />
Tentu saja, untuk memasukinya kami harus punya akses orang Syiah.<br />
Nasser yang Sunni tidak akan mau menemani kami ke Karbala.<br />
Peringatan Asyura tahun lalu diwarnai insiden ledakan bom, yang<br />
mengakibatkan<br />
lebih dari 200 orang tewas. Hampir di seluruh wilayah Karbala<br />
juga belum ada sinyal GSM. Ini berarti, selama meliput di sana, kami akan<br />
lost contact dengan Jakarta. Semua kendala ini menjadi bahan<br />
pertimbangan.<br />
Namun, kami juga memahami keinginan Kedoya. Peringatan Asyura<br />
adalah peristiwa yang sarat nilai berita, baik dari sisi visual maupun nilai<br />
sejarah.<br />
"Mas Bud siap?" tanyaku setelah menimbang semua kendala<br />
terburuk yang mungkin kami hadapi.
Budi mengangguk. "Kamu gimana, Mut?"<br />
Aku pun menganggukkan kepala tanda kesiapanku meliput Asyura.<br />
Aku percaya, jika diawali dengan niat baik, semua akan baik-baik saja.<br />
Insya Allah.<br />
Kami memutuskan, sebelum ke Karbala, kami masuk ke Bagdad<br />
lebih dahulu. Kota ini sudah kami kenal. Dari situ pula, kami akan<br />
mengatur strategi masuk ke Karbala. Bagaimanapun, kami harus segera<br />
masuk ke Irak karena satu minggu sebelum dan sesudah peringatan<br />
Asyura, semua perbatasan masuk dan keluar Irak akan ditutup. Itu<br />
keputusan pemerintah Irak untuk mengamankan peringatan Asyura.<br />
Tampaknya mereka tidak mau insiden yang menewaskan ratusan orang<br />
kembali berulang.<br />
Bahasan berikutnya adalah lewat jalur mana kami masuk Irak: darat<br />
atau udara. Dua-duanya memang tidak aman. Dan, kami harus memilih<br />
yang terbaik di antara yang buruk. Jalur darat, berarti kami harus melewati<br />
Kota Ramadi dan Fallujah, yang dikenal sebagai basis gerakan<br />
perlawanan, dan karena<br />
itu dua wilayah ini sangat rawan pertempuran.<br />
Jalur udara, selain masih jarang pesawat komersial yang beroperasi,<br />
juga tidak lebih aman. Selama peliputan di Bagdad, kami sering<br />
mendengar pesawat menjadi target serangan gerilyawan karena<br />
kebanyakan yang menggunakan jasa pesawat adalah orang asing.<br />
Banyak pesawat yang jatuh, baik sipil maupun militer, diberitakan karena<br />
mengalami kegagalan mesin (engine failure). Padahal, sebenarnya jatuh<br />
ditembak gerilyawan. Setelah aman mendarat pun, ancaman masih<br />
menghadang. Bandara Bagdad kini digunakan juga sebagai pangkalan<br />
militer pasukan koalisi sehingga kerap menjadi target serangan para<br />
gerilyawan.<br />
Dengan berbagai pertimbangan itu, akhirnya aku dan Budi merasa<br />
lebih yakin untuk menggunakan jalur darat. Menyelusup di tengah-tengah<br />
warga lokal pada umumnya.<br />
"Kalau kita harus memilih dua kondisi yang sama berbahayanya, kita<br />
ikuti feeling saja, Mas," kataku meyakinkan keputusan kami.<br />
Lagi pula, berdasarkan pengalaman wartawan Indonesia yang<br />
meliput Irak sebelum dan selama invasi, semua masuk ke Irak melalui<br />
jalur darat. Dan, terbukti aman.<br />
Dan, keputusan kami ternyata salah.<br />
Rasa sesal terus menghunjam kalbuku. Andai saja kami memilih<br />
jalur udara, aku pasti tidak akan terdampar di gurun antah-berantah ini.<br />
Aku pasti siap bermalam dalam kenyamanan kamar Hotel Coral Palace di<br />
Bagdad, sebelum menempuh perjalanan ke<br />
Karbala. Aku keliru terlalu mengandalkan feeling. Atau inikah takdirku?<br />
Seberapa pun ikhtiarku, aku tak bisa menghindari takdir,'<br />
Ah, lebih baik menerima kenyataan ini, sambil memikirkan langkah<br />
apa yang harus kuambil dalam ketidakberdayaanku. Aku tak mau<br />
dikacaukan pikir an-pikiran yang membuatku makin mumet.Lagi pula,<br />
jangan-jangan, kalau aku naik pesawat, malah pesawatku meledak<br />
ditembak gerilyawan. Atau, aku mati di pinggiran bandara yang diledakkan<br />
bom mobil. Mengingat dua kemungkinan terakhir itu, aku merasa lebih<br />
beruntung dengan kondisi yang kualami sekarang.
* * *<br />
GUA itu sedikit melesak ke bawah sehingga tidak mudah dilihat dari<br />
permukaan gurun. Sepertinya ini bukan gua alami, melainkan ciptaan<br />
manusia. Buktinya, ada tumpukan batu yang tertata rapi di sekeliling mulut<br />
gua, membentuk tempat berlindung yang boleh jadi sengaja dirancang<br />
untuk persembunyian. Warna bebatuannya yang kusam menunjukkan gua<br />
itu sudah tua. Mungkin gua ini semula dibangun untuk menyimpan<br />
perlengkapan pertanian karena wilayah Ramadi yang dialiri Sungai Eufrat<br />
dikenal sebagai daerah pertanian yang subur. Namun pascainvasi,terutama<br />
setelah muncul gerakan perlawanan terhadap pasukan<br />
koalisi, gua ini beralih fungsi menjadi tempat persembunyian gerilyawan.<br />
Dan kini, akan menjadi tempat penyekapanku?<br />
Aku tetap berharap dugaanku salah, tetapi ternyata tidak meleset. Tiga<br />
lelaki penculik itu keluar dari gua, dan salah satunya mendatangi Ibrahim.<br />
Setelah keduanya berbincang sejenak, Ibrahim menghampiriku,<br />
memberitahukan bahwa kami harus masuk ke gua. Tubuhku masih<br />
berdiri kaku, padahal tangan Ibrahim beberapa kali memberikan isyarat<br />
agar aku mengikuti perintah mereka. Budi juga terlihat lunglai. Kerut di<br />
wajah dan sorot matanya mengekspresikan seribu tanya yang tak<br />
terjawab. Kami tetap terpaku saat Ibrahim dan tiga lelaki itu mengeluarkan<br />
barang-barang dari mobil, dan memasukkan semuanya ke gua.<br />
Setelah saling pandang seolah-olah mempertanyakan apa yang<br />
tengah terjadi, aku dan Budi dengan enggan melangkah ke dalam gua.<br />
Aku harus sedikit merunduk ketika memasuki mulut gua yang sempit,<br />
padahal tinggiku hanya 159 sentimeter. Mungkin tinggi mulut gua itu hanya<br />
satu setengah meter. Pasti Ibrahim lebih tersiksa, lantaran tubuhnya tinggi<br />
besar, mungkin lebih dari 185 sentimeter. Udara lembap gua langsung<br />
menyerbu hidungku. Untunglah, langit-langit gua lebih tinggi dibandingkan<br />
pintunya, sekitar dua meter. Aku duduk di sisi kiri gua, berjejer bersama<br />
Budi dan Ibrahim.<br />
Ya Tuhan, kami harus berdesakan di gua kecil<br />
ini?<br />
Mataku menyisir ruangan gua. Luasnya mungkin tak lebih dari 3x4<br />
meter. Ada satu lubang di bagian belakang gua yang dipasangi teralis<br />
besi sehingga mirip sel penjara. Persis di tengah gua terdapat<br />
perapian kecil berbentuk persegi panjang. Di bagian tengahnya<br />
terlihat bekas arang yang dibakar. Beberapa bungkus rokok berceceran di<br />
antara bebatuan gua. Langit-langitnya hitam gelap, mungkin karena<br />
bertahun-tahun menerima asap dari perapian.<br />
Karena saat itu masih musim dingin, suhu udara tak lebih dari<br />
sepuluh derajat. Tentu saja ini bagian yang paling menyiksa. Jangankan<br />
kasur, tikar pun tak ada. Kami duduk hanya beralaskan pasir dan<br />
bebatuan. Tubuh Ibrahim tampak menggigil. Apalagi aku dan Budi, yang<br />
tak terbiasa dengan cuaca seperti ini. Dalam kondisi ini, rasanya nasib<br />
kami tak lebih baik dibandingkan tunawisma di kolong-kolong jembatan<br />
Jakarta.<br />
Inikah takdirku? Aku tak mau mengingkarinya. Tetapi, bukankah ada<br />
sisi lain yang harus dilakukan sebelum menerima takdir: ikhtiar? Kalau<br />
saja aku dan Budi menolak perintah kantor untuk kembali ke Irak.Andai<br />
saja aku tidak kembali ke Irak melalui darat. Kalau saja aku naik pesawat
dari Amman ke Bagdad. Pasti penculikan ini tak akan terjadi. Mungkinkah<br />
aku bisa menghindari takdir?<br />
Beberapa menit setelah kami mulai tersimpuh di dalam gua, seorang<br />
penculik berbicara kepada Ibrahim,yang kemudian menyampaikannya<br />
kepadaku dan Budi dengan penuh keyakinan.<br />
"Mereka menunggu Rois. Kalau dia datang, kita bisa bebas malam ini<br />
atau esok. Dia yang akan memutuskan."<br />
Rois, kata Ibrahim, adalah pemimpin kelompok<br />
yang menculik kami. Hanya itu yang dijelaskan Ibrahim, padahal<br />
rasanya banyak sekali penjelasan lelaki penculik itu kepada Ibrahim.<br />
Sesudah itu, kami terdiam dalam dingin yang makin membekukan. Hanya<br />
mata kami yang kadang saling tatap.<br />
Walaupun berharap penjelasan Ibrahim benar, aku enggan terlalu<br />
percaya pada omongan para penculik itu.<br />
Sinar mentari di luar gua tampak sudah redup. Gua pun menjadi<br />
temaram. Pasti omongan penculik itu hanya untuk menghibur.<br />
Namun tiba-tiba, di luar gua sayup-sayup terdengar suara. Pasti itu<br />
suara kendaraan! Di tengah gurun yang sangat sunyi ini, suara langkah<br />
kaki saja sangat jelas terdengar, apalagi kendaraan. Aku tak sangsi lagi,<br />
derum suara yang makin mendekat itu pasti suara mobil. Mereka tidak<br />
bohong. Rois datang dan segera membebaskan kami! Rasanya aku ingin<br />
melonjak. Wajah Budi yang tengah berjuang menahan hawa dingin juga<br />
berubah sum-ringah. Ibrahim pasti merasakan hal yang sama. Namun,<br />
ketika suara mobil itu makin mendekat ke mulut gua dan kemudian<br />
berhenti, kesangsianku berganti harapan. Seorang penculik yang dari tadi<br />
menjaga kami menjemput keluar gua. Suara obrolan dan derap kaki<br />
makin mendekat. Harapanku untuk segera bebas pun kian membulat.<br />
Tiga lelaki melangkah ke dalam gua, salah satunya yang tadi<br />
menjemput keluar. Yang mana Rois? Kenapa mereka membawa selimut,<br />
alas tidur, dan lampu minyak?<br />
Persendianku langsung lemas. Melihat barang-barang yang mereka<br />
bawa, berarti kami harus menginap di gua. Rois tidak datang. Dua orang<br />
itu hanya anggota biasa kelompok penculik, dan mereka datang untuk<br />
mengantar logistik.<br />
"So we sleep here tonight?" Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya<br />
kepada Ibrahim.<br />
Mata para penculik langsung memandang tajam ke arahku. Ibrahim<br />
buru-buru menjelaskan pertanyaanku dalam bahasa Arab, agar mereka<br />
tidak salah sangka. Seorang penyandera menjelaskan panjang lebar<br />
kepada Ibrahim, sambil sesekali menatap ke arahku seolah-olah dapat<br />
membuatku mengerti.<br />
"Yes, we sleep here tonight. Tomorrow Rois will come and he will<br />
decide whether we can be freed or not. Now Rois can not come here<br />
because it's too late to come to Ramadi," kata Ibrahim, menerjemahkan<br />
penjelasan seorang penculik.<br />
Aku yakin penjelasan penculik sebenarnya lebih panjang dan berbelit.<br />
Tetapi intinya, aku dan Budi harus menginap di gua itu.<br />
Dua lelaki pembawa logistik kemudian pergi. Hari makin gelap. Kami<br />
bertiga ditinggal di tengah gurun bersama tiga orang bersenjata. Tiba-tiba<br />
saja, perutku terasa mual.
Apa yang akan terjadi padaku kemudian?<br />
Ketiga penyandera itu mulai sibuk membentangkan selimut untuk<br />
alas tidur kami. Seorang penyandera yang terlihat lebih tua dan sebagian<br />
wajahnya masih ditutup kafiyeh menyuruhku beristirahat di pojok kiri gua.<br />
Untukku seorang. Rupanya<br />
dia masih menghormati privasi seorang wanita meski daiam kondisi<br />
darurat. Tetapi, seorang lelaki lain yang tadi menodongkan senjata AK dan<br />
duduk di jok mobil belakang masih saja tak bersahabat. Bahkan, sorot<br />
matanya kerap membuatku risih.<br />
Budi harus berbagi pojokan lain dengan Ibrahim. Satu pojokan lagi<br />
untuk ketiga penyandera. Tumpukan perangkat liputan kami dua kamera,<br />
tripod, dua laptop, videophone, telepon satelit di salah satu sisi lantai<br />
membuat gua itu makin terasa sempit sehingga kami tidak bisa bergerak<br />
di pojok masing-masing. Dalam posisi tidur, kakiku pasti mengenai<br />
kepala Budi dan Ibrahim, sementara posisi kaki Budi tidak jauh dari<br />
kepala para penyandera.<br />
Lampu minyak dinyalakan. Perapian di te ngah-tengah gua juga diisi<br />
kayu dan dibakar untuk memberikan kehangatan. Seolah-olah ada yang<br />
menggerakkan,kami mulai berkumpul di dekat perapian, menjulurkan<br />
tangan yang mulai membeku ke dekat api. Tak terkecuali para<br />
penyandera.<br />
Suasana pun terasa lebih cair. Rasa kebersamaan tiba-tiba muncul,<br />
meruntuhkan "tembok besar" yang mengadang penyandera dan<br />
tersandera.<br />
Untuk pertama kalinya, kami bertukar senyum dengan dua lelaki yang<br />
lilitan kafiyeh-nya sudah melorot, sambil menikmati hangatnya perapian<br />
kayu bakar. Adapun seorang lelaki yang dari tadi sudah tak berpenutup<br />
muka tetap saja membuatku curiga. Sebagai perempuan dewasa, aku<br />
sangat mengerti arti tatapannya.<br />
Namun, kepada dua penculik lain, aku mulai<br />
berani menatap wajah. Mereka tidak berbeda dengan warga Irak<br />
umumnya. Aku yakin mereka masih muda. Mungkin yang satu malah lebih<br />
muda dariku meski garis-garis pada wajahnya membuatnya kelihatan<br />
lebih tua. Untuk apa mereka melakukan semua ini?<br />
Namun, mendadak dadaku berdebar-debar. Wajah mereka<br />
mengingatkanku pada peristiwa ledakan bom mobil di lapangan At-Tahrir<br />
(Monumen Pembebasan) di pusat Kota Bagdad. Anak-anak muda seperti<br />
merekakah pelakunya? Masih terngiang ketika sebuah suara ledakan<br />
yang sangat besar terdengar hingga ke hotel kami. Waktu itu, aku dan<br />
Budi langsung bergegas menuju lokasi, meninggalkan sarapan pagi kami<br />
yang belum tuntas. Di lokasi, kerumunan massa sudah ramai. Darah<br />
berceceran di jalanan. Pecahan kaca berserakan. Luar biasa, ini<br />
merupakan salah satu ledakan terbesar selama peliputanku di Irak.<br />
Lokasi ledakan persis di jantung kota, dan hanya dipisahkan<br />
jembatan dari markas Komando Militer Amerika. Ini menandakan eskalasi<br />
gangguan keamanan terus meningkat dan semakin berani. Berhubungan<br />
atau tidak dengan hasil pemilu yang ter tunda-tunda, entahlah.Aku dan<br />
Budi berpencar. Dia mengambil gambar sebanyak mungkin, sementara<br />
aku menggali informasi dari para saksi. Kami seperti terlarut dalam<br />
liputan yang mengasyikkan.
Nasser, dengan wajah yang tampak tegang, berlari ke arahku.<br />
"Meutya, segera tinggalkan tempat ini. Berbahaya!"<br />
Tetapi, aku tak menggubrisnya. Sikap Budi juga demikian ketika<br />
Nasser mengingatkannya. Kami malah berlari ke arah serpihan mobil<br />
yang dijaga ketat polisi.Kendaraan pembawa bom itu luluh lantak. Aku<br />
menelisik serpihan di dekat mobil. Ada pecahan dari rangkaian bom yang<br />
tidak turut meledak. Arus deras adrenalin kewartawananku secara refleks<br />
mendorongku untuk melakukannya tanpa kekhawatiran sedikit pun. Budi<br />
pun secara refleks merekam gambarku memegang potongan bom.<br />
Sambil memegang potongan bom, aku menjelaskan peristiwa ledakan<br />
tersebut di depan kamera.<br />
Nasser kembali memohon aku melepaskan potongan bom itu dan<br />
segera meninggalkan lokasi.<br />
Merasa sudah cukup, kami pun segera kembali ke mobil. Mister Wail,<br />
yang rupanya dari tadi gelisah, langsung menancap gas menjauh dari<br />
lokasi ledakan.<br />
"Berbahaya, Meutya. Kamu terlalu mencolok sebagai<br />
wartawan,padahal banyak pihak yang tidak suka wartawan masuk begitu<br />
dekat. Kamu tahu, mungkin pelaku peledakan juga masih berada di<br />
sekitar lokasi dan melihat kamu memegang potongan bom. Apa kamu<br />
tidak berpikir bom itu bisa meledak?" Nasser menjelaskan panjang lebar<br />
kenapa dia memaksa kami segera pergi. Sebenarnya, aku juga<br />
sependapat dengan Nasser. Tetapi, entah kenapa saat itu aku begitu larut<br />
tanpa rasa takut sama sekali.<br />
* * *<br />
DAN kini, aku berhadap-hadapan dengan tiga manusia yang pasti<br />
memiliki kenekatan seperti pelaku bom bunuh diri itu. Meski bisa<br />
tersenyum, aku tak bisa meredakan debaran jantungku dan menutupi<br />
rasa cemasku. Kecemasan itu tambah memuncak ketika kami bersiap<br />
untuk istirahat dan mulai bersandar di pojok masing-masing. Budi dan<br />
Ibrahim tampaknya mulai nyaman walaupun kaki mereka harus ditekuk<br />
dan saling berebut selimut. Ketiga penyandera juga sudah bersandar<br />
dengan senjata laras panjang tergeletak meski masih dalam jangkauan<br />
tangan mereka.<br />
Dalam keadaan begini, rasa mual di perutku kembali terasa dan<br />
mendadak aku menjadi rindu rumah. Belaian tangan mamaku selalu<br />
membuat rasa mual di perutku sirna seketika. Petuah-petuahnya bagai<br />
menyirami hatiku saban aku gundah. Aku rindu Mama. Aku butuh<br />
kehangatannya.<br />
Aku masih ingat wajah kagetnya ketika kuka-bari akan berangkat ke<br />
Irak, padahal baru saja Mama kutinggal pergi ke Aceh dan Makassar.<br />
"Hah, ke Irak? Mau ngapain?" Mama lebih kaget lagi karena aku harus<br />
berangkat malam itu juga. "Nanti malam? Jam berapa? Sama siapa aja?<br />
Berapa orang, Bingbing?" Pertanyaan itu tak bisa distop dari mulut Mama,<br />
yang biasa memanggilku Bingbing.<br />
"Jam 12 malam berangkat. Udah ah, Mama jangan tanya-tanya dulu,<br />
cape nih," jawabku merajuk. "Mending Mama bantuin ngepakin barang aja<br />
yuk. Katanya di sana musim dingin, harus beli kaus<br />
kaki dan sarung tangan, Ma." Mama kemudian sibuk membantu
persiapanku. Tak terucap lagi protes dari mulutnya walau aku bisa<br />
membaca kekhawatiran yang memancar dari wajahnya.<br />
Aku juga teringat Teh Finny. Kakakku inilah yang menggantikan peran<br />
Ayah menjaga keluarga, selepas kepergian Ayah. Dia juga selalu menjadi<br />
teman curhat kalau Mama tidak ada di sampingku. Kemarin, aku masih<br />
mengiriminya SMS. "Teh Finny, Meutya diminta kembali ke Irak, pulang<br />
masih lama, tanggal 25. Diambil positifnya sajalah. They like my reporting,<br />
I guess. Nggak apa-apa kok, I'll be fine." Pasti Teh Finny tidak tahu aku<br />
sedang menghadapi masalah. Pasti saat ini dia sudah tertidur lelap.<br />
Di sini, meski malam makin larut, aku belum juga mampu<br />
memejamkan mata, padahal rasa lelah mendera tubuhku. Aku masih sulit<br />
menerima keberadaanku di gua ini, bersama lima lelaki, empat di<br />
antaranya baru kukenal. Masih terbayang raut beringas para penyandera<br />
ketika menculik kami di pompa bensin.<br />
Jangan-jangan mereka akan menganiayaku ketika aku terlelap.<br />
Terutama lelaki yang satu itu, yang matanya selalu menatapku penuh<br />
nafsu. Tadi dia mencoba merapikan selimutku, tetapi urung karena<br />
tangannya kutepis. Siapa yang mau menolongku jika mereka membunuh<br />
Budi dan Ibrahim lebih dulu, lalu memerko ... ahh,<br />
Tidak!<br />
Aku harus tetap berpikir positif. Kekhawatiran dan ketakutan hanya<br />
membuat panik dan mengikis<br />
kemampuanku berpikir jernih.<br />
Kupandang sekali lagi dua penyandera yang mulai terlelap, juga lelaki<br />
yang satu itu. Betulkah mereka tidur, atau ...? Badan mereka jauh lebih<br />
besar dariku. Kupandang sekali lagi senapan Kalash-nikov mereka.Pasti<br />
sudah merenggut nyawa banyak orang. Batu besar di bawah selimutku<br />
serasa menusuk punggung.Cahaya lampu minyak semakin redup.<br />
Dengkuran kelima lelaki itu mulai terdengar bersahutan.<br />
Rasanya tak ada yang bisa kulakukan saat ini kecuali pasrah dan<br />
berdoa.<br />
Semoga Tuhan melembutkan hati para penyandera, membuat<br />
mereka terlelap malam ini. []<br />
Bab 4<br />
Selamat Jalan, Budi<br />
UDARA seperti beku dan aku menggigil di dalamnya. Ah, pasti aku<br />
lupa mengecilkan volume air conditioner sebelum tidur. Kantuk masih<br />
memberati pelupuk mataku.Tetapi hawa dingin ini, dan lamat-lamat suara<br />
percakapan orang di telinga, memaksaku perlahan membuka mata.<br />
Kenapa langit-langit Hotel Coral Palace hitam legam? Kugosok kedua<br />
kelopak mataku. Ya Tuhan, aku tidak sedang menginap di hotel.<br />
Aku terperanjat bangun.<br />
Budi dan Ibrahim sedang mengobrol dengan lelaki yang kemudian<br />
tersenyum ke arahku.<br />
"Shobahal khoir, Meutya.'" sapa lelaki itu.<br />
Dia mengena/ namaku. Pasti Budi dan Ibrahim memberitahunya.<br />
Atau, mungkin dia mengetahui namaku dari pasporku.<br />
"He said, good morning, Meutya," ucap Ibrahim tersenyum.<br />
Aku sudah akrab dengan sapaan shobahal khoir, yang kerap<br />
diucapkan Nasser dan Mister Wail saat menjemputku di lobi Hotel Coral
Palace, Bagdad.<br />
"Maaf, aku terlambat bangun. Tidurku lelap sekali." Aku membalas<br />
senyum mereka.<br />
"Wah, kamu beruntung. Setiap dua jam aku<br />
selalu terjaga." Ibrahim lalu menjelaskan, tidurnya tak nyenyak karena<br />
saban dua jam selalu diganggu deru pesawat tempur yang terbang di<br />
atas gua. Kalau saja pesawat itu berhasil melacak keberadaan kami,<br />
mungkin mereka akan menembak atau menjatuhkan bom.<br />
"Kita berada di wilayah basis perlawanan. Siapa pun di gua ini pasti<br />
dianggap terlibat gerakan perlawanan," kata Ibrahim lagi.<br />
Terima kasih, ya Aliah. Kau telah membuat tidurku lelap. Kalaupun<br />
pesawat tempur itu menjatuhkan bom, aku akan menghadap-Mu dalam<br />
tidur, tanpa iringan rasa cemas seperti Ibrahim. Aku juga merasa lebih<br />
segar pagi ini.<br />
Lelaki yang tadi menyapaku, yang kini wajahnya tak lagi ditutup<br />
kafiyeh, beranjak ke luar gua.<br />
"Ke mana yang lain?" tanyaku mengenai dua lelaki lain yang tak<br />
tampak.<br />
"Mereka di luar. Kamu tidak diganggu si sontoloyo itu, kan?" Rupanya<br />
Budi juga memerhatikan lelaki yang tingkahnya selalu membuatku risih.<br />
Hm m, cocok juga julukan Budi untuk lelaki itu: si sontoloyo .<br />
Panjang umur dia! Lelaki yang kami bincangkan itu masuk dengan<br />
menenteng senjata kesayangannya, AK-47. Dia berjalan ke arahku. Mau<br />
apa lagi dia? Tanpa berkata-kata, tangan kirinya menggapai dan<br />
merapikan kerudungku. Kurang ajar! Tak cukup ngan tindakan<br />
memuakkan itu, dia kemudian meraih lenganku, mencoba menyeretku ke<br />
luar. Tentu saja aku menepisnya dengan kasar.<br />
Budi dan Ibrahim hanya melongo. Mereka ragu untuk menolong<br />
karena bisa saja senjata di tangan kanan lelaki itu menyalak.<br />
Namun, aku tak peduli. Kali ini kupukul tangannya ketika mencoba<br />
meraih lagi pergelanganku.<br />
"No!" bentakku. Dia bersungut-sungut. Entah apa yang<br />
dikatakannya. Matanya beringas.<br />
Tak berhasil menyeretku, dia berkata kasar pada Ibrahim. Setengah<br />
berbisik, Ibrahim menerjemahkannya pada Budi, "Kita berdua harus<br />
keluar."<br />
Apa maunya lelaki ini? Kenapa kami dipisah? Tubuhku bergidik.<br />
Pikiran-pikiran buruk yang melintas semalam kembali berkecamuk. Aku<br />
sangat takut lelaki ini akan memerkosaku di dalam gua, lalu<br />
membunuhku sebelum menghabisi Budi dan Ibrahim. Ya Allah, kalaupun<br />
aku harus mati, janganlah dengan cara nista seperti ini. Lelaki itu beranjak<br />
keluar, mengiringi Budi dan Ibrahim. Tatapan mata di wajah ketusnya<br />
menusuk jantungku. Jangan-jangan dia akan kembali setelah<br />
"mengamankan" Budi dan Ibrahim. Perasaanku masih terguncang oleh<br />
peristiwa tadi. Aku teringat ucapan lelaki yang lebih bersahabat ketika<br />
melarikan kami di mobil, "Kami tak akan mencelakaimu." Jaminan itu kini<br />
sulit kupercaya. Boleh jadi ketiganya sama saja. Bedanya, yang dua orang<br />
lebih banyak senyum dan sok bersahabat, sedangkan yang satu lagi<br />
kasar. Tetapi, ketiganya sama-sama penculik dan penjahat!<br />
Suara tembakan memecah kesunyian. Ya Tuhan, mereka benar-
enar melakukannya ?<br />
Kesunyian yang sejenak pecah lagi oleh beberapa letusan.<br />
Butir-butir keringat dingin membasahi tubuhku yang kian menggigil.<br />
Selamat jalan, Budi, selamat jalan Ibrahim. Aku akan segera<br />
menyusulmu, mungkin dengan cara yang lebih menyiksa. Mama, maafkan<br />
aku. Aku tak mampu lagi berpikir jernih. Baya ngan-bayangan mengerikan<br />
makin menghantui. Poto ngan-potongan gambar para sandera di Irak<br />
yang pernah kusaksikan di televisi, dan beberapa di antaranya pernah<br />
kubacakan di layar, berkelebat satu demi satu. Beberapa hari lalu, ketika<br />
mengirimkan gambar di kantor APTN Bagdad, aku juga menonton<br />
rekaman gambar kiriman orang tak dikenal, yang memperlihatkan<br />
kelompok perlawanan menembak seorang sandera.Tentara Amerika<br />
Serikat itu ditembak berkali-kali dari jarak sangat dekat. Matanya tertutup<br />
kafiyeh. Tubuhnya ambruk dengan kepala yang bersimbah darah. Tak ada<br />
kata-kata terakhir yang terucap dari mulutnya.<br />
Dan kini, aku tengah menunggu giliran menjalani nasib sang<br />
serdadu.<br />
Gambaran lain muncul. Seorang tawanan, dengan posisi tubuh<br />
bertumpu pada lutut, tengah menyongsong sang maut. Beberapa orang<br />
berdiri di belakangnya dengan muka tertutup. Tangan mereka mengokang<br />
senjata laras panjang. Seorang lagi, dengan wajah yang juga tertutup,<br />
membacakan pernyataan di kertas yang digenggamnya. "Ini peringatan<br />
bagi tentara Amerika dan sekutunya yang menolak<br />
hengkang dari bumi kami." Begitulah salah satu baris<br />
pernyataan yang dibacakan. Sang algojo itu kemudian menggorok leher<br />
sandera dengan sebilah parang, setelah mulutnya mengagungkan nama<br />
Allah. Jeritan sang sandera menggema, diikuti takbir dari para lelaki di<br />
belakangnya. Tubuhnya tersungkur.<br />
Cara kematian inikah yang akan kujalani? Aku pasrah. Seperti apa<br />
pun bentuknya, aku ingin mati dengan tersenyum. Ampuni dosa-dosaku,<br />
ya Allah.<br />
Derap langkah kaki menghampiri mulut gua. Seperti langkah tergesa.<br />
Inikah ajalku? Si sontoloyo muncul. Wajahnya tidak segarang ketika<br />
menggelandang Budi dan Ibrahim keluar. Malah dia mencoba tersenyum.<br />
Mungkin dia ingin memberikan kesan manis dengan menebar senyum di<br />
penghujung hayatku. Tetapi, rasa takut dan benciku tak luruh. Tangan si<br />
sontoloyo memberikan isyarat agar aku keluar. Bayangan kematian<br />
semakin nyata, menyeret ingatanku pada hari terberat yang pernah<br />
kualami.<br />
* * *<br />
HARI itu, 2 Mei 2004, tepat satu hari sebelum perayaan hari jadiku<br />
yang ke-26. Ayah sudah beberapa hari sakit. Awalnya kupikir batuk biasa,<br />
disertai gangguan lambung yang membuatnya terus-mene rus buang air<br />
dan sempat muntah. Wajahnya tampak lemas. Setiap menuju ruang<br />
makan dari kamarnya, Ayah minta dipapah anak-anaknya, termasuk<br />
aku. Kupikir itu hanya cara Ayah bermanja bersama kami. Kadang<br />
kuturuti, kadang lebih sering Mama atau kakak-kakakku yang membantu.<br />
Ayah memang begitu, selalu ingin dimanja olehku. Namun, sering kali<br />
kesibukan kerja dan aktivitasku membuat semua keinginan Ayah
terabaikan.<br />
Dan pagi itu, Mama memintaku mengantar Ayah ke dokter, yang hanya<br />
beberapa blok jauhnya dari rumah kami. Di mobil, kuajak Ayah bercanda,<br />
tetapi dia diam saja. Beberapa kali dia mengeluh bagian lambungnya<br />
sakit.<br />
"Kalau tetap tak mau makan, Ayah harus masuk rumah sakit,"<br />
kataku.Kuharap ucapanku bakal membuat Ayah, yang sangat membenci<br />
rumah sakit, akhirnya mau makan.<br />
Ayah tetap diam, sambil merebahkan kepalanya di pangkuan<br />
mamaku. Walaupun lemas dan mengaku sakit di lambung, bagiku Ayah<br />
masih terlihat cukup sehat. Mungkin mata dan hatiku dibutakan, atau<br />
memang mengingkari kenyataan di hadapanku. Aku lebih memilih<br />
menepati janji makan siang dengan teman dan meninggalkan Ayah di<br />
rumah, setelah kembali dari dokter. Ayah pasti sembuh. Mana mungkin<br />
peiindungku sakit parah. Itulah alasanku meneruskan aktivitas.<br />
Ketika siang hari kakakku mengabarkan bahwa Ayah dibawa ke<br />
rumah sakit karena kondisinya tak membaik, aku juga tidak langsung<br />
pulang. Baru se-mkitar dua jam kemudian, aku tiba di Rumah Sakit<br />
Fatmawati, langsung menuju ruang gawat darurat. Kudapati Ayah masih<br />
sadar dan cukup kuat untuk<br />
bangkit dari tempat tidurnya. Dia memaksa pulang.<br />
"Ayah banyak pekerjaan, Ayah mau pulang," begitu alasannya setiap<br />
kali kami menolak keinginannya. Ayah kemudian memintaku<br />
mendekatkan telingaku ke mulutnya. "Ayah mau pulang, Bing, Ayah mau<br />
pulang ..." bisiknya pelan.<br />
Aku tak punya firasat apa pun ketika dia bilang "mau pulang". Aku<br />
malah balik menjelaskan, Ayah tidak mungkin pulang kalau belum<br />
sembuh. Aku menurut saja ketika kakakku memintaku pulang menemani<br />
Mama. Ayah dirawat di ruang ECU yang tak bisa ditunggui keluarga karena<br />
di ruang yang sama juga dirawat banyak pasien lain. Hanya kakak dan<br />
pamanku yang tinggal di rumah sakit. Aku akan menjagamu nanti, esok<br />
hari, Ayah. Aku tidur di rumah dengan "hanya" sedikit rasa khawatir.<br />
Pukul dua dini hari, aku terjaga oleh ketukan keras di pintu kamar. Aku<br />
tersadar, bukan hanya dari tidurku, tetapi dari kenyataan. Semuanya<br />
tampak begitu jelas. Seketika aku dibuat mengerti. Tidak ada lagi kata<br />
"nanti". Aku berlari ke mobil. Air mata mulai berjatuhan saat aku menyadari<br />
bahwa pada saat yang sama ayahku tengah berjuang mempertahankan<br />
hidup. Berbeda dari biasanya, aku bergerak cepat. Namun perjalanan<br />
mobil, yang sebenarnya bisa mencapai rumah sakit dari kediaman kami<br />
hanya lima menit, rasanya seperti setengah jam.<br />
Aku membanting pintu ketika mobil belum berhenti sempurna, berlari<br />
menuju ruang ECU. Tidak boleh lagi ada kata "nanti" untuk ayahku,<br />
pelindungku.<br />
Waktu Ayah tidak banyak, aku harus berada di sampingnya<br />
segera. Satu detik pun tak akan kulewatkan, bahkan seperseratus detik<br />
pun tidak. Kugedor pintu ruangan, menyeruak masuk melewati pa sienpasien<br />
lain. Dalam lariku, mataku menumbuk sosok Ayah tepat ketika<br />
kakakku, Finny, menutup mata sang pelindungku. Mataku terpaku pada<br />
tubuh Ayah. Seorang suster mulai menarik kain putih. Menutupi kaki, lutut,<br />
paha, terus ke pinggang, dada, bahu, wajah, hingga kepala Ayah. Lututku
tidak kuat lagi menahan tubuhku. Aku terjatuh tepat saat badanku ditarik<br />
keluar ruangan. Tangisku pecah.<br />
Bagaimana mungkin ini terjadi. Bagaimana mungkin Ayah pergi<br />
begitu cepat, dalam usia 63 tahun. Dia masih sehat beberapa jam<br />
sebelumnya. Dia masih memintaku merayakan hari jadiku bersama<br />
keluarga besarku di Bandung. Aku seharusnya giliran menjaganya di<br />
rumah sakit hari ini. Ya Tuhan, aku bahkan belum sempat meminta maaf<br />
padanya. Bagaimana bisa aku begitu bodoh dan tidak membaca<br />
pertanda? Bagaimana bisa aku memilih tidak bersamanya pada detikdetik<br />
terakhir hidupnya? Bagaimana bisa aku tidak menemaninya,<br />
mengusap kepalanya seperti yang selalu dia minta, dan memijat kakinya?<br />
Bagaimana bisa aku tidak mengucapkan ka limat-kalimat manis di akhir<br />
hidupnya? Padahal, sepanjang hidupku, Ayah selalu memujiku,<br />
menyanjungku, menyemangatiku. Atau ... mungkinkah Ayah memilih untuk<br />
pergi tanpa menunggu kedatanganku karena dia begitu kecewa<br />
terhadapku? Aku terlambat!<br />
Aku anak durhaka!<br />
Aku hampir tak sadarkan diri. Darah segar mengalir dari hidungku.<br />
Kulihat mamaku terjatuh lemas dalam pelukan kakakku. Rautnya tampak<br />
sangat terpukul, nyaris tak sadarkan diri. Aku tak boleh terus menangis<br />
demi mamaku. Aku harus kuat. Aku tahan tangisku, tetapi rasa sakit dan<br />
pilu itu justru memuncak. Penyesalan seperti tiada habisnya, mengiris<br />
hatiku. Aku masih ingat betul rasa sakit itu, hingga kini. Teramat sangat<br />
menyakitkan. Tak ada yang mampu menandingi rasa sakit itu. Tidak para<br />
penculik ini. Tidak si sontoloyo!<br />
* * *<br />
SI SONTOLOYO kembali mengibaskan tangannya, memintaku keluar.<br />
Kali ini aku turuti perintahnya tanpa rasa takut. Kulihat tangannya tak<br />
memegang senjata. Mungkin disimpan di luar gua setelah dia<br />
menghabisi nyawa Budi dan Ibrahim. Senyum di wajahnya bagiku seperti<br />
seringai dengan taring berlumur darah. Pasti kulawan kalau dia berbuat<br />
macam-macam padaku mekipun aku harus mati. Kamu tak boleh<br />
menyerah, Meutya!<br />
Aku bangkit dari simpuhku. Kutepis tangan si sontoloyo ketika entah<br />
untuk keberapa kalinya mencoba memperbaiki letak kerudungku.<br />
"Lebih baik bunuh saja aku! Mujahidin seharusnya menghormati<br />
wanita!" Aku setengah berteriak, dengan bahasa Inggris yang sengaja<br />
tanpa aturan<br />
bahasa.<br />
Dan, teriakan itu membuatnya terperanjat, entah karena mengerti<br />
ucapanku entah karena kaget aku memakinya. Namun, ucapan nekatku itu<br />
membuatnya mundur beberapa langkah, melebarkan jalanku beranjak<br />
keluar gua.<br />
Dengan tegar, aku melangkah ke mulut gua. Doa-doa kupanjatkan<br />
untuk menenangkan diri.<br />
Di pintu gua, pandanganku silau setelah lebih dua belas jam berada<br />
di gua yang temaram. Di mana mereka menghabisi Budi dan Ibrahim?<br />
Belum sempat aku melihat sekeliling dengan jelas, suara orang yang<br />
kukenal memanggilku.<br />
"Mut, jemuran yuk sini, biar hangat ..."
Budi? Jadi, mereka tidak membunuhnya? Laiu, siapa yang mereka<br />
tembaki? Setelah beradaptasi dengan cahaya matahari, mataku melihat<br />
jelas lambaian tangan Budi. Dia bersama Ibrahim tengah duduk santai di<br />
atas pasir gurun. Mereka tanggalkan jaket yang semalaman membalut<br />
tubuh. Muka mereka menghadap langit, menikmati sinar matahari. Seperti<br />
para pelancong di bibir pantai. Santai sekali.<br />
Aku tersenyum lega.<br />
Bergegas aku melangkah naik ke lokasi duduk mereka yang<br />
datarannya lebih tinggi dari mulut gua. Dua penyandera juga duduk santai<br />
bersama Budi dan Ibrahim. Si sontoloyo menyusul di belakangku. Aku<br />
duduk berjajar dengan Budi.<br />
"Mas, tadi kok ada suara tembakan. Siapa yang ditembak?"<br />
"Oh, itu si sontoloyo iseng nembak ke arah sana.<br />
Kayaknya sengaja buat nakutin kamu." Budi menunjuk si sontoloyo<br />
yang sudah duduk, agak jauh dari kami.<br />
Penculik yang lebih ramah bertanya pada Ibrahim, "Meutya takut ya<br />
tadi?" Mereka tertawa, juga si sontoloyo. Tetapi di mataku, bentuk bibirnya<br />
ketika tertawa seperti seringai yang mengejek.<br />
Aku tak mampu menahan malu. Kurang ajar, rupanya aku dikerjain.<br />
Suasana pun kembali cair. Budi dan Ibrahim berdiri untuk melakukan<br />
peregangan. Aku juga menggerakkan tubuh yang terasa kaku dengan<br />
gera kan-gerakan senam sederhana. Karena kesibukanku, sudah lama<br />
aku tak berolahraga. Kesempatan langka itu malah kuperoleh saat aku<br />
diculik.<br />
Lima belas menit berlalu. Wajah Budi dan Ibrahim basah oleh<br />
keringat. Seorang penculik berbisik pada Ibrahim, yang dilanjutkan<br />
Ibrahim pada Budi.<br />
"Kami duluan, Mut,"kata Budi seraya menyambar jaket tebalnya.<br />
Aku ditinggal iagi sendirian ?<br />
Seolah-olah memahami isi pikiranku, si penculik yang bersahabat<br />
menjelaskan pada Ibrahim, yang kemudian menerjemahkannya<br />
untukku,"Mereka khawatir kalau ada patroli udara akan mencolok<br />
perhatian. Jadi, harus bergantian."<br />
Aku bisa memaklumi. Mereka tentu tahu pesawat pengintai tentara<br />
koalisi bisa lewat kapan saja. Nyawaku juga terancam jika pasukan<br />
koalisi mengetahui keberadaan kami.<br />
Namun, dengan kepergian Budi dan Ibrahim<br />
kembali ke gua, aku menjadi tidak bebas bergerak. Tiga lelaki masih<br />
mengawalku. Dan, tatapan si sontoloyo tetap saja mencurigakan<br />
meskipun bibirnya kini jadi murah senyum.<br />
Tetapi, aku tak mau pusing memikirkannya. Aku memilih duduk santai<br />
menikmati sinar matahari pagi menghangatkan kulitku.<br />
Tiba-tiba, kami dikejutkan suara dari dalam gua. Tiga lelaki<br />
pengawalku dengan cepat meraih senjata laras panjang, mengokangnya,<br />
dan berlari ke dalam gua. Ada apa lagi? Aku mendengar suara si<br />
sontoloyo dan seorang lagi bersungut-sungut. Sepertinya pada Ibrahim.<br />
Suara mereka makin meninggi, dan sesekali kudengar jawaban Ibrahim.<br />
Entah apa. Aku tak mau mendatangi mereka, khawatir menambah runyam<br />
persoalan.<br />
Si sontoloyo muncul di mulut gua. Tangannya memberikan isyarat
agar aku masuk. Perasaanku campur aduk. Tetapi, aku tak mau lagi<br />
mengumbar rasa takut. Rasa takut berlebihan malah membuat emosi tak<br />
terkendali.<br />
Di dalam gua, telepon seluler milik Ibrahim dan Budi sudah<br />
berpindah tangan ke seorang penculik. Rupanya yang kudengar tadi suara<br />
telepon seluler yang baru diaktifkan.<br />
"Mut, handphone-mu juga harus diserahkan," kata Budi.<br />
"Apa yang terjadi?" Aku penasaran kenapa Budi atau Ibrahim<br />
menghidupkan telepon seluler. Tak ku-pedulikan lagi apakah tiga<br />
penyandera akan curiga dengan percakapan kami yang tak mereka<br />
pahami.<br />
"Ibrahim diam-diam mencoba menghidupkan handphone. Tetapi,<br />
bunyinya malah membuat tindakannya ketahuan. Mereka marah. Yo wis,<br />
serahkan saja handphonemu."<br />
Aku heran kenapa Ibrahim melakukan tindakan konyol itu. Mestinya<br />
dia tahu, ponsel dalam posisi on pun percuma kalau tak ada sinyal di<br />
tengah gurun pasir ini, apalagi di dalam gua.<br />
"Dia hanya mencoba, siapa tahu bisa mengabari keluarganya," kata<br />
Budi lagi.<br />
Aku bergegas membuka tas, merogoh telepon selulerku, dan<br />
menyerahkannya kepada penculik.<br />
"Akan dikembalikan kalau kita bebas," kata Ibrahim setelah<br />
mendengar penjelasan seorang penculik.<br />
Aku diam saja.<br />
* * *<br />
TERDENGAR sayup-sayup suara kendaraan mendekat ke arah gua.<br />
Ketiga penyandera dengan sigap memasang kafiyeh untuk menutup<br />
muka mereka. Tatapan mereka berubah drastis, tidak lagi ramah.<br />
"Rois datang," seorang penyandera menjelaskan pada Ibrahim.<br />
Rois? Mudah-mudahan kali ini mereka tidak bohong. Sambil<br />
merapikan kerudung, aku mempersiapkan diri dengan baik. Pertemuan<br />
dengan Rois akan sangat menentukan, apakah kami langsung<br />
dibebaskan atau tidak, seperti dijanjikan para penculik<br />
itu. Atau, apakah kami boieh terus hidup atau harus mati?<br />
"Assalamu 'alaikum." Suara dari pintu gua terdengar menggema.<br />
Tampak seorang lelaki berpenutup muka.<br />
"Waalaikum salam," jawab kami, juga tiga penculik yang sikapnya kini<br />
bak tentara dengan senjata terkokang. Bisa kurasakan bagaimana para<br />
penculik itu menaruh hormat kepada sang Rois. Kedatangan Rois<br />
membuat suasana jadi lebih formal.<br />
Bersama Rois muncul di belakangnya dua orang lain yang juga<br />
berpenutup muka. Entah berapa orang yang menunggu di luar gua.<br />
Sosok Rois berbeda dari bayanganku tentang pemimpin kelompok<br />
yang disebut Ibrahim sebagai Mujahidin. Kupikir Rois berusia setengah<br />
baya, mengenakan gamis (pakaian tradisional timur tengah) dengan<br />
serban melilit kepala. Rois ternyata sangat muda, mungkin belum 30<br />
tahun. Dia memakai jaket tebal yang trendi.Kulit di bagian wajahnya yang<br />
tak tertutup kafiyeh putih bersih. Sepertinya dia seorang yang sangat<br />
akademis.<br />
Rois mendekati aku dan Budi sambil mengeluarkan pulpen dari
sakunya. Dia meminta secarik kertas dariku. Kuberikan beberapa lembar<br />
kertas kosong dari buku notes Metro TV. Ibrahim duduk di antara aku dan<br />
Rois. Pertanyaan demi pertanyaan meluncur dari mulutnya yang tertutup<br />
kafiyeh. Mulai dari identitas kami, asal negara, profesi, tujuan kami di Irak,<br />
hingga sikap Indonesia terhadap Irak.<br />
Rois memilih bicara dalam bahasa Arab walaupun<br />
aku yakin dia mengerti bahasa Inggris. Seperti biasa,Ibrahimlah<br />
yang bertugas menerjemahkannya. Aku merasakan aura ketegasan dari<br />
sikap Rois yang tenang. Dia berbicara seperlunya. Sikapnya dingin, tetapi<br />
tidak memusuhi. Rois mencatat semua jawa-banku.<br />
"Kenapa kalian masuk ke Irak padahal sudah tahu di sini tidak<br />
aman?" tanya Rois setelah mencatat semua jawaban tentang identitas<br />
kami.<br />
"Kami ingin melihat dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di<br />
Irak dari kacamata pers Indonesia. Kami ingin informasi yang berimbang<br />
dibanding yang selama ini kami peroleh dari pers Barat."<br />
Rois manggut-manggut. Kuharap jawabanku bisa menggugah<br />
simpatinya.<br />
"Kami tak yakin Anda menyajikan berita yang berimbang." Rupanya<br />
Rois meragukan jawabanku.<br />
Aku merasa tertantang dengan pernyataannya. Maka, aku<br />
menawarkan diri untuk meliput kelompok Rois dalam menjalankan<br />
berbagai aksinya.<br />
"Biasanya wartawan asing ikut bersama dengan pasukan koalisi,<br />
tetapi kami akan ikut bersama kelompok Mujahidin kalau Anda izinkan."<br />
Lebih baik sekalian ikut meliput perang mereka daripada tersandera di<br />
tengah gurun antah-berantah ini.<br />
Rois kaget mendengar tawaran nekatku. Kutatap matanya agar dia tak<br />
menganggapku main-main. Sepertinya dia percaya.<br />
"Jika kalian ikut meliput kami, kalianlah yang akan jadi target pertama<br />
pasukan koalisi, bukan kami. Begitu juga kalau kalian mencoba meliput<br />
bersama<br />
pasukan koalisi, kalianlah yang akan menjadi target pertama<br />
untuk kami tembak."<br />
Kali ini aku yang kaget mendengar ucapan Rois. Masuk akai juga.<br />
"Siapa yang menunggu kalian di Irak?" Rois mengaku heran kenapa<br />
kami memutuskan kembali ke Irak dalam waktu cepat. Dia curiga kami<br />
memiliki agenda tersembunyi.<br />
"Tidak ada yang menunggu kami. Itu perintah dari kantorku.Tidak ada<br />
yang tahu kami masuk kembali ke Irak, kecuali kantor di Jakarta." Aku<br />
sengaja tak mengungkapkan alasan soal liputan Asyura. Aku tahu,<br />
kelompok perlawanan di Ramadi dan Fallujah mayoritas beraliran Sunni.<br />
Rencana liputan Asyura yang biasa diperingati kelompok Syiah tentu akan<br />
menyinggung perasaan Rois.<br />
"Lalu, siapa yang menjaga kalian di Irak? Anda menyewa jasa<br />
pengamanan?" Aku lega mendengar pertanyaannya. Rois tidak<br />
melanjutkan pertanyaan soal alasan kami kembali ke Irak.<br />
"Tidak, kami tidak punya bodyguard." Aku sengaja memakai<br />
istilah bodyguard, bukan guide. Terlihat tatapan Rois seperti meragukan<br />
jawabanku.
"Jadi, tidak akan ada yang mencari kalian? Bagaimana dengan<br />
kedutaan?"<br />
"Sejak invasi, untuk sementara Kedutaan Indonesia di Bagdad tutup.<br />
Yang terdekat ada di Amman, Yordania."<br />
Rois menggeleng-gelengkan kepala. Sepertinya dia heran, atau<br />
mungkin takjub, kenapa kami berani meliput di Irak tanpa jaminan<br />
keselamatan dari negara<br />
kami.<br />
"Apakah kalian punya cukup baju dan bekal? Kalau tidak, kami akan<br />
belikan. Katakan apa yang kalian inginkan." Melihat tatapan matanya, aku<br />
yakin Rois tidak berbasa-basi. Dan, tawaran Rois membuatku merasa<br />
lebih nyaman. Ini kesempatan untuk mengambil simpatinya.<br />
"Kami punya cukup bekal. Hanya saja, jika diizinkan, kami ingin<br />
mewawancarai Anda." Aku mencoba keberuntunganku meskipun aku tahu<br />
tak semudah itu dia mau muncul di depan kamera. Di depanku saja dia<br />
menutup muka. Sejenak Rois terdiam. Tatapan matanya seolah-olah<br />
bertanya apakah aku bersungguh-sungguh. Aku membalas tatapan itu,<br />
menunjukkan bahwa aku serius.<br />
"Mungkin saja, lain kali." Meskipun aku sudah menduga jawaban itu<br />
akan muncul, aku tetap berharap Rois mengatakan "Ya!" tetapi tak apa. Itu<br />
saja sudah cukup untuk menarik simpatinya.<br />
Kujelaskan, sebelum aku berangkat ke Irak, berkali-kali terjadi demo<br />
besar-besaran di Jakarta yang memprotes kebijakan Amerika Serikat di<br />
Irak. Kukatakan juga, aku baru kembali meliput bencana tsunami di Aceh<br />
sebelum berangkat ke Irak.<br />
Sepertinya Rois senang mendengarnya. Kuharap penjelasanku dapat<br />
melunakkan hatinya agar dia segera melepaskan kami.<br />
Seperti memahami keinginanku, Rois mengatakan tak bisa<br />
membebaskan kami segera. Dia akan membebaskan setelah<br />
pengambilan gambar kami. "Kami akan memberikan pernyataan melalui<br />
media<br />
terkait dengan penyanderaan kalian," kata Rois.<br />
Oh, Tuhan, berarti prosesnya masih panjang. Pupuslah harapanku<br />
dan Budi untuk bisa bebas hari ini. Kupikir kalian salah tangkap dan akan<br />
langsung melepaskan kami.<br />
Kini, aku memilih diam. Percuma bicara panjang lebar untuk menarik<br />
simpatinya kalau pada akhirnya tetap saja kami tak dibebaskan segera.<br />
Melihatku tak lagi banyak bicara, Rois kemudian memeriksa paspor<br />
dan kartu identitas wartawan kami. Aku dan Budi hanya menunjukkan ID<br />
card Metro TV. Adapun ID card untuk peliputan Irak dari Joint Security<br />
Council, pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat, kami sembunyikan di<br />
sudut terdalam tas kami. Bisa jadi kartu mati kalau terlihat. Beberapa kali<br />
Rois bertanya apakah institusi yang mengirim kami, Metro TV, berafiliasi<br />
dengan pemerintah. Dia juga bertanya apakah kami kenal dengan<br />
Presiden, pernah bertemu dengan Presiden. Sepertinya dia ingin<br />
menegaskan keberadaan kami di Irak tak ada kaitannya dengan<br />
pemerintah, dan semata untuk melakukan tugas jurnalistik.<br />
"Kami bekerja di televisi swasta. Dari belasan stasiun televisi di<br />
Indonesia, hanya satu milik pemerintah."<br />
Jawabanku mengakhiri berondongan pertanyaan Rois seputar tempat
kerjaku.<br />
"Terus terang kukatakan pada kalian, kami sebenarnya tak suka<br />
wartawan datang ke sini.Kami menghormati alasan kalian meliput di sini<br />
untuk menyajikan pemberitaan yang berimbang. Tetapi, kami<br />
meragukannya. Kenyataannya malah banyak yang memojokkan<br />
perjuangan kami. Bahkan, ada juga mata-mata yang berkedok sebagai<br />
wartawan."<br />
Aku kaget mendengar pernyataan Rois. Aku memahami bahwa yang<br />
terjadi di Irak bukan hanya perang senjata, melainkan juga perang<br />
informasi. Mulut dan tulisan wartawan membentuk opini yang gaungnya<br />
merambah seluruh dunia. Pantaslah jika Rois bilang bahwa wartawan<br />
akan menjadi target utama kelompok perlawanan jika mereka ikut<br />
(embedded) dengan pasukan koalisi. Demikian pula sebaliknya.<br />
Tampaknya Rois kecewa karena pembentukan opini cenderung<br />
memojokkan kelompok perlawanan.<br />
Sebelum ini tak pernah kubayangkan betapa berbahayanya posisi<br />
wartawan. Walaupun beberapa kali aku menyaksikan berita soal<br />
wartawan diculik atau dibunuh, tak pernah kubayangkan kami, wartawan,<br />
adalah target utama perang ini. Perang informasi.<br />
* * *<br />
HAMPIR satu jam proses interogasi berlangsung. Sebelum pamit,<br />
Rois memerintahkan kepada para anggotanya untuk keluar dari gua. Lima<br />
menit kemudian, Rois muncul lagi di mulut gua. Tangannya<br />
mengisyaratkan agar Ibrahim mendekat. Dalam obrolannya, sesekali<br />
tangan Rois menunjuk ke arahku. Ibrahim juga menjelaskan sesuatu<br />
kepada Rois, entah apa. Rois kemudian melambaikan tangan sambil<br />
mengucap salam.<br />
Sepeninggal Rois, aku bertanya kepada Ibrahim apa yang tadi<br />
dipesankan.<br />
"Saya titipkan Meutya kepada kamu. Jika ada dari anggota saya yang<br />
berani menyentuh satu helai rambutnya sekalipun, laporkan pada saya.<br />
Orang itu menjadi urusan saya." Menurut Ibrahim, Rois menegaskan<br />
bahwa tidak ada Mujahidin yang boleh mengganggu wanita. Jika ada yang<br />
menggangguku, berarti mencoreng perjuangan kelompok Mujahidin.<br />
Hukumannya bisa saja kematian.<br />
Aku takjub pada Rois dan merasa tersanjung mendengar penjelasan<br />
Ibrahim. Memang, sebagai satu-satunya wanita, tentu sangat berat<br />
menerima keadaan ini. Aku harus tinggal dengan para lelaki tak kukenal<br />
yang 24 jam menjagaku dengan senjata laras panjang, dalam gua yang<br />
sangat kecil tanpa privasi, tanpa fasilitas MCK. Kalau mereka berniat jahat,<br />
tak akan ada yang peduli nasib kami.<br />
Dua penculik masuk ke gua. Wajah keduanya yang tak lagi tertutup<br />
kafiyeh kini lebih ramah, dan banyak mengumbar senyum. Pasti atas<br />
perintah Rois.<br />
"Ana Muhammad," kata lelaki yang umurnya kelihatan lebih tua, yang<br />
selama ini bersikap ramah padaku, mengenalkan namanya. Baru saat<br />
itulah, aku mengamati bahwa lelaki ini bertubuh tak terlalu tinggi. Mungkin<br />
hanya berbeda satu atau dua senti dengan Budi. "Huwa Ahmad,"<br />
tambahnya sambil menunjuk lelaki yang lebih muda darinya, yang<br />
sosoknya lebih besar dan tinggi, meski kalah tinggi diban-
dingkan Ibrahim. Ke mana si sontoloyo? Mungkin dia masih berjaga<br />
di luar.<br />
Aku dan Budi kembali duduk di sudut masing-masing. Ibrahim<br />
berbincang dengan dua lelaki itu, yang mulai sibuk menyalakan perapian.<br />
Hari merambat sore dan hawa dingin kembali menggigit kulit. Ahmad dan<br />
Muhammad juga membuka bungkusan makanan yang mungkin<br />
didatangkan bersama Rois. Mereka menawarkan roti khas Irak kepada<br />
kami.<br />
Budi menyambutnya, tetapi aku tak berselera. Aku bergerak dari<br />
pojokanku ke tengah gua, untuk menghangatkan tangan di atas<br />
perapian.Muhammad kembali menawarkan roti, tetapi aku menggeleng<br />
seraya tersenyum.<br />
Setengah jam berlalu, si sontoloyo belum juga muncul. Penasaran,<br />
kutanyakan kepada Ibrahim.<br />
"Kepada Rois kulaporkan sikap kurang ajarnya padamu. Rois marah<br />
dan melarangnya lagi berjaga di sini," kata Ibrahim.<br />
Jawabannya membuatku kaget, tetapi sekaligus lega. Satu ancaman<br />
telah terlewati, mudah-mudah an ini pertanda baik.<br />
Kukuatkan batinku untuk menjalani satu malam lagi dalam siksaan<br />
hawa dingin. Setelah pengambilan gambar esok, mimpi buruk ini<br />
berakhir. Malam ini, setidaknya aku bisa bernapas lega. Tak lagi dihantui<br />
si sontoloyo. Sehari lagi, Meutya, sehari lagi kau bebas.[]<br />
Bab 5<br />
Memelihara Harapan<br />
DENTING suara gelas mengusik lelapku pada pagi kedua. Aku<br />
terbangun, disambut sapa teman-teman segua. Ya, Budi, Ibrahim, serta<br />
dua penculik kami, Muhammad dan Ahmad. Aku tersipu karena lagi-lagi<br />
bangun belakangan. Budi sedang mencuci gelas, Muhammad<br />
menyiapkan teh, dan Ahmad menjerang air. Aku segera menarik tisu dan<br />
mengelap gelas. Ibrahim kami daulat supaya duduk saja bak raja.<br />
Ibrahim memang yang paling tua di antara kami. Usianya kutaksir<br />
menjelang 40 tahun, tetapi garis-garis wajahnya, ditambah berewoknya<br />
yang lebat, membuatnya tampak lima tahun lebih tua. Dia cukup lancar<br />
berbahasa Inggris, boleh jadi karena Yordania memang negeri yang<br />
modern dan dekat dengan Amerika. Selama ini dia sering mengantar para<br />
wartawan negara Barat, terutama Inggris dan Amerika. Ibrahim lalu<br />
bercerita. Di Irak, terutama pada musim dingin, ada kebiasaan untuk<br />
membuat chai. Teh ini memiliki rasa dan penyajian yang khas, yakni<br />
menggunakan gelas kecil, yang diameternya kira-kira tiga sentimeter.<br />
Meski merupakan kegiatan sederhana, upacara membuat teh ini<br />
menjadi sumber keakraban di antara kami, para penculik dan terculik.<br />
Sambil menunggu air matang, kami berlima berdiang tangan di pusat<br />
api.Karena sempitnya gua, tangan-tangan kami pun bersentuhan. Ini<br />
membuatku sedikit rileks. Apalagi, Ahmad dan Muhammad sudah<br />
melepas kafiyeh yang selalu menutup muka, dan malahan meletakkan<br />
senjata AK mereka di pojok gua. Dua hari sebelumnya, komunikasi kami<br />
hanya lewat tatapan mata belaka.<br />
Selama dua hari itu pula, kami dilayani. Pagi inilah pertama kalinya<br />
kami boleh ikut menyeduh teh sendiri. Ini bukan karena soal keamanan,<br />
melainkan, "Begitulah orang Arab menghormati tamu," kata Ibrahim.
Memang, selama disandera, makanan dan minuman kami tidak seperti<br />
dalam kisah penculikan yang aku tonton di film. Pada hari pertama, kami<br />
disuguhi ayam panggang dengan nasi. Hari ini, mereka menyuguhkan<br />
kebab yang potongannya begitu menggugah selera. Selain nasi, laukpauk,<br />
dan buah buahan, mereka juga membawakan untuk kami soft drink.<br />
Bukan cuma ritual ngeteh, acara makan pun membuat kami semua<br />
"akrab". Ruangan gua yang sangat sempit mengharuskan kami banyak<br />
berdekatan. Jika kami akan makan, alas tidur dan selimut harus digulung<br />
agar tidak terkena tumpahan makanan. Lalu di bagiantengah, dekat<br />
perapian, dialasi plastik, bak meja makan untuk perjamuan. Di situlah roti<br />
khubus, daging, minuman ringan, air putih, gelas,<br />
dan tisu ditata. Pada malam hari, kami makan ditemani nyala<br />
lampu minyak yang bergoyang ditiup angin. Cukup romantis. Sayang kami<br />
tidak sedang menikmati acara candle light dinner, tetapi sedang<br />
disandera.<br />
Aku menghargai upaya penculik menyenangkan aku dan Budi. Mereka<br />
membuat suasana makan yang kekeluargaan. Kami makan tanpa piring.<br />
Ibrahim menyebutnya cara makan khas Arab. Tetapi, bagiku ini sangat<br />
primitif. Roti khubus dimakan bersama-sama, bergantian. Ibrahim, tetua<br />
kami, menjadi penyobek pertama. Begitu pula dengan kebabnya. Daging<br />
diciduk dengan tangan. Padahal, setahuku Ahmad dan Muhammad<br />
makan tanpa mencuci tangan.<br />
Perlakuan terhadap minum pun sama. Air ditaruh di wadah besar, lalu<br />
diminum bergantian, tetapi hanya sekali, di awal saja. Mereka menyadari<br />
kerisi-hanku, dan mulai menghafal kebiasaanku meminum dari gelas<br />
yang sama: gelas plastik dengan gambar bunga kecil. "Gelas Meutya,"<br />
kata mereka.<br />
Namun, aku makan tanpa selera. Aku hanya mengambil roti dan<br />
daging sedikit saja. Sepertinya Ahmad gemas, dia lalu menyobekkan aku<br />
bagian kebab yang agak besar. Ah, mereka begitu menghormati<br />
aku.Tetapi,aku tak menyentuhnya. Muhammad menanyakan lewat Ibrahim,<br />
apakah aku mau memakai sendok atau sumpit. Makanan itu hanya<br />
kuaduk-aduk tanpa kusuapkan. Bukan aku tak suka, atau tak lapar. Tetapi<br />
sebagai orang terjajah, selera makanku yang besar lenyap ditelan gurun.<br />
"Meutya, kamu harus makan. Mereka bisa tersinggung,"<br />
bisik Ibrahim kebapakan. Aku tetap tak peduli.<br />
Di luar dugaanku, Ibrahim marah. Dengan nada tinggi, dia<br />
mengatakan bahwa makanan ini disediakan dengan susah payah oleh<br />
Muhammad dan Ahmad. Dia mengulang lagi soal penghormatan orang<br />
Arab kepada tamu. "Mereka sengaja menyiapkan daging untuk kita,<br />
padahal mereka sebulan sekali pun belum tentu makan daging," katanya.<br />
Aku paksakan makan sebab para Mujahidin itu tak mau mulai jika aku<br />
dan Budi tak makan. Namun, aku tak mampu mengunyah makanan yang<br />
tersedia. Kucoba mendorong makanan dengan soft drink, tetap saja<br />
gagal. Meski mulai tercipta suasana tenang yang muncul dari keakraban<br />
pagi ini, perasaanku masih bergalau rasa takut, kesal, dan entah apa lagi,<br />
yang membuatku tak bisa menikmati makanan selezat apa pun.<br />
Meski demikian, aku berjanji, siang nanti aku akan makan apa pun<br />
yang disajikan. Entah sudah berapa kali aku menuang teh ke gelas<br />
superkecil itu. Budi pun begitu. Udara dingin membuatku terus haus.
Ahmad menanyaiku, apakah aku menginginkan sesuatu. Entah makanan,<br />
minuman, atau kebutuhan apa pun. Biasanya, menjelang siang, akan<br />
datang utusan membawa segala keperluan. Mulai dari air hingga tisu.<br />
Menyeruput teh di tengah keheningan gurun, dan di tengah<br />
ketidakjelasan nasib, bukanlah pagi yang indah. Kata Ahmad, pada hari<br />
ketiga ini Rois akan datang lagi untuk mengambil gambar aku dan<br />
Budi. Aku tak sabar menunggu saat itu. Apa yang akan terjadi?<br />
Baikkah atau burukkah? Aku pun terdiam. Muhammad mencoba bercanda<br />
menenangkan. "Jangan tegang, jangan khawatir, hanya pengambilan<br />
gambar. Nanti kamu akan terkenal ke seluruh dunia. Kalau sudah<br />
terkenal, jangan lupa kami ya," katanya terkekeh. Canda yang sama sekali<br />
tak lucu.<br />
Ingin aku meninggalkan reriungan itu. Tetapi, mau ke mana? Berjalan<br />
keluar terlalu berbahaya. Bisa didor penculik yang curiga, atau dibom<br />
pesawat yang melintas rutin di udara. Kucoba tersenyum meski pahit.<br />
Budi mencairkan suasana, dengan menanyakan cara membawa logistik<br />
buat kami.<br />
Penculik itu pun bercerita. Tak jauh dari gua tempat kami disekap, ada<br />
sebuah kampung. Adik Ahmad membawa air, makanan, minuman, tisu,<br />
serta kebutuhan lain menggunakan mobil tua. Mereka memanfaatkan<br />
kekosongan patroli Amerika, lalu melaju menyusuri padang pasir. Sebuah<br />
upaya menyabung nyawa, untuk menjaga nyawa kami agar selalu bisa<br />
makan dan minum.<br />
Hal yang menarik perhatianku adalah air. Setiap datang, mereka<br />
membawa air dalam ember besar untuk persediaan sehari. Air itu mereka<br />
datangkan dari Sungai Eufrat, satu di antara dua sungai besar di Irak, yang<br />
jaraknya kira-kira satu jam dari gua. Tetapi, tak pernah ada kepastian,<br />
apakah besok air bisa datang lagi. Maka, kami pun berbagi air secara<br />
hemat. Kami hanya bisa cuci muka dan sikat gigi. Mandi tak mungkin,<br />
selain karena air terbatas, juga<br />
tidak ada tempat. Aku tersenyum ketika menyadari bahwa sudah tiga<br />
hari aku tak "ke belakang" untuk buang air besar. Ketidaknyamanan, yang<br />
berbaur dengan ketakutan dan ketidakpastian, membuat ritual yang<br />
biasanya rutin pagi hari tersebut terlupakan. Apalagi, tidak ada tempat<br />
khusus untuk itu. Hanya buang air kecil yang masih bisa kulakukan. Itu<br />
pun dengan terpaksa kalau sudah tak tahan lagi. Sungguh tidak nyaman,<br />
di alam terbuka tanpa pelindung. Ditambah lagi waktu yang diberikan<br />
penyandera amat terbatas. Berbeda dengan Budi, pagi-pagi dia sudah<br />
pamit membentuk kubangan pasir, membuang hajat dan menimbun<br />
kembali. "Aku biasa melakukan seperti itu di kampung waktu kecil,"<br />
katanya.<br />
Terdengar suara mobil di kejauhan. Kini, berada di kesunyian dalam<br />
kondisi ketidakpastian, suara mobil adalah kemewahan tak terperi. Suara<br />
itu se olah-olah menjadi petunjuk kehidupan. Sebuah harapan yang<br />
melegakan. Mungkin itu mobil adik Ahmad yang akan mengantar logistik.<br />
Atau, boleh jadi Rois. Sebab, hari ini dia menjanjikan pengambilan<br />
gambar kami: para terculik. Siapa pun itu, yang datang ada/ah kehidupan.<br />
Jika mobil butut, artinya logistik lancar. Jika bukan, berarti Rois yang akan<br />
mengambil gambar. Rekaman itu akan menjadi alat penculik untuk<br />
mengabarkan bahwa di tangan mereka ada sandera yang akan dijadikan
alat tawar-menawar perjuangan. Tetapi bagiku, itu adalah komunikasi<br />
diam dengan keluarga dan teman di tanah air.<br />
Sebagai reporter televisi, aku sudah sering menonton tayangan<br />
sandera. Beberapa kali aku ke-bagian membacakannya di buletin berita<br />
Metro TV. Bahkan, aku pula yang mewawancarai Casingkem dan<br />
Istiqomah setelah dua tenaga kerja Indonesia yang disandera di Irak itu<br />
dibebaskan, September 2DD4.<br />
Namun, tak pernah sekali pun tebersit di benakku bahwa pada suatu<br />
masa akulah yang berpose seperti itu. Sebagian dari tayangan<br />
penyanderaan memuat syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk<br />
pembebasan. Bisa dalam bentuk penarikan pasukan, jika si tersandera<br />
berasal dari negara yang tergabung dalam pasukan koalisi. Bisa juga<br />
berupa pemerasan dalam bentuk uang tebusan.<br />
Apa gerangan yang dikehendaki para penculik ini? Indonesia tidak<br />
mengirim pasukan ke Irak. Indonesia pun berkali-kali mengutuk serangan<br />
Amerika ke Irak. Lalu, apakah untuk uang? Aku tersedak.Jika itu yang<br />
mereka tuntut, aku akan merasa sangat berdosa kepada bangsaku.<br />
Negeriku sedang dalam kesusahan karena baru tiga bulan lalu tsunami<br />
maha dahsyat melanda Aceh, menewaskan ratusan ribu jiwa.<br />
Ya Allah, semoga penculik ini tidak meminta uang dari negeriku.<br />
Budi tiba-tiba sudah ada di sisiku. "Bagaimana kalau kita tawarkan,<br />
aku yang mengambil gambar," kata Budi. Perasaan kami sama: gelisah.<br />
Sebab, hingga siang tim pengambil gambar belum juga datang. Jika<br />
gambar terlambat<br />
diambil, pembebasan kami pun bisa tertunda.<br />
Tawaran itu ditolak Muhammad. "Ada juru kamera khusus untuk itu,"<br />
katanya.<br />
Siang pun berlalu dalam gelisah.<br />
Suara mobil semakin dekat. Ahmad dan Muhammad segera<br />
bersiaga. Mereka pun dengan sigap memasang penutup muka.<br />
Sebenarnya, kata Muhammad, mereka tidak boleh sama sekali<br />
memperlihatkan muka mereka kepada kami. Tetapi, sejalan dengan<br />
makin "akrabnya" kami, Ahmad dan Muhammad melanggar aturan itu.<br />
Ahmad dan Muhammad bergegas keluar menyambut rombongan.<br />
Aku mengintip dari celah gua. Berbeda dengan sehari sebelumnya,<br />
rombongan kali ini cukup ramai. Aku sempat menghitung ada lima orang,<br />
tanpa penutup muka. Berbeda dengan penculik penjaga, Mujahidin yang<br />
datang berbadan tegap, bersih, dan berpakaian modern. Aku mendekat ke<br />
celah, untuk melihat lebih jelas suasana di luar.<br />
Namun, hardikan Ibrahim mengagetkanku. "Meutya! Jangan<br />
mengintip. Itu tidak sopan!"<br />
Aku berbalik dengan sebal. Aku bilang kenapa Ibrahim marah hanya<br />
karena urusan kecil itu.<br />
"Ini bukan soal sepele. Kalau mereka marah, kita bisa fatal," terang<br />
Ibrahim.<br />
Suara Ibrahim melembut. Dia memintaku merapikan kerudung dan<br />
duduk dengan posisi tegak.<br />
"Assalamu 'alaikum." Para tamu masuk ke gua dengan muka tertutup<br />
kafiyeh.<br />
Setelah berbasa-basi menanyakan kabar dan kesehatan, mereka
meminta aku dan Budi keluar<br />
dari gua. Ibrahim tetap tinggal. Aku terkejut melihat Ahmad sudah siap<br />
berdiri memegang AK. Aku dan Budi digiring. Memelihara Harapan ke<br />
dekat Ahmad. Satu lagi Mujahidin yang baru datang berdiri di sisi lain.<br />
Juga, memegang senjata AK.<br />
Kedua Mujahidin dengan muka tertutup itu lalu mengangkat senjata,<br />
dalam posisi siap tembak. Suara "klik" senjata dikokang membuatku<br />
bergidik. Sebab, di luar gua ternyata sudah lebih banyak lagi anggota dari<br />
kelompok tersebut berkumpul. Siapa tahu mereka hanya berbohong.<br />
Walaupun selama ini kekhawatiranku tidak terbukti, tetap saja rasa takut<br />
kembali menyergap. Terbayang lagi hal-hal buruk, seperti yang diterima<br />
sandera lain yang pernah aku beritakan. Ada yang ditembak, ada yang<br />
bahkan dipenggal.<br />
Rois menjelaskan bahwa senjata itu hanya untuk keperluan<br />
pengambilan gambar. Dia berjanji tidak akan melukai kami dan meminta<br />
kami tetap tenang.<br />
Aku melihat juru kamera sedang mencari tempat pengambilan<br />
gambar yang tepat. Dia layaknya juru kamera profesional, melihat arah<br />
matahari untuk menentukan arah cahaya. Karena matahari siang tengah<br />
berada persis di atas kepala, dia pindah lagi ke sebelah kanan gua. Tiga<br />
kali dia bergeser tempat, mencari latar belakang yang sesuai. Akhirnya,<br />
dia berhenti di sebuah titik, yang cahayanya terlindung oleh tebing batu,<br />
dan yang bagian lainnya menjadi dinding gua tempat kami disekap.<br />
Kutekan gelisahku dalam-dalam. Kulirik Budi,<br />
yang juga menuruti saja kemauan para penculik. Namun, berbeda<br />
dengan biasanya, kali ini wajah Budi tampak sangat tegang. Mulutnya<br />
komat-kamit entah berdoa atau sekadar penawar rasa takut. Pengambilan<br />
gambar siap dimulai. Kamera jenis ha-ndycam lengkap dengan tripodnya<br />
sudah tersedia di depan kami. Kami diminta memegang paspor dan kartu<br />
identitas wartawan ke hadapan kamera. Di sebelah juru kamera, seorang<br />
narator membacakan dengan suara lantang pesan dari kelompok Faksi<br />
Tentara Mujahidin:<br />
Bismiiiahirrahmanirrahim,<br />
Kami, Faksi Tentara Mujahidin di Irak, menahan dua wartawan ini<br />
ketika mereka dalam perjalanan di wilayah Irak. Setelah kami<br />
menginterogasi keduanya, mereka mengaku dalam tugas jurnalistik atas<br />
perintah kantor mereka di Indonesia.<br />
Sudah diketahui oleh seluruh pemerintahan di dunia ini bahwa Irak<br />
adalah wilayah konflik. Dan, jiwa setiap orang yang datang ke Irak dalam<br />
kondisi terancam.<br />
Kami tidak menjamin keselamatan siapa pun yang masuk ke negeri<br />
kami. Keselamatan mereka berada di tangan pemerintah yang<br />
seharusnya menjaga keselamatan rakyatnya.<br />
Dan untuk itu, kami meminta pemerintah Indonesia Memelihara<br />
Harapan menjelaskan status kedua orang ini. Jika tidak, maka jiwa<br />
mereka dalam keadaan bahaya. Allahu Akbar!<br />
Tertanda<br />
Faksi Tentara Mujahidin<br />
Menurut Ahmad, beberapa jam ke depan, rekaman yang menguak<br />
keberadaan kami akan segera tersebar ke pelbagai penjuru dunia,
termasuk ke Indonesia.Aku membayangkan wajah Mama dan kakakku<br />
melihat kondisiku yang seperti itu. Tadi dalam diamku, aku berusaha<br />
sekuat tenaga menatap kamera dengan tegar. Aku tidak mau Mama<br />
melihatku lemah dan menangis.Aku tidak mau menambah penderitaan<br />
mereka, yang pasti sudah sangat hebat, begitu mendengar aku hilang di<br />
negeri orang. Melalui mataku, aku coba mengatakan Mama, jangan<br />
khawatir, aku sehat dan baik-baik saja.<br />
Aku bersyukur, penculik membiarkan kami berdiri sejajar dengan<br />
mereka. Tak seperti Casingkem dan Istiqomah yang merunduk ketakutan<br />
di bawah todongan senjata.i Aku juga tak sepilu Giulliana Sgre-na,<br />
wartawan I/Manifesto Italia, yang diculik kelompok perlawanan sepekan<br />
sebelum kami. Dia bukan hanya duduk, melainkan dibuat dalam posisi<br />
berlutut, mengiba negaranya agar menarik pasukan dari Irak, sesuai<br />
dengan keinginan penyandera.<br />
1 Kedua Tenaga Kena Indonesia itu diadang gerilyawan Irak di<br />
Fallujah, lokasi yang tidak jauh dari tempat aku dan Budi diculik, dalam<br />
perjalanan dari Amman menuju Ramadi bersama agen penyalur TKI.<br />
Keduanya dibebaskan setelah ada permintaan dari Abu Bakar Ba'asyir.<br />
Setelah rombongan Rois pergi, Ibrahim menjelaskan bahwa<br />
penyandera tidak menuntut apa-apa. Padahal biasanya, para penyandera<br />
mengajukan bermacam tuntutan, mulai dari penarikan pasukan hingga<br />
tuntutan uang tebusan dalam jumlah besar.<br />
Aku merasa ini awal yang baik. Seberapa pun pesimistisnya aku di<br />
tengah ketidakpastian ini, di sudut hatiku yang dalam aku terus<br />
memelihara harapan bisa segera bebas. Kembali ke Jakarta, ke pelukan<br />
Mama.<br />
Petang hampir berlalu di gua. Kulirik jam tanganku, yang belum<br />
kuubah dari waktu Jakarta: di sana hampir tengah malam. Semoga<br />
televisi APTN atau Af-Jazeerah sudah menyiarkannya. Kata Muhammad,<br />
penculik hanya membutuhkan pernyataan Presiden bahwa kami benar<br />
wartawan yang sedang bertugas.<br />
Puncak ikhtiar pembebasanku saat ini ada di tangan Presiden<br />
Indonesia.<br />
Di gurun sunyi, aku tiba-tiba merasa sangat dekat dengan Presiden.<br />
Semoga Bapak Presiden membantu kami.<br />
Sepi kembali menyungkup.[]<br />
Bab 6<br />
Harapan yang Pupus<br />
THIARA...thiara...!<br />
Teriakan Ahmad bergema di dalam gua kecil itu. Itu adalah aba-aba<br />
agar kami semua bersiaga. Di tengah gurun senyap, suara selirih apa<br />
pun memang jelas terdengar. Tetapi, karena masih sayup-sayup, kami<br />
belum bisa membedakan apakah itu thayyarah (helikopter) atau sayyarah<br />
(mobil). Sebagai orang tempur, Muhammad dan Ahmad rupanya selalu<br />
berpikir yang terburuk. Suara itu mereka anggap helikopter. Mereka cepatcepat<br />
menyuruh kami diam, mematikan api, lalu keluar membersihkan<br />
apa pun yang bisa jadi penanda ada kehidupan. "Ini Ramadi, basis<br />
tempur. Jika itu helikopter Amerika, kita bisa habis disiram peluru dan<br />
bom," kata Ahmad menjawab keherananku.<br />
Suara itu semakin jelas: mobil.
Ahmad dan Muhammad memasang penutup wajah. Aku lega. Lega<br />
karena tidak ada serangan. Juga, lega karena di tengah ketiadaan<br />
komunikasi dengan dunia luar, kedatangan mobil adalah pembawa<br />
harapan. Mungkinkah mobii yang datang menyampaikan<br />
kabar kebebasan? Aku memelihara harapan meskipun hari<br />
semakin sulit belakangan ini. Empat hari lewat sudah tanpa kepastian. Di<br />
tangan orang yang mengancam keselamatan pula.<br />
Tadi malam, sebelum tidur, aku sempat melihat Budi menangis<br />
menciumi foto anak-istrinya. Lestari, istri Budi, sedang hamil tiga bulan.<br />
Biasanya, setiap petang Budi dan aku "melapor" ke kantor dan keluarga<br />
masing-masing. Pada pagi hari sebelum masuk kembali ke Irak pun, Budi<br />
menelepon Ari menanyakan kehamilannya. Tetapi anaknya, Laras,<br />
sedang sekolah. Siangnya Budi kembali menelepon, Laras sedang tidur.<br />
Budi pun berjanji akan menelepon lagi, tetapi tidak kesampaian hingga<br />
hari ini. Bulir air mataku pun luruh.<br />
Suara mobil semakin dekat. Muhammad berlari menyongsong. Aku<br />
mulai hafal, tanpa dilarang, tidak ikut keluar dan tidak mengintip.<br />
Muhammad masuk, menenteng bungkusan plastik. Wajahnya keruh. Aku<br />
menangkap sesuatu yang buruk. "Belum ada kabar," katanya sambil<br />
meletakkan logistik. Mungkin dia merasa bersalah karena pernah berjanji,<br />
kalau gambar sudah direkam, kami akan dibebaskan.<br />
Aku terdiam. Kupandangi isi plastik yang justru lebih banyak<br />
dibandingkan biasanya. Ini gelagat buruk. Aku hitung kotak tisu, ada lima.<br />
Mereka juga membawa berbotol-botol soft drink. Badanku langsung<br />
lemas. Berarti kami akan lebih lama lagi di sini.<br />
Budi meminta Ibrahim menanyakan mengapa kabar pembebasan<br />
belum tiba. Ahmad menyorongkan soft drink dan kebab ke arahku.<br />
Seorang Mujahidin<br />
yang baru datang menjelaskan bahwa gambar rekaman kami<br />
sedang dalam perjalanan ke Bagdad. Huh ... Jadi, rupanya rekaman<br />
gambar tersebut beium dikirim sejak kemarin. Kata Muhammad,<br />
rencananya, jika aman, gambar akan dikirim tanpa nama ke kantor berita<br />
APTN. Mungkinkah APTN menolak menyiarkannya karena kami bukan<br />
jurnalis dari negara besar? Aku tak menyalahkan Muhammad dan Ahmad.<br />
Mereka hanyalah operator lapangan, yang tidak menentukan kebijakan<br />
Faksi Mujahidin.<br />
Ibrahim, yang biasanya tenang dan menyabarkan keresahan kami,<br />
kali ini juga terdiam dengan mulut terkatup.<br />
Aku baru sadar bahwa orang yang menjelaskan kabar tadi bukanlah<br />
yang biasa datang mengantar logistik. Mungkinkah dia seorang Rois<br />
juga? Aku mencoba memecah kebuntuan. Naluri jurnalistikku bekerja.<br />
Kalau orang ini aku wawancarai, ini bisa jadi bahan berita setelah kami<br />
bebas.Jika kami bebas. Aku tawarkan wawancara. Budi pun bergerak<br />
ingin menyiapkan kamera. Lelaki itu menolak direkam, tetapi bersedia<br />
menjawab.<br />
"Apakah kalian melawan Amerika karena mendukung Saddam<br />
Husein?"<br />
"Kami bukan pendukung Saddam, tetapi tidak berarti sudi negeri kami<br />
dijajah Amerika," jawabnya tegas.<br />
"Berarti Anda bekerja untuk Abu Musab Al Zarqawi." Aku menyebut
nama tokoh tanzim (organisasi) Al-Qaidah, musuh nomor satu Amerika di<br />
Irak. "Kami tidak sevisi dengan Al-Qaidah, tetapi kami sepakat untuk samasama<br />
mengusir Amerika. Jika Irak merdeka, kami akan berhenti."<br />
"Berapa banyak anggota pasukan Mujahidin di Irak?"<br />
"Lebih banyak dibanding seluruh pasukan negara koalisi di Irak."<br />
"Apakah ada anggota Anda yang menyusup di pemerintahan?"<br />
"Tentu, kami ada di mana-mana."Wajah lelaki itu menunjukkan<br />
keseriusannya, seolah-olah memastikan bahwa dia tidak berbohong.<br />
Rois yang tidak aku ketahui namanya itu pun pergi bersama<br />
pulangnya mobil. Mereka memang tak pernah singgah lama. Sebab,<br />
keberadaan mobil di situ bisa membahayakan kami semua, penghuni<br />
gua di tengah gurun sunyi. Mobil bisa jadi alat deteksi yang manjur bagi<br />
patroli udara Amerika, untuk tahu ada aktivitas di padang pasir.<br />
Setelah suara mobil menghilang ditelan padang pasir, gua kembali<br />
dicekam keheningan. Tak ada yang menyentuh makanan dan minuman.<br />
Kali ini giliran Muhammad yang memecah kesunyian. Dia membuka<br />
kafiyeh penutup muka, lalu mengajak kami keluar dari gua. "Mari kita<br />
olahraga pagi."<br />
Lambat, aku dan Budi menyeret langkah. Di luar, Budi berlari-lari kecil<br />
mengelilingi gua. Ibrahim berjalan di belakangnya. Aku memilih duduk<br />
saja, berjemur di dekat pintu masuk gua. Untuk apa oiaraga, keiuar<br />
selamat saja belum tentu.<br />
Aku menghadapkan mukaku ke langit, menantang<br />
hangatnya matahari. Cakrawala yang luas, yang hanya berupa<br />
garis batas padang pasir kelabu, membuat pikiranku kembali<br />
menerawang. Mungkinkah kami bisa keluar dari gurun o? Setiap hari para<br />
penculik, termasuk Rois, yang berkali-kali datang mengunjungi kami,<br />
selalu meyakinkan bahwa kami akan dibebaskan secepatnya. Tetapi<br />
nyatanya?<br />
Awalnya aku kira, setelah gambar direkam, kebebasan itu akan<br />
segera tiba. Rupanya aku kelewat optimistis. Semakin lama, semakin sulit<br />
untuk berpikir positif. Tebersit keinginan kabur. Namun, saat kupandangi<br />
luasnya gurun, logikaku bekerja. Kabur berarti mati. Mati ditembak<br />
penyandera, atau kelelahan karena tak tahu tujuan pelarianku. Sudahlah,<br />
aku tidak mau lagi berharap. Aku tidak mau peduli lagi. Lebih baik aku<br />
pasrahkan semua kepada-Nya.<br />
Sebagai manusia, aku merasa kecil. Tanpa daya, hanya menunggu<br />
takdir-Nya.<br />
Ah, benar ceramah para ustad yang dulu hanya kudengar selintas,<br />
yang kini terasa sangat berarti, "ketika pasrah semua menjadi lebih<br />
mudah". Dengan "pasrah", semua jadi lebih ringan. Rasa takut dan gentar<br />
dapat kuredam karena aku tahu ada Dia yang menjagaku. Rasa sedih<br />
hilang karena, tiba-tiba saja rasanya, sepertinya tidak ada alasan lagi<br />
untuk sedih. Aku rindu Mama, aku rindu kakak-kakakku. Tetapi, "rasa<br />
dekat" dengan-Nya membuatku sadar bahwa semua itu pada akhirnya<br />
adalah milik-Nya, yang bisa Dia ambil dan jauhkan dariku kapan pun Dia<br />
berkehendak. Begitu juga dengan karier dan semua "materi" yang telah<br />
aku kumpulkan<br />
dengan keringatku,semua itu hanya "pinjaman" dari-Nya. Semua
hanya milik-Nya.<br />
"Kamu belum berkeluarga kan Meut," tanya Ibrahim sambil mencomot<br />
potongan daging kebab, saat kami sudah kembali ke dalam gua.<br />
"Kamu hanya ditunggu ibu dan kakakmu, sedangkan aku ditunggu 8<br />
anak dan 2 istri," lanjutnya. Kami pun tergelak.<br />
"Salah sendiri punya istri dua," sambar Budi. Ibrahim lalu<br />
menjelaskan alasannya berpoligami. Pekerjaannya sebagai sopir trans<br />
Yordania-Irak membuatnya banyak berdiam di dua tempat berbeda. Ya<br />
Irak, ya Yordania. A/asan mengada-ngada, batinku. Tetapi, cerita itu cukup<br />
mencairkan suasana kaku pada pagi itu. Ibrahim memang paling bisa<br />
mencairkan suasana.<br />
Dia melanjutkan ceritanya. Semula, dia sudah berjanji ini adalah<br />
perjalanannya yang terakhir sebagai sopir trans Irak-Yordania. Atas<br />
permintaan istri pertamanya yang tinggal di Yordania, dia memutuskan<br />
untuk beralih profesi menjadi sopir bus wisata saja.<br />
"Membawa turis berkeliling Yordania, melihat-lihat daerah bersejarah<br />
abad dulu di kawasan Pet-ra," katanya menerawang. Istrinya beralasan,<br />
keadaan Irak semakin berbahaya. Kejadian ini membuat Ibrahim<br />
menyesal tidak mengikuti keinginan istrinya lebih awal.<br />
Hening sejenak.<br />
"Jadi, kalau harus ada yang mati, akulah yang paling banyak ditangisi,<br />
2 istri dan 8 anak!" lanjut<br />
Ibrahim.<br />
Kami terbahak lagi. Seolah-olah kematian begitu dekat dengan kami,<br />
para tersandera di tengah gurun pasir sunyi. Terkadang, berbicara tentang<br />
kematian membuat kita sepenuhnya menghargai arti hidup.<br />
Sekali lagi, kesadaran akan adanya Dia membuat tak ada alasan<br />
untuk bersedih. Sekian hari berada di gua pastilah merupakan ujian dari<br />
Tuhan untuk menguatkan aku setelah kehilangan Ayah. Sejak kepergian<br />
Ayah, aku menjadi manusia yang rapuh. Rasa percaya diriku menurun<br />
drastis. Sebelumnya, setiap ada masalah,bukan hanya masalah yang<br />
terkait materi, melainkan dalam setiap masalah yang aku lalui, aku selalu<br />
merasa tetap aman karena ada Ayah yang akan menjadi penolongku,<br />
pelindungku. Tetapi dalam penyanderaan ini, aku sendiri tidak dapat<br />
mengadu kepada siapa pun. Komunikasi kami dengan dunia luar putus.<br />
Aku harus kuat, aku harus mampu menjalaninya dengan sikap yang<br />
dewasa dan menanggalkan sikap manjaku (karena sebagai anak bungsu<br />
terbiasa dimanja oleh Ayah dan Mama).<br />
Mungkin karena itu tadi, merasa sendiri tanpa ada yang dapat<br />
menolong kecuali Allah, rasa pasrah itu muncul. Aku berserah diri karena<br />
dalam kondisi itu memang tidak ada pilihan lain selain pasrah. Nyawaku,<br />
nasibku, ada di tangan Penciptaku. Dalam kepasrahan, kami bisa tertawa<br />
ketika membicarakan kematian.<br />
Tanpa diminta, giliran Muhammad yang bercerita. Mungkin dia teringat<br />
keluarga juga. Dia mengaku<br />
punya dua putri. "Tapi satu istri," katanya tersenyum simpul.<br />
Ibrahim yang disindir hanya meringis. Muhammad adalah mantan<br />
tentara era Presiden Saddam Hussein. Ketika Amerika menginvasi Irak<br />
tahun 2003, bersama ribuan tentara dia melawan dengan senjata<br />
terbatas. Sebagian mati, sebagian tertangkap, dan sebagian lain
menyerahkan diri. Muhammad memilih lari ke Yordania. Muhammad<br />
menunjukkan kartu anggota tentara miliknya. Wajahnya di foto bersih<br />
tanpa jambang. Jauh berbeda dengan saat ini.<br />
"Kamu ganteng kalau bersih begini," kata Budi sambil menimang<br />
kartu.<br />
Muhammad baru berusia 25 tahun. Dua tahun lebih muda dari aku.<br />
Tetapi, gurat-gurat di wajahnya mengesankan dia jauh lebih tua dari itu.<br />
Ketika pendudukan Amerika tak juga memberikan perdamaian seperti<br />
yang dijanjikan, Muhammad dan kawan-kawan kembali masuk Irak dan<br />
membentuk kelompok perlawanan. Muhammad bergabung dengan Jaish<br />
Al Mujahideen. "Kami tak membenarkan Saddam, tetapi kami juga tak<br />
mau dijajah," Muhammad berubah serius.<br />
Aku tak pernah bertanya apa itu kelompok Jaish Al Mujahideen. Tetapi<br />
belakangan, aku tahu bahwa organisasi mereka cukup rapi. Selain orang<br />
seperti Muhammad dan Ahmad yang memanggul senjata, ada pemasok<br />
logistik, dokumentasi, urusan media, juga Rois. Rois inilah yang banyak<br />
mengambil keputusan di tingkat kebijakan. Dari wajah saja,<br />
para Rois sudah berbeda. Mereka lebih rapi, baik dari cara<br />
berpakaian maupun urusan rambut dan jambang. Menurut Ibrahim,<br />
sehari-hari mereka bekerja seperti warga Irak lainnya. Ada yang jadi<br />
dokter, dosen, mahasiswa, politisi, atau bahkan pegawai pemerintahan.<br />
Tampaknya Ahmad terbawa suasana. "Ketika pergi dan menculik<br />
kalian, kepada ibuku aku pamit menginap di rumah saudara," katanya. Dia<br />
yakin ibunya gelisah menunggunya. Keluarganya tak ada yang tahu<br />
Ahmad ikut kelompok bersenjata. Ini lazim dilakukan pemuda Irak sebab<br />
jika keluarga tahu justru bikin repot. Keluarga bisa jadi sasaran jika<br />
musuh mencari para pemuda.<br />
Meski mengaku berumur 20 tahun, seperti juga Muhammad, Ahmad<br />
terlihat jauh lebih tua dari usianya. Mungkin perjalanan hidup yang getir di<br />
negeri seribu mesiu memaksanya matang lebih cepat daripada<br />
seharusnya. Ahmad amat senang menceritakan berbagai serangan yang<br />
disertainya. Entah benar entah tidak, Ahmad mengaku mereka banyak<br />
menembak jatuh pesawat pasukan koalisi. "Tapi media Barat menyebut<br />
pesawat itu jatuh karena gagal mesin," Ahmad tersenyum pahit.<br />
Kami tak menanggapi.<br />
Ahmad juga menjelaskan keyakinannya bahwa Tuhan selalu<br />
bersama para Mujahidin. Dia menceritakan suatu pertempuran hebat di<br />
Ramadi di mana anggota pasukan koalisi jauh melebihi jumlah Mujahidin,<br />
dengan peralatan perang yang jauh lebih canggih. Pasukan Mujahidin<br />
terpaksa ditarik mundur,<br />
tetapi beberapa gelintir memilih bertahan dan bertempur hingga<br />
matahari turun. Malam itu Ahmad dan warga sekampung dikejutkan oleh<br />
suara ringkikan pasukan kuda. Di Irak, apalagi di gurun, tidak pernah ada<br />
kuda. Keesokan paginya, warga kampung Ahmad menyaksikan tubuh<br />
tubuh pasukan koalisi bergelimpangan. Di lain kesempatan, masih<br />
menurut Ahmad, seorang anak di kampungnya pulang dari bermain.<br />
Kedua tangannya menjewer telinga dua tentara koalisi menggiring<br />
mereka ke kampung-nnya. Entah dari mana sumber kekuatan anak<br />
tersebut.<br />
Mungkin Ahmad mengira kami menganggap ceritanya hanya bualan.
Dia lalu berdiri. Tak lama kemudian, tangannya sudah menggenggam<br />
keping VCD. Budi mengambil laptop, memeriksa baterainya, lalu<br />
mengambil VCD di tangan Ahmad.<br />
Kami pun menatap layar komputer yang menggambarkan proses<br />
pelaksanaan bom bunuh diri. Ada rapat persiapan, juga ledakan<br />
mematikan. Mobil yang membawa bom diambil gambarnya dari tiga sudut<br />
berbeda. Terlihat betul bahwa mereka amat berhati-hati, tidak ingin<br />
kehilangan momen dengan menggunakan tiga kamera. Aku tercekat<br />
menyaksikan mobil berisi seorang pemuda meledak ketika menghantam<br />
tank koalisi. Pastilah tubuh pemuda itu terberai. Gambar itu dikompilasi<br />
dalam VCD dan disebar lewat pasar gelap. "Warga kami perlu diberi tahu<br />
bahwa kami mampu melawan pasukan koalisi," kata Ahmad bangga.<br />
Ahmad memasukkan VCD lainnya. Kali ini layar<br />
laptop memperlihatkan suasana rapat persiapan yang mirip dengan<br />
VCD sebelumnya. Bedanya, mereka yang hadir dalam rapat mengenakan<br />
abaya hitam dengan kerudung menutupi hampir seluruh kepala, hanya<br />
menyisakan bagian mata. "Mereka ini wanita yang juga memilih mati di<br />
jalan Allah. Mujahida. Meutya berminat menjadi Mujahida?" Raut Ahmad<br />
tersenyum, tetapi serius menunggu jawaban.<br />
Bingung bagaimana harus bersikap, aku hanya tersenyum<br />
kepadanya.<br />
Ahmad lalu menanyakan pengalaman meliput aku dan Budi.<br />
Kami bercerita tentang kedahsyatan tsunami, yang beritanya juga<br />
mereka lihat di Irak. Aku juga bercerita mengenai keluargaku. Kutunjukkan<br />
foto almarhum Ayah. Budi memperlihatkan foto istri dan anaknya. Mereka<br />
juga bertanya mengenai pekerjaan sebagai jurnalis. Mengapa datang ke<br />
Irak, yang jelas-jelas sedang bergolak. Aku jelaskan bahwa kehadiran<br />
kami, jurnalis dari negeri berpenduduk mayoritas Islam, adalah membagi<br />
informasi yang seimbang. Bahaya adalah risiko pekerjaan. Sama dengan<br />
para Mujahidin, yang justru lebih dekat dengan kematian.<br />
"Kalian berjuang dengan senjata, Budi dengan kamera, dan aku<br />
dengan pulpen dan kertas," kataku.Aku berharap jalan pikir mereka<br />
dibukakan bahwa perjuangan bersenjata bukan satu-satunya pilihan.<br />
Ahmad juga menanyakan gajiku. Tetapi, aku hanya tertawa. Aku<br />
beralasan tak mungkin menjawab karena di situ ada Budi. Giliran Ahmad<br />
dan Muhammad<br />
tertawa. Mereka berjanji akan menagih jawabannya kalau<br />
Budi sedang keluar gua.<br />
Pembicaraan terhenti karena kami sadar belum makan siang. Acara<br />
makan siang berlangsung tanpa kata. Mungkin karena suasana yang<br />
terbangun membawa kami jadi sentimental.Aku bersyukur, empat hari di<br />
gua, hal-hal yang kutakutkan di awal penculikan tidak terjadi.Tidak ada<br />
todongan senjata yang menggentarkan hati. Sebagai perempuan, tak<br />
sekali pun aku merasa dilecehkan lewat perkataan, apalagi perbuatan.<br />
Kecuali oleh tatapan cunihin si sontoloyo. Tidak ada hari tanpa makanan<br />
lezat. Ahmad dan Muhammad tidak akan makan sebelum aku makan.<br />
Ketika aku mulai lemas, karena nafsu makanku yang turun drastis,<br />
mereka membawakan soft drink dan buah-buahan, bisa apel, jeruk,<br />
kadang-kadang pisang. Ketika aku tertawa melihat gelas kecil khas Irak<br />
untuk minum teh, mereka membelikan gelas besar. Ketika persediaan
tisuku semakin menipis, mereka membawakanku sekotak tisu. Padahal,<br />
untuk bolak-balik ke gua, taruhannya adalah nyawa.<br />
Waktu yang lambat terus merayap.<br />
Dan, malam yang menjelang kembali membawa kesepian yang<br />
menikam. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Di dalam gua yang<br />
kecil ini, cara membuat suasana pribadi, memiliki sekadar privasi, adalah<br />
menutup seluruh tubuh dengan selimut. Mungkin karena tidak letih, atau<br />
pikiran yang kalut, kantuk tak kunjung datang. Kuraih buku Yasin<br />
bersampul gambar Ayah. Tetapi, lampu minyak yang<br />
bergoyang ditiup angin membuatku sulit membaca.<br />
* * *<br />
MATAKU panas. Bukan karena lelah membaca dalam lampu<br />
temaram. Aku rindu Ayah. Ingat masa-masa kecil bersamanya. Aku lahir 3<br />
Mei 1978 di Bandung. Ayahku, Doktor Anwar Hafid, dan mamaku, Meity<br />
Hafid, memberiku nama Meutya Viada Hafid. Nama yang sering membuat<br />
orang menyangkaku orang Aceh. Padahal, nama "Meutya" itu diambil dari<br />
nama grup bola voli sekolah Mama. Mama juga pengagum Bung Hatta,<br />
dan beliau memberi nama anaknya Meutya2.Adapun "Viada" diambil dari<br />
IADA, organisasi Ayah waktu mengambil gelar doktor di University of The<br />
Philipine, Los Banos, Filipina.<br />
Oh ya, gara-gara tinggal di Filipina itu pula,aku memiliki panggilan<br />
masa kecil "Bingbing". Ceritanya, sampai usiaku dalam kandungan 8<br />
bulan, Ayah dan Mama masih tinggal di negeri jiran itu. Anak perempuan<br />
kecil di sana biasa dipanggil "Bingbing", seperti "Neneng" di Sunda.<br />
Panggilan itu melekat di kalangan terdekat hingga aku SD. Tetapi, karena<br />
teman-teman SD memelesetkannya menjadi "belimbing", aku tak mau<br />
dipanggil Bing lagi.<br />
Mama selalu mengulang cerita yang sama bahwa waktu aku lahir<br />
hujan turun cukup deras di Bandung. Tiga kakakku (almarhum) Farid,<br />
Finny, dan Fitri tidak pernah berhenti melingkari keranjangku, mengamati<br />
gerak-gerik adik kecil mereka.Di Bandung<br />
2 Sekarang Menteri Urusan Perempuan.<br />
aku hanya menumpang lahir sebab Ayah segera pindah ke Bogor. Di<br />
sana, kami mengontrak sebuah rumah mungil, di sebuah gang kecil di<br />
Jalan Bangka.<br />
Di kota hujan itulah, aku tumbuh. Polah Meutya kecil menyedot<br />
perhatian tetangga. Setiap petang, selepas memandikan, membedaki,<br />
dan mengikat rambutku ke atas menyerupai air mancur, Mama selalu<br />
mendudukkanku di bangku kayu di depan rumah. Kata Mama, rumah kami<br />
yang kecil membuatku harus banyak bermain di luar.Tak lebih dari lima<br />
menit, ada saja tetangga yang menggendongku, membawa pergi<br />
berkeliling hingga azan magrib berkumandang.<br />
Dua tahun kemudian, kami pindah lagi ke Ujung pandang3. Ayah<br />
menjadi dosen di Universitas Hasanuddin. Panasnya Makassar yang<br />
berbeda jauh dengan Bandung dan Bogor membuatku tak betah.<br />
Untunglah, banyak rekan sebaya di kompleks dosen di Baraya, Jalan<br />
Sunu, Makassar. Aku pun mengecap pendidikan formal awal di kota nenek<br />
moyangku dari garis ayah itu. Ayah, yang sudah punya cukup<br />
tabungan,membeli mobil kecil. Cukuplah untuk membawa kami bermain<br />
ke rumah nenek, di seberang Pantai Losari. Makassar pun menjadi
tempat tumbuh yang menyenangkan dan penuh kenangan. Termasuk<br />
rekor membolos selama tiga bulan, sampai guru TK-ku datang ke rumah<br />
untuk membujukku, agar mau sekolah.<br />
Hanya sebentar aku memakai seragam putih-<br />
3 Sekarang bernama Makassar.<br />
merah, kami harus pindah lagi. Kali ini ke Jakarta. Perilaku malasku<br />
tak berubah. Persiapan berangkat sekolah menjadi episode pagi yang<br />
menegangkan dan melelahkan. Mulai dari pekerjaan rumah (PR) yang<br />
lupa dikerjakan, dasi dan topi yang hilang tak tahu rimbanya, buku<br />
pelajaran yang tercecer, hingga kuku yang belum dipotong. Ditambah lagi,<br />
aku sulit bangun pagi, hingga keriuhan itu berlangsung dalam suasana<br />
pendek. Ketika lonceng sekolah jelas terdengar berdentang hingga ke<br />
rumah, barulah aku diseret setengah berlari. Sampai menginjak bangku<br />
SMP, kondisi itu tak jauh berubah. Aku menjadi langganan koperasi<br />
sekolah, dan nyaris setiap Senin pagi aku datang membeli topi dan dasi.<br />
Ah, masa lalu yang indah ....<br />
Selain slebor, aku juga disebut mamaku sebagai pemberontak cilik.<br />
Darah Bugis dari Ayah sepertinya tertanam kuat dalam diriku. Prinsipku<br />
sering sulit ditawar. Aku harus memilih baju dan gaya kuncir rambut<br />
sendiri. Padahal, Mama sedang senang-senangnya mendandani anak<br />
bungsunya, dengan baju-baju yang khusus dia beli untukku. Walhasil,<br />
setiap ada acara undangan keluarga, drama menegangkan itu selalu<br />
berulang. Mama yang memaksa mengganti bajuku, dan aku yang matimatian<br />
bertahan. Rengekan dan bentakan saling bertukar di tengah aksi<br />
tarik-tarikan baju.<br />
Untunglah, kenakalanku tertutupi dengan prestasi sekolah. Namaku<br />
tidak pernah absen dari minimal peringkat tiga terbaik. Tatkala duduk di<br />
kelas S SD, tahun 1986, aku berangkat ke Jepang menjadi<br />
duta cilik dalam pertemuan anak se-Asia-Pasifik. Tiga tahun<br />
kemudian, aku ke Jepang lagi, tepatnya di Fukuoka, untuk mengikuti<br />
pertukaran pelajar Asia-Pasifik dengan pelajar Jepang dalam program<br />
The As ia-Pacific Children's Convention (APCC). Tinggal di Fukuoka,<br />
sebuah kota industri dan pendidikan terkemuka di Jepang, meski hanya<br />
dua minggu, membuat cara pikirku mulai berubah. Inilah kali pertama aku<br />
tinggal berjauhan dengan orangtua dan hidup bersama keluarga yang<br />
budayanya jauh berbeda. Aku pun melihat sikap anak-anak Jepang yang<br />
berbeda 180 derajat dari gaya hidupku. Mereka begitu teratur, terjadwal,<br />
rajin, dan menghormati orang tua.Pagi di keluarga Jepang yang menjadi<br />
semangku sungguh bukan pagi yang rutin aku jalani di tanah air.<br />
Bukan pola hidup itu saja pelajaran yang kupetik, dari bertemu anakanak<br />
dan budaya negara lain. Binar mata kebanggaan Ayah dan Mama,<br />
ketika menyambutku pulang, memperkaya batinku bahwa aku bukan<br />
semata-mata anak yang nakal. Prestasiku menjadi penawar yang sejuk,<br />
pengobat kelelahan mereka mengurus anak yang nakal ini.<br />
Mama, Ayah, kakak-kakakku, maafkan aku. Rasanya selama hidup,<br />
apalagi saat ini, aku selalu menjadi biang masalah. Doakan aku lepas<br />
dari persoalan berat ini.<br />
* * *<br />
SUARA derum mesin mengoyak keheningan malam.<br />
Helikopter. Muhammad mengecilkan nyala lampu minyak.
Suasana di gua berubah menjadi temaram dan mencekam. Meski semua<br />
terbangun, kami larut dalam diam. Belakangan, patroli udara Amerika<br />
semakin sering saja. Bisa saja mereka sudah mendeteksi keberadaan<br />
kami di gurun ini, dari bolak-baliknya mobil pengantar logistik. Sebuah<br />
repetisi yang menguntungkan sekaligus mencelakakan.<br />
Cahaya bulan yang masuk dari celah gua membuat gua tak terlalu<br />
temaram. Ketika cahaya buatan manusia tiada, sinar bulan dan bintang<br />
terlihat lebih benderang dan indah. Berteman cahaya rembulan, di atas<br />
pasir gurun, aku mencoba pasrah. Memejamkan mata, berusaha<br />
menghalau rasa takut.<br />
Ahmad mengajak kami berdoa. Kami membaca surat-surat pendek,<br />
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas. Di bawah deru suara helikopter, kami, aku<br />
dan Budi jurnalis asal Indonesia, Ibrahim sopir asal Yordania, serta<br />
Muhammad dan Ahmad kelompok Mujahidin Irak yang menculik kami-larut<br />
dalam kebersamaan, tunduk dalam doa agar esok masih bersua<br />
matahari. []<br />
Bab 7<br />
Hilangnya Kesabaran<br />
MATAKU mengerjap-ngerjap oleh berkas sinar terangyang menimpa<br />
wajah. Bukan sinar bulan. Cahaya matahari menerobos celah gua. Aku<br />
bersyu-kur,malam yang menegangkan telah berlalu. Aku tak ingat kapan<br />
akuterlelap. Kehadiran pagi membuatku semakin optimistis.Apalagi ini<br />
adalah hari kedua setelah pengambilan gambar. Mungkin gambar<br />
penyanderaan kami sudah ditayangkan.Ibrahim dan Budi sudah duduk<br />
berbincang.<br />
Ibrahim mengaku tidak dapat tidur nyenyak karena ketakutan.Budi pun<br />
tak bisa tidur lelap. Tetapi,dia tidak bisa tidur karena kedinginan. Rupanya,<br />
malam tadi Budi berbagi selimut dengan Ahmad yang berbadan besar.<br />
Akibatnya, sebagian badannya tidak terlindung selimut. Aku beruntung<br />
memiliki "ruang privasi", tak harus bersenggolan dengan orang lain. Tak<br />
harus berbagi selimut.Karena itu, aku sering malu, bangun paling akhir.<br />
Ritual membuat teh bersama sudah dimulai. Budi mengulurkan<br />
telapak tangannya di dekat air yang dijerang. Tetapi, kami tidak banyak<br />
bicara.<br />
Ketegangan semalam masih terbawa. "Aku jenuh, Mut," bisik Budi.<br />
Aku mengangguk, menyetujui. Maklum, sebagai jurnalis, aku dan Budi<br />
terbiasa dengan kehidupan yang dinamis, dari satu peristiwa ke peristiwa<br />
lain nyaris tanpa jeda. Aku mendadak mengerti pentingnya sebuah<br />
kemerdekaan.<br />
Pagi pun kubuka dengan mood yang kurang baik.<br />
"Ada apa?" tanya Ibrahim.<br />
Aku jelaskan bahwa kami sudah bosan tanpa kepastian. "Kalau<br />
begini terus, rasa hormatku kepada Mujahidin yang mulai terbangun bisa<br />
runtuh."<br />
"Mujahidin itu tugas suci, dan pelakunya pasti orang tepat janji,"<br />
Ibrahim tetap saja membela.<br />
Aku tekankan padanya, belajar dari keadaan tadi malam, keberadaan<br />
kami di gua semakin tidak a-man."Kita bisa mati konyol di sini," keluhku.<br />
Muhammad, yang duduk di seberang kami, tampaknya menangkap<br />
gelagat kurang baik. Dia membuka perbincangan ringan. Tentang gelas
kami yang lebih besar dari milik mereka. Tentang air yang diambil dari<br />
Sungai Eufrat. Muhammad, seperti juga Ibrahim, selalu membanggakan<br />
air Sungai Eufrat. Menurut mereka,kualitas air sungai ini hanya sedikit di<br />
bawah air zam-zam. Muhammad juga bercerita bahwa Irak pada masa<br />
silam disebut Mesopotamia tanah di antara sungai-karena mencakup<br />
sebagian besar dataran alluvial yangsubur di antara sungai-sungai Eufrat<br />
dan Tigris.<br />
Sejarah yang menarik, pikirku, tetapi diceritakan<br />
ditengah keadaan kurang baik, membuatku tak antusias.<br />
Lalu Hening.<br />
Gantian Ahmad yang membuka perbincangan. Diamenanyai Budi<br />
apakah komputer jinjing masih bisa dipakai. Budi mengecek dan<br />
mengangguk tanda oke.Ahmad mengeluarkan VCD dari saku jaketnya.<br />
Tanpa bicara, kami lalu merubung komputer, membiarkan gambar<br />
berputar. Anak-anak dan perempuan menjerit kesakitan di sebuah rumah<br />
sakit. Orang-orang berlumuran darah datang silih berganti. Kawasan<br />
permukiman penduduk. Raungan pesawat tempur melintas,lalu<br />
dentuman bom menimpa rumah penduduk. Asap membubung dari rumah<br />
yang menyala terbakar. Wargapanik berlarian tanpa arah yang jelas.<br />
"Inilah hari pertama Amerika menyerang negara kami," suara Ahmad<br />
memecah keheningan.<br />
Ahmad lalu menceritakan bahwa gambar itu diambildi Ramadi, kota<br />
kelahiran Ahmad dan Muhammad. Juga, kota tempat kami diculik.<br />
Suasana saat invasi itu berbeda jauh dengan yang kami lihat saat<br />
melintas sebelum penculikan. Gedung-gedung saat ini lebih sedikit<br />
dibandingkan sebelum invasi. Rupanya sebelum Amerika datang, Ramadi<br />
merupakan kawasan pertanian yang subur. Setelah invasi, segala<br />
ketenteraman itu pun sirna.<br />
"Ini salah satu alasan kami berontak," ujar Ahmadsambil matanya tak<br />
lepas dari layar komputer.<br />
Menyaksikan tayangan VCD itu, tiba-tiba aku teringat Suha, putri<br />
bungsu Muhammad Nasser.<br />
Nasser adalah orang Irak yang menjadi penerjemah kami padahari<br />
pertama datang ke Irak. Dulu, waktu Budi meliput pertama kali ke Irak<br />
tahun 2003, dia pernah bekerja diKBRI. Dia adalah kamus berjalan yang<br />
mengabarkanperbedaan sebelum dan sesudah Amerika menginvasilrak.<br />
Ketika kami masuk Bagdad, dia menunjukkan bekas lokasi patung<br />
Saddam Hussein, yang dirobohkan ketika serdadu Paman Sam masuk<br />
pusat kota. Melihat bangunan yang porak-poranda, dan dijelaskan<br />
bangunanapa itu dulunya, capai rasanya. Apalagi melihat tentara Amerika<br />
dengan senjata pongah berseliweran di mana-mana.<br />
Suha adalah bocah cantik berusia sembilan tahun. Wajahnya khas<br />
perempuan Arab. Hidungnya mancung, kulitnya bersih, dan rambutnya<br />
ikal. Aku tanya kenapa dia tidak sekolah. Dia hanya tersenyum.<br />
"Saya melarangnya sekolah," Nasserlah yang menjawab. Nasser<br />
melarang anak-anaknya sekolah, sebab bangunan yang mestinya bebas<br />
dari perang, termasuk sekolahan, kini sering dijadikan arena bom bunuh<br />
diri.<br />
Aku dan Budi pernah meliput suasana sekolah-sekolah di Irak.<br />
Beberapa sekolah yang kami kunjungi tampak lengang. Aku tercengang
melihat pintu sekolahyang dijaga oleh pria bersenjata laras panjang.<br />
Pikirku, bagaimana mau menimba ilmu dengan tenang kalau mau masuk<br />
sekolah saja harus menyaksikan orang bersenjata. Tetapi, beberapa anak<br />
kecil di depan sekolah sepertinya sudah terbiasa dengan senjata. Mereka<br />
tak acuh dan meneruskan<br />
bermain. Anak-anak lain yang tidak diizinkan orangtua mereka<br />
bersekolah, seperti anak-anak Nasser misalnya, memilih mengisi harihari<br />
dengan bermain bola dan kejar-kejaran di gang-gang di antara rumah<br />
susun mereka.<br />
"Semua tak lagi peduli anak-anak. Semua demi perjuangan," lanjut<br />
Nasser kecut.<br />
Suha adalah satu-satunya anak perempuan Nasser. Abbas, kakak<br />
laki-laki Suha yang baru berusia dua belas tahun, menurut Nasser, sudah<br />
pandai menggunakan senjata. "Aku terpaksa mengajarkannya untuk<br />
keamanan. Kalau hal buruk terjadi padaku, Abbas harus mampu<br />
melindungi keluarga," ujar Nasser.<br />
Seperti halnya Suha, Abbas sudah cukup lama absendari sekolah.<br />
Adik laki-laki Suha yang baru berusia lima tahun, Mikhail, belum mengerti<br />
banyak. Dia lebih sering bermain di kamarnya.<br />
Nasser lalu membawaku berkeliling ke sekitar kampung tempatnya<br />
tinggal. Suasananya mirip dengan kompleks rumah susun di Jakarta. Di<br />
situ aku melihat puluhan anak lainnya, sebaya dengan anak bungsu<br />
Nasser. Yang lelaki asyik bermain bola, yang perempuan bermain kejarkejaran.<br />
Semua tak bersekolah karena alasan yang sama.<br />
Melihat aku dan Budi, mereka berhenti bermain. Diawali satu anak,<br />
mereka tahu-tahu sudah mengelilingi aku dan Budi.<br />
Mereka berebut mengucapkan sesuatu,tetapi aku tak mengerti.<br />
"Mereka minta difoto bersama," teriak Nasser<br />
mengatasi suara berisik anak-anak.Aku tergelak dan memeluki<br />
mereka.<br />
* * *<br />
AKU berangkat ke Irak sebagai jurnalis yang berusaha independen.<br />
Tidak mengasihani bangsa Irak,tetapi juga tidak menyalahkan Amerika.<br />
Namun, tayangan VCD yang belum berhenti menggambarkan berbagai<br />
kehancuran membuatku terenyuh. Nun di lubuk hati terdalam, aku mulai<br />
memahami pilihan mereka. Ketika manusia ditekan di luar batas<br />
kewajaran, maka insting pertama adalah memberontak. Mungkin bagi<br />
Ahmad dan Muhammad, masalahnya sederhana. Keberadaan pasukan<br />
asing merupakan bentuk penjajahan, dan penjajahan harus dilawan.<br />
Bukankah kita juga menganut paham bahwa penjajahan di muka bumi<br />
harus dihapuskan?<br />
Aku tak menyalahkan jalan pikiran mereka yangmenurutku terlalu<br />
hitam-putih. Nyaris sepanjang usianya, Ahmad dan Muhammad didera<br />
konflik berkepan-jangan. Untuk mengecap pendidikan yang layak di dalam<br />
negeri saja, mereka tidak punya banyak kesempatan. Wajar kalau hal itu<br />
membuat mereka berpikiran sempit. Aku merasa beruntung, di usiaku<br />
yang masih muda, aku sudah bepergian ke banyak negara, bahkan<br />
menetap bertahun-tahun, serta bergaul dengan berbagaibangsa dan<br />
agama.<br />
Singapura, meski bukan negara yang asing lagi yang pernah
kudatangi, memiliki banyak kenangan dalam hidupku. Semua berawal<br />
dari iklan yang dilihat<br />
Mama tahun 1993. Saat itu, aku baru saja lulus SMP.ASEAN<br />
Secondary Scholarship, yang dibiayai Kementerian Pendidikan<br />
Singapura,memberikan beasiswa untuk belajar di sana. Ayah<br />
menantangku, "Nak, kamu berani tidak sekolah sendiri di Singapura?"<br />
Ayah tahu betul kebiasaanku:kalau ditantang berani atau tidak,pasti<br />
menjawab berani.<br />
Dimulailah perburuan itu. Mama mengambil sendiri formulir di<br />
Kedutaan Singapura. Lalu Mama, Ayah, dan kakak bergotong-royong<br />
menyiapkan data. Aku sendiri sibuk menonton televisi saja. Semua dataku<br />
sudah tertulis rapi di kolomnya. Aku tersenyum melihat isian NEM (Nilai<br />
Ebtanas Murni) SLTP-ku: 10 untuk matematika. Pelajaran itu memang<br />
favoritku, selain ilmu pengetahuan alam, IPA. Matematika itu pula yang<br />
mengantarku menuju kehidupan mandiri di negara tetangga, Crescent<br />
Girls Scho ol, Singapura.<br />
Menjelang si bungsu ini pergi, kegembiraan berubah. Ayah, yang<br />
pada awalnya paling bersemangat mendukung kepergianku, menjadi<br />
susah tidur. Rupanya, Ayah tidak siap melepasku hidup sendiri di negeri<br />
orang,di usiaku yang baru beranjak remaja. Tepat sehari sebelum<br />
keberangkatanku, Ayah ambruk. Ayah terserang stroke ringan. Darah<br />
tingginya memuncak karena sedih luar biasa. Melihat kondisi Ayah,<br />
keluarga mempertimbangkan ulang kepergianku. Namun di tengah<br />
kegalauan, Ayah memutuskan aku tetap berangkat. Keputusan Ayah ini<br />
membawaku ke lembar baru dalam hidupku. Sistem pendidikan<br />
Singapura yang sangat kompetitif tidak hanya<br />
mengajariku hidup mandiri,tetapi juga arti kerja keras. Akh ... andai<br />
Ayah masih hidup, pastilah dia sedih bukan kepalang anak<br />
perempuannya hilang tiada rimba.<br />
Dari Singapura, aku melanjutkan studi ke Sydney, Australia. Tahun<br />
1996, Aku menjadi mahasiswa Schoolof Manufacturing Engineering,<br />
University of New SouthWales. Fakultas yang aku pilih merupakan favorit<br />
dikalangan international students. Jadi, aku banyak bertemu dengan<br />
mahasiswa dari berbagai negara. Banyak nilai dan paham di antara kami<br />
yang berbeda. Tetapi,itu semua kami jadikan masukan untuk<br />
memperkaya khazanah, bukan untuk pertentangan.<br />
Tinggal di Australia jauh dari keluarga juga mengajarkan padaku<br />
pentingnya perjuangan. Dua tahun kuliah, Indonesia dilanda krisis<br />
ekonomi dahsyat. Nilai tukar dolar terhadap rupiah melambung.<br />
Beasiswaku dari pemerintah Indonesia diputus sepihak.Ayah sebenarnya<br />
memintaku pulang.Tetapi, dia juga tahu bahwa menyelesaikan SI di<br />
UNSW adalah impianku. "Ayah mau kamu tetap melanjutkan kuliah di<br />
Australia. Kita akan tempuh segala usaha untuk membiayai," kata Ayah<br />
waktu itu.<br />
Aku pun semakin rajin mendatangi toko dan gerai favoritku. Kali ini<br />
bukan untuk shopping, melainkan melamar kerja. Setelah ke sana kemari<br />
tanpa hasil, akhirnya nasibku tersangkut di restoran ayam cepat saji, yang<br />
letaknya tidak jauh dari kampus. Aku memulai sebagai pramusaji, lalu<br />
kasir, hingga akhirnya dipercaya meracik bermacam jenis burger.<br />
Meutya yang mengurus diri sendiri saja tidak becus kini harus pintar
menyiapkan masakan. Tak jarang kulit tanganku terciprat minyak panas<br />
atau tersengat pemanggang roti burger. Aku bekerja sepulang kuliah<br />
hingga tengah malam, lalu paginya bersiap lagi kuliah. Kadang, kalau<br />
butuh uanglebih, aku terpaksa membolos kuliah.<br />
Penghasilan kerja paruh waktu itu, aku gunakan untuk membayar<br />
sewa rumah. Untuk makan, aku punya trik khusus berhemat. Setiap<br />
malam, aku membawa ayam sisa untuk disantap besok siangnya. Untuk<br />
makan pagi, aku membawa roti burger yang dibuang restoran karena<br />
tanggal kedaluwarsa akan habis keesokan harinya. Penggal hidup yang<br />
pahit.<br />
Namun, itu pun belum cukup. Libur akhir tahun,yang waktu itu jatuh<br />
bertepatan dengan bulan Ramadhan, ku siasati dengan menambah jam<br />
kerja. Sejak krisismoneter, aku tidak lagi merasakan kehangatan<br />
Ramadhan bersama keluarga.<br />
Terhambat oleh aturan bahwa pelajar asing hanya boleh kerja 20 jam<br />
seminggu, aku pun mencari kerja yang membayar tunai supaya tidak<br />
terpantau imigrasi.Ada pabrik pengepakan majalah di pinggir Kota<br />
Sydney,yang biasa melakukan kebijakan seperti itu untuk mempekerjakan<br />
imigran. Karena lokasi pabrik cukup jauh, aku harus berangkat sebelum<br />
matahari terbit. Mengejar bus paling awal menuju central station, lalu naik<br />
kereta api ke tempat kerja.<br />
Pukul tujuh tepat, aku sudah berdiri mengelilingi<br />
belt, di mana majalah akan berputar. Aku kebagian tugas<br />
menempelkan lembaran tambahan atau hadiah,kehalaman tengah<br />
majalah. Selama sepuluh jam, dipotong istirahat makan siang 30 menit,<br />
tanganku terus-menerus bergerak naik-turun,menyerupai mesin,<br />
menempelkan hadiah. Jika kelamaan, badanku sering limbung karena<br />
pusing terus-menerus melihat ribuan majalah yang tak berhenti berputar.<br />
* * *<br />
DAN waktu terus berputar di gurun sepi ini. Sudah hari kelima kami<br />
diam tanpa kegiatan berarti. Sudah dua hari pula sejak pengambilan<br />
gambar. Tetapi, tanda-tanda pembebasan itu tak kunjung tiba. Rois yang<br />
kami nantikan untuk mengabarkan masa indah itu belum muncul hingga<br />
menjelang siang. Gundahku membuncah menjadi kesal. Aku sadar, sifat<br />
kerasku bisa muncul pada saat seperti ini.<br />
Ketika Rois kemudian datang tengah hari, kesabaranku sudah hilang.<br />
Dia menyatakan belum bisa melepas kami karena pernyataan Presiden<br />
Indonesia yang mereka tunggu belum ada. Aku bersikeras menagih janji<br />
pembebasan.<br />
"Saya hargai jihad kalian. Kalian berjihad dengan senjata, tetapi saya<br />
juga ingin meneruskan jihad saya. Jihad saya dengan ini, jihad Budi<br />
dengan itu," kataku seraya mengangkat pulpen tinggi-tinggi dan<br />
menunjuk-nunjuk kamera yang tergeletak di lantai.<br />
Semua diam.<br />
"Apa artinya berjihad jika kita hanya diam menghabiskan<br />
waktu di gua. Kalau dibom, kita bukan syahid,tetapi mati<br />
sia-sia," lanjutku.<br />
Ibrahim tampak agak bingung. Dan, aku yakin dia tidak<br />
menerjemahkan semua unek-unekku. Dia menyensor pernyataanku,untuk<br />
menjaga situasi tetap kondusif. Matanya menatapku, seolah-olah
memintaku meredakan amarah. Budi sendiri hanya menunduk.Tetapi,aku<br />
tak peduli lagi.Hanya satu dalam pikiranku: aku ingin bebas! Berharap<br />
pada kebaikan Rois saja tidak cukup. Aku harus perjuangkan<br />
kebebasanku!<br />
Rois tampak terkejut dengan perubahan sikapku. Mungkin tidak<br />
banyak orang yang bersuara tinggi dihadapannya. Namun, dia kelihatan<br />
berusaha tetap tenang, tidak membalas kata-kataku. Dia sepertinya<br />
menanyai Ibrahim, kenapa aku berubah galak siang itu.<br />
Sebelum pergi, dia mengulangi lagi janji pembebasan kami. Tetapi,<br />
aku tidak mau lagi menanggapi janjinya itu.<br />
Yang tersisa hanyalah keheningan.<br />
Sepeninggal Rois, suasana di gua berubah kaku. Ahmad dan<br />
Muhammad ikut salah tingkah. Mereka bukan lagi sekadar penculik,<br />
melainkan teman. Dan sebagai teman, Muhammad dan Ahmad<br />
sepertinya memahami kemarahanku. Ada rasa tidak enak yang terselip<br />
dalam hatiku karena aku memarahi pemimpin Ahmad dan Muhammad.<br />
Jangan-jangan mereka dihukum karena tidak bisa menjagaku.<br />
Dan, siang kembali merayap menuju malam.<br />
Namun, malam yang dingin berpadu dengan<br />
suasana hati yang juga dingin. Tak ada makan malam bersama. Aku<br />
mencomot sedikit daging, lalu menyepi disudut privasiku.Yang lain pun<br />
begitu. Sayangnya, usahaku memejamkan mata diganggu suara tikus.<br />
Entah dari mana datangnya tikus itu hingga sampai di gua kami.<br />
Tampaknya dia terperangkap mencari pintu keluar. Karena ukuran gua<br />
yang kecil, gerakan tikus terdengar jelas. Banyaknya plastik sisa<br />
pembungkus membuat gerakan tikus terdengar makin jelas. Aku<br />
memekik ketika tiba-tiba tikus itu berlari ke arahku. Yang lain tertawa.<br />
"Berani ke Irak, kok sama tikus saja takut," kata Ibrahim.<br />
Kusembunyikan wajahku di balik selimut. Aku tersenyum simpul. Aku<br />
tahu mereka mencoba mencairkan suasana. Tetapi, kemarahanku masih<br />
membara. Kutarik selimut lebih lekat.[]<br />
Bab 8<br />
Kabar Pembebasan<br />
SATU malam lagi telah kulewati dalam gua di tengah gurun. Tetapi,<br />
dingin pagi yang merejam-rejam kulit membuatku enggan keluar dari<br />
sedikit kehangatan dalam selimut.Tak ada suara-suara pengundang<br />
semangat dan tawa canda yang mengiringi ritual chai.<br />
Mungkinkah mereka marah atas sikapku kemarin?<br />
Kalau begitu, aku harus minta maaf. Buru-buru akubangkit. Tak ada<br />
Ahmad.Juga, Muhammad. Apakah mereka sedemikian tersinggungnya,<br />
Rois mereka aku marahi sehingga mereka pergi tanpa pamit?<br />
Namun, bersama Budi dan Ibrahim ada dua lelakilain, yang baru<br />
kulihat.<br />
Aku bilang kepada Ibrahim, "Hammam, ham-mam. "Maksudnya, aku<br />
mau ke belakang dan sikat gigi, meski arti sebenarnya adalah "kamar<br />
mandi" atau "toilet". Cukup lama aku di luar, sampai Budi meneriakkan<br />
namaku.<br />
"Ahmad dan Muhammad pergi pagi-pagi sekali. Mereka titip salam,"<br />
kata Budi sesampainya aku kembali di gua.<br />
Rupanya bukan kemarahan yang membuat dua penjaga itu pergi.
Menurut Ibrahim, yang mencuri dengar pembicaraan, Ahmad dan<br />
Muhammad memiliki tugas lain, yaitu menjaga sandera baru. Di gurun itu<br />
memang ada gua lain yang kabarnya lebih besar. Tetapi, aku tak tahu di<br />
mana letaknya. Aku tak pernah ke mana-mana.Aku hanya bisa bergerak<br />
dari gua ke luar gua, dan kembali ke dalam gua.<br />
Meski aroma hangat chai yang khas tetap menggelitik hidungku, ritual<br />
minum pagi hari itu berlangsung dingin. Ini mengulang hari-hari awal<br />
penculikan enam hari lalu. Kami duduk mengelilingi pusat perapian<br />
dalam diam. Biasanya, Ahmad selalu memberikan semangat padaku<br />
dengan senyum hangat dan candanya. Tetapi, pagi ini, di tengah<br />
ketidakpastian kabar pembebasan, suasana akrab yang mulai terbangun<br />
pun pelan-pelan memudar.<br />
Budi dan Ibrahim juga terlihat tidak seceria hari-hari sebelumnya.<br />
Kami hanya berbicara seperlunya. Boleh jadi pikiran kami sama, yakni<br />
bahwa kami belum merasa dekat dengan penjaga yang menggantikan<br />
Muhammad dan Ahmad.Kami bahkan tak ingat nama mereka. Salah<br />
satunya, yang berbadan tinggi, kami panggil saja si Jangkung. Walaupun<br />
mereka menunjukkan sikap yang santun dan baik, tetap saja kedekatan<br />
kami berbeda. Tak pernah terpikir olehku bahwa aku bisa merasa<br />
kehilangan sosok orang yang menculik dan menodongkan senjata<br />
kepadaku.<br />
Budi bilang, ketika meninggalkan kami kemarin, Muhammad berjanji<br />
akan menemui kami sebelum<br />
kami bebas. Mereka berusaha meyakinkan bahwa kami dalam<br />
kondisi aman meski bukan mereka yang mengawal. Muhammad juga<br />
bilang, dia pulang sebentar menengok anak dan rumahnya. Sedangkan<br />
Ahmad, khawatir ibunya mencari-cari karena dia terlalu lama<br />
meninggalkan rumah. Namun, menurut Ibrahim, itu tadi, mereka<br />
mengawal sandera lain. Menurut Ibrahim juga, sandera baru itu adalah<br />
warga Irak, yang dituduh berkhianat dengan memberikan informasi<br />
kepada pasukan koalisi mengenai keberadaan kelompok pergerakan.<br />
"Biasanya, kelompok seperti itu tidak disandera lama. Jika tidak<br />
menguntungkan, mereka akan dibunuh dengan cara dipenggal atau<br />
ditembak. Dokumentasinya disebarkan, agar menjadi peringatan bagi<br />
warga lain supaya tidak melakukan hal bodoh serupa," kata Ibrahim.<br />
Aku bergidik. Aku teringat gambar video yang pernah kulihat di kantor<br />
berita APTN, Bagdad. Ketika itu,aku dan Budi tengah mengirimkan<br />
rekaman laporan kami ke Jakarta dengan menyewa jasa satelit APTN.<br />
Pada saat yang bersamaan, datang sebuah rekaman video yang dikirim<br />
tanpa nama. Ketika diputar, kaset tersebut ternyata berisi rekaman adegan<br />
yang sungguh mengerikan. Tiga orang yang terlihat seperti warga Irak<br />
berbaris rapi dengan mata ditutup,kemudian orang bersenjata dengan<br />
muka tertutup menembak mereka dari belakang. Peluru menembus dada<br />
ketiga orang tersebut. Visual berikutnya merekam seseorang yang<br />
mengenakan seragam tentara koalisi, dengan muka tertutup dan posisi<br />
jongkok, menunggu eksekusi. Ketika tembakan<br />
pertama mengenainya, dia sempat bereaksi dengan menyumpah<br />
dalam bahasa Inggris. Tembakan berikutnya pun bersusulan, membuat<br />
badan si tentara terguncang, terlempar, dan tak bergerak lagi. Perlakuan<br />
terhadapnya mirip dengan perlakuan terhadap seekor binatang hasil
uruan. Tak lebih. Mengerikan.<br />
Tak kubayangkan sosok Ahmad dan Muhammad yang baik dan<br />
santun sanggup melakukan hal seperti itu. Mungkinkah mereka<br />
meninggalkan kami untuk sebuah eksekusi? Ah, kalau Presiden<br />
terlambat, atau salah merespons pernyataan para penculik, mungkinkah<br />
...? Aku membuang jauh-jauh bayangan buruk itu. Sebagian besar<br />
keyakinanku menyatakan tidak akan terjadi hal seperti itu. Mulai dari<br />
penculikan, hingga berhari-hari menghabiskan waktu bersama, aku selalu<br />
berpikir positif tanpa aku paksakan. Ataukah pikiran positif itu hanya<br />
ungkapan alam bawah sadar yang muncul sebagai penolakan terhadap<br />
kemelut ini?<br />
Namun, aku sadar bahwa rekaman gambar yang pernah aku dan<br />
Budi saksikan bisa juga menimpa kami. Biasanya, kelompok perlawanan<br />
yang menyandera jurnalis hanya memberikan batas waktu tiga hari bagi<br />
negara asal si sandera, untuk memberikan tanggapan. Ini sudah hari<br />
keempat dari pengambilan rekaman gambar, dan kabar dari Indonesia<br />
belum juga datang. Apakah Ahmad dan Muhammad tak tega, lalu<br />
menyerahkan tugas eksekusi kepada orang lain?<br />
Bayangan kematian lagi-lagi membawa lamunanku ke Indonesia.<br />
Sebelum meninggalkan tanah<br />
air, Indonesia tengah dicoba dengan ujian yang luar biasa dahsyat.<br />
Dalam hitungan menit, ratusan ribu nyawa melayang akibat tsunami yang<br />
meluluhlantakkan Aceh. Aku yangditugasi ke Aceh berusaha<br />
mengabarkan bagaimana dahsyatnya kerusakan. Termasuk dari Aceh<br />
Barat dan Aceh Jaya, kabupaten yang bersisian dengan pantai.<br />
Menumpang helikopter, aku terbang bersama Pangdam Iskandar<br />
Muda, Mayjen TNI Endang Su-warya, melihat Phangha, salah satu titik<br />
terisolir di Aceh Jaya. Ketika aku meminta turun, pilot ragu sebab<br />
kehancuran wilayah itu tak terperi sehingga untuk mencari koordinat<br />
pendaratan saja susah. Dari jendela aku lihat kawasan gersang, tidak ada<br />
satu pun pohon yang berdiri tegak.Tak juga rumah. Semua rata dengan<br />
tanah. Pangdam marah ketika aku tawarkan supaya aku dan juru kamera<br />
tinggal. Di sana tak ada tempat berteduh, tak ada makanan dan minuman.<br />
Begitu helikopter nyaris menapak tanah, warga dibawah sana<br />
berlarian mendekat.Seolah-olah menyambut malaikat penolong. Aku<br />
terenyuh, mataku hangat oleh genangan air mata. Ratusan ribu nyawa<br />
melayang, ratusan ribu pula kehilangan tempat tinggal dan butuhperhatian<br />
pemerintah. Berlebihankah berharap banyak kepada Presiden untuk<br />
menyelamatkan nyawaku dan Budi, di tengah maha duka yang melanda<br />
negeriku?<br />
Toh, nun di lubuk hati terdalam,aku tetap yakin Presiden akan<br />
menyelamatkan kami. Ini hanya soal waktu. Aku cukup mengenal sosok<br />
Presiden, dalam<br />
hubungan wartawan dan sumber berita. Presiden bijak dalam<br />
memutuskan, juga bisa berdiplomasi. Sisi kecil kehidupan pribadinya aku<br />
dengar dari anaknya, Lettulnf Agus Harimurti. Agus aku kenal ketika dia<br />
bertugas di Meulaboh, saat meliput pelaksanaan Darurat Militer di Aceh,<br />
tahun 2003. Agus sering bercerita bahwa SBY adalah sosok ayah yang<br />
penuh perhatian dan penyayang. Tetapi, mungkinkah dia juga punya<br />
perhatian dan sayang akan nasibku? Sudikah dia berdiplomasi dengan
kelompok yang dicap oleh negara Barat sebagai teroris? Aku meringis<br />
membayangkan jawaban tidak. Sebab, pernyataan Presiden menjadi<br />
kunci kebebasan kami.<br />
* * *<br />
TERDENGAR derum mobil di kejauhan. Kedua penjaga baru bersiap<br />
menyambut. Aku berharap yang datang Rois, membawa kabar bahagia.<br />
Entah kenapa, aku juga berharap yang datang adalah Ahmad dan<br />
Muhammad. Ternyata yang datang sosok lelaki muda yang kukenal<br />
sebagai adik Ahmad, yang pernah datang mengantar logistik. Dia muncul<br />
dengan wajah yang ceria. Dengan penuh semangat, dia pun bercerita<br />
kepada Ibrahim. Aku melihat Ibrahim menegakkan duduknya, dan<br />
matanya membelalak girang. Aku menangkap sesuatu yang<br />
menyenangkan, tetapi tak mau menyela. Akuhanya menangkap dua kata,<br />
televisyen dan Rois. Apakah Rois yang dia maksud Presiden Yudhoyono,<br />
dan muncul di televisi? Aku tetap diam sambil menyembunyikan<br />
harapan besar.<br />
Aku menatap Ibrahim, bak mengiba agar dia segera menjelaskan apa<br />
yang tengah terjadi.<br />
"Adik Ahmad mengatakan dia melihat presiden kalian di televisi," kata<br />
Ibrahim.<br />
Aku menyipitkan mata ke arah adik Ahmad untuk memancing<br />
penjelasan lebih detail.<br />
"Presiden Anda tampan dan tinggi besar?" tanya adik Ahmad, yang<br />
diterjemahkan Ibrahim.<br />
Aku mengangguk tersenyum membayangkan sosok Presiden SBY.<br />
Mungkin adik Ahmad kaget karena menduga orang Indonesia semua<br />
mungil seperti aku dan Budi.<br />
"Menurutnya, Presiden ingin sekali kalian segera kembali," tambah<br />
Ibrahim.<br />
Kali ini, air mataku benar-benar bergulir. Ku lihat mata Budi juga<br />
berkaca-kaca. Aku menunduk dalam diam, tidak lagi memancing adik<br />
Ahmad menjelaskan lebih terperinci. Keyakinanku bahwa Presiden akan<br />
menyelamatkan kami terbukti.<br />
Namun, adik Ahmad rupanya belum puas meyakinkan kami. Dengan<br />
bersemangat, dia terus menjelaskan apa yang dia lihat di televisi.<br />
"Istri Budi bersama anak perempuan, juga ada ditelevisi," kata<br />
Ibrahim menerjemahkan dengan senang.<br />
Budi, yang tadinya hanya berkaca-kaca, kini sesenggukan.<br />
Adik Ahmad kemudian berbalik ke arahku. Dia mengatakan sesuatu,<br />
tetapi aku hanya menangkap kata"Ummi ... Ummi ..."Ibrahimlah yang<br />
membuat<br />
segalanya jadi jelas."Adik Ahmad juga melihat ibu dan kakakmu,<br />
menangis di televisi.<br />
"Kali ini aku tak kuasa lagi menahan air mata yang menderas.Mama<br />
menangis gara-gara aku. Sungguh berdosa aku membuatnya merana.<br />
Isak tangisku bersahutan dengan isak tangis Budi. Selama diculik,<br />
inilah kali pertama aku menangis didepan orang lain. Kuraih kotak tisu di<br />
sebelah perapian. Kuambil selembar untuk mencoba menyeka air<br />
mataku.<br />
Sejak awal aku terjun ke dalam profesi jurnalistik ini, aku sudah
menyiapkan diri untuk segala risiko dan konsekuensi. Tetapi, tidak<br />
mamaku. Pasti dia sangat terpukul. Dia tidak siap untuk ini. Aku telah<br />
berbuat tidak adil, membuat mamaku dan keluarga ikut menanggung<br />
risiko profesiku. Aku merasa telah bersikap egoistis, yakni demi kepuasan<br />
pribadi mengorbankan perasaan keluarga. Apalagi perasaan Mama.<br />
Tangisan kami tampaknya membuat adik Ahmad kaget. Dia, yang<br />
semula bercerita sambil berdiri, kini terdiam dan duduk berlutut. "Kenapa<br />
mereka sedih? Bukankah aku membawa kabar gembira? Mereka akan<br />
dibebaskan," katanya kepada Ibrahim.<br />
Dari balik kertas tisu, aku mengintip. Raut muka adik Ahmad terlihat<br />
sedih. Aku buru-buru menghapus sisa air mataku. Aku tidak mau ada<br />
orang lagi yang bersedih karena kami. Budi juga sudah dapat<br />
mengendalikan dirinya. Aku jadi malu, mungkin mataku bengkak saat ini.<br />
Tetapi, aku tak peduli. Tanpa mata bengkak pun penampilanku pasti<br />
sudah<br />
amburadul. Enam hari tak pernah mandi dan ganti baju, tentu saja,<br />
cukup untuk membuat wajahku tidak keruan.<br />
"Apa betul kami akan segera dibebaskan?" Ku-beranikan menatap<br />
mata adik Ahmad.<br />
"Ya, itu janji dari Rois kami. Tetapi, kalian harus menunggu<br />
kedatangan Rois untuk menyatakan pembebasan secara resmi." Kali ini<br />
pengawal yang menggantikan Ahmad yang menjawab.<br />
Adik Ahmad pun pamit. Dia datang hanya untuk menyampaikan kabar<br />
itu. Tanpa logistik, yang jumlahnya selalu aku perhatikan karena menjadi<br />
penanda lama tidaknya kami akan disandera. Aku merasa bersalah telah<br />
membuatnya sedih, padahal dia datang secara pribadi, dan pasti tidak<br />
peduli dengan segala risiko, khusus untuk membagi kabar bahagia.<br />
Kabar pembebasan.<br />
"Mudah-mudahan Rois segera datang untuk membebaskan kalian,"<br />
kata adik Ahmad sebelum melangkah meninggalkan gua.<br />
"Insya Allah," jawab kami bersamaan. Aku bahkan lupa berterima<br />
kasih atas kedatangannya. Aku kesulitan mencari kalimat yang tepat.<br />
Dadaku masih disesaki rasa haru. Tayangan televisi yang kudengar<br />
dari adik Ahmad menyadar-kanku bahwa begitu banyak pihak yang<br />
berkorban demi keselamatan kami. Keluarga, Presiden, bangsaku, serta<br />
media massa. Adik Ahmad pasti menonton tayangan tadi di saluran<br />
internasional. Sebagai jurnalis televisi, aku paham bahwa pernyataan Presiden<br />
dan keluarga kami pastinya memakan durasi yang tak sedikit.<br />
Padahal, di televisi, waktu sedetik itu sangat mahal. Ternyata prasangka<br />
kukeliru bahwa jaringan televisi internasional Barat enggan memberitakan<br />
keadaanku.<br />
Lama setelah adik Ahmad pergi, kembali terdengar suara mobil.<br />
"Rois datang! Rois datang!"teriak Ibrahim. Entah mengapa dia begitu<br />
yakin yang datang adalah Rois. Penjaga membiarkan saja. Padahal<br />
biasanya, jika ada suara, semua waspada. Setelah melilitkan kafiyeh,dua<br />
penjaga itu segera menyongsong pemimpin mereka. Tak tahan, aku pun<br />
melanggar larangan, mengintip. Benar, mobilnya bagus. Itu pasti Rois.<br />
Kurapikan kerudungku,lalu duduk dengan tegak. Kali ini aku mau terlihat<br />
lebih siap menyambut kabar bahagia itu, tidak seperti siangtadi.<br />
Aku dan Budi saling tatap dan melempar senyum. Akhirnya,
pembebasan itu tiba.<br />
"Assalamu 'alaikum ..." Rois menyapa kami ramah sekali. Aku jadi<br />
menyesal, marah-marah sewaktu bertemu kemarin."<br />
Tolong jelaskan kepada Meutya. Jawaban dari permintaannya<br />
kemarin sudah bisa saya berikan. Sesuai dengan janji kami, kalian akan<br />
bebas segera setelah kami mendapat reaksi dari Indonesia. Hari ini kami<br />
sudah melihat pernyataan dari Presiden Indonesia. Jadi, tidak ada alasan<br />
untuk menahan kalian," kata Rois kepada Ibrahim, yang dengan senang<br />
menerjemahkannya untukaku dan Budi.<br />
"Syukron jazzilan," jawabku dengan bahasa Arab<br />
yang kupungut dari percakapan Ahmad dan Muhammad.<br />
Aku tak kuasa menutupi kebahagiaanku. Budi berkali-kali<br />
mengucapkan kalimat hamdalah sebagai rasa syukur.<br />
Rois lalu berbincang serius dengan Ibrahim. Setelah pembahasan<br />
yang cukup panjang, Ibrahim menjelaskannya kepada kami.<br />
"Rois mengatakan kita sudah bebas. Tetapi, kita harus ambil gambar<br />
lagi. Sebab, ketika kalian diculik, mereka mengeluarkan pernyataan resmi.<br />
Jadi, ketika kalian bebas, juga harus ada pernyataan resmi," kata Ibrahim<br />
dengan hati-hati. Mungkin dia mengerti, setelah dinyatakan bebas, waktu<br />
satu jam pun bisa terasa lama bagi orang terpenjara.<br />
"Mafi muskila, no problem," jawabku ke arah Rois, lagi-lagi dengan<br />
memungut kata-kata Arab yang pernahkudengar.<br />
Waktu menunggu kedatangan juru kamera, kamimanfaatkan untuk<br />
berkemas.Budi bersenandung riang. Berkemas adalah pertanda pulang.<br />
Kata yang kamidamba selama hampir sepekan.<br />
Di luar gua, matahari masih berada di atas kepalakami dengan<br />
sinarnya yang menyengat. Aku dan Budi tetap bersemangat mengikuti<br />
sesi pengambilan gambar. Berbeda dengan pengambilan gambar<br />
terdahulu, kali ini kami lebih rileks. Aku dan Budi telah siap di lokasi, tepat<br />
di sisi kanan gua, dengan latar belakang yang sama dengan rekaman<br />
pernyataan penculikan. Aku juga lebih bebas memandang siapa-siapa<br />
saja yang hadir. Rombongan kali ini<br />
lebih ramai. Banyak yang tidak menutup muka dengan kafiyeh. Gaya<br />
mereka terlihat santai, dengan celana dan baju yang terkesan modern,<br />
yang kadang terlihat di balik mantel musim dingin (winter-coat) mereka.<br />
Wajah mereka pun rapi dan bersih. Tak seperti Ahmad dan Muhammad.<br />
Seorang penjaga berkafiyeh, tanpa senjata, mendekati kami. Dia<br />
berdiri di sebelah Budi, memegang secarik kertas catatan yang berkalikali<br />
dia latih hafalkan. Mujahidin lainnya lalu berkumpul mendekati posisi<br />
juru kamera. Selama menunggu persiapan, aku bebas mengobrol<br />
dengan Budi.<br />
"Mas, aku sudah cantik belum?" bisikku pada Budi, sambil meminta<br />
Budi memerhatikan pas atau tidaknya letak kerudungku. "Masa<br />
komposisinya saja yang bagus, objeknya juga harus dong."<br />
"Lebih cakep daripada kalau mau siaran di kantor, kok."<br />
Aku melotot. Jelas saja Budi menyindir. Sudah enam hari aku tidak<br />
mandi. Selama itu pula aku tak pernah berkaca. Melihat tampang Budi<br />
yang amburadul, aku yakin penampilanku juga sama hancur.<br />
"Aku gimana, Mut?" balas Budi sambil melepas kupluknya.<br />
"Ganteng, Mas, tenang aja," jawabku sambil menahan geli. Rambut
Budi yang gondrong terlihat berantakan karena tidak dicuci dan disisir<br />
selama sepekan.<br />
"Pakai kupluk lebih keren, deh," usulku karena tak tega melihat<br />
rambutnya.<br />
"Pokoknya kita harus keren, Mut. Kita kan masuk<br />
CNN," kata Budi tertawa.<br />
Nyaris saja tawaku lepas. Aku sadar betapa beruntungnya aku<br />
berpasangan dengan Budi ketika menghadapi musibah ini. Budi, yang<br />
apa adanya, selalu berusaha membuatku tersenyum pada saat tersulit<br />
sekali pun. Cara pikirnya tidak rumit dan melihat persoalan dari titik<br />
pandang yang berbeda dariku.<br />
Suasana yang jauh dari tegang membawa pikiranku melayang ke<br />
rumah. Gambaran nikmatnya tidur di atas kasur empuk bergantian<br />
dengan bayangan wajah Mama, kakak-kakakku, serta kerabatku. Pasti<br />
seru sekali kalau kami bertemu nanti. Tak berhenti di situ. Aku juga<br />
membayangkan sepiring nasi dengan lauk semur bikinan Mama, lengkap<br />
dengan kerupuk. Tak ketinggalan bakso, pempek, dan tentu saja steak,<br />
makanan favoritku.<br />
Belum berhenti, aku juga sudah membayangkan keramaian mal,<br />
menghabiskan waktu bersama saha bat-sahabatku di kafe. Juga,<br />
nikmatnya pijatan tukang lulur langgananku. Dua hari lalu, di tengah keputusasaanku,aku<br />
sempat merasa bahwa hidup dan dunia bukan<br />
lagihakku. Detik demi detik yang terbayang adalah bertemusang Pencipta.<br />
Hari ini semua berbalik. Keindahan duniawi kembali menghiasi<br />
pikiranku. Padahal, kami belum seutuhnya bebas. Padahal pula, selama<br />
di gua, sebenarnya aku sudah mulai terbiasa hidup tanpa ponsel, yang<br />
disitaoleh penculik.<br />
Sebelum penyanderaan, di tengah kesibukan kerjaku, biasanya<br />
tanganku nyaris tak pernah lepas<br />
dari ponsel. Teknologi informasi memang membawa<br />
banyakkebaikan, tetapi membuat kita, manusia, menjadi<br />
sangatbergantung padanya. Satu-dua hari di gua aku merasa janggal<br />
tanpa ponsel. Tetapi lama-kelamaan, ternyata bukan masalah (padahal<br />
kalau di Jakarta sepertinya satu jam saja tak ketemu ponsel, semua jadi<br />
serba susah), bahkan aku mulai bisa menikmati hari-hari tanpa<br />
ponsel.Aku jadi lebih konsentrasi dengan lawan bicara dan memberikan<br />
perhatian penuh pada orang-orang di sekitarku, yang akhirnya membuat<br />
aku dalam waktu singkat dapat mengenal dengan baik dan pada level<br />
tertentu memahami para penculik. (Berbeda sekali dengan pertemuanku<br />
dengan orang-orang di acara "kumpul-kumpul" di Jakarta, kalaupun<br />
menghabiskan waktu bicara cukup lama, jarang tercapai saling<br />
memahami.)<br />
Putusnya komunikasi juga memberiku banyak waktu untuk<br />
berkomunikasi tidak hanya dengan para penculik,tetapi juga dengan diri<br />
sendiri/batin. Setelah sekian lama"tidak sempat", pantas aku kadang sulit<br />
memahami diri sendiri.<br />
"Siap!" Juru kamera memberikan aba-aba. Keheningan membuat<br />
suasana kembali tegang. Jurukamera menghitung mundur dengan kode<br />
jari. Aku menghela napas panjang untuk menenangkan diri agar tampak<br />
rileks di depan kamera. Ketika sampai pada hitungan "satu", lampu merah
di kamera menyala, tanda rekaman dimulai. Mujahidin di sebelah Budi<br />
mendekat, tangan kanannya merangkul pundak Budi. Tangan kirinya<br />
mengangkat<br />
secarik kertas catatan. Dia lalu mulai membaca dengan suara<br />
lantang pernyataan dalam bahasa Arab, yang kalau diterjemahkan adalah<br />
sebagai berikut.<br />
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilala min. Atas dasar<br />
pertimbangan nurani dan rasa persaudaraan para anggota tentara<br />
Mujahidin, tibalah waktunya bagi kami untuk membebaskan dua wartawan<br />
Indonesia, meiihat perilaku dan niat tulus yang telah ditunjukkan kedua<br />
wartawan ini. Dan karena menghormati hubungan baik dan rasa<br />
persaudaraan antar kedua bangsa. Serta mengingat sikap Indonesia yang<br />
menentang agresi ke Irak. Selama ini kami memperlakukan kedua<br />
wartawanini dengan baik dan penuh rasa hormat. Atas semua<br />
pertimbangan tersebut, dengan ini kami memutuskan pembebasan<br />
kedua wartawan Indonesia, tanpa syarat apa pun. Wallahuakbar.<br />
Mujahidin.<br />
Kamera kemudian diarahkan kepada Budi. Seorang Mujahidin<br />
mendekat. Dia menyerahkan Al-Qur an kepada Budi. Setelah berjabatan,<br />
secara refleks Budi mengangkat Quran dan menciumnya. Para Mujahidin<br />
seperti kaget dengan aksi tersebut. Kamera dimatikan. Mereka lalu<br />
berdiskusi ramai.<br />
Aku dan Budi kebingungan. Jangan-jangan mereka tidak setuju<br />
dengan reaksi Budi. Kulihat muka Budi menjadi tegang.<br />
"Mut, jangan-jangan kita mau dites baca Quran. Gawat ini!" bisik Budi<br />
dengan raut muka begitu khawatir.<br />
"Bukan, Mas. Mungkin mereka surprise dengan reaksi Mas," kataku<br />
menghibur.<br />
Juru kamera mendekati Budi. Budi semakin pucat. Mereka<br />
menjelaskan dalam bahasa Arab. Lalu Mujahidin lain berteriak, "More...<br />
more." Rupanya, mereka ingin Budi mengulang "adegan" mencium Al-<br />
Quran tadi. Saking leganya, karena kekhawatirannya tidak terbukti, Budi<br />
mencium Al-Quran berkali-kali. Para Mujahidin yang ikut menonton<br />
tergelak. Selain hadiah Al-Quran, Budi juga diberi beberapa batang siwak,<br />
tasbih, dan kopiah. Spontan kupluk lusuhnya dilepas, berganti dengan<br />
kopiah. Dengan Al-Quran dan tasbih di tangan, serta kopiah di kepalanya,<br />
Budi benar-benar terlihat seperti seorang ustad.<br />
Kini, kamera berganti menghadap ke arahku. Rupanya mereka<br />
membutuhkan penjelasan lebih buatku. Ibrahim, yang ada di dalam gua,<br />
dipanggil keluar.Ibrahim menjelaskan kepadaku bahwa Mujahidin yang<br />
akan memberikan buah tangan meminta agar tangan kami tidak boleh<br />
bersentuhan sedikit pun. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. "Ini<br />
serius, Meutya. Jika dilanggar, bisa-bisa pembebasan kita terganggu."<br />
Kamera berputar. Pemberian pertama Al-Quran, langsung kudekap<br />
erat. Lalu siwak dan tasbih, yang semuanya kugenggam dengan tangan<br />
kananku. Rupanya masih ada satu hadiah lagi, yaitu kerudung<br />
bercorak putih biru yang terlipat rapi. Aku panik, harus mengambil<br />
dengan tangan yang mana. Tangan kananku sudah penuh, sementara<br />
mengambil dengan tangan kiri bukan adab yang baik dalam Islam. Mau<br />
menaruh Al-Quran di pasir, urusan bisa panjang. Seperti kata Ibrahim tadi,
pembebasan bisa terganggu.<br />
Akhirnya, aku minta Mujahidin tersebut meletakkan saja kerudung di<br />
atas Al-Quran. Toh hanya untuk kepentingan pengambilan gambar, berarti<br />
tidak lama.<br />
Ternyata aku keliru. Mereka ingin aku memakai kerudung pemberian<br />
itu. Karena sudah memakai kerudung, aku sampirkan saja di bahu.<br />
Tidak, mereka mau aku memakainya. Budi, yang sudah selesai<br />
dengan "adegan"nya melirik ke arah ku. Dia tampak ingin membantu,<br />
tetapi khawatir karena kami tidak boleh bersentuhan. Mimiknya serba<br />
salah. Aku bertambah panik ketika upayaku memakai kerudung dengan<br />
satu tangan digagalkan angin kencang yang tiba tiba bertiup.<br />
Syukurlah, mereka menyadari kesulitanku, dan menghentikan<br />
shooting.<br />
Dalam hati aku berteriak, aku bebas!<br />
Aku, Budi, dan Ibrahim kembali ke dalam gua. Kamikembali menata<br />
barang-barang untuk memastikan tidakada yang tertinggal. Kamera,<br />
laptop, dan barang-barang mudah pecah kami kumpulkan sendiri agar<br />
tidak terganggu oleh koper dan barang berat lainnya. Atas nasihat Ibrahim,<br />
kami juga mengumpulkan sampah agar gua kembali bersih. Menurutnya,<br />
itu adab seorang tamu yang baik. Ah, siapa yang sedang<br />
bertamu, kami disandera, kok. Ibrahim menambahkan, nanti jika ada<br />
korban penculikan lain, gua sudah siap pakai.Alasan yang menggelikan.<br />
Dalam hati aku berharap, jangan lagi ada orang, apalagi jurnalis, yang<br />
harus mengalami apa yang kami jalani.<br />
Rois menyusul masuk. Aku tersenyum, menunjukkan bahwa kami<br />
siap berangkat.<br />
Tetapi, dia langsung mendekati Ibrahim. Mereka berbincang serius.<br />
Daripada menunggu pembicaraan, aku pamit keluar gua untuk sikat gigi<br />
dan membasuh muka. Ini ritual yang biasa aku lakukan sebelum siaran<br />
agar terlihat segar. Siapa tahu, di perbatasan Irak-Yordania nanti sudah<br />
banyak yang menunggu. Kasihan mereka kalau sampai terganggu<br />
dengan bau kami. Aku menyeka wajah yang sudah seminggu tak pernah<br />
disapu make-up. Hmm ... tak lama lagi aku akan kembali menikmati<br />
tangan profesional yang selalu berusaha membuat aku tampil cantik.<br />
Rambutku yang kini dipenuhipasir gurun akan kumanjakan dengan<br />
creambath danblow dry.<br />
Aku kembali masuk. Wajah Ibrahim keruh. Muka Budi, yang tadi<br />
berseri-seri, tidak lagi tersenyum.<br />
Sebelum aku sempat bertanya, Ibrahim langsung menjelaskan.<br />
"Meutya, ada masalah. Kita batal pulang hari ini."<br />
Aku seperti dihantam badai pasir. Badanku, yang sesaat lalu terasa<br />
penuh energi, mendadak lemas.<br />
"Kenapa lagi?" tanyaku kepada Ibrahim. Aku juga<br />
memandang Rois. Kenapa orang ini selalu menunda<br />
pembebasanku? pikirku.<br />
"Mobil GMC kita harus diambil terlebih dahulu darisebuah tempat. Itu<br />
makan waktu dua jam. Berarti matahari mulai terbenam. Mereka tidak mau<br />
kita dalam bahaya dengan berjalan di waktu malam," kata Ibrahim.<br />
Aku memahami logika Ibrahim, tetapi tak bisa menerima cara Rois.<br />
Mengapa dia tidak menyiapkan mobil itu, seperti dia menyiapkan
pengambilan gambar? Mengapa dia tega memainkan perasaan dan<br />
harapan kami? Apa lagi yang dimaui kelompok ini? Sederet<br />
pertanyaanberbaur dengan kemarahan ber tubi-tubi menikam kepalaku.<br />
Tetapi, aku diam saja, tak mendebat. Aku lelah. Percuma saja bertanya.<br />
Aku terlampau kecewa kepada Rois. Kupikir, dia dan anggotanya tidak<br />
layak dipercaya. Seharusnya, aku tidak terbius dengan janji-janji manis<br />
mereka. Simpatiku terhadap kelompok ini turun drastis. Kepercayaanku<br />
juga terhapus seketika.<br />
Rois sendiri tampaknya tidak merasa bersalah. Diamalah bertanya<br />
dengan nada datar. "Jadi bagaimana? Apa kalian sudah memutuskan<br />
kembali ke Yordania petang ini juga, atau menginap semalam lagi di<br />
gua?"<br />
Aku malas menanggapi pertanyaan basa-basi<br />
ini.<br />
"Terserah Ibrahim," jawabku pendek.<br />
"Saya rasa besok lebih baik," jawab Ibrahim, seperti dugaanku. "Rois<br />
sudah berjanji akan mengantar mobil pagi-pagi sekali," lanjut Ibrahim.<br />
Apa jaminannya besok mobii itu datang iebih awai? Toh, selama ini<br />
sudah berbilang kali, mereka mangkir dari janji. Selalu berjanji besok,<br />
besok, dan besok.Nyatanya, sepekan juga kami di gua ini. Bahkan, ketika<br />
pernyataan Presiden datang, kami tetap tertunda pulang.<br />
"Ya sudahlah, mau bagaimana lagi," kataku sengit.<br />
Sulit menerima keadaan, harus menginap satu malam lagi, pada<br />
saat pintu kebebasan sudah di depan mata. Meutya, seminggu yang berat<br />
saja sudah kamu lewati, apa susahnya melewatkan satu malam lagi? Aku<br />
menghibur diri. Padahal, jangankan satu malam, satu jam lagi saja sudah<br />
berat buatku. Hari ini pergerakan mobil ke lokasi penculikan banyak dan<br />
berulang. Siapa yang bisa menjamin, justru setelah dibebaskan penculik,<br />
kami lalu mati di tangan pasukan koalisi. Pernyataan bebas sudah<br />
direkam. Kalau ada apa-apa, penculik bisa saja menyatakan kami sudah<br />
bebas dalam keadaan sehat. Selanjutnya, keselamatan bukan tanggung<br />
jawab mereka. Kini, kami ibarat mangsa yang siap diburu oleh berbagai<br />
pihak.<br />
"Sampai jumpa besok pagi, assalamu 'alai kum."Rois pamit.<br />
Aku menjawab salam, tetapi tak sudi melihat wajahnya. Aku juga tak<br />
mau membahas soal ini dengan Ibrahim karena dia terlihat rikuh<br />
mengetahui kami sangat kecewa dengan keputusan Rois. Aku memilih<br />
meringkuk di balik selimut yang kutarik hingga menutup wajah. Aku juga<br />
sengaja membalik badan<br />
membelakangi Ibrahim. Aku lihat Budi juga melakukan hal yang<br />
sama.<br />
"Meutya ... jam segini kok sudah mau tidur," tanya Ibrahim.<br />
Aku hanya mendehem, menunjukkan aku sudah bersiap tidur.<br />
"Ayolah, ini hari terakhir kita di gua, dan kita sudah bebas. Mari kita isi<br />
dengan perayaan. Bukan dengan tidur." Ibrahim mencoba membujuk.<br />
Aku tak menanggapi. Budi pun tidak terdengar menjawab. Aku dan<br />
Budi merajuk.[]<br />
Bab 9<br />
Pembebasan yang Berliku<br />
PERBINCANGAN Ibrahim dengan si Jangkung membuatku susah
memejamkan mata. Apalagi, ketika mencoba berangkat tidur tadi, aku<br />
memang belum mengantuk. Ditambah pula suasana hati yang tidak enak.<br />
Suara Ibrahim malam ini lebih keras dibandingkan biasa. Mungkin dia<br />
berupaya membuat suasana lebih cair. Sepertinya kedua penjaga itu juga<br />
kikuk melihat aksi diam kami. Karena ukuran gua yang kecil, perasaan<br />
dan kegundahan cepat menular di antara sesama penghuni.<br />
Dengan menyibakkan selimut sedikit, aku mengintip. Si Jangkung<br />
terlihat gelisah. Berkali-kali dia berdiri, lalu keluar gua menenteng senjata.<br />
Kadang sebentar, tetapi kadang agak lama baru dia muncul lagi.<br />
Aku ikut gelisah. Bosan pura-pura tidur, aku putuskan untuk duduk<br />
saja. Tiada guna merajuk pada saat seperti itu. Toh tidak mengubah<br />
kondisi, malah menjadikan suasana semakin tidak nyaman. Tak lama<br />
Budi juga bergabung.<br />
"Ada apa dengan si Jangkung?" tanyaku pada<br />
Ibrahim. Ibrahim menggelengkan kepala.<br />
"Kenapa dia mondar-mandir membawa senjata lengkap?" Aku terus<br />
mencari tahu.<br />
"Saya tidak tahu, tetapi yang jelas pasti ada sesuatu di luar sana.<br />
Mungkin dia membaca situasi bahaya."<br />
"Bahaya bagaimana?"<br />
"Yang jelas, terlalu bodoh keluar gua di udara dingin begini. Pasti ada<br />
alasan kuat di balik itu." Suara Ibrahim terdengar cemas.<br />
Aku masih ingin bertanya. Kurasa Ibrahim tahu sebab si Jangkung<br />
selalu pamit padanya saat hendak keluar gua. Keinginanku bertanya<br />
terputus dengan masuknya si penjaga. Ibrahim menatapku. Sorot<br />
matanya menunjukkan dia tidak menginginkan pembicaraan lanjutan,dan<br />
berharap aku cukup pandai untuk memahami situasi. Aku segera<br />
menyimpulkan: pasti daerah ini sudah diketahui musuh. Tetapi, kenapa si<br />
Jangkung perlu waktu begitu lama melihat situasi di luar gua? Apa yang<br />
dialihat? Bukankah sejauh mata memandang yang tampak hanya gurun?<br />
Tak cuma bersenjata, si Jangkung juga menutupi wajahnya dengan<br />
kafiyeh. Aku berharap dia melakukannya hanya karena dia tak kuat<br />
menahan dingin. Lagi-lagi si Jangkung melesat keluar gua.<br />
Daripada menunggu di tengah ketidakpastian, kami menyantap<br />
kebab. Ibrahim makan tanpa semangat. Aku tak mau bertanya. Tetapi, aku<br />
berusaha membuat suasana lebih santai. Pertemanan di tengah<br />
kesulitan membuat kami pintar membaca situasi.<br />
Ketika aku sedang "tinggi", Ibrahim mampu mengatur keseimbangan<br />
emosi. Hanya Budi yang relatif selalu tenang. Kini, kulihat Ibrahim perlu<br />
bantuan untuk mengimbangi emosi dan perasaannya.<br />
"Sedang membayangkan ketemu keluarga, ya?" godaku.<br />
Namun, Ibrahim menjawab datar. "Meutya, kamu dengar suara<br />
pesawat tempur dan helikopter? Belakangan suara itu semakin sering<br />
muncul. Artinya, kawasan ini sudah tidak aman."<br />
"Ya, aku dengar, tetapi mereka kan tidak melihat kita." Aku mencoba<br />
tenang meski membenarkan ucapan Ibrahim. Padahal, aku takut<br />
setengah mati. Peluru tidak bisa membedakan mana Mujahidin mana<br />
wartawan.<br />
"Kalau kita masih bersua dengan hari esok, danbisa bertemu<br />
keluarga, kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah," tambah Ibrahim.
"Kita tetap harus meyakini bisa melewati malam ini,Ibrahim. Hanya<br />
satu malam lagi," jawabku, se olah-olah menyemangati Ibrahim saja.<br />
Padahal, itu juga usahaku menghibur diri sendiri. Aku juga sudah sangat<br />
letih, menghitung malam, menghitung pagi, dalam kondisi tertekan dan<br />
tidak pasti seperti ini.<br />
Ucapan Ibrahim, kalau kita masih bersua deng-man hari esok, begitu<br />
meresap di hatiku. Hanya kuasaNya yang kini kunanti. Pekan lalu, ketika<br />
mobil kami disergap, aku menganggap dan menerima detik itu sebagai<br />
akhir hidupku. Ketika batinku dilanda ketakutan luar biasa, menghadapi<br />
tiga lelaki kekar bersenjata yang menyekapku di tempat terasing jauh<br />
dari peradaban, akal dan fisikku hanya bisa pasrah menerima<br />
yang terburuk. Namun, Yang Maha Menjaga punya rencana lain. Nyatanya,<br />
aku masih melihat hari esoknya. Nyatanya, bukan penganiayaan ataupun<br />
pelecehan yang aku terima, melainkan sikap bersahabat dan kelembutan<br />
serta kesantunan sikap. Ketika udara dingin dan angin gurun yang kering<br />
terus menerpa, meski tanpa selimut memadai, mimisan (penyakit<br />
bawaanku sejak kecil) tak pernah terjadi. Subhanallah.<br />
Malam terus merayap. Cahaya lampu terasa kian suram dan dingin<br />
malam gurun semakin menusuk. Si Jangkung belum juga kembali. Deru<br />
pesawat tempur melecut suasana menjadi semakin mencekam. Nun<br />
dilubuk hati, aku berdoa.<br />
Tuhan, apakah Kau masih menghendaki kami hidup? Jika iya,<br />
kenapa begitu suiit perjalanan kami untuk bebas? Jika tidak, kenapa tidak<br />
Kaumatikan saja kami dari awal penculikan ?<br />
Apakah peristiwa ini Kau tunjukkan agar aku tersadar sebelum<br />
Kauambil nyawaku, sesaat lagi?<br />
Apakah malam ini dapat aku lalui dengan selamat seperti malammalam<br />
sebelumnya? Jika iya, tunjukkan padaku.<br />
Tuhanku, agar cerita ini dapat aku bagi dengan saudara-saudaraku di<br />
tanah air, cerita tentang indahnya kebersamaan seorang manusia dan<br />
Sang Pencipta, justru<br />
di dalam kondisi yang serba terbatas dan jauh dari kenikmatan<br />
duniawi...jangan jadikan malam ini malam terakhirku di bu mi-Mu.<br />
Tuhanku... beri aku kesempatan berbagi cerita ini agar menjadi cerita dan<br />
kenangan indah, tidak hanya bagiku, tetapi bagi semua. Beri aku<br />
kesempatan berbakti dan kembali ke tanah airku...<br />
"Siyarra!" Ibrahim setengah berteriak. Aku menatap Ibrahim.<br />
"Kenapa malam begini ada mobil yang datang?" Ibrahim melongok<br />
lewat celah gua, melihat suasana diluar. Raut mukanya khawatir. Belum<br />
pernah sekali pun mobil para Mujahidin datang malam begini.<br />
Di tengah kebingungan berbaur ketakutan, si Jangkung setengah<br />
berlari menerobos masuk. "Cepat keluar! Cepat keluar!" teriaknya.<br />
Dia tak sendirian. Di belakangnya ada kepala wilayah kelompok<br />
pergerakan. Dia pernah mampir ke gua bersama pengantar logistik.<br />
Mereka berdua terlihat tergesa. Melihat kepanikan mereka, aku tak<br />
mendebat atau bertanya. Aku langsung berdiri mengambil barang-barang<br />
yang mampu ku jinjing. Budi dan Ibrahim pun demikian. Dibantu kepala<br />
wilayah dan dua penjaga, kami membawa semampu dan secepat<br />
mungkin. Kami berlari keluar gua. Barang ditumpuk di bagasi sekenanya.<br />
Kami pun berebutan masuk ke sedan tua milik kepala wilayah Ramadi
tersebut. Ketika aku mau melangkah, kepala wilayah<br />
menahanku.<br />
"Tunggu! Ibrahim, pinjamkan jubahmu," ucapnya meminta Ibrahim<br />
melepaskan overcoat-nya.<br />
"Terlalu besar," aku menolak.<br />
"Pakai saja!" desak Ibrahim. Tanpa menunggu perintah<br />
berikutnya, aku langsung mengenakan jaket Ibrahim. Jaket itu<br />
sedemikian besar sehingga hampir menutup seluruh tubuhku, dari<br />
leherhingga betis.<br />
"Lilitkan ini," kata Ibrahim sambil meletakkan kafiyeh di kepalaku.<br />
Kepala wilayah terus memberikan perintah lain lewat Ibrahim.<br />
Belum sempurna aku menutup kepala dan wajah, aku sudah<br />
didorong masuk ke mobil. Mobil pun langsung dipacu kencang sebelum<br />
pintu tertutup rapat. Raungannya membelah gurun yang senyap dan<br />
gelap.<br />
"Apakah aku harus menutup mata dengan kain ini?" tanyaku sambil<br />
merapikan kafiyeh.<br />
"Seperti ini, Meutya!" Yang menjawab adalah Mujahidin yang menyetir.<br />
Aku mengenali suaranya: Muhammad. Aku bersorak dalam hati. Di<br />
tengah kepanikan, ternyata Muhammad ikut menjaga. Aku menahan diri<br />
untuk berbicara. Seminggu disekap, belum pernah aku melihat suasana<br />
panik di kalangan penculik. Apa sebenarnya yang terjadi?<br />
Aku duduk di belakang bersama Ibrahim dan Budi. Muhammad<br />
memegang kemudi. Kepala wilayah dan si Jangkung berdesakan di jok<br />
depan, yang lazimnya untuk satu orang. Untung satu pengawal lain<br />
ditinggal di gua. Jika tidak, pasti mobil tua ini akan makin keberatan<br />
beban. Enam penumpang dan barang-barang, termasuk alat-alat<br />
peliputan yang berat, membuat mobil terseok-seok. Tetapi, kepala wilayah<br />
tidak peduli. Dia meminta gas terus ditancap. Jadilah suara mesin<br />
meraung-raung di tengah sunyinya gurun. Aku menatap ke luar<br />
jendela.Kami berjalan tanpa penerangan lampu mobil, untuk menghindari<br />
pantauan udara. Untunglah langit sedang bertabur bintang. Maha besar<br />
Engkau ya Allah, malam begitu indah. Pendar-pendar cahaya bintang<br />
membuat gurun begitu eksotis.<br />
Mobil terus dipacu seolah-olah ada yang mengejar.<br />
Braakk! Mobil terantuk keras, sampai-sampai kepalaku nyaris<br />
menghantam jok depan. Mesin mobil mati. Si Jangkung dan Ibrahim<br />
segera turun. Rupanya, mobil terantuk batu besar. Ibrahim, sopir yang<br />
biasa menangani mobil, meneliti kerusakan.<br />
"Astaghfirullah, bensin bocor," Ibrahim menepuk jidatnya.<br />
Lengkap sudah! Aku semakin pasrah. Hanya kuasa-Nya yang bisa<br />
menyelamatkan kami keluar dari gurun dengan tangki bensin yang bocor.<br />
"Ayo ... ayo segera masuk ...," perintah kepala wilayah.<br />
Mobil kembali dihidupkan.<br />
Namun, upaya men-starter gagal.<br />
Beberapa kali mobil dicoba dinyalakan, tetapi gagal dan gagal lagi.<br />
"La haula wala quwwata ilia billah," seru si<br />
kepala wilayah, yang secara refleks kami ikuti bersama. Tiada daya<br />
dan kekuatan kecuali dengan izin Allah.<br />
Hening sesaat. Disertai ucapan basmalah, mesin kembali coba
dihidupkan. Berhasil. Mesin menderum.<br />
Inikah pertanda Engkau masih menyayangiku? Mobil dipacu, khawatir<br />
tabung bensin yang bocor semakin terkuras. Jujur saja, ini lebih<br />
menegangkan dibandingkan saat penculikan. Semula, ketika kami<br />
diminta keluar dari gua, aku tak tahu apa yang terjadi. Tetapi sekarang,<br />
aku paham bahwa, kalau mau selamat, yang pertama kali harus dilakukan<br />
adalah keluar dari kegelapan gurun. Apalagi tadi, sebelum mobil datang,<br />
si Jangkung sudah kelihatan sangat gelisah.<br />
"Mereka tahu pasukan infanteri mendekat ke lokasi gua kita," bisik<br />
Ibrahim.<br />
Aku senang Ibrahim memberitahuku setelah di kejauhan aku melihat<br />
cahaya lampu, tetapi takutku tak luntur. Di sebelahku, Budi terus<br />
mendaras doa dengan wajah tegang. Dia berzikir tiada putus,<br />
menggunakan tasbih pemberian Mujahidin sore tadi.<br />
Pepohonan mulai tampak. Lalu, pagar-pagar pembatas, seperti<br />
pembatas daerah perkampungan. Setelah melewati pagar, kami pun<br />
sampai di perkampungan. Aku mulai melihat rumah. Tetapi, Ibrahim<br />
memintaku tidak usah banyak melihat ke luar, dan lebih baik merunduk.<br />
Aku menurut. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilihat dikegelapan.<br />
Pekarangan rumah warga rata-rata hanya diterangi lampu yang temaram.<br />
Mobil lalu berbelok, memasuki gang kecil. Tibalah kami di sebuah<br />
rumah berpagar kayu. Ukurannya cukup besar. Warnanya hijau, warna<br />
kesukaanku. Aku menyukai tempat ini. Entah karena warnanya, entah<br />
karena sudah lama aku tak melihat rumah. Apakah kami akan disekap<br />
lagi?<br />
"Meutya, turun! Cepat berjalan menuju pintu itu,"Ibrahim<br />
menerjemahkan perintah Mujahidin. Pintu yang ditunjuk berada di sebelah<br />
kanan rumah. Itu pintu bangunan yang terpisah dari rumah utama. Seperti<br />
paviliun. Aku turun dan berlari kecil.Senang rasanya bisa mendorong pintu<br />
lagi. Aku menyapu pandang ke ruangan besar itu. Tidak ada kursi. Ruang<br />
itu beralas karpet dan dilengkapi bantal duduk. Khas Arab. Budi dan<br />
Ibrahim menyusul masuk. Kami saling pandang dan tersenyum penuh<br />
arti. Gerbang pembebasan telah kami lewati. Gua yang sempit berganti<br />
ruangan besar. Tak ada lagi alas tidur plastik. Langit-langit yang tinggi ikut<br />
membuatku senang. Biasanya, semua serba sumpek dan sempit. Aku<br />
duduk di salah satu pojok. Budi dan Ibrahim di pojok lain. Rasanya kami<br />
jauh sekali. Selama ini, tidur pun kakiku menyenggol kepala Budi.<br />
Kurebahkan badanku tanpa dipersilakan. Nyaman sekali. Tidak ada<br />
pasir atau batu yang menu suk-nusuk tubuh. Kutarik bantal ke arah<br />
kepalaku. Aku bahkan sudah hampir lupa nikmatnya tidur dengan bantal.<br />
"Wuenak, empuk ya, Mut." Budi tersenyum menikmati<br />
bantalnya.Ibrahim juga tertawa.<br />
"Iya Mas, ini baru oke. Coba dari kemarin-kema<br />
rin.<br />
"Kami hanya bertiga di ruangan tersebut. Sambil leyah-leyeh<br />
menikmati kemewahan bantal dan alas tidur yang empuk, samar-samar<br />
terdengar suara a-nak kecil menangis. Makin lama tangisannya semakin<br />
keras.<br />
"Ini baru kehidupan," kata Ibrahim tertawa.
Maklum, selama disandera di gurun, kami tidak pernah mendengar<br />
suara makhluk hidup lain di luar suara kami sendiri, kecuali<br />
satu:tikus.Suara lain hanya mesin mobil, pesawat, dan helikopter.<br />
"Ibrahim, rumah siapa ini?"<br />
Ibrahim menggeleng. "Mungkin tempat mereka biasa berkumpul.<br />
"Pintu terbuka. Kepala wilayah masuk bersama Muhammad. Ahmad<br />
ternyata turut serta. Dia terlihat jauh lebih bersih, baik wajah maupun<br />
pakaiannya. Aku nyaris tak percaya bisa bertemu mereka lagi. Ahmad<br />
tersenyum, lalu mengambil tempat di sisi ruangan berseberangan<br />
denganku. Kepala wilayah duduk dekat Ibrahim di bagian tengah ruangan.<br />
Mungkin karena ada pemimpinnya, Ahmad dan Muham mad sungkan<br />
terlihat akrabdengan kami.<br />
"Besok pagi kalian akan berangkat pulang dari rumah ini. Mobil akan<br />
siap pukul delapan. Kami janji, tidak akan ingkar," kata kepala wilayah<br />
membuka percakapan.<br />
Dia lalu menyodorkan sebuah kantong plastik.<br />
"Ini barang-barang kalian kami kembalikan. Tolong diperiksa apa ada<br />
kekurangan," lanjutnya.<br />
Kami mengeluarkan telepon seluler kami. Bukan hendak memeriksa,<br />
tetapi karena senang, pertanda kebebasan semakin besar.<br />
"Kalau tidak ada masalah, silakan istirahat.<br />
"Kepala wilayah berdiri untuk undur diri. Tetapi, Muhammad dan<br />
Ahmad masih di dalam ruangan. Rupanya kepala wilayah meminta agar<br />
kami, walau sudah dinyatakan bebas, tetap dijaga. Tetapi kali ini, tidak lagi<br />
dengan senjata.<br />
"Ahmad, ceritakan apa yang terjadi tadi," Ibrahim memohon.<br />
Ahmad dan Muhammad bercerita bergantian. Seperti biasa, aku dan<br />
Budi harus sabar menunggu sampai perbincangan selesai, lalu Ibrahim<br />
menerjemahkan untuk kami.<br />
Rupanya gerak maju tentara Amerika sudah semakin jauh ke<br />
kawasan yang dikuasai Mujahidin. "Itulah yang membuat suara tembakan<br />
bisa terdengar hingga ke gua," terang Muhammad.<br />
Patroli udara semakin sering karena mereka mencurigai mobil yang<br />
mengarah ke gua setiap hari. Bahkan Ahmad bercerita, tadi sore dia ingin<br />
mampir ke gua, tetapi batal karena melihat pasukan tentara semakin<br />
mendekat. Ahmadlah yang melapor kepada kepala wilayah, yang<br />
kemudian memutuskan kami harus dievakuasi mendadak.<br />
"Terlambat lima menit saja, ceritanya akan berbeda," kata Ahmad.<br />
Aku meringis. Kalau tidak karena Ahmad, kami bisa saja mati konyol<br />
di gurun. Andai tentara koalisi menemukan kami bersama penyandera,<br />
kemungkinan<br />
besar kami ikut dihabisi.<br />
"Tuh, Mut, mereka bisa saja membiarkan kita digurun. Mereka<br />
menyabung nyawa lho untuk menyelamatkan kita," Ibrahim kembali<br />
memuji Mujahidin.<br />
Ahmad dan Muhammad tertawa. Ibrahim betul, mereka sudah<br />
membuat pernyataan pembebasan melalui media, jadi bisa saja lepas<br />
tangan jika mau.<br />
"Meutya, tidak ada yang ganggu kan selama kami tidak ada?" tanya<br />
Muhammad kepada Ibrahim. Dia mungkin khawatir si Jangkung bersikap
seperti si Sontoloyo, salah satu penjaga kami pada hari pertama.<br />
"Dia baik-baik saja, hanya rindu saja kepada kalian," canda Ibrahim.<br />
Aku hanya tersipu.<br />
Namun, kami semua senang bisa bersama-sama lagi malam ini. Aku<br />
dan Budi ingin memberikan kenangan. Budi meninggalkan kamera untuk<br />
Muhammad. Aku memberikan jaket dan kaus berlogo Metro TV untuk<br />
Ahmad dan SIM card Irak yang masih berisi pulsa untuk Muhammad.<br />
"Kalau rindu pada aku dan Budi, pakai kartu ini untuk menelepon ya,"<br />
kataku sambil memberikan kartu nama.<br />
Kusodorkan secarik kertas dan pulpen, dan kuminta mereka<br />
menuliskan alamat yang bisa dikontak, tetapi mereka hanya tertawa.<br />
"Meutya, jangan bercanda! Orang pergerakan tidak punya alamat,"<br />
tegur Ibrahim, yang kami sambut dengan tawa bersama.<br />
"Untuk saya mana? Masa cuma Ahmad dan Muhammad yang dapat,"<br />
pinta Ibrahim.<br />
Aku dan Budi saling pandang. Kami lupa. Mengira kami masih punya<br />
waktu bersamanya sebelum bebas nanti. Budi lalu menyodorkan jaket<br />
yang baru saja dia beli di Yordania sebelum kami masuk lagi ke Irak untuk<br />
kedua kalinya.<br />
"Ini hanya cukup untuk anak saya. Tetapi terima kasih, dia pasti akan<br />
senang sekali," ujar Ibrahim, yang memang bertubuh jauh lebih tinggi dan<br />
lebih besar dibandingkan Budi, sambil melipat pemberian itu. Dia tampak<br />
senang menerimanya.<br />
Keharuan menyelimuti pertemuan malam itu. Besok kami akan pergi.<br />
Bisa jadi ini pertemuan terakhir kami.Aku biasa berteman dalam tugas<br />
peliputanku. Banyak di antaranya yang berteman baik hingga kini. Tetapi,<br />
dengan Ahmad dan Muhammad berbeda. Selain berjauhan, mereka tidak<br />
bebas berkomunikasi. Hampir tidak mungkin kami akan bertemu kembali.<br />
Ini betul-betul perpisahan.<br />
Meski lelah, dan memiliki alas tidur empuk, kami terus saja<br />
mengobrol hingga tengah malam. Sampai Muhammad mengingatkan<br />
kami untuk istirahat karena besok kami akan berangkat pagi. Muhammad<br />
berjaga di luar ruangan saja, biar kami beristirahat dengan tenang. Kami<br />
saling mengucapkan salam perpisahan. Ahmad mengingatkanku agar<br />
tidak lupa melambaikan tangan ke arah kamera yang meliput kami nanti.<br />
Jika menontonnya, mereka akan menganggap itu sebagai salam.<br />
Beberapa saat setelah dua penjaga itu keluar, aku sudah terlelap. Aku<br />
tak sabar menunggu matahari terbit. []<br />
Bab 10<br />
Tegang Tiada Akhir<br />
SENIN, 21 Februari 2DD5<br />
Pukul delapan pagi, pintu ruangan diketuk. Kepala wilayah meminta<br />
kami segera berkemas. Kudengar mesin mobil sudah dinyalakan. Dia<br />
memintaku memakai kembali jaket Ibrahim untuk penyamaran. Aku dan<br />
Budi juga harus melilitkan kafiyeh penutup muka.Setelah merasa cukup<br />
aman,kami digiring menuju mobil yang kami gunakan semalam. Kepala<br />
wilayah duduk di belakang setir, didampingi Muhammad. Aku, Budi, dan<br />
Ibrahim duduk di jok belakang. Mobil pun melesat menembus wilayah<br />
perkampungan, melalui jalanan yangtak terlalu besar. Jika berpapasan<br />
dengan mobil lain, laju mobil dipelankan. Lalu, mobil segera digas
kembali,terutama jika bertemu sekelompok pejalan kaki.<br />
"Di sini banyak mata-mata. Itulah kenapa lokasikalian tercium Tentara<br />
Koalisi kemarin malam, karena ada informan. Mereka dibayar dengan<br />
imbalan besar untuk menjual harga diri kepada asing," ujar kepala<br />
wilayah ketus.<br />
"Sekarang, lebih baik kalian menunduk. Aku tidak<br />
mau membuat orang curiga. Wajah kalian sudah di mkenal di televisi.<br />
Berita pembebasan kalian ditayangkan berulang-ulang hampir di semua<br />
televisi," lanjut kepala wilayah, mengingatkan kami.<br />
Cepat sekali rekaman itu tersebar. Berbeda dengan rekaman<br />
pernyataan penculikan yang memakan waktu beberapa hari.<br />
Mobil berbelok ke jalan utama, meninggalkan wilayah<br />
perkampungan.Kepala wilayah mempercepat laju mobil. Di kawasan ini<br />
tank dan humvee pasukan koalisi memang banyak beroperasi. Kami<br />
melewati beberapa pos mereka. Syukurlah mobil kami tak diperiksa.<br />
"Mobil GMC kalian ada di tangan rekan kami. Kita akan bertemu<br />
mereka di suatu tempat," kata kepala wilayah.<br />
Dia menghubungi seseorang dengan ponselnya. Setelah berbicara di<br />
telepon, dia membelokkan mobil secaram mendadak ke arah bangunan<br />
tua yang kosong. Bersama Muhammad, dia keluar dari mobil ke arah jalan<br />
raya.<br />
"Ada apa lagi ini?" tanyaku pada Ibrahim.<br />
"Ada miskomunikasi dengan kelompok pembawa GMC. Mereka tak<br />
jelas berada di mana.<br />
"Oh, kenapa ketegangan belum juga usai? Kulihat kepala wilayah<br />
berbicara melalui ponsel sambil mondar-mandir. Wajahnya kesal dan<br />
bingung. Muhammad berjaga di tengah jalan untuk memastikan tidak ada<br />
yang membuntuti kami.Rautnya juga tampak tegang.<br />
"Kita akan pindah meeting point. Di sini terlalu<br />
berbahaya," kata kepala wilayah sekembalinya ke belakang kemudi.<br />
Keputusan yang melegakan. Sisa-sisa kehancuran bangunan tua ini<br />
akibat serangan bom membuatku tak nyaman berlama-lama di sini. Mobil<br />
kembali melaju dan berhenti di sebuah restoran yang cukup besar. Ada<br />
beberapa mobil yang parkir di depan restoran.<br />
"Kenapa ke tempat ramai begini? Mana bisa makan kita?" bisikku<br />
pada Ibrahim.<br />
Ibrahim hanya menggelengkan kepala.<br />
"Kita akan menunggu di sini. Restoran ini milik salah satu dari kami.<br />
Tempat ini aman," kata kepala wilayah.<br />
Muhammad tak banyak bicara. Namun, dia ikut mengantar kami<br />
masuk ke restoran, melalui pintu samping. Ada tirai kain panjang yang<br />
memisahkan kami dengan pengunjung lain sehingga mereka tak dapat<br />
melihat kami.<br />
"Mungkin kita masih harus menunggu agak lama. Kalian sarapan<br />
saja yang kenyang," kata kepala wilayah lagi.<br />
Saran yang aneh, memangnya lagi pelesir! Aku ingin secepatnya<br />
bebas. Aku tak butuh sarapan!<br />
Tak berapa lama kemudian, makanan datang. Dua tusuk sate Arab<br />
untukku dan Budi. Mirip sate di Indonesia, hanya saja ukurannya 10 kali<br />
lebih besar. Penusuknya pun menggunakan besi sebesar
kelingking.Walau tak lapar, aku coba nikmati juga sajian spesial ini.<br />
Pertama kali sejak disandera, aku menyantap makanan yang masih<br />
hangat.<br />
"Kalian sekarang terkenal. Lihat wajah kalian<br />
ditelevisi," kata seseorang yang menurut Ibrahim adalah pemilik<br />
restoran. Dia menunjuk ke arah televisi. Kulihat adegan Budi sedang<br />
mencium Al-Quran di sebuah saluran televisi lokal. Aku dan Ibrahim<br />
kontan mengolok Budi."Wah, ada bintang baru, nih." Budi hanya<br />
tersenyum. "Assalamu 'alaikum.<br />
"Pintu samping restoran terbuka. Muhammad dan kepala wilayah<br />
berdiri menyambut Rois, yang datang bersama dua orang. Mereka<br />
bergabung ke meja kami.<br />
"Sabar, mobil kalian tidak lama lagi datang," ujar Rois menenangkan.<br />
"Ibrahim, apakah Meutya senang akhirnya bebas?" Aku merasa ucapan<br />
Rois sengaja mengolokku karena aku sempat ngambek padanya didalam<br />
gua.<br />
"Katakan padanya, ketika pulang nanti dia akan menikmati akibat<br />
penculikan ini." Ibrahim menyampaikan pesan Rois padaku. Menikmati<br />
akibat penculikan ini? Mamaku menangis, bangsaku ikut susah,<br />
kerabatku khawatir, dan dia bilang aku akan menikmatinya?<br />
Aku berbisik kepada Ibrahim. "Ibrahim, tolong sampaikan ke Rois,<br />
kalau memang nikmat, suruh saja kita bertukar tempat. Kita yang menjadi<br />
penculik, dia yangkita sandera di gurun, mau tidak?"<br />
Ibrahim hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala. Dia tak<br />
berani menyampaikan pesanku.<br />
Tak berapa lama kemudian, kepala wilayah dan Muhammad mohon<br />
diri. Aku baru mengerti. Rupanya pembebasan kami dilakukan berantai.<br />
Pemimpin wilayah menyerahkan kami kepada Rois. Setelah berada di<br />
tangan Rois, berarti tugas kepala wilayah dan Muhammad selesai. Aku<br />
sedikit kecewa Muhammad tak bisa menunggu hingga kami berangkat.<br />
Sebelum meninggalkan kami, dia menjabat erat tangan Ibrahim,<br />
kemudian Budi.<br />
Ketika tiba giliran pamit padaku, Muhammad hanya menganggukkan<br />
kepala. Dia mengangkat tangan kanannya dengan jari tengah dan telunjuk<br />
mengarah ke matanya.Aku mengerti maksudnya. Dia hendak<br />
mengingatkanku agar tidak lupa janji melambaikan tangan ditelevisi untuk<br />
mereka. Tangan ke arah mata, berarti mereka akan mengikuti dan<br />
menonton dengan saksama perjalanan kami hingga tiba di tanah air.<br />
Sebelum menghilang dari pandangan kami, Muhammad berkali-kali<br />
meminta maaf karena telah menculik kami di POM bensin.<br />
Rois lalu menyarankan agar kami mengontak pihak kedutaan untuk<br />
mengatur pertemuan di perbatasan Irak-Yordania. Dia agak terkejut ketika<br />
tahu aku dan Budi belum berkomunikasi dengan pihak luar, padahal<br />
ponsel kami telah dikembalikan. Aku dan Budi memang sepakat baru<br />
akan melakukan kontak keluar jika sudah betul-betul bebas. Rindu<br />
kepada keluarga memang tak tertahankan, tetapi kami khawatir<br />
komunikasi dengan keluarga akan memancing emosi, padahal kami<br />
masih perlu fokus pada upaya keluar dari Irak. Namun, saran Rois ada<br />
benarnya. Harus ada yang mengetahui keberadaan
kami. Aku dan Budi sepakat hanya membuat satu kontak telepon,<br />
yaitu kepada Musyurifun Lajawa, Kepala Bidang Penerangan KBRI di<br />
Amman. Kami yakin, sebagai Kepala Bidang Penerangan KBRI,<br />
Musyurifun akan menyampaikan info keberadaan kami kepada pihakpihak<br />
yang tepat.<br />
"Di mana posisi Meutya? Semua baik-baik saja? "Nada suara<br />
Musyurifun menggambarkan kekagetan seseorang yang sudah lama<br />
menunggu kabar. Dia mengenal nomor ponselku.<br />
"Kami baik, Pak. Kami masih berada di suatu tempat di wilayah<br />
Ramadi. Mungkin satu jam lagi berangkat. Tolong ada yang menjemput<br />
kami di perbatasan, ya," pintaku.<br />
"Orang kita sudah stand by. Kamu masih bersama penyandera?<br />
Budiyanto di mana? Jam berapa tiba diperbatasan?" Pertanyaan<br />
Musyurifun bertubi-tubi.<br />
"Ya, masih. Karenanya saya belum bisa bicara leluasa. Sampai<br />
ketemu di border. Insya Allah.<br />
"Suara Musyurifun terdengar panik. Aku tak mau tertular kepanikannya.<br />
Telepon kututup.<br />
Dua jam kami menunggu, mobil GMC kami akhirnya tiba. Serah<br />
terima kunci mobil dilakukan di dalam restoran. Rois menjelaskan melalui<br />
Ibrahim bahwa dari titik tersebut kami akan kembali ke perbatasan Irak-<br />
Yordania dengan GMC, bertiga. Tidak ada anggota Mujahidin yang ikut.<br />
Hanya saja, akan ada anggota mereka yang mengawal kami, secara<br />
undercover, untuk memastikan kami tiba di perbatasan dengan selamat.<br />
Kami tidak akan tahu keberadaan<br />
dan identitas para pengawal itu.<br />
Sebelum membiarkan kami pergi, Rois menyampaikan permintaan<br />
maaf kepada Presiden dan bangsa Indonesia jika aksi penculikan oleh<br />
kelompoknya telah menyusahkan berbagai pihak. Rois juga mengatakan<br />
bahwa bangsa Indonesia sangat sayang padaku. Inginaku bertanya apa<br />
maksudnya, tetapi urung karena tidak mau berlama-lama lagi di sana.<br />
Kami segera menuju mobil GMC. Ibrahim kaget melihat mobil putih<br />
kesayangannya sangat kotor sehingga berubah warna jadi kecokelatan.<br />
Mobil Rois masih membuntuti kami. Ketika kami membelok ke arah POM<br />
bensin untuk mengisi bahan bakar, kulihat mobil Rois membelok ke arah<br />
berlawanan.Kupandang sekelilingku. Kami berada di POM bensin yang<br />
sama dengan etika kami diculik. Kami kembali ke titik Nol.<br />
* * *n<br />
ALHAMDULLILLAH, selamat," penjaga POM bensin melongokkan<br />
kepalanya masuk jendela. Dia mengenali kami. Dia memerhatikan Budi<br />
agak lama, lalu tersenyum sambil menunjuk ke arah peci Budi, pemberian<br />
Mujahidin. Pasti dia melihat rekaman pembebasan kami di televisi.<br />
Ibrahim melenggang meninggalkan mobil.<br />
"Ibrahim, jangan pergi jauh-jauh!" teriakku. Terbayang lagi ketika<br />
pertama kami diculik, Ibrahim sedang meninggalkan mobil, entah ke<br />
mana.<br />
"Aku harus cari bantuan. Persneling kita rusak. "Duh, jangan sampai<br />
kami diculik orang lagi. Aku<br />
masih trauma dengan suasana POM bensin.<br />
Tak berapa lama, Ibrahim kembali dengan seorang mekanik.
Tangannya menenteng plastik hitam.<br />
"Kacang arab, oleh-oleh untuk istri," katanya. Aku tersenyum. Masih<br />
sempat Ibrahim mengingat oleh-oleh.<br />
Mekanik yang memeriksa mobil kami mengatakan bahwa perbaikan<br />
akan memakan waktu lama. Ibrahim memutuskan untuk meneruskan<br />
perjalanan dengan kondisi persneling bermasalah. Konsekuensinya,<br />
menurut Ibrahim, mobil kami tidak bisa melaju kencang. Berarti tambah<br />
lama sampai di perbatasan. Cobaan belum jugausai.<br />
Ibrahim melajukan mobil perlahan meninggalkan Ramadi, memasuki<br />
jalur utama.Jalan raya sepanjang 1.000 km yang menghubungkan<br />
Amman-Bagdad ini, sejak invasi Amerika Serikat, kerap disebut rute maut.<br />
Hingga perbatasan Yordania, tidak ada tempat istirahat, restoran, atau<br />
bengkel. Mobil biasanya masuk kedaerah ini berkonvoi, demi keamanan.<br />
Semua mobil yang melaju di sini keluaran baru dengan kondisi prima.<br />
Mogok di jalur ini berarti fatal. Dan, kami harus menumpang mobil yang<br />
persnelingnya rusak!<br />
Ibrahim membetulkan posisi kaca cermin di dalam mobil. "Oh Tuhan,<br />
aku terlihat jelek sekali." dia mengusap jambangnya yang tak beraturan.<br />
Tak sabar memandang wajah setelah tujuh hari tak bertemu<br />
bayangan diri, aku dan Budi berebut mendekati Ibrahim. Alhasil muka<br />
kami bertiga beradu dalam kaca. Semua sama jeleknya. Kami pun tertawa<br />
geli.<br />
"Ssstt!" Ibrahim tiba-tiba meminta kami diam dan kembali duduk rapi.<br />
Kulihat konvoi pasukan koalisi dijalur berlawanan mendekat ke arah kami.<br />
Aku teringat VCD-VCD pemberian Ahmad. Segera kukeluarkan dari tasku<br />
dan kuselipkan di bawah karpet, khawatir VCD propaganda Mujahidin ini<br />
bisa jadi masalah.<br />
"Jangan, Mut. Nanti kalau mobilnya dipe- riksa, ketahuan.<br />
Sembunyikan di badan saja," saran Budi. Dibadan? Lalu kalau ketahuan,<br />
bagaimana aku bisa ber-kelit?<br />
"Wanita tidak akan diperiksa sampai dalam baju.Jadi, harus kamu<br />
yang sembunyikan," kata Budi lagi,seperti bisa membaca kesangsianku.<br />
Aku tak punya pilihan. Ketiga VCD tersebut aku jejalkan di balik<br />
jaketku. Tank-tank tempur semakin mendekat. Tentara yang memegang<br />
senjata di atas humvee memandang ke arah mobil kami. Aku dan Budi<br />
merunduk. Konvoi tentara pun melewati kami tanpa berhenti.<br />
Ibrahim tampak menarik napas lega. Sejak itu kamitak lagi banyak<br />
tertawa. Masing-masing tenggelam memandangi gurun yang senyap.<br />
Jarang sekali terlihat mobil lain di luar kendaraan militer. Sekali ada mobil<br />
yang lewat, Ibrahim selalu melambatkan laju kendaraan dan menyapa<br />
sopirnya dengan senyum.<br />
"Siapa tahu mereka utusan Mujahidin." Ah, Ibrahim terlalu percaya<br />
kepada Rois. Aku sendiri tak begitu yakin Rois menugasi anggotanya<br />
mengawal<br />
kami hingga perbatasan<br />
* * *<br />
DI HADAPAN kami, matahari semakin turun dila-ngit barat.<br />
Perbatasan Irak-Yordania tak jauh lagi. Entah mengapa konvoi pasukan<br />
koalisi lebih banyak dari biasanya. Mungkin karena Irak tengah<br />
memperingati perayaan Asyura sehingga perbatasan dijaga ketat.
Beberapa kilometer sebelum perbatasan, aku dan Budi mengaktifkan<br />
ponsel milik kantor. Ponsel nomor pribadi kami sengaja kami matikan.<br />
Kami perlu berkoordinasi dengan tim penjemput. Betul saja. Baru satu<br />
detik aktif, ponselku langsung berdering. Pasti KBRI.<br />
"Halo Meutya, ini Bapak. Kamu sudah di mana? Bapak sudah<br />
menunggu dari tadi di border." Suara orang di ujung telepon terdengar<br />
sangat bersuka cita. Suara yang sangat kukenal. Pak Surya Paloh di<br />
perbatasan?<br />
"Pak Surya?" tanyaku hati-hati, untuk memastikan apakah suara yang<br />
kukenal betul suara milik Pemimpin Umum Media Grup, Surya Paloh.<br />
"Iya, ini Bapak. Bapak sama teman-teman semua menunggu kamu di<br />
border. Ada Sandrina dan Thia. Kami semua menunggu kamu." Tidak<br />
mungkin Pak Surya dan teman-teman sampai menjemput kami ke<br />
Yordania! Mataku basah. Aku masih tidak yakin pemimpin kami dan<br />
sejumlah rekan Metro TV datang menjemput. Kujelaskan kepada Surya<br />
Paloh bahwa aku dan Budi hanya tinggal beberapa menit dari<br />
perbatasan. Aku janji cerita lebih banyak di Amman. Lalu, telepon<br />
ditutup.<br />
Tak berapa lama telepon kedua masuk. "Meutya, sudah sampai<br />
perbatasan, ya? Selamat ya. Kami sambungkan on air ya di studio dengan<br />
Boy No-ya." Rupanya telepon dari Kedoya, kantor Metro TV.<br />
On air? Belum sempat aku protes, suara Boy Noya, seorang<br />
presenter Metro TV, terdengar di ujung telepon. Kutengok jam tanganku,<br />
pukul 22.45 Waktu Indonesia Barat. Biasanya, tidak ada program berita<br />
jam segini, pasti mereka menyelipkan breaking news. Awalnya aku dan<br />
Budi sepakat tidak berbicara kepada pers, paling tidak sampai kami tiba di<br />
titik aman, Yordania.Tetapi, terlambat untuk menolak. Kudengar suara Boy<br />
bertanya mengenai kondisi terakhir dan penculikan. Aku enggan<br />
menjawab banyak. Hanya mengucapkan terima kasih kepada Presiden<br />
dan semua pihak yang telah membantu. Andai saja aku bisa menjelaskan<br />
kepadanya bahwa kami belum sepenuhnya aman selama masih<br />
menginjak tanah Irak. Perasaanku sungguh tidak enak.<br />
Betul saja.<br />
Gerbang perbatasan Irak-Yordania sudah di depan mata, tetapi<br />
beberapa penjaga berkebangsa-an Arab menghadang laju mobil kami.<br />
Aku tak peduli lagi dengan sambungan on air. Ponsel kuserahkan kepada<br />
Budi.<br />
"Kenapa kita tidak boleh lewat, Ibrahim?"<br />
"Menurut para penjaga,perbatasan Irak-Yordania di tutup karena<br />
perayaan Asyura. Tak ada yang boleh keluar ataupun masuk Irak," jelas<br />
Ibrahim. Wajahnya<br />
tampak pasrah setelah berusaha meyakinkan para pen-jaga<br />
tanpa hasil.<br />
"Apa mereka tidak tahu kita baru saja bebas dari penyanderaan?" Aku<br />
tak bisa menahan kekesalan ku. Sebelum kami masuk kembali ke Irak,<br />
aku memang diberi tahu ada penutupan perbatasan hingga tanggal 24<br />
Februari. Berarti kami masih harus menunggu tiga malam lagi? Tidak<br />
adakah pengecualian untuk kasus khusus seperti korban penculikan?<br />
"Ya. Mereka sudah sangat tahu, bahkan ketika baru melihat mobil<br />
kita." Ibrahim mencoba meredam kekesalanku. "Mereka mengikuti kasus
kalian melalui televisi. Mereka sangat senang kalian selamat. Tetapi, pintu<br />
baru akan dibuka kalau ada izin dari pusat. Bagdad."<br />
"Coba jelaskan pada mereka bahwa perwakilan pemerintah<br />
Indonesia juga menunggu di perbatasan seberang!"<br />
"Dengar, Meutya. Aku sangat yakin mereka tahu. Perbatasan Irak dan<br />
Yordania selalu saling memantau dan berkomunikasi. Tetapi, perintah<br />
dari pusat menyatakan demikian. Mereka menyarankan agar perwakilan<br />
pemerintahmu di perbatasan segera meminta izin ke Bagdad. Atau, kita<br />
yang kembali ke Bagdad<br />
"Aku terperangah. Kami harus kembali ke Bagdad? Tidak mungkin.<br />
Risikonya terlalu tinggi.<br />
Budi masih sibuk menjawab pertanyaan dari Boy.Aku merebut ponsel<br />
dari tangannya.<br />
"Boy, kami ada masalah. Kami tidak diizinkan melewati perbatasan.<br />
Kami harus tutup di sini.<br />
"Tanpa menunggu jawaban Boy, sambungan ku tutup. Aku merasa<br />
sedikit bersalah, tetapi tak ada pilihan lain. Wawancara live by phone kami<br />
dengan MetroTV kemungkinan dipantau media asing. Jika media tersebut<br />
menayangkan detail pernyataan kami dan dapat ditangkap oleh televisi<br />
Irak, berarti pergerakan dan pernyataan kami dapat dipantau oleh<br />
kelompok Mujahidin dan tentu lawan mereka, tentara koalisi. Kalau kami<br />
salah bicara sedikit saja atau terkesan memihak atau menyinggung salah<br />
satu kelompok, nyawa kami taruhannya.<br />
Apalagi setelah wawancara tadi, kuprediksi semua pihak kini<br />
mengetahui lokasi kami. Tidak sulit bagi mereka untuk menangkap<br />
kembali atau memeriksa kami.<br />
Mungkin kekhawatiranku terlalu berlebihan. Tetapi, pengalaman<br />
disandera mengingatkanku bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun di Irak<br />
yang be tul-betul aman, terutama untuk jurnalis. Kami harus segera<br />
keluardari negeri ini.<br />
Teleponku berdering lagi. Kali ini dari nomor Yordania.<br />
"Halo Meutya. Perkenalkan, saya Triyono Wibo-wo.Saya bersama tim<br />
ditugaskan oleh Jakarta membawa kalian kembali. Kami di perbatasan<br />
Yordan sedang mengupayakan secara diam-diam melobi para penjaga<br />
Irak melalui bantuan pihak intelijen Yordan. Tolong jangan berbicara dulu<br />
pada pers mana pun. Itu mengganggu lobi kami." Suara di ujung telepon<br />
seperti mencoba tetap tenang. Namun, aku bisa menangkap si penelepon<br />
menahan amarahnya. Aku<br />
yakin dia tidak senang dengan wawancara via telepon kami. Aku<br />
mengiyakan permintaannya. Dia berjanji akan berusaha maksimal<br />
membuka jalan kami keluar dari Irak.<br />
Lagi-lagi teleponku berdering. Orang di ujung telepon mengaku<br />
sebagai wartawan BBC. Dia mengaku sedang menunggu di perbatasan<br />
bersama puluhan jurnalis lain. Dia menanyakan alasan kami tak boleh<br />
melintasi perbatasan. Aku minta maaf kepadanya dan menjelaskan belum<br />
boleh memberikan keterangan apapun sampai kami berhasil keluar dari<br />
Irak.<br />
Telepon terus berdering. Surya Paloh, yang terus memantau posisiku,<br />
mengaku terkejut kami tertahan. Kedoya juga mengontak.Telepon dioper<br />
bergantian dari Don Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi, lalu Usi
Karundeng, Manager Talent yang membawahi presenter. Semua panik<br />
setelah tahu kami tak bisa segera keluar dari Irak. Semua meminta kami<br />
melobi penjaga pintu per-batasan Irak untuk membuka pintu. Mereka tak<br />
tahu keputusan ini sulit diubah, seperti harga mati. Penjaga perbatasan,<br />
berbeda dengan ketika kami masuk, kali ini tak bisa di-lobi. Mungkinkah<br />
ada instruksi untuk menahan kami di perbatasan dengan maksud<br />
memancing reaksi kelompok penyandera?<br />
Tim Deplu di perbatasan juga berulang-ulang menelepon,<br />
menanyakan situasi terakhir. Kukatakan, kami merasa tidak aman dan<br />
memohon tim masuk ke Irak mendampingi kami. Namun, sepertinya sulit<br />
berharap banyak kepada tim di perbatasan.<br />
Bagaimana mereka menyelamatkan kami keluar Irak, masuk ke Irak<br />
pun mereka tidak bisa.<br />
Ibrahim menawarkan dua solusi. Pertama, mencari tempat aman di<br />
dekat pintu perbatasan dan menunggu sampai para penjaga berubah<br />
pikiran.Entah sampaikapan. Atau kedua, mendatangi pos komandan<br />
pasukan koalisi yang bertugas di perbatasan.<br />
"Merekalah sebenarnya yang berkuasa menentukan mobil masuk dan<br />
keluar Irak," kata Ibrahim.<br />
Namun, alternatif kedua bukan tanpa risiko. Kami bisa saja<br />
diinterogasi untuk menjelaskan keberadaan kelompok Mujahidin yang<br />
menangkap kami.<br />
Aku memilih alternatif pertama. Lebih baik menunggu, walau tak jelas<br />
berapa lama, daripada diinterogasi. Mobil kami parkir persis ke depan<br />
kantor imigrasi, tak jauh dari gerbang perbatasan. Beberapa kali pejabat<br />
imigrasi mengetuk jendela. Dia menawari kami tidur di dalam kantor. Aku<br />
menolak. Perasaanku tak tenang. Aku tak bisa percaya kepada siapa pun.<br />
Syukurlah Ibrahim dan Budi setuju. Kami putuskan tidur dimobil saja.<br />
Angin bertiup melalui celah-celah tipis jendela. Dinginnya masih tetap<br />
membuat kulitku seperti membeku.Suhu malam musim dingin Irak selalu<br />
di bawah 10 derajat celsius. Dan,kami harus tidur tanpa selimut dengan<br />
perut kosong. Sulit sekali memejamkan mata, tetapikupaksa juga.<br />
Badanku mulai menggigil, tetapi keringat membasahi tubuhku. Keringat<br />
dingin. Ternyata disan-dera di gua lebih nyaman.<br />
* * *<br />
PAGINYA, tak kuat menahan lapar, kami menyerah juga dengan<br />
tawaran sarapan bersama pejabat imigrasi. Dia sangat ramah menjamu<br />
kami. Beberapa kali dia meminta maaf karena tak bisa mengizinkan kami<br />
keluar perbatasan.<br />
Aku menerima telepon dari Juru Bicara Departemen Luar Negeri,<br />
Marty Natalegawa. Mulai pagi ini, koordinasi lebih banyak dilakukan<br />
langsung dengan Jakarta karena hingga pagi tim penanggulangan krisis<br />
yang dikirim ke perbatasan belum juga berhasil menjemput kami. Lobi ke<br />
Bagdad juga banyak dilakukan langsung tim pembebasan di Jakarta.<br />
Marty menjelaskan, pihak-nya sudah mengirim faksimile surat permintaan<br />
izin ke Kementerian Dalam Negeri Irak, tetapi belum ada tanggapan.<br />
Sulit kumengerti mengapa Bagdad tak juga mengizinkan kami keluar,<br />
padahal mereka tahu persis pernyataan Presiden yang mengharapkan<br />
kami segera pulang. Mungkinkah karena Indonesia tak lagi memiliki<br />
perwakilan di Irak sejak invasi? Entahlah. Yang jelas, hingga siang hari
nasib kami masih terka tung-katung. Padahal, Kedutaan Irak di Jakarta<br />
juga sudah membantu melobi pemerintah pusat di Bagdad, termasuk<br />
berbicara langsung dengan pejabat imigrasi di perbatasan melalui<br />
ponselku. Dia memerintahkan membuka pintu perbatasan untuk kami.<br />
Namun, para pejabat imigrasi tak mengindahkannya.<br />
Matahari semakin meninggi, kabar baik tak juga<br />
datang. Kami kembali ke mobil. Sudah 20 jam kami menunggu. Aku<br />
semakin panik dan tak mampu lagi mengontrol emosi.Aku merutuki<br />
petugas imigrasi yang menurutku tidak punya hati nurani.<br />
"Kalau saja kami berkebangsaan Amerika atau Inggris dan baru<br />
dibebaskan dari penyanderaan, pasti kami sudah diizinkan lewat.<br />
"Kepada Triyono dan tim penanggulangan krisis diperbatasan, aku<br />
mengaku kecewa karena mereka tidak mampu mendampingi kami di<br />
perbatasan Irak. Aku juga kecewa kepada teman-teman Kedoya yang<br />
memintaku selalu melaporkan kondisi terkini yang kualami. Hampir dalam<br />
setiap penugasanku selama lima tahun menjadi jurnalis, aku bersedia<br />
melaporkan berbagai hal, terkadang yang dapat membahayakan diriku<br />
sendiri. Tetapi, aku tak mau melakukan tugas reportase dan menjadi<br />
objek liputan dalam kondisi seperti ini.<br />
Aku mendadak tersadar. Beginikah perasaan yangdialami para<br />
korban musibah tertentu, ketika aku wawancarai?<br />
Marty Natalegawa, yang kembali mengontakku, tak luput dari repetan<br />
panjangku. Dia memintaku untuk tenang.<br />
"Aku baru bisa tenang kalau ada perwakilan pemerintah yang masuk<br />
untuk mendampingi dan menjaga kami di perbatasan Irak," kataku.<br />
Terbayang di benakku ketika beberapa wartawan atau pekerja asing<br />
baru dilepaskan dari penyanderaan di Irak,perwakilan negara masingmasing<br />
menjemput dan mengevakuasi mereka dari pihak<br />
penculik. Casingkem dan Istiqomah pun diserahkan penyandera ke<br />
Kedutaan Besar Arab Saudi, lalu didampingi Tim Bulan Sabit Merah keluar<br />
dari Irak hingga ke Kedutaan Indonesia di Amman. Mengapa kami<br />
dibiarkan berjuang sendiri?<br />
Tak lama setelah kontakku dengan Marty, kudengar Menteri Luar<br />
Negeri Hassan Wirajuda memerintahkan kepada Duta Besar Indonesia di<br />
Yordania, Ridhan A.Wahab, untuk masuk ke Irak menjemput kami. Kabar<br />
tersebut membuatku tenang. Aku menyesal telah emosional. Rupanya<br />
semua pihak bekerja keras mengupayakan kepulangan kami. Kini,<br />
pilihanku tinggal berserah diri.<br />
Aku, Budi, dan Ibrahim menunggu dalam diam. Tim Metro TV di<br />
Amman dan Jakarta, serta tim Dep lu di duatempat yang sama, tidak lagi<br />
menelepon. Kami semua menunggu ketidakpastian.<br />
Di tengah kepasrahan itu, jawaban datang. Tanpa menunggu<br />
kedatangan Dubes RI, sore hari petugas penjaga menghampiri mobil,<br />
mengabarkan bahwa kami dapat izin keluar Irak. Tanpa alasan yang jelas.<br />
* * *<br />
SELASA, 22 Februari, pukul 19.35 WIB. Mobil mulai melaju ke gerbang<br />
pertama yang membatasi Irakdan Yordania. Di dalam mobil, aku dan Budi<br />
ber sorak-sorak, tak mampu menahan luapan kegembiraan. Ibrahim pun<br />
menyenandungkan sebuah lagu Arab. Mobil melaju pelan seakan-akan<br />
menghayati
momen-momen meninggalkan Irak. Waktu seolah-olah turut<br />
merambat pelan.<br />
Kuhubungi Marty Natalegawa untuk mengabarkan berita gembira<br />
ini.Sepertinya Marty dapat menduga dari suaraku yang ceria menyapanya.<br />
"Meutya, please tell me we made it."<br />
"Yes Pak Marty. We did. I'll be with the team in lessthan five."<br />
Aku geli sendiri mendengar Marty, yang kukenal cukup tenang,<br />
memekikkan teriakan gembiranya. Dia menutup telepon untuk segera<br />
mengabari tim di per-batasan Yordania. Aku lalu menghubungi teman<br />
MetroTV di perbatasan, Mauluddin Anwar, mengabarkan berita gembira ini.<br />
Namun di tengah kegembiraan, kulihat wajah Ibrahim berubah<br />
muram.<br />
"Meutya, kamu dijemput banyak orang. Apakah kamu dan Budi akan<br />
ikut teman-temanmu ke Amman dan meninggalkanku menyetir seorang<br />
diri?" Suaranya tak mampu menyembunyikan kesedihan. Dia menyadarkanku<br />
bahwa tidak lama lagi kami harus berpisah.<br />
"Tidak, Ibrahim." Aku mencoba menghibur- nya. "Dari perbatasan, kita<br />
akan tetap bersama-sama hingga Amman, sampai ke hotel tempat kamu<br />
menjemput kami." Tak mungkin kami membiarkan Ibrahim menyetir<br />
sendiri ke Amman.<br />
Namun, semua itu hanya harapan. Kenyataan harus memisahkan<br />
kami. Aku dan Budi bahkan tak sempat mengucapkan kalimat perpisahan<br />
kepada Ibrahim. Setelah melewati gerbang perbatasan Yordan,<br />
sejumlah lelaki berbadan tegap telah menunggu kami. Aku juga<br />
lihat Musyurifun Lajawa dan beberapa orang yangkuduga adalah anggota<br />
tim penanggulangan krisis Deplu. Mereka meminta mobil kami berhenti.<br />
Aku dan Budi langsung ditarik keluar mobil oleh tim. Sementara, Ibrahim<br />
ditarik oleh pria berbadan tegap berseragam tentara Yordania. Kami<br />
dibawa ke ruangan terpisah.<br />
Aku meronta meminta Ibrahim ikut bersama kami. Ibrahim hanya bisa<br />
memandang kami karena kedua tangannya dipegang erat dua pria dan<br />
dibawa masuk ke sebuah ruangan. Menurut Musyurifun, Ibrahim<br />
harusmenjalani interogasi bersama intel Yordania, untuk dimintai<br />
keterangan tantang kelompok penculik. Juga, untuk memastikan bahwa<br />
Ibrahim tidak terlibat dalampenculikan.<br />
Aku terkejut. Ingin kuikut menjelaskan bahwa Ibrahim tak mungkin<br />
terlibat penculikan. Namun, aku tidak dapat berbuat banyak untuk<br />
meyakinkan pihak Yordania. Ibrahim adalah warga negara Yordania, dan<br />
mereka berhak menginterogasinya. Lagi pula, badanku mendadak lemas.<br />
Aku baru sadar sejak turun dari mobil jalanku dipapah. Mungkin karena<br />
sudah mencapai puncak ketahananku, akhirnya badanku menyerah juga<br />
pada kondisi sebenarnya.<br />
"Keduanya sudah sampai, Pak. Keduanya baik-baik saja. Hanya saja,<br />
Meutya kelihatan lemas dan pucat. "Sambil dibawa menuju sebuah<br />
ruangan, kudengar samar-samar seorang anggota tim berbicara dengan<br />
seseorang di ujung telepon.<br />
"Mbak Meutya, Pak Syamsir ingin bicara." Pak<br />
Syamsir siapa? Belum sempat kubertanya, ponsel disodorkan ke<br />
arahku.<br />
"Meutya, syukurlah kalian telah selamat. Saya Syamsir Siregar.
Anggota kami di Yordania ikut membantu pembebasan. Kami semua<br />
senang Anda dan Budi selamat." Rupanya Kepala Badan Intelijen Negara,<br />
Syamsir Siregar. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Aku<br />
yakin tim dari BIN telah bekerja keras untuk mengupayakan kami kembali<br />
ke tanah air.<br />
Di ruang tunggu, chai hangat sudah tersaji. Harum aromanya<br />
melegakanku. Aku menyeruputnya.<br />
Tiba-tiba, ponsel kembali disodorkan ke arahku.<br />
"Mbak Meutya, Pak Menlu mau bicara."<br />
"Alhamdullillah, selamat ya Meutya. Segera kembali ke tanah air."<br />
Menlu Hassan Wirajuda menjelaskan bahwa akudan Budi sudah<br />
ditunggu segera oleh Presiden S BY. Aku mengucapkan penghargaan dan<br />
terima kasihku atas kerja tim yang telah mengupayakan pembebasan<br />
kami. Setelah barang-barang bawaan kami selesai diperiksa, aku dan Budi<br />
dibawa ke mobil besar yang diparkirdi belakang gedung.<br />
Aku tidak melihat satu pun wartawan di sana. Sepertinya mobil<br />
sengaja disiapkan untuk keluar dari pintu belakang, untuk menghindari<br />
wartawan. Aku merasa tak enak. Rekan-rekan seprofesiku, yang sengaja<br />
menginap di perbatasan menunggu kebebasanku, tak dapat merekam<br />
gambarku. Sebagai jurnalis, aku mengerti bagaimana kesalnya sudah<br />
me- nunggu lama tetapi tak memperoleh gambar.<br />
Aku juga teringat Ibrahim. Aku telah berbohong padanya. Tetapi, aku<br />
tak punya pilihan karena dijaga ketat tim penjemput. Ibrahim harus<br />
menyetir sendiri selama empat jam lebih ke Amman. Ibrahim,<br />
maafkanaku.<br />
Sebelum meninggalkan perbatasan, aku meminta tolong Musyurifun<br />
memberikan sejumlah uang kepada Ibrahim untuk menutupi kerugian<br />
mobilnya yang rusak karena penculikan, dan tambahan uang saku yang<br />
belum sempat kubayarkan.<br />
Mobil yang membawaku melaju cepat menuju Wisma Indonesia di<br />
Amman, yang berjarak sekitar empat jam dari perbatasan.<br />
* * *<br />
DI PINTU wisma, aku disambut keramaian. Suasana malam hari<br />
membuatku tak bisa melihat jelas siapasaja mereka. Hanya saja<br />
kudengar pekikan "Allahu akbar, Allahu akbar" mengiringi langkahku ke<br />
pintu masuk wisma.<br />
Di depan pintu masuk, kulihat sosok yang kukenal. Pak Surya Paloh!<br />
Dia menyambutku dengan tangan terbuka lebar. Kurasakan kelegaan<br />
seorang bapak dalampelukannya.<br />
Kemudian, kurasakan juga pelukan dari rekan kerjaku di Metro TV,<br />
Sandrina Malakiano dan Thia Vufada. Mereka tak melepaskan pelukan<br />
sambil mengiringi kumasuk menemui lebih banyak lagi teman-teman<br />
MetroTV, Muchlis Hasyim dari Media Grup,<br />
produserku Mauluddin Anwar, Kusdaryanto, Sudirman juru<br />
kamera.Kami sudah seperti keluarga. Luar biasa nikmatnya disambut<br />
orang-orang yang menyayangi.<br />
Penyambutan tak selesai sampai di situ. Duta Besar dan tim Deplu<br />
juga menyambut kami sukacita. Tak habis-habisnya aku menerima
ucapan selamat dan ungkapan sayang dari semuanya. Tidak sedikit juga<br />
lontaran pertanyaan tentang saat-saat penculikan. Ibu Dubes<br />
mempersilakan aku mandi.Tergiur membayangkan segarny aair di<br />
tubuhku, aku langsung menerima tawarannya. Itulah pertama kalinya aku<br />
mandi, keramas, dan buang air besar setelah delapan hari disekap di<br />
dalam gua.<br />
Pukul 8 malam waktu Amman, aku dipanggil turun. Kulihat ruang<br />
tamu wisma sudah dipenuhi wartawan.Belum satu jam aku menikmati<br />
keindahan itu, aku danBudi langsung diadang konferensi pers. Begitu<br />
banyak pertanyaan yang terlontar, dan aku tak lagi keberatan<br />
menjawabnya. Selain karena aku dan Budi telah merasa betul-betul aman<br />
di Wisma Idonesia, yang secara hukum dilindungi oleh pemerintah<br />
Yordania, kami juga merasa nyaman dikelilingi orang-orang yang<br />
menyayangi kami. Setelah dua jam, kututup sesi tanya-jawab dengan<br />
mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis karena telah<br />
membantu menekan kelompok penculik melalui pemberitaan mereka.<br />
Malam ini aku menginap di Wisma Indonesia, menunggu kepulangan<br />
ke tanah air esok hari. Nyaman rasanya tidur di kasur empuk. Tempat tidur<br />
ukuran<br />
kinghanya untukku sendiri, dilengkapi bantal dan gulingjuga<br />
selimut tebal.<br />
Kusempatkan menelepon mamaku. Banyak cerita yang ingin<br />
kusampaikan, tetapi aku harus membatasi diri. Kumatikan lampu kamar.<br />
Ini bukan gua di gurun, Mut, tidak ada penyandera di sini. Tidurku nyenyak<br />
sekali.[]<br />
Bab n<br />
Aku Pulang<br />
JAKARTA sudah di depan mata. Dari jendela pesawat, aku melihat<br />
liukan sungai berwarna kecokelatan, berpadu dengan bias kemerahan<br />
atap-atap genting. Beberapa menit lagi, aku akan menjejak tanah air.<br />
Berkali-kali aku pulang dari negeri seberang, tetapi perasaan rinduku<br />
kepada tanah air kali ini berbeda sekali.<br />
Dua puluh empat hari setelah meninggalkan tanah air, sejak 31<br />
Januari 2005, aku akhirnya bisa pulang. Aku rindu sekali.<br />
Mendadak, saat melaju di ketinggian angkasa, akumerasakan bahwa<br />
drama yang kualami, mulai dari mobil kami dibawa lari, dan selama harihari<br />
di dalam gua, semuanya sudah ada yang mengatur. Dan, hanya atas<br />
kuasa-Nyalah kami dapat bertahan hidup, sehari lagi, sehari lagi, sampai<br />
akhirnya dibebaskan.<br />
Di tengah hari-hari penyanderaan, aku yakin pasti Allah sengaja<br />
mengajak dan mengajarkan padaku melalui perjalanan spiritual (aku<br />
melihat penyanderaan ini juga sebagai perjalanan spiritual dari<br />
Tuhan, mungkinkarena selama ini aku banyak melupakan-Ny a,<br />
banyak meninggalkan perintah-Nya, karena terlalu sibuk mengejar dunia).<br />
Tiba-tiba, semu-a yang kukejar atau yangdikejar oleh banyak orang<br />
selama di dunia ternyata tidak bisa menolongku keluar dari masalah,<br />
keluar dengan selamat dari gua. Hanya Dialah dan atas kehendak-Nyalah<br />
aku dapat selamat. Materi, harta, uang,tidak dapat menolong keluar dari<br />
masalah karena toh yang diinginkan para penculik bukan materi.<br />
Selama di gua, tidur tanpa alas yang memadai dengan ruang sangat
terbatas (dibandingkan tempat tidurku di rumah yang besar dan empuk),<br />
baju-baju di lemariku yang bertumpuk tidaklah berarti. Selama tujuh hari,<br />
aku tidak ganti baju. Semua serba terbatas, bahkan air sebagai kebutuhan<br />
utama juga terbatas karena satu ember harus kami bagi berlima.<br />
Di pesawat, aku duduk bersama Sandrina dan Thia Yufada, dua<br />
rekanku sesama presenter yang turut menjemput ke Yordania. Thia<br />
menggenggam tanganku, memberikan kekuatan. Sandrina sesekali<br />
mengusap kepalaku. Mungkin mereka memerhatikan mataku yang mulai<br />
berkaca-kaca. Aku masih tidak percaya akhirnyadapat betul-betul kembali<br />
ke tanah air. Thia dan Sandrina banyak bercerita bahwa ke-pulanganku tak<br />
lepas dari dukungan masyarakat luas. Masyarakat turut menangis dan<br />
berdoa untuk keselamatan aku dan Budi.Anak-anak yatim ikut menangis<br />
dan mendoakan keselamatanku. Kenapa mereka begitu perhatian?<br />
Merekakan tidak kenal<br />
aku? Lagi-lagi pipiku basah oleh airmata. Thia dan Sandrina<br />
memelukku erat.<br />
Pesawat Qatar Airways yang membawa kami dari Yordania akhirnya<br />
menjejakkan roda-rodanya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Aku<br />
masih setengah tak percaya, perjuangan panjang kembali ke tanah<br />
kelahiran akhirnya berujung juga. Penumpang lain turun lebihdahulu<br />
dibandingkan rombongan kami. Seperti biasa, dipintu keluar pesawat<br />
sejumlah kru bandara bersiaga. Ternyata ada yang khusus menunggu<br />
kami. Aku, Budi, diiringi Tim Metro TV, dan Tim Deplu. Setelah mendapat<br />
kalungan untaian bunga anggrek yang indah, aku dan Budi langsung<br />
dibawa menuju sebuah ruang tunggu yang berbeda dengan penumpang<br />
lainnya.<br />
Belum sampai masuk, di pintu kulihat beberapa sosok yang kukenal<br />
menungguku. Ada Don Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi Metro TV.<br />
Banyak juga petinggi kantor lainnya. Don memelukku erat, hingga aku sulit<br />
bernapas. Dia juga menciumi telapak tanganku. Betul kata Sandrina, Bang<br />
Don sempat bersumpah, kalau aku kembali dengan selamat, dia akan<br />
mencium tanganku ibarat seorang putri. Meski kikuk, aku membiarkannya.<br />
Sebab, dia tengah menunaikan janji. Marty Natalegawa, Juru Bicara<br />
Departemen Luar Negeri, menyambutku dengan senyum lebar. "Keluarga<br />
menunggu di istana," kata Marty, yang mengerti mataku mencari-cari.<br />
Seorang petugas menyodorkan tas berbahan karton."Itu titipan untuk<br />
Mbak Meutya," katanya manis. Didalamnya ada baju jas dan celana<br />
panjang<br />
hitam. Aku mengenalinya, itu bajuku. Ada pula surat. Di amplop<br />
tertulis "untuk adekku Meutya". Ce pat-cepat kusobek amplopnya.Sambil<br />
membaca,aku digiring petugas wanita itu ke ruang ganti.<br />
Hi adekku,<br />
Welcome back, ini titipan baju kalau mau ganti.<br />
Trus di bawah ini contoh tanda terima kasih, siapa tahu perlu,<br />
habis kan jadi resmi karena ke istana.<br />
Adek bayi akan pake baju baru loh, tetapi nunggu di rumah.<br />
Ah, kakak-kakakku begitu perhatian dan pengertian. Mereka mengerti<br />
aku butuh baju yang pantas untuk dikenakan ke istana karena baju-bajuku<br />
dari Irak belum dicuci. Aku tersenyum mengingat "si adek bayi",<br />
keponakanku Aisha yang baru berusia satu tahun. Aku sudah sangat rindu
akan polahnya yang selalu menggemaskan. Ah, tidak sabar rasanya ingin<br />
pulang.<br />
Setelah berganti baju, kami pun berangkat. Budi memakai jas abuabu<br />
yang disiapkan kantor, dan tetap mengenakan peci pemberian<br />
penyandera.Kami menumpang mobil yang sama dengan Marty<br />
Natalegawa dan Surya Paloh. Di luar, aku melihat kamera rekan-rekan<br />
wartawan yang menunggu ingin mengambil gambar kami. Beberapa di<br />
antaranya berlari mengejar laju mobil. Biasanya akulah yang di sana,<br />
menunggu dan memburu nara sumber. Maafkan aku teman-teman,<br />
kami harus mengikuti jadwal protokoler istana.<br />
Sirene fore rider yang membelah macet sore Jakarta membuat<br />
perjalanan dari bandara hanya kurang dari satu jam. Turun di pintu<br />
belakang Istana Negara, aku terpana melihat sambutan meriah. Dari jauh<br />
kulihat gazebo di bagian belakang istana sudah ramai sekali.Puluhan<br />
kamera mengarah kepada kami. Canggung jugarasanya menjadi objek<br />
berita. Gugup sejenak memikirkan apa yang akan kusampaikan nanti.<br />
"Papa ...I"<br />
Seorang anak kecil berlari girang menyongsong. Laras, anak sulung<br />
Budi yang berusia tujuh tahun, berteriak dengan air mata berderai di pipi.<br />
Dia melompat ke arah Budi. Sang ayah memeluknya erat-erat.<br />
Dibelakangnya ada Lestari, istri Budi. Juga orang tua Budi,Niti Heru dan<br />
Disih, yang sengaja datang dari Desa Ganjuran, Mertoyudhan, Magelang,<br />
untuk menyambut kembalinya si anak hilang.<br />
Lalu, sosok yang sangat kukenal dan kurindukan berlari ke arahku.<br />
Mama. Juga, ada kakakku Finny dan Fitri. Kami berpelukan lama, seolaholah<br />
tak ingin lepas.Pelukan yang menguatkan hatiku, sebelum<br />
melangkah ke pendopo. Menghadap Presiden.<br />
Di gazebo, pertemuan dengan Presiden berjalan hangat dan santai.<br />
Presiden membuka pertemuan dengan memberikan kata sambutan.<br />
"Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah Swt.<br />
Karena ridha Al /ah, akhirnya yang sangat kita cintai Saudara Budiyanto<br />
dan Saudara Meutya Hafid telah kembali dengan selamat dan berjumpa<br />
dengan orang-orang yang sangat disayangi. Telah kembali berada di<br />
tengah-tengah kita, di tengah keluarga besar bangsa Indonesia yang terus<br />
berdoa siang dan malam agar mereka segera dibebaskan dan kembali<br />
dengan selamat ke Indonesia. Atasnama pemerintah, atas nama rakyat<br />
Indonesia, tentu disamping bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,<br />
saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua<br />
pihak yang telah dengan ikhlas, dengan gigih, berbuat sesuatu untuk<br />
menyelamatkan dan membebaskan kedua wartawan kita yang sangat<br />
saya cintai ini. Pertama-per tama, saya ingin mengucapkan terima kasih<br />
kepada Menteri Luar Negeri, termasuk Dubes RI di Amman, penghubung<br />
kita di Bagdad, Saudara Triyono dari Tim Krisis,dan seluruh jajaran<br />
termasuk dari BIN yang atas nama pemerintah telah bekerja keras,<br />
dengan diplomasi danmelaksanakan semua upaya pembebasan.<br />
"Kutebar pandang menyisir ruangan. Selain Presiden,ada Menteri<br />
Luar Negeri Hassan Wirajuda, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Jubir<br />
Presiden Andi<br />
Mallarangeng dan Dinno Pati Djalal.<br />
Presiden juga menyampaikan terima kasih kepa da Metro TV.
"Yang kedua, saya berterima kasih kepada pihak Metro TV, sahabatsahabat<br />
dari Metro TV yang peduli dan berusaha. Oleh karena itu, saya<br />
memberikan penghargaan dan terima kasih. Juga kepada tokoh-tokoh<br />
lain, ulama kita, saudara-saudara kita, baik di Indonesia maupun di Timur<br />
Tengah yang berdoa, menyampaikan seruan, menyampaikan statement<br />
dengan berbagai cara agar Meutya dan Budiyanto bisa selamat dan bebas<br />
dan kembali kepada keluarga dan sau dara-saudaranya di Indonesia.<br />
"Surya Paloh dan petinggi Media Group yang ha dir menyambutnya<br />
dengan tepukan tangan keci Presiden melanjutkan,<br />
"Saya mengajak kita semua untuk memetik hikmah dan pelajaran,<br />
dan bagaimana kita memandang ke depan. Tugas wartawan sering<br />
berhadapan dengan risiko dan bahaya, apalagi di daerah konflik, baik di<br />
tanah air maupun di luar negeri. Tetapi, jangan sampai adanya episodeini<br />
melunturkan keberanian, semangat, dan kegigihan dari rekan-rekan<br />
wartawan untuk melakukan tugas jurnalis-tiknya. Wartawan juga menjadi<br />
bagian penting dari upaya menegakkan kebenaran, misi kemanusiaan,<br />
bahkan<br />
dalam pengembangan demokrasi di negara kita. Teruslah<br />
berjuang, teruslah ber= profesi, untuk kepentingan kita semua.<br />
"Kali ini tepukan semakin meriah. Kawan-kawan yang meliput ikut<br />
bertepuk tangan.Mereka yang kukenal dalam peliputan ada yang<br />
melambaikan tangan dan melempar senyum ke arahku.<br />
Presiden pun menutup sambutannya.<br />
"Saya kira itu/ah yang dapat saya sampaikan, syukur kita, terima kasih<br />
saya, dan mudah-mudahan ini pelajaran yang bisa kita petik bersama.<br />
Saya kira akan menjadi bagian penting dalam biografi, dalam sejarah<br />
kalian berdua suatu saat untuk menulis riwayat hidup. Dan tentunya kami<br />
lebih bersyukur karena orangtua, keluarga, anak tentunya lebih bersyukur,<br />
lebih berbahagia, terutama bagi Meutya dan bagi Budiyanto.<br />
"Setelah memberikan kata penyambutan, Presiden menanyakan<br />
ihwal penculikan dan bagaimana perlakuan selama kami disandera.<br />
"Kami tak pernah menangis secara terbuka, hingga menerima kabar<br />
bahwa kami bebas karena Bapak merespons dengan cepat," jawabku<br />
dengan takzim, sambil berterima kasih atas perhatian Presiden, yang<br />
menjadi kunci utama pembebasan kami. Aku juga menyampaikan pesan<br />
Rois, berupa permohonan maaf kepada Presiden dan masyarakat Indonesia<br />
karena telah menculik dan membuat susah bangsa Indonesia.<br />
"Rois memuji Bapak, katanya betapa sayangnya Presiden kepada kalian."<br />
Budi menambahi cerita tentang strategi melunakkan hati<br />
penyandera."Di tengah tekanan, kami berusaha sabar dan menempatkan<br />
diri sebagai tamu yang baik. Kadang-kadang, kami menservice mereka.<br />
Membuat teh, jugamencuci gelas. Walaupun tangan harus kedinginan".<br />
Presiden mendengar kisah kami dengan sung guh-sungguh.<br />
Presiden juga bercerita pernah melintas dari Amman ke Bagdad, tahun<br />
1999.<br />
"Jadi, saya bisa membayangkan kondisinya," tutur Presiden.<br />
Pertemuan 20 menit pun ditutup dengan berfo-to bersama Presiden.<br />
Penyambutan yang tak kalah meriah diberikan teman-teman di kantor<br />
Metro TV. Begitu mobil memasuki gerbang kantor di Kedoya, Jakarta Barat,<br />
karangan bunga berjejer hingga lobi utama. Dari balik kaca mobil, aku
aca beberapa pengirim. Ada departemen, wakil rakyat, hingga LSM, yang<br />
sebagian besar ku kenal dari peliputan. Air mataku kembali menetes.<br />
Begitu banyak perhatian ditujukan kepadaku.<br />
Mendekati lobi, rekan-rekan kerjaku berjejer menyambut sambil<br />
membawa spanduk bertuliskan "Selamat datang teman, sahabat tercinta,<br />
Meutya dan Budiyanto". Di situ juga ada fotoku dan Budi saat disandera.<br />
Jeritan teman-teman memanggil-manggil nama kami.Aku mengenali<br />
salah satu suara:<br />
Najwa Shihab. Karib ku di kantor yang rajin menyemangati setiap aku<br />
berhadapan dengan penugasan berat. Dia berlari ke arahku.Aku<br />
melepaskan diri dari kawalan sekuriti kantor. Kami berpelukan erat<br />
sekali.Kawan-kawan lain ikut memelukku.Profesi membuat kami banyak<br />
menghabiskan waktu di kantor. Membuat kami dekat seperti keluarga.<br />
Ingin rasanya aku menghabiskan waktu lebih banyak dengan mereka<br />
semua. Tetapi, sekuriti langsung menggiring aku dan Budi ke lantai tiga,<br />
menuju grand studio. Rupanya, di sana lebih banyak lagi kawan-kawan<br />
lainnya. Mereka bertepuk tangan dan memanggil-manggil, saat kami<br />
memasuki studio. Di panggung ada Virgie Baker dan Tommy Cokro, dua<br />
rekanku sesama presenter.Ternyata kantor menyiapkan siaran langsung<br />
untuk penyambutan kami. Aku dan Budi naikke panggung. Ikut pula Laras,<br />
yang memeluk erat boneka unta oleh-oleh ayahnya dari Yordania.<br />
Hening. Di keremangan, televisi berlayar lebar menayangkan gambargambar<br />
apa yang terjadi di kantor selama kami diculik.Awalnya kami<br />
hanya tersenyum melihat tingkah kawan-kawan di layar TV. Bahagia<br />
rasanya bisa bertemu kembali kawan-ka wan, handaitaulan, dan kerabat,<br />
setelah sempat berpikir bahwa dunia akan berakhir.<br />
Lambat laun, gambar pun menyingkapkan keharuan. Tiga hari<br />
setelah kami hilang kontak, kantor menyiarkan Breaking News. Prita Laura<br />
dan Virgie Baker bergantian membawakannya.Virgie melakukan siaran<br />
sambil menitikkan air mata dengan suara terbata.Gambar<br />
beralih ke suasana newsroom. Kawan-kawan yang<br />
bertangisan setiap ada kabar terbaru dari Irak. Ketika akhirnya kabar<br />
penculikan dipastikan oleh pernyataan lewat video, tangisan pun pecah di<br />
kantor.Ada kepanikan di wajah mereka. Sabtu, 19 Februari dini hari, Metro<br />
TV menyiarkan penculikan itu lewat Breaking News. Mas Helmi Yohan-nes<br />
yang membawakannya. Dia tampil tegang, tetapi mencoba tenang.<br />
Siaran dini hari itu juga ditonton Mama di rumah. Mama berpelukan<br />
erat dengan kedua kakakku, sambil memirsa siaran yang mengumumkan<br />
secara resmi aku terculik.<br />
Potongan gambar yang kami kirim sebelum penculikan, dipadu pula<br />
dengan aku tampil on sere en dibeberapa lokasi, disiarkan dalam<br />
Breaking News itu.<br />
Pada bagian lain, ditampilkan pula pernyataan Presiden, yang<br />
dibacakan tengah malam dan disiarkan Al-Jazeerah:<br />
"Saya, Doktor Haji Susiio Bambang Yud-hoyono, Presiden Republik<br />
Indonesia, menyampaikan bahwa keduawartawan itu be nar-benar<br />
menjalankan tugas sebagai jurnalis seputar pelaksanaan pemilu di Irak.<br />
Mereka samasekali tidak terlibat dalam masalah politik maupun<br />
konflikyang sedang terjadi di Irak.<br />
"Selain Presiden, ada juga pernyataan mantan presiden K.H.
Abdurrahman Wahid, mantan Ketua<br />
MPR Amien Rais, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua PMI Mar'ie<br />
Muhamad, Ketua PP Muhammadiyah Prof.Din Syamsuddin, Ketua PB NU<br />
K.H. Hasyim Mu-zadi, mantan menteri agama Dr. Quraisy Shihab, dai<br />
K.H.Abdullah Gymnastiar, dan Ustad Abu Bakar Ba1 asyir. Peran mereka<br />
selaku tokoh politik dan agama dijaminkan demi kebebasan kami. Semua<br />
satu suara bahwa kami adalah jurnalis yang bertugas murni untuk<br />
peliputan. Rupanya, setelah pernyataan Presiden disiarkan,tetapi belum<br />
ada langkah pembebasan, kantor mengupayakan pernyataan para tokoh<br />
itu, melalui stasiun Al-Jazeerah.<br />
Begitu besar perhatian itu. Membuat air mataku seolah-olah tak<br />
berhenti menggenang.<br />
Di layar aku juga melihat tim khusus Metro TV yang dipimpin Surya<br />
Paloh, berangkat ke Amman, Yordania. Kesibukan juga terjadi di<br />
Departemen Luar Negeri. Juru Bicara Marty Natalegawa banyak<br />
memberikan keterangan pers mengenai detail kejadian yang kami alami<br />
selama 168 jam di gurun. Ada pula suasana rekan kerjaku di newsroom,<br />
yang setiap sore melantunkan doabersama untuk kebebasan kami, rekan<br />
mereka.<br />
Persis pada hari pembebasan kami, suasana kantor lebih heboh lagi.<br />
Hampir semua petinggi Metro TV dan Media Indonesia ada di ruang<br />
master control, tempat seluruh tayangan dikoordinasi. Mereka berpelukan<br />
dan bertangis-tangisan mensyukuri kebebasan kami. Bahkan, ada doa<br />
syukur yang dipimpin mantan Ketua MPR Amien Rais, di Mesjid Al-Ikhsan,<br />
di kompleks kantor.<br />
Aku bersyukur, ada hikmah persaudaraan yang begitu kental di antara<br />
rekan kerja. Aku ingat ketika pertama kali memutuskan merambah dunia<br />
jurnalistik, Desember 2000. Aku memulai karier ini dari titik nol. Tertantang<br />
dengan konsep televisi berita 24 jam, aku bergabung bersama Metro TV.<br />
Tanpa pengalaman, dan tanpa latar belakang pengetahuan<br />
kewartawanan. Aku harus tandem dengan wartawan senior, untuk<br />
memulai peliputan. Belajar teknik mencari berita, mendapatkan sudut<br />
berita yang baik, juga menemukan nara sumber dan mewawancarainya.<br />
Melihat liputanku di Irak diputar, aku merasa sudah jauh berjalan.<br />
Keluarga sempat menyuruh aku mundur karena ini jauh dari pelajaran<br />
Teknik Industri yang ku dalami di Australia. Ayah ingin aku bekerja di<br />
bidang yang sesuai dengan sekolahku.Lewat pertentangan hebat, aku<br />
meluluhkan hati keluarga. Apalagi di awal liputan, aku bergelut dengan<br />
dunia teknologi. Aku meliput dan membawakan program gaya hidup era<br />
digital, e-Lifestyle.<br />
Belakangan, area liputanku banyak berkaitan dengan wilayah konflik<br />
dan bencana. Darurat Militer tahun 2003 menjadi langkah pertamaku<br />
menjejak bumi Aceh. Aku seolah-olah akrab dengan Aceh, apalagi ketika<br />
bencana tsunami melanda Desember 2004. Tsunami menjadi liputan<br />
paling berkesan dalam karierku.Selain bisa melihat sendiri dampak<br />
bencana, aku juga menemukan pengalaman yang tidak biasa, seperti<br />
lebih sering naik helikopter ketimbang naik mobil.<br />
Profesi jurnalis membuatku banyak bertemu<br />
hal-hal baru. Termasuk bersua dengan wajah duka, kepanikan,dan<br />
bermacam ketidakbahagiaan lainnya. Empati yang muncul melahirkan
kesedihan pada diriku. Apalagi akuharus menekan rasa itu, ketika muncul<br />
di layar, yang mengharuskan penampilan tetap prima.Tak jarang,aku<br />
menangis beberapa waktu setelah tugasku selesai. Seusai meliput<br />
bencana tsunami, misalnya, aku masih suka menangis mengingat<br />
penderitaan para korban. Tak terbayang suatu masa, empati atas<br />
kesedihan itu terjadi atas diriku. Perasaan bersalah, bahwa pilihan profesi<br />
telah melukai hati keluarga,kembali mencuat.Aku telah membuat Mama<br />
dan rekan kerjaku menangis dan panik. Mestinya, aku yang menanggung<br />
semua akibat dari pilihan hidupku.<br />
* * *<br />
LAMPU studio menyala benderang. Pemred Metro TV, Don Bosco<br />
Selamun, maju ke panggung. Dia membawakan seikat kembang untuk<br />
Budiyanto. Di belakangnya, Najwa Shihab memberikan kembang yang<br />
serupa untukku. Kami berpelukan berteman derai air mata. Kantor juga<br />
menyiapkan tumpengan, yang potongannya kuberikan kepada Surya<br />
Paloh dan Mama. Perjuangan dan perhatian yang diberikan oleh keluarga<br />
dan institusiku, yang sungguh di luar dugaan, membuat air mataku<br />
kembali meleleh.<br />
Setelah beberapa kata sambutan, acara penyambutan pun diakhiri.<br />
"Keluarga juga ingin menyambut mereka," begitu kata pembawa acara.<br />
Salaman,<br />
pelukan, dan suara-suara memanggil kembali terdengar. Aku<br />
ingin menyalami semuanya, ingin menyampaikan terima kasihku yang<br />
tiada terhingga.<br />
Ketika kami pulang, jalanan sudah mulai gelap. Aku dan Budi<br />
berpisah mobil. Aku semobil dengan Mama dan kakak. Tidak ada lagi<br />
ingar-bingar. Suasana di mobil hangat, tenang. Sesekali Mama menyela<br />
ketenangan dengan bercerita tentang kakek dan nenekku yang sengaja<br />
datang dari Tasikmalaya untuk menyambutku dirumah. Teh Finny<br />
menimpali bahwa saudara-saudara dari Bandung juga ikut menunggu di<br />
rumah.<br />
Aku memeluk erat Mama. Menangis di pangkuannya. Aku akhirnya<br />
pulang. Bahagia, rindu, dan rasa bersalah, berbaur menjadi satu.<br />
Sebelum terlelap, aku sempat mendengar perkataan Mama: "Di rumah<br />
sudah tersedia semur daging dan kerupuk kesukaanmu." Kantuk kian<br />
menyergap. Kelelahan fisik dan jiwa membuatku lelap di pangkuan Mama.<br />
Dalam tidurku, suara Ibrahim terngiang: "Kalau kita masih bertemu<br />
hari esok dan sampai pada keluarga masing-masing, kita harus betulbetul<br />
bersyukur kepada Allah."[]<br />
Bab 12<br />
Kapan Harus Berhenti?<br />
(Sebuah Refleksi)<br />
"Tidak ada berita yang nilainya lebih dari nyawa"<br />
KARENA karier jurnalistikku masih seumur jagung, aku senantiasa<br />
mengingatkan diri untuk tidak menantang pergi ke medan peliputan yang<br />
berat dan berisiko.Aku tak mau dengan sengaja mencari-cari, atau<br />
meminta penugasan yang berbahaya dari atasanku. Tetapi, apa bisa dan<br />
apa enaknya, seorang wartawan selamanya hanya "mengerjakan<br />
peliputan yang aman", menghindari penugasan berisiko? Ketika pada<br />
akhirnya penugasan berisiko itu datang juga padaku, selalu kuingatkan
diri bahwa nyawa dan keselamatan adalah prioritas utama.<br />
Namun, di medan peliputan, tak semudah itu menentukan garis tegas<br />
dan prioritas, antara menyelamatkan nyawa dan mengejar berita.<br />
Tantangan untuk memperoleh informasi dan visual dari dekat dengan<br />
alasan "it's not good enough, it's not close enough", tekananuntuk<br />
mendapat gambar eksklusif, hiruk pikuk di lapangan, semakin membuat<br />
adrenalin<br />
meluap-luap, menjadikan pandangan seorang wartawan kabur.<br />
Dedikasi terhadap profesi, cinta pada kegiatan reportase, tanpa disadari<br />
menjadi pembenar untuk maju selangkah lebih dekat lagi pada risiko<br />
yang bisa saja berakibat kematian. Garis batas itu semakin sulit terbaca<br />
karena, sebagai jurnalis, penilaianku kerap dikaburkan nikmatnya berada<br />
di tengah kancah sebuah berita "panas". Sebuah medan peliputan konflik<br />
atau bencana memang ibarat magnet yang menyedot seluruh perhatian,<br />
menghipnotis, memacu semangat. Hingga lupa bertanya pada diri, "kapan<br />
saya harus berhenti?"<br />
Aku harus bersyukur karena Tuhan telah mengingatkanku dengan<br />
cara halus. Penyanderaan yang kualami membuatku melihat garis batas<br />
yang sebelumnya kabur itu menjadi jelas dan terang. Juga membuatku<br />
sadar, sebagai pencari berita, aku juga bisa matidi medan tugas, dan<br />
menjadi berita. Mungkin terdengar sangat naif, tetapi risiko ini kerap<br />
terlupa ketika diri dirasuki kenikmatan meliput sebuah peristiwa. Bagiku,<br />
penyanderaan ini adalah teguran halus-Nya untuk mengingatkanku, di<br />
sinilah aku harus berhenti.<br />
Aku teringat guide kami, Muhammad Nasser, yang berteriak-teriak<br />
memintaku melepaskan serpihan bom sesaat setelah terjadi ledakan<br />
besar di pusat Kota Bagdad, Tahrir Square. Aku tidak mengindahkannya.<br />
Barang bukti itu kupegang dan kutunjukkan ke kamera sembari kukatakan:<br />
"Inilah satu rangkaian bom yang digunakan untuk meledakkan pusat Kota<br />
Bagdad, hanya beberapa kilometer dari pusat<br />
komando pasukan koalisi." Ada kepuasan (juga kebanggaan)<br />
berhasil menunjukkan kepada pemirsa benda kecil yang telah<br />
mengakibatkan kerusakan masif itu. Saking "asyiknya", tak terpikir olehku,<br />
serpihan bom tersebut masih bisa meledak di tanganku.<br />
Nasser juga membujukku dan Budi yang sibuk mengambil gambar<br />
korban ledakan, untuk segera meninggalkan lokasi. Ceceran darah dan<br />
serpihan tubuh manusia membuat Budi terpaku pada lensa<br />
kameranya,dan aku fokus mengumpulkan data. Dari sisi visual dandata,<br />
peristiwa ledakan bom ini memang sangat kuat nilai beritanya. News<br />
judgement-ku spontan mengatakan peristiwa ini akan menjadi headline<br />
berita petang kami. Dan terbukti benar, redaksi Metro TV di Kedoya<br />
menjadikan peristiwa ini berita pertama dalam program Metro Hari Ini.<br />
Begitu bersemangatnya aku dan Budi, hingga lupa untuk beberapa saat<br />
bahwa menjadi wartawan tidak berarti kami tidak bisa menambah statistik<br />
jumlah korban.Tak terpikir sama sekali, ketika itu,badanku juga bisa<br />
terburai persis seperti serpihan daging korban yang berceceran di lokasi<br />
ledakan.<br />
Karena terbukti selamat dan peliputan kami dianggap berhasil oleh<br />
redaksi di Kedoya, aku dan Budi semakin menjadi-jadi. Penugasan kedua<br />
masuk ke Irak untuk meliput perayaan Asyura di Kota Karbala kami
sambut dengan semangat. Padahal ku akui, di lubuk hati, penugasan ini<br />
amat berbahaya dengan tingkat kesulitan yang amat tinggi. Pertama, kami<br />
tidak punya akses keKarbala. Nasser yang beraliran<br />
Sunni tidak mungkin mengantar kami ke Karbala yang dihuni<br />
mayoritas kelompok Syiah. Sementara itu, menggantungkan kepercayaan<br />
dan keselamatan kami kepada orang baru akan terlalu riskan di daerah<br />
konflik seperti Irak. Kedua, Kota Karbala ketika itu tidak terjangkau sinyal<br />
teleponseluler, padahal terlalu riskan masuk ke daerah tersebut tanpa alat<br />
komunikasi. Ketiga, perayaan Asyura daritahun ke tahun kerap diwarnai<br />
insiden. Setahun sebelumnya terjadi kerusuhan yang menewaskan 200an<br />
orang.<br />
Kerusuhan, bagiku, adalah keadaan konflik yang paling berat karena<br />
polanya sulit dipahami dan dibaca. Pawai damai yang diikuti ribuan orang<br />
bisa berubah kacau dalam sekejap. Pada peristiwa Mei 1998 di Jakarta,<br />
misalnya, kelompok yang terlibat menciptakan huru-hara tidak jelas. Siapa<br />
yang menunggangi dan siapa yang ditunggangi susah diterka. Pada<br />
perayaan Asyura 2004, pihak yang diduga bermain juga beragam, mulai<br />
dari intelijen Israel Mos sad, kelompok Sunni Arab,dan kepentingan adu<br />
domba Sunni-Syiah oleh AmerikaSerikat dan Inggris. Jika benar huru-hara<br />
didasari konflik Sunni-Syiah, tentu persoalannya lebih kompleks lagi<br />
karena melibatkan emosi dan sejarah panjang pergolakan sektarian<br />
sejak awal peradaban Islam.<br />
Di tengah tantangan yang begitu berat dan tingkat keberhasilan<br />
peliputan yang kurasa tipis, aku dan Budi tetap memutuskan menjalankan<br />
penugasan itu. Entahapa yang menggerakkan kami untuk terus<br />
melangkah. Mungkin karena merasa ini suatu<br />
bentuk amanah yangharus diemban, atau karena naluri jurnalistik<br />
kamisemata. Ditambah dengan alasan "nilai berita yang kuat" dan<br />
kepercayaan pada takdir, kami maju terus.<br />
Kini, dalam pikiran jernihku, aku merasa "beruntung" dan bersyukur<br />
kami "dipaksa" berhenti oleh penyandera, sebelum terlambat. Apalagi<br />
belakangan kudengar, perayaan Asyura tahun 2005, yang sedianya<br />
hendak kuliput, memakan korban yang tidak sedikit. Sayangnya, tidak<br />
semua wartawan "sebe-runtung" aku dan Budi. Terlalu banyak rekan<br />
jurnalis yang berhenti ketika sudah terlambat. Setelah maut menyergap.<br />
Pengalaman di Irak membuatku kerap diundang lembaga-lembaga<br />
internasional, mendiskusikan masalah keselamatan jurnalis. Di situ pula<br />
aku berkenalan dengan Sarah de Jong dari International News Safety<br />
Institute (INSI), yang mendata semua wartawan yang mati atau mengalami<br />
kekerasan dalam peliputan di berbagai belahan dunia. Sebagian besar<br />
adalah wartawan senior,wartawan pilihan yang sudah memiliki jam<br />
terbang cukup tinggi. Sebagian sudah dilengkapi standar pengamanan<br />
terbaik, termasuk menggunakan jasa bodyguard dan security consultant.<br />
Semua kemewahan tersebut menjadi tak berarti karena mungkin lupa<br />
bertanya pada diri sendiri, kapan harus berhenti. Industripers kehilangan<br />
banyak orang terbaiknya di garis depan, kadang karena kesalahan sepele.<br />
Kenyataan pahit yang mengerikan.<br />
Melihat statistik itu, aku jadi merasa bodoh<br />
karena tidak merasa takut ketika berangkat ke Irak. Bukan berarti aku<br />
menyesal telah menerima penugasan ini, tidak. Naluri jurnalistikku pasti
tetap menerima penugasan ini dengan bersemangat. Hanya saja, sedikit<br />
"rasa takut" mungkin dapat membantuku membaca garis batas yang jelas<br />
ketika asyik meliput di medan berbahaya. Mungkin aku tidak akan<br />
mengangkat serpihan bom secara refleks ketika mengetahui bahwa<br />
benda tersebut sebenarnya masih bisa meledak. Mungkin sedikit "rasa<br />
takut" adalah sisi manusiawi yang penting kumiliki ketika memasuki<br />
daerah konflik untuk membuatku mampu menjawab "kapan saya harus<br />
berhenti".Ketidakkhawatiranku di awal penugasan kuanggap sebagai<br />
sikap positive thinking yang baik,tetapi membuatku kurang cermat<br />
mencerna kemungkinan buruk.<br />
Sebagai seorang anchor, aku sudah sering membawakan berita<br />
penyanderaan wartawan di Irak. Tetapi, aku tidak membayangkan aku dan<br />
Budi berada dalam kondisi tersebut. Aku berangkat dengan semangat<br />
tinggi dan kesiapan yang, menurutku saat itu, bulat. Tetapi, betulkah aku<br />
sudah siap?<br />
Hari-hari panjang penyanderaan di gua memberiku banyak waktu<br />
untuk merenung, menyadari, dan akhirnya mengakui bahwa sepanjang<br />
perjalanan jurnalistikku, aku mungkin belum pernah betul-betul siap<br />
dalam peliputan. Pemimpin dan seniorku di Metro TV kerap memuji. Aku<br />
selalu siap dan tidak pernah menolak tugas, aku siap dengan fisikku yang<br />
tahan banting, aku siap dengan berbekal ilmu dan daya nalar yang cukup<br />
baik, aku siap dengan kemampuan<br />
lobi menembus narasumber,aku siap dengan kelincahan dan<br />
kelihaianku mengemas sebuah berita menjadi menarik, aku tidak pernah<br />
gentar masuk daerah konflik. Aku siap dengan logistik dan teknologi<br />
pendukung, tetapi siapkah aku? Ternyata belum.<br />
Ketika meninggalkan Jakarta menuju Irak, secara fisik dan mental aku<br />
memang siap meliput. Tetapi, aku belum siap dengan berbagai<br />
konsekuensinya, termasuk menghadapi kemungkinan terburuk: kematian.<br />
Aku baru bisa mengatakan betul-betul siap meliput di daerah konflik hanya<br />
ketika aku siap dengan kemungkinan terburuk itu. Ini bukan berarti aku<br />
bersedia mati untuk sebuah berita, melainkan semata memahami dan<br />
siap menghadapi risiko itu, jika ditakdirkan. Berada dalam tangan<br />
kelompok penyandera membuatku mengerti arti siap yang sebenarnya.<br />
Sayangnya, aku baru menyadarinya ketika memang tak punya pilihan lain,<br />
selain mempersiapkan diri untuk risiko terburuk: kematian.<br />
"Kalau di peluru itu tidak tertera nama kita, ya kitatidak akan kena,<br />
Mut." Ucapan Budi ini menjadi modal keberanianku selama bertugas di<br />
Irak. Ber-sandarkan kepasrahan dan kepercayaan pada takdir, aku melaju<br />
tanpa takut. Yang aku lupa, pasrah adalah penyerahan diri, setelah usaha<br />
maksimal dilakukan.<br />
Seorang tentara Irak pernah bertanya padaku danBudi ketika kami<br />
meliput. "Kenapa tidak memakai rompiantipeluru?" Kujawab, "Tidak<br />
punya." Dia bertanya lagi, "Kenapa tidak memakai helm anti peluru?"<br />
Jawabanku sama, "Tidak punya." Penasaran dia bertanya lagi,<br />
"Lalu apa pelindung kalian?" Aku dan Budi menjawab mantap: "Bismillah!"<br />
Budi mengeluarkan Al-Quran kecilnya dari saku dan menempelkannya di<br />
kening.Tentara dengan pengamanan lengkap, helm dan rompi anti peluru<br />
serta senjata laras panjang itu, tertawa. Sebagai seorang Muslim yang<br />
juga percaya takdir, dia agak sulit mendebat alasan kami.
Bermodalkan "Bismillah" dan "La haula wa laquw wata illa billah",<br />
kami juga tegar keluar masuk daerah zona merah yang berbahaya.<br />
Sebelum berangkat ke Irak, aku memang kurang bersimpati terhadap cara<br />
peliputan beberapa televisi asing yang dikenal dengan hotel journalism.<br />
Wartawan melaporkan langsung dari hotel, dengan data-data yang<br />
disiapkan oleh stringer, orang lokal yang membantu mencari data dan<br />
rekaman visual. Reporter tersebut biasanya menambahkan perspektif dan<br />
analisis dalam laporannya, seolah-olah dia terjun langsung dan<br />
mengetahui persis fakta di lapangan. Aku tidak mau demikian. Aku dan<br />
Budi, ditemani Nasser, sengaja masuk ke zona merah, mencoba<br />
menggali informasi dan melihat langsung bagaimana masyarakat<br />
memandang pelaksanaan pemilu pertama di Irak pasca kejatuhan<br />
Saddam Hussein. Lagi-lagi hanya berbekal kepasrahan dan keyakinan<br />
akan takdir. Salahkah?<br />
Tidak ada salahnya pasrah dan bergantung pada takdir. Bahkan<br />
bagiku, itu adalah keniscayaan, salah satu modal utama yang<br />
membantuku berhasil<br />
menuntaskan berbagai tugas reportaseku. Hanya saja, kalau boleh<br />
aku mewakili kecenderungan orang Indonesia pada umumnya, sikap ini<br />
kadang cenderung membuat kita tidak berhati-hati dan menyerahkan<br />
semuanya padatakdir. Menyepelekan masalah, tanpa diiringi usaha<br />
maksimal.<br />
Padahal, banyak yang bisa disiapkan sebelum keberangkatanku ke<br />
kawasan konflik seperti Irak. Jaket pengaman dan helm antipeluru,<br />
misalnya. Umumnya halini tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan<br />
anggaran. Bagi sebuah stasiun televisi Indonesia, mengirimkan krunya<br />
untuk meliput ke Irak, dengan perhitungan memberikan laporan langsung<br />
minimal satu kali sehari,sudah merupakan suatu kemewahan. Atau,<br />
kalaupun perusahaan pers tertentu sebenarnya telah memilikiperangkat<br />
lengkap peliputan di kawasan konflik, sangwartawan Indonesia sengaja<br />
tidak membawanya, dengan berbagai alasan. Ribet dan berat, biasanya,<br />
menjadi alasan utama. Tanpa perangkat pengamanan liputan tadi,aku<br />
sendiri dan Budi merasa sudah mempersiapkan segalanya secara<br />
maksimal meskipun tidak seratus persen. Dan, modal utama yang kami<br />
persiapkan cukup baik adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap<br />
medan peliputan.<br />
Sepulangku dengan selamat dari Irak, aku banyak berdialog dengan<br />
aktivis lembaga yang menangani persoalan wartawan di kawasan konflik,<br />
seperti International News Safety Institute (INSI). Aku juga berdiskusi<br />
dengan seorang trainer perusahaan security consultant, AKE. Dari mereka<br />
aku mendapat<br />
pelajaran bahwa modal utama jurnalis ketika memasuki daerah<br />
konflik bukan peralatan komunikasi atau pun keamanan, melainkan<br />
knowledge, yakni pengetahuan atau pemahaman terhadap medan<br />
peliputan, baik wilayah maupun sosiokultural warganya. "Knowledge is the<br />
mostvaluable safety material,"kata Peter Williams,wartawan CNN yang<br />
meliput huru-hara di Bradford, Inggris,tahun 2001.<br />
Dalam penugasanku, peran Budiyanto sangat besar. Sebelum<br />
bertugas bersamaku, Budi sudah dua kali masuk ke Irak dan memiliki<br />
memori yang kuat mengenai lokasi lokasi penting di sana. Budi juga
membuka banyak akses melalui Nasser, yang sudah dikenalnya sejak<br />
tahun 2003. Berbekal pemahaman Budi itulah, kami putuskan masuk ke<br />
Irak melalui jalur darat, dengan berbagai pertimbangan, bukan sebuah<br />
keputusan asal-asalan.<br />
Pemahaman mengenai sensitivitas konflik Sunni-Syiah amat<br />
membantu kami menghadapi penyanderaan. Ibrahim menjelaskan, lokasi<br />
penculikan kami adalah Ramadi. Aku teringat catatanku, Ramadi adalah<br />
basis kelompok Sunni. Karena itu, ketika para penyandera menanyakan<br />
tujuan peliputan kami di Irak, aku langsung menjawab: meliput pemilu.<br />
Jika saja kami menjelaskan tujuan sebenarnya, yaitu meliput Asyura yang<br />
biasa diperingati warga Syiah, tentu bisa berakibat fatal. Konflik sektarian<br />
di Irak kembali menguat pasca-invasi Amerika.<br />
Namun, pemahaman dan pengetahuan, yang awalnya kurasa sudah<br />
cukup, ternyata belum. Soal penculikan, misalnya. Ketika kami<br />
memutuskan kembali<br />
kelrak melalui jalur darat, hanya selintas kemungkinan risiko<br />
diculik mampir di kepala kami. Risiko terburuk yang banyak aku dan Budi<br />
diskusikan malah soal penghadangan oleh sekelompok orang yang biasa<br />
meminta uang di perjalanan, yang dikenal dengan sebutan Ali Baba. Jika<br />
sudah dibayar, mereka akan membiarkan kami lewat. Risiko lain adalah<br />
masuk ke wilayah pertempuran antara kelompok perlawanan dan<br />
pasukan koalisi, dan kami terjebak di antara mereka. Perjalanan darat<br />
juga berisiko menginjak ranjau, atau menjadi korban bom mobil. Tetapi<br />
soal risiko penculikan, lagi-lagi, hanya melintas sekelebat. Entah kenapa,<br />
padahal sudah sering terjadi penculikan, termasuk pada wartawan di Irak,<br />
dan aku kerap pula membacakan beritanya di layar Metro TV.<br />
Setelah penyanderaan itu, aku rajin membaca buku tentang peliputan<br />
di daerah konflik, yang umumnya disusun berdasarkan pengalaman<br />
jurnalistik. Dari buku-buku itu pula kuketahui dua kategori penyanderaan:<br />
surprise attack atau serangan dadakan dan planne dattack atau<br />
penyanderaan terencana. Kasusku dan Budimasuk kategori pertama.<br />
Kasus Ferry Santoro dan almarhum Ersa Siregar dari RCTI, yang<br />
disandera kelompok Gerakan Aceh Merdeka, bisa dimasukkan kategori<br />
kedua. Pada penyanderaan terencana, penyandera biasanya menjebak<br />
wartawan dengan iming-iming untu kmewawancarai atau mendapat<br />
peliputan eksklusif.<br />
Aku juga mengenal berbagai motif penyanderaan, mulai dari<br />
komoditas politik, komoditas ekonomi,<br />
balas dendam, sandera untuk jaminan keamanan bagi<br />
penyandera, hingga kemungkinan salah tangkap. Walau terkesan sepele,<br />
ketika berada dalam penyanderaan, mengenali motif adalah hal penting.<br />
Penyanderaan ku dan Budi kemungkinan besar bermotif politik, yaitu untuk<br />
meraih atensi luas dari dunia internasional. Adapun motif penyanderaan<br />
terhadap wartawan media Barat biasanya lebih kompleks lagi. Bisa saja<br />
motif politik, ekonomi (permintaan uang tebusan), balas dendam terhadap<br />
kebijakan pemerintah asal si wartawan, atau sandera untuk jaminan<br />
keamanan di penculik, bercampur aduk.<br />
Mengenali motif penculikan tentu akan membantu menentukan<br />
langkah apa yang harus diambil. Dalam kasusku dan Budi, penyandera<br />
hanya memanfaatkan kami sebagai komoditas politik. Karena itu, kami
sebagai sandera tak perlu berpikir keras melarikan diri. Sebab,<br />
kemungkinan besar kami dibebaskan. Lain halnya dengan para sandera<br />
dari Eropa dan Amerika Serikat. Kemungkinan dibebaskan penyandera<br />
teramat kecil sehingga dianjurkan untuk escape (melarikan diri).<br />
Pengalaman penyanderaan di Irak juga menya-darkanku bahwa<br />
kelengkapan berbagai peralatan keamanan tidak akan membantu tanpa<br />
pendekatan "hati". Keberingasan para penyandera memang sempat<br />
membuatku takut setengah mati. Langsung terbayang di kepalaku<br />
bagaimana tayangan televisi memperlihatkan kelompok penyandera<br />
memenggal kepala sandera. Aku coba melawan stigma itu dengan<br />
meyakinkan diri bahwa mereka juga manusia<br />
yang memiliki nurani. Seberbeda apa pun pandangan dan cara hidup<br />
mereka, sebagai manusia, aku yakin mereka dan kami memiliki beberapa<br />
persamaan nilai, terutama menyangkut keluarga.<br />
Kami cukup berhasil mencairkan suasana ketika aku dan Budi<br />
mengeluarkan foto keluarga, sekaligus menanyakan perihal keluarga<br />
mereka. Dari sosok yang beringas dan keras, tiba-tiba mereka melunak<br />
saat bercerita tentang anak dan ibu mereka. Dan rupanya, mereka adalah<br />
orang-orang yang merasa terpinggirkan, tak pernah mendapat perhatian<br />
dan penghargaan yang layak dalam keseharian mereka. "Strategi" saling<br />
mencurahkan isi hati seputar keseharian kami ternyata berhasil menjebol<br />
tembok kekakuan. Sejak itu, moncong senjata tidak lagi diarahkan kepada<br />
kami walau mereka tetap siaga. Aku bersyukur, di tengah kepanikan<br />
danketakutan, Tuhan memberiku ketenangan, untuk melihat para<br />
penyandera bukan sebagai penjahat atau teroris. Di balik aksi perlawanan<br />
dan kekerasan yang mereka lakukan, ternyata mereka juga manusia<br />
biasa yang berhati nurani. Aku tidak setuju cara perjuangan mereka<br />
dengan menculik kami atau wartawan dan pekerja asing lain. Namun,<br />
mereka tentu punya alasan kuat untukmelakukannya.<br />
Keluhan Rois (pemimpin penyandera), bahwa media tidak adil dan<br />
cenderung memojokkan mereka, kurenungkan selama penyanderaan.<br />
Pergeseran nilai keterlibatan media dalam meliput daerah konflik<br />
memang semakin terasa. Dulu, wartawan dilindungi berbagai pihak, kini<br />
justru menjadi target sandera<br />
dan pembunuhan. Konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan<br />
terhadap sipil kerap tidak diindahkan lagi. Dalam konvensi itu, disebutkan<br />
bahwa wartawan mempunyai hakyang sama sebagai warga sipil, untuk<br />
mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, pembunuhan,<br />
pemenjaraan, dan penyiksaan. Pihak yang melanggar hak-hak wartawan,<br />
dari pihak militer atau pun milisi, dapat dituntut sebagai penjahat perang.<br />
Kesepakatan yang dibentuk tahun 1949 dan diratifikasi oleh hampir<br />
semua negara ini tak lagi mampu melindungi wartawan di kawasan<br />
konflik.<br />
Yang menyedihkan, kenyataan ini kerap tidak lepas dari ulah<br />
wartawan sendiri. Distorsi fungsi wartawan sebagai pihak yang mestinya<br />
"netral" sesungguhnya sudah terjadi sejak perang Vietnam. Wartawan,<br />
tidak hanya yang berkebangsaan Amerika yang ketika itumemang tengah<br />
memerangi Vietnam, ikut memakaiseragam militer dan angkat senjata.<br />
Perang Teluk tahun 1991 juga menjadi catatan penting dalam pergeseran<br />
nilai wartawan. Ketika itu, reporter televisi Amerika dan Inggris tampil di
layar, melaporkan langsung dengan memakai atribut militer. Mereka biasa<br />
disebut wartawan embedded, yang mengenakan kelengkapan seragam<br />
militer. Di Kandahar, Walter Rodgers, seorang wartawan CNN,<br />
melaporkan dari kamp tentara Amerika memakai seragam US Marine. Hal<br />
yang sama dilakukan Geraldo Rivera, reporter Fox News. Ketika tiba di<br />
Jalalabad, diamenenteng senjata dengan target ikut memburu Osama bin<br />
Laden. Rivera telah bergesar jauh dari<br />
fungsinya sebagai seorang reporter, menjadi seorang combatant.<br />
Detik itu juga, gugur semua haknya sebagai jurnalisyang dilindungi<br />
konvensi Jenewa.<br />
Semakin banyak kupelajari tentang keselamatan jurnalis, semakin<br />
sering kulihat, insiden buruk yang menimpa wartawan kerap bermula dari<br />
kesalahan kecil dan sepele. Terakhir, kematian rekan Muhamad Guntur<br />
Saefullah, juru kamera SCTV, dan Suher-man, juru kamera Lativi, dalam<br />
tragedi tenggelamnya kapal Levina, membuatku terpukul. Kalau saja<br />
Guntur dan Suherman memakai pelampung, tanpa bermaksud<br />
mempertanyakan takdir, mungkin karya-karya jurnalistik mereka masih<br />
dapat kita nikmati. Lebih terpukul lagi, aku melihat kepiluan yang<br />
dirasakan keluarga kedua wartawan itu. Langsung ku-teringat Mama dan<br />
keluargaku yang juga mengalami masa-masa sulit selama<br />
penyanderaanku. Begitu egoisnyakah aku? Begitu egoisnyakah para<br />
wartawan yang memperjuangkan sebuah gambar eksklusif dengan risiko<br />
kematian, dan melupakan dampak buruknya bagi orang-orang yang<br />
mencintai mereka? Ataukah ini semata bentuk pengorbanan wartawan<br />
terhadap profesinya?<br />
Peristiwa tertembaknya dua wartawan perang yangsangat dihormati<br />
karena pengalaman dan kemampuannya "membaca" medan, Kurt Shorck<br />
(Reu ters) danMiguel Gil Moreno (Associated Press), menjadi peringatan<br />
untukku. Shorck dan Moreno, yang ditugasimeliput konflik di Sierra Leone<br />
pada tahun 2DDD, memutuskan untuk masuk hingga melewati garis<br />
depan walaupun telah menerima laporan<br />
mengenai bahaya didaerah tersebut. Bahkan jurnalis terbaik pun,<br />
ketika sudah berada di medan liputan, kesulitan<br />
menemukankeseimbangan antara insting untuk menyelamatkan diridan<br />
keinginan untuk memperoleh berita eksklusif.<br />
Perjalanan 168 jam dalam penyanderaan men-yadarkanku, betapa<br />
pengetahuan dan keberanian tidaklah cukup sebagai modal wartawan<br />
perang. Yang lebih penting lagi adalah kemampuan untuk mengendalikan<br />
diri: kapan kita harus melangkah di tengah bahaya dankapan saatnya<br />
berhenti. Berhenti, bukan hanya untuk dirisendiri, melainkan juga untuk<br />
orang-orang yang mencintai dan menunggu kepulangan kita, dengan<br />
selamat.<br />
Aku teramat bersyukur dan tersanjung ketika keluargaku, kawankawan<br />
seprofesi, dan pemimpin bangsaku, dengan tulus mengupayakan<br />
dan mendoakan pembebasanku dari penculikan, akibat keteledoranku.<br />
Terimakasih atas doa dan air mata yang memudahkan langkahku kembali<br />
ke tanah air, kembali ke pelukan orang-orang yang mencintaiku.[]<br />
Lampiran<br />
Pergolakan Sebuah Ruang Redaksi<br />
Oleh Don Bosco Selamun Pemimpin Redaksi Metro TV 2004-2005
BERITA itu membuat seisi ruang redaksi gaduh dan panik. Ada yang<br />
histeris, ada yang menangis. Sebagian tertegun, tertunduk lesu. Raut<br />
sedih merebak seantero ruangan yang sesak. Di ruang pengendali<br />
siaran, kegaduhan lebih terasa. Sesungguhnya kegaduhan dan<br />
kepanikan biasa terjadi saat menayangkan breaking news. Tapi kali ini<br />
bercampur ketidakpastian, perasaan getirdan sedih. Karena yang<br />
diberitakan adalah nasib Meutya Viada Hafid dan Budiyanto, wartawan<br />
MetroTV, sahabat kami sendiri. Keduanya dinyatakan hilang ketika meliput<br />
pemilihan umum di Irak.<br />
Hari itu, Jumat, 18 Februari 2DDS. Empat jam sebelumnya, di tengah<br />
rapat kerja Metro TV di Hotel Hilton (kini Hotel Sultan), seseorang berbisik<br />
kepada saya. "Bang, ada berita dari Deplu, dari Pak Marty. Meutya dan<br />
Budiyanto hilang di Irak. Bang Don diminta ke Deplu," kata Henny<br />
Puspitasari. Hen ny adalah PR Manager Metro TV yang pertama kali<br />
menerima kabardari Marty Natalegawa, Juru Bicara Kementerian<br />
LuarNegeri saat itu.<br />
Serasa disambar petir saya mendengarnya. Saya tinggalkan ruangan<br />
raker dengan gugup. Sekujur tubuh terasa dingin, badan lemas. Menyusul<br />
kemudian Zsa Zsa Vusaryahya, Direktur Programming dan PR, yang juga<br />
diberitahu Henny. Beberapa manager dari divisi pemberitaan, Claudius<br />
Boekan, Desi Anwar, Makroen Sandjaya, Bambang Hamid, Retno Shanti,<br />
dan UsiKarundeng susul-menyusul keluar ruangan. Dan dilorong depan<br />
pintu tempat raker berlangsung, saya sampaikan kabar ini. Mereka<br />
terkejut.<br />
Di tengah ketidakpastian tentang nasib Meutya dan Budi, begitu<br />
keduanya biasa dipanggil, kami menggelar koordinasi darurat di lorong<br />
itu. Zsa Zsa dan Desi Anwar bertugas menyampaikan kabar ini kepada<br />
keluarga Meutya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Claudius Boekan,<br />
manager peliputan, balik ke Kantor Metro TV, memimpin para kordinator<br />
peliputan (korlip) melacak posisi Meutya dan Budi. Juga memberitahu<br />
keluarga Budiyanto di Rawamangun, Jakarta Timur.<br />
Makroen Sandjaya, manager produksi, juga balik kekantor<br />
menyiapkan berita jika peristiwa ini benar terjadi. Endah Saptorini,<br />
manager Current Affairs, membantu Makroen dan timnya. Sementara<br />
Helmy Vohanes, Services Manager, diminta menghubungi televisi-televisi<br />
asing. Praktis, hanya Bambang Hamid, sekretaris redaksi, dan Retno<br />
Shanti, manager News Magazine,yang tersisa untuk mewakili Divisi<br />
Pemberitaan mengikuti raker yang mestinya berakhir sebelum makan<br />
sianghari itu. Bersama Usi Karunde-ng, saya bergegas<br />
menujuDepartemen Luar Negeri, di Jl Pejambon, Jakarta Pusat.<br />
* * *n<br />
MEUTYA dan Budi hilang?" Itulah pertanyaan pertama yang memagut<br />
kepala saya ketika pertama kali mendengar berita itu dari Henny.<br />
"Bagaimana nasib kedua anak buah saya itu?" Pertanyaan kedua ini<br />
merangsang adrenalin kecemasan yang membuat saya limbung. "Tuhan,<br />
lindungi kedua sahabat saya yang telah berkorban meninggalkan<br />
keluarga untuk melaksanakan tugas yang telah saya bebankan ke pundak<br />
mereka. "Hanya itu untaian doa singkat mengiringi perasaan cemas yang<br />
menekan batin.<br />
Ini kali pertama selama lebih dari 20 tahun karier kewartawanan saya,
saya dipanggil ke Deplu. Lagi pula, sangat jarang Deplu bersangkut paut<br />
dengan pemanggilan seorang pemimpin redaksi, kecuali coffee<br />
morninguntuk menyampaikan berita-berita baru.Itu pun biasanya ramerame<br />
dengan wartawan lain. Karena itu, insting saya mengatakan<br />
"sesuatu yang genting," telah terjadi. Tetapi, apakah "sesuatu yang buruk"<br />
telahmenimpa Meutya dan Budi?<br />
Menghadap Deplu saya siapkan berbagai bahan. Saya hubungi<br />
kembali Claudius Boekan untuk mengumpulkan semua catatan dari para<br />
Korlip tentang posisi perjalanan Meutya dan Budi, dari awal hingga data<br />
paling akhir. Laporan yang dibuat Claudius<br />
Boekan di crosscheck dengan laporan langsung dari para Korlip.<br />
Hampir semua Korlip ketika itu, Dadi R. Sumaatmadja,Budiyono, Muchlis<br />
Ainurrofiq, Muzakkir Hussain, Ferry Putra Utama, saya hubungi untuk<br />
mendapatkan gambaran tentang jejak Meutya dan Budi, hingga kontak<br />
terakhir dengan keduanya selama meliput di Irak.<br />
Dari para Korlip diperoleh gambaran bahwa kontak terakhir dengan<br />
Meutya dan Budi terjadi tanggal 14Februari, sore hari waktu Jakarta, atau<br />
siang hari waktu Amman, Yordania. Kontak itu terjadi ketika keduanya<br />
tengah mengurus visa di Amman, hanya beberapa saat sebelum kembali<br />
ke Bagdad. Visa sebelumnya hanyasingle trip rupanya. Penugasan untuk<br />
balik ke Irak, langsung berasal dari saya sebagai pemimpin redaksi.<br />
Seingat saya, ketika mendengar Meutya dan Budi sudah kembali ke<br />
Amman, dengan keras saya meminta Dadidan Claudius untuk<br />
menugaskan kembali Meutya danBudi ke Irak, meliput hari raya Asyura di<br />
Karbala. Lagi pula, hasil pemilu Irak belum tuntas. Padahal keduanya<br />
sangat produktif.<br />
Laporan Korlip menjelaskan, kontak selanjutnya tidak ada lagi.<br />
Alasannya, kemungkinan ada blank spotarea dalam perjalanan dari<br />
Amman menuju Bagdad. Kemungkinan serupa terjadi dalam perjalanan<br />
dari Bagdad menuju Karbala, kota terakhir tujuan peliputan Meutya dan<br />
Budi. Seluruh catatan kontak dengan keduakru sebelum tanggal 14<br />
Februari itu tercatat lengkap dilog book Korlip. Log book adalah catatan<br />
harian yangsangat rinci tentang A sampai Z kegiatan seluruh kru yang<br />
bertugas di lapangan.<br />
Sedangkan semua laporanlangsung yang mereka sajikan selama<br />
bertugas di Irak, tercatat rapi dalam run down berbagai progam berita<br />
rutin.<br />
Usai mendapatkan rekam jejak kedua kru ini, saya menelepon Surya<br />
Paloh, pemilik Metro TV."Ada apa Don?" jawab Surya Paloh, seperti<br />
biasanya, dengan nada bariton.<br />
"Ada berita buruk, Bang," kata saya gugup.<br />
"Berita buruk apa?"<br />
"Bang, tiga hari ini kita kehilangan kontak dengan Meutya dan Budi<br />
yang meliput di Irak. Menurut orang Deplu, keduanya hilang di Irak," kata<br />
saya. "Kenapa?"<br />
"Belum tahu, Bang. Cuma selama ini Korlip menghubungi mereka<br />
dan tidak dapat berkomunikasi dengan keduanya. Asumsi kita, mereka<br />
mungkin berada diblank spot area. Saya sekarang ke Deplu. Mereka juga<br />
mendapat kabar dari jaringannya telah kehilangan kontak dengan Meutya
dan Budi," saya jelaskan detil yang saya ketahui.<br />
"Oke, Don. Kita harus ambil semua langkah yang diperlukan. Jangan<br />
pikirkan biaya." Surya meminta saya segera menemuinya seusai<br />
pertemuan di Deplu.<br />
Saya dan Usi tiba di Deplu sebelum pukul 11. ?D. Kami langsung<br />
bertemu Marty Natalegawa. Pertanyaan demi pertanyaan pun meluncur<br />
dari mulut Marty. Benarkah Metro TV mengirim wartawan bernama Meutya<br />
Hafid dan Budiyanto ke Irak? Untuk tujuan apa? Apakah ada agenda<br />
politik? Sudah berapa lama Metro TV tidak dapat berkomunikasi dengan<br />
keduanya? Saya amati wajah Marty tampak<br />
sangat serius. Pertanyaan terakhir, sangat penting. Karena tidak saja<br />
tentang posisiterakhir Meutya dan Budi, tetapi juga bagaimana kondisi<br />
terakhir kedua kru Metro TV ini. Siapa tahu, Deplu mendapat informasi<br />
lebih cepat dan langsung dari tanganpertama.<br />
"Jaringan kami melaporkan bahwa kedua wartawan Metro TV itu<br />
kehilangan kontak. Kita juga berupaya mendapatkan hubungan dengan<br />
mereka," kata Marty sambil menjanjikan perlunya kerja sama untuk<br />
mencari kedua wartawan ini.<br />
Marty menjelaskan tentang arti "kehilangan kontak". Dia kemudian<br />
membawa Usi dan saya bertemu Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda.<br />
Dalam percakapan yang berlangsung 3D menit, Menlu berjanji untuk<br />
memanfaatkan saluran-saluran diplomatik agar segera mengetahui nasib<br />
Meutya dan Budi. Sesuai penjelasan yang saya berikan, Menlu kemudian<br />
mengkonfirmasikan kembali bahwa penugasan Meutya dan Budi benarbenar<br />
penugasan jurnalistik, tidak ada maksud politik di belakangnya.<br />
Kesimpulan ini rupanya penting, sebagai dasar bagi Deplu untuk menjalin<br />
kontak lebih lanjut melalui jaringan-jaringan yang tersedia.<br />
Pertemuan dengan Deplu itu memastikan bahwa Meutya dan Budi<br />
"kehilangan kontak" dengan Metro TV, keluarga mereka, dan dunia luar.<br />
Makna "kehilangan kontak," seperti dijelaskan Marty, mengandung<br />
beberapa kemungkinan. Mungkin karena blank spotarea, mungkin diculik,<br />
tetapi mungkin juga ini yang terburuk tewas karena konflik yang<br />
berkecamuk dilrak. "Tetapi, mudah-mudahan tidak terjadi<br />
sesuatu yang buruk," kata Marty.<br />
Dua kemungkinan terakhir yang diungkap Marty membuat saya shock.<br />
Usai pertemuan, saya coba menepis kemungkinan terburuk itu, atau<br />
kemungkinan diculik kelompok tertentu di Irak. Tetapi pikiran itu tetap<br />
melekat di kepala sepanjang perjalanan dari Deplu hingga kantor Metro<br />
TV, di kawasan Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Perjalanan terasa<br />
begitu lama.<br />
Perasaan yang paling membebani pikiran adalah, bagaimana cara<br />
saya mempertanggungjawabkan penugasan ini kepada keluarga Meutya<br />
dan Budi? Bagaimana pula mempertanggungjawabkan penugasan ini<br />
kepada awak redaksi dan rekan-rekan di tingkat manajemen, termasuk<br />
Surya Paloh, pemilik Metro TV? Lalu, bagaimana menjelaskan kepada<br />
publik, bahwa ini benar-benar tugas professional? Jangan sampai<br />
mengesankan bahwa saya, dan beberapa rekan yang menugaskan<br />
Meutya dan Budi ke Irak, dinilai salah secara profesional. Soalnya Irak<br />
layak menjadi berita di satu sisi, tetapi memang, sangat berbahaya karena<br />
konflik dan perang di sisi lain.
Dalam perjalanan, saya hubungi Makroen, An-drianus Pao, Agus<br />
Guna Diatmika, Wayan Eka Putra dan beberapa produser untuk<br />
menyiapkan breaking news. Disamping karena sudah mendapatkan<br />
konfirmasi dari Deplu, kantor berita asing, APTN (Associated Press<br />
Television News) juga sudah memberitakan hilangnya Meutya dan Budi,<br />
walaupun kantor berita yang berpusatdi London itu belum mendapatkan<br />
gambar.<br />
Makin dekat ke kantor Metro TV, saya mencoba sekuat tenaga<br />
menghilangkan pertanyaan-pertanya an apologetik itu. Langkah awal yang<br />
harus diupayakan adalah bagaimana dapat berkomunikasi dengan<br />
Meutya dan Budi, karena faktanya adalah kami "kehilangan kontak." Tetapi,<br />
jika kemungkinan paling buruk yang terjadi tewas tertembak di daerah<br />
perang oh, betapa pahitnya mulut saya yang menugaskan kedua rekan ini<br />
ke daerah bahaya. Sesaat itu pula saya merasa menjadi seorang<br />
pemimpin redaksi paling bodoh, karena lalai menghitung risiko sebesar<br />
ini.<br />
Sambil memikul beban perasaan itu saya masuki ruang redaksi.<br />
Saya minta Bambang Hamid, sekretaris redaksi, mengumpulkan seluruh<br />
kru pemberitaan. Seluruh direksi, Ana Wijaya, Lestari Luhur, John<br />
Balonso, dan Zsa Zsa Yusaryahya juga hadir. Saya umumkanhasil<br />
pertemuan dengan Menlu Hassan Wi-rajuda. Semua diam. Saya minta<br />
semuanya berdoa menurut keyakinan masing-masing memohon<br />
keselamatan jiwa dan raga kedua sahabat ini. Semoga tidak terjadi<br />
sesuatu yang buruk atas keduanya. Sangat nyata di ruangan itu, betapa<br />
semua awak Metro TV, memperlihatkan rasa kebersamaan yang luar<br />
biasa.<br />
Saya kemudian mengumpulkan semua korlip, produser eksekutif,<br />
produser dan para manajer di lingkungan divisi pemberitaan. Saya minta<br />
pandangan mereka tentang langkah konkret yang bisa segera ditempuh<br />
agar secepatnya bisa berkomunikasi<br />
dengan Meutya danBudi. Pertemuan kilat itu memutuskan beberapa<br />
langkah.Pertama, mencari liason of ficer di Irak atau Yordaniayang<br />
mempunyai akses luas ke berbagai kelompok dilrak. Tentang itu, Mauluddin<br />
Anwar, produser MetroHari Ini, menyebutkan nama Mohammad<br />
Nasser. Menurut beberapa rekan, Nasser mempunyai hubungan yang<br />
luas dengan beberapa kelompok di Irak. Sejumlah biaya perlu<br />
dipersiapkan untuk operasionalnya.<br />
Kedua, membentuk kelompok khusus yang fasih berbahasa Arab.<br />
Mereka bertugas mengakses seluruh informasi berbahasa Arab, baik<br />
memonitor siaran radio, televisi, koran, maupun mengais data dan<br />
informasi viain ternet, berbagai milis dan lain-lain, khususnya yang<br />
berbahasa Arab. Lebih khusus lagi memantau siaran Al-Arabiyah dan Al-<br />
Jazeerah. Tim ini sekaligus ditugaskan untuk selalu berhubungan dengan<br />
kedua stasiun televisiitu. Kedua orang yang dikontrak khusus masingmasing<br />
Sugiri dan Mohamad Syarif. Sugiri pernah dikontrak Metro TV, dan<br />
Syarif dikontrak stasiun TV-7 (sekarangTrans 7) sebagai penerjemah<br />
simultan berita-berita Al-Jazee rah ketika tentara sekutu menyerang Irak.<br />
MetroTV mempunyai dua produser yang fasih berbahasa Arab, yaitu<br />
Mauluddin Anwar dan Muchlish Ainurrofiq.<br />
Ketiga, membentuk tim khusus untuk berhubungan dengan Deplu
yang juga sudah membentuk tim khusus. Keempat, mengutus pimpinan<br />
untuk segera berangkat kelrak. Kelima, menjalin hubungan dengan<br />
beberapa tele-visi seperti CNN, Al-Jazee rah, Al-Arabiyah, kantor berita<br />
televisi asing seperti<br />
APTN dan Reuters, yang mempunyai peliputan luas di Irak. Keenam,<br />
tim bekerja 24 jam.<br />
Pukul tiga sore, usai breaking news, saya menghadap Surya Paloh.<br />
Baru memasuki pintu ruangan kerjanya, Surya langsung menyapa. "Saya<br />
siap berangkat kelrak, Don," katanya. Tentu saja saya surprise. Melihat<br />
saya terkejut, Surya melanjutkan, "Siapkan beberapakru untuk pergi<br />
bersama saya." Jawaban Surya benar-benar di luar dugaan. Semula saya<br />
menduga Surya Palohakan marah dan mempersalahkan saya atas<br />
penugasanini, lalu memberhentikan saya atau memberikan sanksi berat.<br />
Bagi saya itu sudah menjadi risiko dan tanggung jawab jabatan. Ternyata<br />
tidak ada sama sekali nada marah. Juga tidak mempersalahkan saya.<br />
Tentu saja saya respek atas kesediaan Surya.<br />
Surya Paloh, seperti para karyawan mengenalnya, sangat memegang<br />
teguh komitmen atas dedikasi, loyalitas, kesetiaan dan pengorbanan<br />
karyawan terhadap perusahaan. Nilai ini sangat penting bagi Surya. Harga<br />
kesetiaan dan loyalitas, bagi Surya, melampaui apapun. Kali ini, Surya<br />
siap berkorban untuk anak buah yang loyal itu. Termasuk mengambil alih<br />
tanggung jawab atasakibat keputusan saya.<br />
"Terima kasih Bang," jawab saya, dan kami pun terlibat dalam diskusi<br />
yang intens mengenai lang kah-langkah yang akan diambil.<br />
Bagi saya, keberangkatan Surya mempunyai beberapa keuntungan.<br />
Pertama, akses untuk berhubungan dengan berbagai pihak akan lebih<br />
mudah.<br />
Kedua, kalau Meutya dan Budi diculik, Surya Paloh dapat langsung<br />
mengambil keputusan untuk menyetujui dan menyiapkan uang tebusan<br />
jika itu menjadi syarat pembebasan. Ketiga, jika kemungkinan terburuklah<br />
yang terjadi, yaitu Meutya dan Budi tewas tertembak di daerah konflik,<br />
perusahaan telah menunjukkan itikad yang sungguh-sungguh total dan<br />
ikhlas kepada keluarga, rekan-rekan di Metro TV, dan publik dengan<br />
menerjunkan pemilik Metro TV sendiri.<br />
Usai bertemu Surya Paloh, saya menanyakan ke APTN apakah<br />
mereka mempunyai gambar tentang berita kehilangan Budi dan Meutya.<br />
Kantor berita ini memang mengindikasikan Meutya dan Budi kemungkinan<br />
diculik di sekitar Ramadi. Tapi berita itu tidak menjelaskan lebih jauh<br />
bagaimana keadaan keduanya. Segera setelah mendapatkan berita itu,<br />
saya hubungi, Y.K. Chan, representatif APTN di Hong Kong. Kami sudah<br />
lama saling kenal. Saya mencari tahu lebih lanjut tentang kebenaran<br />
berita itu. Y.K. Chan meyakinkan berita itu benar. Tetapi sebagai orang<br />
televisi, "seeingis believing". Baru percaya jika ada gambar.<br />
Y.K. (baca: waikei), begitu biasanya dia disapa, mengatakan APTN<br />
belum mendapat gambar. Janjinya, akan segera mengabari begitu<br />
mendapat gambar. Tetapi tidak jelas kapan, semuanya tergantung Irak.<br />
"Tolong feed segera ke alamat Metro TV jika Anda punya gambar," kata<br />
saya. Pada saat bersamaan, saya membaca news tickers di CNN tentang<br />
Budi dan Meutya yang hilang di Irak. Al-Ja<br />
zeerah juga memberitakan nasib keduanya. Menyaksikan berita-berita
itu, saya merasakan betapa besarnya peristiwa ini.<br />
Berita sependek itu tentu saja memancing perhatian rekan-rekan<br />
wartawan lainnya di tanah air. Beberapa saat kemudian saya mendapat<br />
telepon dari teman-teman wartawan menanyakan nasib Budi dan<br />
Meutya.Mereka juga menanyakan alasan penugasan keduanya ke<br />
Irak.Keesokannya, hampir semua media cetak menyajikan berita ini di<br />
halaman depan.<br />
Keadaan di ruang redaksi Metro TV benar-benar tegang. Saya melihat<br />
wajah-wajah sedih. Menyaksikan pemandangan itu, sekali lagi, saya<br />
merasa menjadi orang paling bodoh. Karena penugasan sayalah<br />
keduanya harus menderita dan mengalami nasib yang tak jelas. Bagi<br />
saya, dan awak Metro TV, perjalanan waktu dari pukul 10 hingga pukul 3<br />
sore hari itu tidak saja terasa lama, tetapi juga sangat meletihkan secara<br />
mental.<br />
* * *<br />
MENGAPA Meutya dan Budiyanto yang saya tugaskan? Pengenalan<br />
saya tentang Meutya secara pribadi, sebetulnya belum terlalu lama.<br />
Terhitung dari masa penugasan sebagai pemimpin redaksi Met ro TV,Juni<br />
2DD4, saya baru mengenal Meutya sekitar delapan bulan. Tapi<br />
pemunculan Meutya sebagai presenter Metro TV jelas memudahkan<br />
pengenalan terhadap kemampuannya. Beberapa kali kami berdialog.<br />
Diam-diam saya juga mengevaluasi rekaman wawancaranya<br />
sepertisaya lakukan atas wawancara dari penyiar-penyiar lainnya.<br />
Sebagai presenter Meutya tergolong bagus, baik dalam news delivery<br />
maupun mewawancarai nara sumber. Teknik delivery-nya otoritatif dan<br />
kredibel, walaupun belum didukung kualitas vokal yang bagus. Itu pun<br />
ditutupinya dengan artikulasi yang clear. Dari beberapa wawancara,<br />
Meutya mampu mengambil per-spektif tertentu, sehingga wawancaranya<br />
mengalir,fokus dan mudah dipahami. Meutya juga mampu mendalami<br />
jawaban-jawaban nara sumbernya.<br />
Tetapi bukan itu alasan utama mengapa Meutya yang dikirim ke Irak.<br />
Yang istimewa, dia juga andal melakukan laporan langsung dari<br />
lapangan, dari me dan-medan yang sulit. Setiap kali ditugaskan ke<br />
lapangan, tidak ada keraguan, dia pasti berhasil, dan menyajikannya<br />
dengan menarik. Pergaulannya yang luwes membuatnya mudah menjalin<br />
kerjasama tim, sebuah syarat mutlak dalam kerja televisi. Walaupun<br />
posturnya mungil, Meutya mempunyai daya tahan, endurance,yang kuat<br />
menghadapi medan berat. Chit-chat-nya jugalively.<br />
Salah satu puncak penugasan lapangan untuk Meutya adalah ketika<br />
pada awal hingga minggu ketiga Januari, meliput Aceh sesaat setelah<br />
gempa dan gelombang tsunami menerjang Tanah Rencong, dan<br />
menelan lebih dari 100 ribu korban jiwa. Meutya dan juru kamera Gideon<br />
Sinaga, ditugaskan di kawasan Meulaboh. Adalah Meutya dan Gideon<br />
yang<br />
menyusurui wilayah-wilayah terisolir di pantai barat Aceh itu.<br />
Keduanya memasuki Teunom dan Phang-ha, yang oleh berbagai<br />
kalangan dianggap sebagai daerah merah karena, konon, banyak<br />
anggota GAM di sana ketika itu.<br />
Ketika bertugas di sana, saya mendapat laporan Meutya dan juru<br />
kameranya harus "mengojek" untuk menggapai wilayah-wilayah bencana
yang oleh para petugas penolong pun belum dapat dijangkau. Mereka<br />
menyajikan gambar-gambar jenazah korban tsunami yang masih<br />
tergeletak di sejumlah lokasi, dia bahkan tidak takut kalau-kalau tukang<br />
ojek yang membawanya adalah anggota GAM.<br />
Bagaimana keduanya bisa sampai ke daerah terpencil itu? Meutya<br />
melobi seorang pilot heli hanya untuk didrop ke pantai barat itu. Keduanya<br />
menjadi jurnalis pertama yang masuk ke kawasan yang gelap gulita dan<br />
tidak ada sinyal telepon. Selama dua hari mereka menyusuri daerah itu<br />
dan kehilangan kontak dengan poskodi Metro TV. Bagaimana keduanya<br />
bisa keluar darisana? Saya mendapat laporan hanya faktor kebetulan<br />
belaka mereka tertolong oleh sebuah heli yang hendak mengevakuasi<br />
para korban.<br />
Hasil liputan dari Meulaboh, Aceh, itu tidak saja memperlihatkan<br />
kualitas laporannya yang mendalam dan lengkap.Tetapi juga, terutama,<br />
teladannya bagi rekan-rekan penyiar lainnya tentang pentingnya<br />
kelincahan dan pengalaman di lapangan. Dia juga mampu<br />
menyampaikan hal-hal penting lain tentang apa yangterjadi di belakang<br />
gambar dan apa yang belum<br />
terwakili dalam gambar.<br />
Atas dasar itulah, ketika baru saja beristirahat beberapa hari dari<br />
peliputan di Meulaboh, saya meminta Claudius dan Dadi untuk<br />
menugaskan Meutya meliput pemilihan umum di Irak. Tidak ada<br />
keberatan sedikit pundari kedua atasannya ini. Setelah keduanya<br />
menghubunginya, Meutya pun tak berkeberatan.<br />
Mengapa pemilu Irak? Ada tiga alasan yang melatarbelakanginya.<br />
Pertama, bagi penonton Indonesia, Irak bukanlah sesuatu yang asing.<br />
Proximity psikologisnya sangat dekat. Lagi pula sajian-sajian televisi<br />
asing seperti CNN, Fox News Channel, dan Al-Jazeerah ketika perang Irak<br />
bergolak, memperlihatkan betapa tingginya perhatian penonton di sini.<br />
Kejatuhan Saddam Husein, beberapa waktu sebelumnya, menjadi<br />
pembicaraan di mana-mana.<br />
Kedua, adalah cukup penting melihat bagaimana masa depan Irak<br />
berdasarkan hasil pemilu yang berlangsung pada awal Februari itu. Di<br />
tengah-teng ah hingar-bingar konflik yang melibatkan tentara koalisi<br />
danloyalis Saddam Husein yang dituduh melakukan bombunuh diri dan<br />
bom mobil di mana-ma na, pemberitaan konflik Syiah-Sunni di Irak juga<br />
merebak luas. Ketiga, media-media barat sering berat sebelah dalam<br />
menggambarkan keadaan di Irak. Membandingkan cara Al-Jazeerah<br />
memberitakannya, jelas ada sudut pandang yang berbeda. Di tengah<br />
situasi yang "serba kurang jelas" itulah mengapa Metro TV, sebagai<br />
televisi berita, perlu mengirim kru meliput pemilu Irak ini.<br />
Menilik kelincahan fisik dan kemampuannya untuk belajar cepat, tidak<br />
sedikit pun muncul keraguan bahwa Meutya akan berhasil menyajikan<br />
lapor an-laporan yang lengkap dan mendalam dari Irak. Kemampuan<br />
berbahasa Inggrisnya memudahkan Meutya menggali bahan-bahan dari<br />
sumber lainnya. Juga akan mendapatkan hasil maksimal karena<br />
kemampuannya lebih dari cukup untuk mewawancarai tokoh-tokoh politik<br />
penting di Irak jika sewaktu-wak tu diperlukan.<br />
Mengapa Budiyanto? Saya mengenal Budiyanto dua hari setelah saya<br />
bergabung dengan Metro TV. Penampilannya yang rendah hati dengan
smiling fa-cenya membuat saya langsung mengingat namanya sejak<br />
pertemuan pertama. Beberapa hari kemudian saya baru tahu, Budi adalah<br />
kordinator cameramen divisi pemberitaan. Budi lincah, kerjasama timnya<br />
bagus. Dari sikap dan tutur katanya, Budi menjalankan model<br />
kepemimpinan dengan memberikan teladan.Dia tidak pernah menolak<br />
tugas kemanapun dan kapan pun. Dia jugamerupakan instruktur yang<br />
andal.<br />
Budi dikenal memiliki multiskill alias serba bisa. Selain mengambil<br />
gambar, dia mampu memilih dan menyunting gambar yang bernilai berita.<br />
Budi mampu memperbaiki kamera yang tidak berfungsi, atau<br />
mengoperasikan telepon satelit yang masih langka ketika itu.Dia sangat<br />
familier dengan pengiriman gambar (feeding) melalui satelit. Semua<br />
kemampuan itu menjadi prasyarat yang lebih dari cukup untuk suksesnya<br />
sebuah peliputan. Dalam keadaan tertentu,<br />
Budi mampu menjalankan fungsinya sebagai "video journalist"<br />
(VJ) jika sesewaktu tidak ada reporter yang tersedia tepat waktu. Dalam<br />
penugasan di Irak, jika terjadi suatu peristiwa yang sangat penting, Budi<br />
akan mampu jalan sendiri dan Meutya bisa menyewa juru kamera lokal<br />
atau asing sehingga Metro TV mempunyai dua pasang kru di sana.<br />
Dan kelebihan lain dari Budi, dia sudah pernah dua kali ditugaskan<br />
dalam Perang Irak. Artinya, dia sudah mengenal medan. Dalam beberapa<br />
percakapan di kantin dan informal, saya juga mendengar Budi pernah<br />
ditugaskan ke daerah konflik seperti Aceh. Di tanah Rencongitu, Budi<br />
menyusuri bukit, gunung, dan lembah, yangmembuatnya matang di<br />
lapangan.<br />
Tentang dedikasi Budi, saya pernah memintanya untuk bertemu<br />
dengan kakak Cut Putri pada jam 2.30 dini hari sesaat setelah gempa dan<br />
tsunami mengguncang Aceh. Cut Putri adalah kontributor video amatir<br />
yang mengambil gambar pertama dan satu-satunya tentang bagaimana<br />
dahsyatnya gelombang tsunami menghantam Banda Aceh dan<br />
menghantam rumah sanak kerabatnya sendiri. Gambar itu<br />
memperlihatkan gelombang pasang yang sangat tinggi dan deras<br />
menyapu rumah-rumah yang letaknya 9 km dari pantai.<br />
Kisahnya, sekitar pukul 1.30 dini hari, saya dihubungi Ferry Putra<br />
Utama, Korlip yang bertugas malam. Menurut Ferry, ada seseorang yang<br />
ingin memberikan gambar tsunami ke Metro TV. Ketika saya tanyakan<br />
apakah gambar itu layak tayang, Fer ry tak bisa memastikan. Saat itulah<br />
saya memintanya<br />
pergimelihat gambar itu bersama Budi. Untuk memastikan,saya<br />
hubungi Budi untuk berangkat bersama Ferry.<br />
Sekitar pukul 03.00 dinihari itu juga Budi dan Ferry menghubungi<br />
saya. Budiyanto meyakinkan saya bahwa secara teknis gambar itu kurang<br />
layak tayang, tetapi sebagai berita, gambar itu sangat representatif untuk<br />
menggambarkan kedahsyatan tsunami yang menimpa Banda Aceh.<br />
Artinya, tidak ada ruginya Metro TV mengambil gambar itu dengan harga<br />
mahal sekalipun. Deskripsi Budi atas gambar itu meyakinkan saya untuk<br />
segera mengikat dan "mengunci" Cut Putri atau kakaknya agar gambar itu<br />
tidak jatuh ke tangan televisi lain. Gambar itu nyatanya memang sangat<br />
dramatis. Tidak mengherankan jika kemudian di relay CNN dan beberapa<br />
televisi asing. Menjadi rekan kerja Budi terasaenak, karena dia hampir tak
pernah bilang "tidak".<br />
Kombinasi kemampuan Meutya dan Budiyanto meyakinkan saya<br />
bahwa penugasan mereka ke Irak akan berhasil. Artinya, secara<br />
profesional sangat bisa dipertanggungjawabkan. Secara ekonomis,<br />
karena biayanya mahal, penugasan ini jelas tidak merugikan perusahaan.<br />
Hasil peliputan mereka tidak saja akan memperkuat posisi Metro TV<br />
sebagai televisi berita tetapi juga menjadi "credit point" yang besar bagi<br />
perjalanan karirjurnalistik keduanya.<br />
Seperti penugasan kru televisi pada umumnya, pre-paration atau<br />
persiapan yang baik sudah menjamin 100 persen keberhasilan peliputan<br />
berita televisi. Denganprobabilitas sebesar itulah, mengapa<br />
keduanya dikirim ke Irak. Semula ada saran agar mengirim reporter<br />
priake Irak untuk menghemat biaya kamar hotel di sana.Maklum, kalau<br />
keduanya pria, cukup membayar satukamar saja. Tetapi pikiran saya<br />
untuk mempercepat pematangan Meutya di lapangan, dengan harapan<br />
memotivasi beberapa penyiar baru lainnya, adalah hargayang cukup<br />
pantas untuk mengubah sikap kerja tim Metro TV dalam jangka menengah<br />
dan panjang.<br />
Karena ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tentu saja saya<br />
berharap keduanya dapat bertahan lamadi Irak. Dan, nyatanya, perkiraan<br />
saya tidak meleset. Selama seminggu penuh bertugas di sana di luar<br />
waktu perjalanan banyak sekali liputan eksklusif yang mereka sajikan.<br />
Beberapa kali, Meutya melakukan standup dari lokasi bom mobil yang<br />
baru saja meledak,atau mewawancarai tokoh-tokoh politik di Irak. Di<br />
tengah deru konflik yang tak menentu, rupanya Budi dan Meutya langsung<br />
menyusuri area-area berbahaya dikota Bagdad. Sementara kebanyakan<br />
wartawan lainnya, sesuai instruksi penguasa perang di Irak, hanyaboleh<br />
meliput dari green zone, kawasan yang relatif lebih aman.<br />
Tidak heran, saya begitu terkejut ketika mendengar keduanya sudah<br />
keluar dari Irak lebih a-wal dari yang saya perkirakan. Saya ingat, ketika<br />
dua atau tiga hari, tanggal 12 dan 13 Februari, saya tidak lagi<br />
menyaksikan laporan Meutya dan Budiyanto dari Bagdad, saya tanyakan<br />
hal itu ke Korlip. Begitu mendengar kabar bahwa keduanya sudah berada<br />
di Amman, serta merta saya minta Dadi secepatnya<br />
mengirim kembali Meutya dan Budi ke Irak. Mereka harus<br />
membatalkan kepulangannya ke Jakarta.<br />
Ada dua pertimbangan. Pertama, keduanya masih diperlukan untuk<br />
meliput hari raya Asyura,tradisi memperingati hari wafatnya Hussein bin<br />
Ali, cucu Nabi Muhammad, di Kota Karbala, yang biasa dilakukan<br />
kelompok Syi'ah. Peristiwa ini tidak saja penting, tetapi juga menarik dan<br />
dramatis mengingat pemilu di Irak mungkin dimenangkan oleh Kelompok<br />
Syi'ah. Kedua, hasil penghitungan suara pemilu Irak belum selesai.<br />
Sayang jika tugas keduanya tidak tuntas. Tapi, rupanya penugasan itulah<br />
yang membawa kedua kru ini masuk dalam catatan: mereka disandera di<br />
kota Ramadi. Dan saya, yang menugaskan kembali keduanya ke Irak,<br />
terpenjara dalam perasaan bersalah dan penyesalan mendalam.<br />
* * *<br />
SEBAGAI orang yang menanti kejelasan nasib Meutya dan Budi,<br />
rasanya waktu berjalan teramat lambat. Tapi perasaan seperti itu sangat<br />
terbalik dengan kesibukan awak redaksi yang mengikuti perkembangan
peristiwa ini dari detik demi detik. Pada pukul dua siangitu, Metro TV<br />
sudah menyiarkan breaking news tentang kehilangan Meutya dan Budi di<br />
Irak. Dua jam kemudian muncul berita bahwa kedua kru Metro TV itu<br />
diculik disekitar kota Ramadi. Tapi tidak jelas siapa penculiknya,untuk<br />
tujuan apa mereka menculik, dan bagaimana nasib keduanya.<br />
Sekitar pukul 10 malam mulai ada titik terang.<br />
Sebuah berita yang diterima dari kru Al-Jazee rah menjelaskan bahwa<br />
Budi dan Meutya diculik oleh kelompok pejuang Mujahiddin. Kabarnya<br />
mereka menuntut agar pemerintah Indonesia menjelaskan untuk tujuan<br />
apa Meutya dan Budi dikirim ke Irak. Dari Korlip saya mendapat kabar<br />
beberapa saat kemudian kru Al-Jazeerah di Jakarta akan merekam<br />
pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang tujuan<br />
kepergian Meutya dan Budiyanto. Bersamaan dengan itu, kru Metro TV di<br />
Jakarta merapat ke Istana.<br />
Menjelang pukul 12 malam, saya mendapat kabardari APTN Hong<br />
Kong bahwa tidak lama lagi London akan mengirim gambar<br />
penyanderaan Meut ya dan Budi. Melihat perkembangan yang begitu<br />
cepat, HelmyYohanes, dkk. yang mempersiapkan program MidnightLive,<br />
siaga dengan breaking news.Dan benar saja, tepat pukul 00.30 WIB,<br />
Sabtu dini hari, 19 Februari, gambar Meutya dan Budiyanto muncul.<br />
Gambar itu muncul pada APTN News update pukul 17.30 GMT.<br />
Gambar berdurasi 1.43 menit itu sungguh mendebarkan hati.<br />
Bagaimana tidak? Meutya dan Budi berada di bawah todongan senjata.<br />
Meutya tampak gugup, Budiyanto komat-kamit, tidak jelas sedang bicara<br />
apa. Tidak ada soundbite yang terdengar, kecuali gambar yang<br />
memperlihatkan keduanya sedang berada dibawah ancaman berat.<br />
Gambar medium shot itu mem-perlihatkan keduanya berada di sebuah<br />
wilayah gurunpasir.<br />
Gambar itu hanya memberikan satu makna: Meutya dan Budi berada<br />
di bawah teror yang menakutkan.<br />
Bersamaan dengan breaking news itu, di istana, Presiden Susilo<br />
Bambang Yudhoyono membuat pernyataan pada dini hari itu juga. Inti<br />
pernyataan Presiden ada dua. Pertama, menyatakan bahwa Meutya dan<br />
Budi yanto adalah benar dua warga negara Indonesia yangsedang<br />
menjalankan tugas jurnalistik murni. Kedatangan mereka ke Irak tidak ada<br />
sangkut pautnya dengan kepentingan politik apa pun.Kedua,Presiden<br />
meminta para penyandera membebaskan Meutya dan Budiyanto.<br />
Pernyataan pertama Presiden itu mengingatkan pada isi penjelasan saya<br />
kepada Menlu Hassan Wirajuda dan Jubir Marty Natalegawa pada siang<br />
harinya. Dalam pertemuan itu baik Hassan maupun Marty tidak hanya<br />
sekali mengkorfimasikan motif politik ini.<br />
Hanya dalam waktu beberapa menit kemudian, Al-Jazeerah<br />
menayangkan gambar penyanderaan itu. CNN juga menayangkan<br />
gambar yang sama. Kedua televisi ini juga menyiarkan pernyataan<br />
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal yang sama dilakukan oleh<br />
Metro TV. Kecepatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi<br />
permintaan para penyandera itu membuat saya ikut merasa sebagai<br />
warga negara yang diperhatikan oleh pemimpinnya.<br />
Pemunculan gambar penyanderaan itu menjadi babak baru<br />
penantian Metro TV. Pertama, kini menjadi jelasbahwa Budi dan Meutya
disandera kelompok pejuang Mujahiddin. Kedua, pemerintah, seperti<br />
dijanjikan Menludan Presiden, ikut ambil bagian dalam usaha<br />
pembebasan ini atas nama perlindungan kepada warga negara. Tapifase<br />
penyanderaan ini justru menimbulkan teka-teki barutentang masa depan<br />
Budi dan Meutya. Apakah mereka selamat di tangan penyandera?<br />
Bagaimana perlakuan penyandera terhadap Meutya dan Budi?<br />
Bagaimana nasib Budiyanto dan Meutya jika tentara koalisi menghajar<br />
para penyandera dan keduanya tertembak peluru nyasar seperti beberapa<br />
kejadian sebelumnya? Bagaimana caranya bisa berhubungan langsung<br />
atau bernegosiasi dengan penyandera? Bagaimana perasaan keluarga<br />
Meutya dan Budi setelah menonton gambar ini?<br />
Seperti pemberitaan mengenai penyanderaan pada umumnya,<br />
memang selalu tersedia ruang sempit untuk memikirkan kemungkinan<br />
yang positif. Misalnya, penyandera hanya ingin menyampaikan pesan<br />
politik tertentu melalui tindakan penyanderaan. Dalam beberapa kasus<br />
mereka tidak melukai dan atau membunuh korbannya. Kemungkinan lain,<br />
motif kriminal dengan meminta uang tebusan. Dalam kedua kasus<br />
tersebut, jikatujuan politik atau tujuan finansialnya tercapai,<br />
korbanbiasanya dilepas.<br />
Ditilik dari permintaan Mujahidin agar pemerintah Indonesia<br />
menjelaskan posisi Meutya dan Budiyanto, dapat diduga, penyanderaan<br />
ini berlatar belakang politis. Hal itu juga diperkuat oleh penayangan<br />
gambar penyanderaan dan pernyataan Presiden Susilo Bambang<br />
Yudhoyono, pada primetime news untuk penonton Al-Jazeerah di kawasan<br />
Timur<br />
Tengah atau dini hari waktu Indonesia, dan siang hari waktu CNN<br />
yang mewakili penonton dunia barat. Tapi situasi konflik yang tidak jelas<br />
petanya di Irak membuat semua analisis itu tetap terasa tidak ada<br />
gunanya. Dan selalu muncul kemungkinan terburuk. Namun, lepas dari<br />
semua itu, berita penyanderaan ini rupanya tidak saja menjadi perhatian<br />
pers Indonesia, tetapi juga pers dunia.<br />
Penayangan pernyataan Presiden Susilo Bambang Vudhoyono pada<br />
stasiun televisi Al-Jazeerah memunculkan inspirasi baru. Pada rapat<br />
keesokan paginya, muncul saran pada rapat redaksi agar merekam<br />
pernyataan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh untuk disiarkan melalui<br />
Al-Jazeerah.Rapat itu juga menyepakati agar para tokoh itu berbicara<br />
dalam bahasa Arab. Maka rapat itu pun sepakat untuk menghubungi<br />
tokoh-tokoh seperti Amin Rais, Gus Dur, KH Quraish Shihab, Hidayat Nur<br />
Wahid, KH Ha-syim Muzadi, dan beberapa tokoh lainnya.<br />
Suara tokoh-tokoh ini diharapkan sampai ke kelompok penyandera<br />
atau jaringan-jaringan mereka. Untuk itu beberapa rekan lainnya<br />
menghubungi Al-Jazeerah agar membantu penayangan pernyata anpernyataan<br />
para tokoh itu. Di luar dugaan, permintaan ini disambut baik<br />
oleh Al-Jazeerah. Isinya kurang lebih sama dengan pernyataan Presiden<br />
Susilo Bambang Vudhoyono.Lebih dari itu, mereka juga diminta<br />
menyampaikan pesan untuk mengundang empati kelompok pejuang<br />
Mujahiddin maupun jaringannya di mana pun mereka berada agar<br />
melepaskan Budi dan Meutya.<br />
Sejumlah kru dikerahkan untuk menemui tokoh-tokoh itu. Saya,<br />
bersama beberapa teman menghadap DR. Hidayat Nur Wahid di gedung
MPR. Untunglah tokoh-tokoh ini menyambut antusias permintaan ini. Agar<br />
efektif, Metro TV mengirim pesan-pe san itu pada malam hari sehingga<br />
dapat ditayangkan pada earlyprime time Al-Jazeerah. Jalan pikirannya<br />
sederhana saja. Jika para penyandera sudah mendengar pesan dari<br />
pemerintah Indonesia melalui Al-Jazeerah, pesan-pesan tokoh Muslim<br />
Indonesia ini pun sangat mungkin sampai ke jaringan-jaringan pejuang<br />
Mujahiddin, termasuk kelompok penyandera yang ada di gurun pasir dekat<br />
kota Ramadi.<br />
Upaya-upaya itu jelas tak dapat diukur hasilnya. Namun ada<br />
keyakinan pesan-pesan ini cepat atau lambat akan sampai juga pada<br />
penyandera. Re aksi-reaksi atas pesan-pesan ini dipantau oleh<br />
Mohammad Nasserdi Irak maupun Yordania. Beberapa awak Metro TV<br />
yang mempunyai teman dekat di kawasan Timur Tengah, khususnya di<br />
Yordania, Mesir, Arab Saudi, Suriah, dan lain-lain melaporkan mereka<br />
menonton pesan-pesan itu melalui Al-Jazee rah. Pada saat bersamaan,<br />
hasil pengaisan informasi melalui milis-milis di internet mau-pun<br />
beberapa koran yang terbit di Timur Tengah tidak ditemukan berita-berita<br />
buruk tentang nasib Budi dan Meutya. Satu-satunya soal pokok dalam tiga<br />
hari itu adalah menunggu dalam ketidakpastian. Dalam suasana "gelap"<br />
semacam ini selalu saja muncul pikiran terburuk tentang nasib Budi dan<br />
Meutya.<br />
Tetapi, menyaksikan gambar penyanderaan yang<br />
menakutkan jelas menjadi beban mental. Maka pada pagi tanggal<br />
19 Februari itu saya merasa sudah saatnya menjelaskan kepada publik<br />
tentang latar belakang penugasan Meutya dan Budi ke Irak. Selain<br />
menjelaskan latar belakang penugasan keduanya itu kepada publik,<br />
melalui Metro TV pula, saya meminta maaf secara terbuka kepada<br />
keluarga karena penugasan ini telahmenyusahkan mereka.<br />
Usai siaran pagi itu, masih tanggal 19 Februari, setelah mengikuti<br />
rapat redaksi Metro TV, saya merasa sudah tepat waktunya mengunjungi<br />
keluarga Meutya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara Claudius<br />
dan beberapa korlip lainnya, yang menjadi atasan langsung Budi,<br />
mengunjungi istri dan anak Budi di Rawamangun, Jakarta Timur.<br />
Mengunjungi keluarga adalah tugas mulia, tetapi terasa berat bagi saya<br />
karena akan begitu banyak yang hendak saya katakan, namun saya<br />
merasa tidak pantas mengatakan apa pun kepada keluarga yang sedang<br />
dirundung duka ini. Sehari sebelumnya Zsa Zsa Yu-saryahya dan Desi<br />
Anwar sudah berkunjung ke Lebak Bulus.<br />
Di rumah ibu Metty Hafid, saya diterima Finny, kakak Meutya. Sesaat<br />
kemudian saya bertemu Ibu Metty, seorang wanita tua yang tampak tegar,<br />
tenang dan tabah. Saya memperkenalkan diri sebagai pemimpin redaksi<br />
yang menugaskan Meutya ke sana. Saya minta maaf atas kejadian ini.<br />
Lebih dari itu, saya tidak bisa mengatakan apa pun. Saya mengunci mulut<br />
untuk tidak mengatakan "ini risiko tugas." Kata-kata seperti ini hanya<br />
membela diri. Lagi<br />
pula, untuk peliputan di area konflik seperti ini, risi ko-risiko itu<br />
mestinya sudah menjadi pertimbangan. Secara etis, hidup atau nyawa<br />
selalu lebih penting dari apa pun.<br />
Saya percaya kata-kata memang dapat menghibur, tetapi jika saya<br />
pun berada dalam posisi keluarga Meutya atau keluarga Budi,kata-kata itu
sama sekali tidak ada artinya bagi saya dibanding nyawa anak tercinta.<br />
Karena itu saya lebih banyak diam. Selebihnya saya menjelaskan kepada<br />
Finny bahwa pimpinan MetroTV , Surya Paloh, akan segera bertolak ke<br />
Amman dan Irak untuk ikut memimpin upaya pembebasan. Kemungkinan<br />
salah satu anggota keluarga akan diikutsertakan. Upaya ini akan berjalan<br />
bersama langkah pemerintah, atau Deplu. Selebihnya, Usi Karundeng<br />
yang juga hadir di situ meneguhkan hati Ibu Metty. Sekitar satu jam saya<br />
berada di sini, tanpa banyak kata.Di benak saya, makin banyak kata, hanya<br />
akan berkesan membela diri, dan hanya menyakitkan hati keluarga.<br />
Bukan kali ini saja saya mengalami tekanan mental akibat<br />
penugasan yang langsung maupun tidak langsung atas rekan-rekan kerja<br />
yang berujung pada risiko berat. Sepuluh tahun lalu, wartawan Liputan 6<br />
SCTV, Ferdinandus Sius (kami biasa memanggilnya Max karena wajahnya<br />
mirip Max Sopakua, mantan reporter olahraga TVRI) dan juru kamera<br />
Yance Iskandar, tewas dalam penerbangan Garuda yang menabrak<br />
GunungSibayak, Medan, sesaat sebelum mendarat di Bandara Polonia.<br />
Ketika mengantar jenazah Ferdinandus ke Kupang, kami masih<br />
mempunyai hubungan kerabat jauh,sambil meratap, keluarga<br />
menanyakan kepada saya mengapa Ferdinandus yang ditugaskan<br />
meliput kasus asap Suma-tera yang membuat Singapura dan Malaysia<br />
menderita. Saya benar-benar kehilangan kata-kata untuk menjawab<br />
ratapan pilu itu.<br />
Masih di SCTV, ketika menjadi wakil pemimpin redaksi, bersama<br />
Karni Ilyas yang menjadi pemimpin redaksi ketika itu, saya ikut panik<br />
karena kehilangan kontak selama tiga hari dengan Reporter Merdi Syof<br />
yan syah dan juru kamera Dwi Guntoro ketika Perang Irak mulai<br />
berkecamuk. Ingatan akan peristiwa itu membayang-bayangi perasaan<br />
saya ketika Meutya dan Budi diculik.<br />
Sepulang dari rumah Meutya, sekitar jam 3 siang, saya kembali<br />
menghadap Surya Paloh. Sudah jelas pada waktu itu, tim yang akan<br />
dikirim bersama Surya Paloh adalah empat wartawan masing-masing<br />
Thia Vufada, Mauluddin Anwar dan juru kamera Kusdaryanto dan<br />
Sudirman Mustari. Pada kesempatan itu, Surya Paloh menyarankan<br />
Sandrina Malaki-ano ikut. Semula saya keberatan karena akan terlalu<br />
banyak kru yang ikut, tetapi saya kembali menyerahkan itu kepada<br />
keputusan Surya.<br />
Dalam pertemuan dengan Surya Paloh siang itu saya mendapati Lisa<br />
Luhur, sekretaris yang sudah lama bekerja dengan Surya, membawa<br />
segepok plastik besar uang dollar Amerika. Insting saya mengatakan<br />
mungkin uang itu dipersiapkan sebagai bagian dari uang tebusan jika<br />
para penyadera memintanya sebagai syarat pembebasan. Atau<br />
setidaknya<br />
uang itu bisa digunakan untuk mencarter pesawat di Irak untuk<br />
menjangkau Ramadi. Tapi saya tidak menanyakan itu kepada Surya. Bagi<br />
saya,yang penting, tim ini sudah siap dengan segala kemungkinan.<br />
Kepada Surya saya juga ungkapkan tentang kemungkinan salah satu<br />
anggota keluarga Meutya dan Budi diikutsertakan. Tapi karena waktunya<br />
sangat sempit, Surya menjanjikan mereka mungkin akan berangkat jika<br />
sudah ada tanda-tanda pembebasan atau sebaliknya akan terjadi.<br />
Pembicaraan itu juga membahas berbagai skenario peliputan jika sudah
sampai di Irak. Surya Paloh dkk berangkat pada sore hari tanggal 20<br />
Februari.<br />
Bersamaan dengan itu, awak pemberitaan selalu sibuk memantau<br />
berbagai sumber berita di Timur Tengah yang berkaitan dengan berita<br />
penyanderaan ini. Dalam dua hari itu, hubungan dengan Mohammad<br />
Nasser sangat intens. Demikian juga dengan Al-Jazeerah. Untuk<br />
mengetahui keadaan lebih lanjut, karena berita dan gambar<br />
penyanderaan ini berasal dari APTN, saya kembali menghubungi Y.K.<br />
Chan di Hong Kong. Jawabannya, belum ada perkembangan yang<br />
menggembirakan.<br />
Saya juga menghubungi posko di Departemen Luar Negeri. Juga<br />
belum ada kabar dari jaringan-jari ngan mereka. Dari Marty saya dapatkan<br />
gambaran diplomat-diplomat mereka di Timur Tengah, khususnya di<br />
Amman, sedang bekerja keras. Saya juga mendapat informasi bahwa<br />
Deplu mengirim diplomat senior,Triyono Wibowo, ke Amman. Triyono<br />
Wibowo adalahKetua Penanggulangan Krisis yang dibentuk<br />
Deplu untuk menangani kasus penculikan ini<br />
* * *<br />
DALAM penantian, waktu tiga hari terasa sangat lama. Selain<br />
melelahkan, keputusasaan sudah mulai muncul di sana-sini. Tapi semua<br />
itu harus dilalui. Sepanjang pagi menjelang siang, pada 21 Februari, awak<br />
redaksi melakukan tugas-tugas rutin, termasuk mengontak berbagai<br />
jaringan di Timur Tengah. Menjelang jam 12 siang, saya mendapatkan<br />
kabar di ruang redaksi bahwa Mohammad Nasser sudah mengontak<br />
seorang ulama besar yang disegani di dekat kota Ramadi. Seseorang<br />
yang menerima berita itu mengatakan ulama itu siap menyampaikan<br />
pesan kepada kelompok penyandera untuk membebaskan Meutya dan<br />
Budi. Kabar itu tidak jelas benar, tetapi di tengah situasi tak pasti, sekecil<br />
apapun kebenarannya perlu diricek ke mana-mana.<br />
Toh, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu itu tiba juga. Tepat pukul<br />
13.15, ruang redaksi gempar. Pada saat itu rupanya berita teks tentang<br />
pembebasan Budi dan Meutya dari APTN sudah masuk ke ruang redaksi.<br />
Lima belas menit kemudian, gambar pembebasan Meutya dan Budi<br />
muncul. Semua awak redaksi berdesak-desakan di receiver APTN.<br />
Semua orang berjingkrak-jingkrak dan saling berpelukan di ruang redaksi.<br />
Kali ini, air mata yang mengalir dari sebagian awak redaksi adalah air<br />
mata haru dan gembira. Saya sendiri, sebagai orang yang paling<br />
bertanggung jawab atas penugasan ini serasa baru<br />
melepaskan beban sangat berat yang sulit tertanggungkan. Air mata<br />
saya pun menetes sambil berpelukan dengan begitu banyak kru.<br />
Gambar berdurasi 1.53 menit itu memperlihatkan Budi sedang<br />
tersenyum menerima kitab suci Al-Qur an dan ucapan selamat dari<br />
penyandera. Sementara Meutya berdiri di sampingnya dengan ekspresi<br />
wajah yang menyembunyikan kegembiraan.Seketika itu juga, Makroen<br />
Sandjaya, dkk. menyiapkan breaking news mengenai pembebasan ini.<br />
Memasuki Control Room, semua kru tampak seperti sedang dilanda<br />
euforia pembebasan. Pemandangan yang sangat jauh berbeda dengan<br />
breaking news empat hari sebelumnya tentang penyanderaan,yang<br />
diwarnai dengan rasa sedih, takut dan cemas.<br />
Setelah penayangan gambar pembebasan itu, semua orang di ruang
edaksi bertepuk tangan. Sungguh, jika pun peristiwa ini bukan apa-apa<br />
bagi orang lain, tetapi bagi awak Metro TV, ini adalah sebuah momen, draft<br />
sejarah yang sulit dilupakan.Dan bagi saya, ini adalah salah satu sejarah<br />
penting dalam karier kepemimpinan saya. Usai breaking news saya<br />
memasuki ruang kerja saya dan sejenak mengangkat syukur ke hadirat<br />
Tuhan.<br />
Tapi ini barulah awal dari berita pembebasan yang, ternyata berjalan<br />
tidak mulus. Ada hal penting yang belum terjawab. Benar pada siang hari<br />
itu berita pembebasan Budi dan Meutya sudah diketahui, tapi belumlah<br />
jelas benar karena posko di Jakarta belum dapat berkomunikasi langsung<br />
dengan Budi dan Meutya. Menilik medan yang berat dari Ramadi<br />
menuju perbatasan Irak-Yordania, kekhawatiran atas<br />
keselamatan Budi dan Meutya tetap saja menjadi momok yang<br />
menakutkan. Mungkin mereka sudah lepas dari tangan penyandera di<br />
Ramadi, tapi tidak ada jaminan perjalanan mereka akan aman dari<br />
penculikan lainnya. Yang juga menakutkan adalah keganasan tentara<br />
sekutu yang tidak mengenal ampun menembaki orang-orang yang<br />
dicurigai.<br />
Cuma kali ini, cukup menggembirakan karena penanganan<br />
pembebasan sudah melibatkan berbagai pihak. Para diplomat Deplu di<br />
Amman, misalnya, sudah berkordinasi kemana-mana. Deplu juga akan<br />
mengirim diplomat seniornya menuju perbatasan Irak. Surya Paloh dan<br />
tim dari Metro TV yang sudah dua hari berada di Amman, Yordania, juga<br />
bergerak menuju perbatasan. Sehari sebelumnya, Surya Paloh muncul<br />
dalam program Metro Hari Ini, langsung dari Amman. Di kantor Metro TV<br />
Kedoya, semua a-wak redaksi juga siaga untuk melanjutkan breaking<br />
news pembebasan ini, jika sesewaktu sudah mendapat kontak langsung<br />
dengan Budi dan Meutya.<br />
Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu itu tiba juga. Sekitar pukul 9<br />
malam, untuk pertama kalinya saya mendengar suara Meutya melalui<br />
telepon malam itu. Betapa mengharukan setelah saya dan ka wan-kawan<br />
menanti dalam ketidakpastian. Suara Meutya mengesankan<br />
perjalanannya menuju perbatasan Irak-Yordania tidaklah aman. dia<br />
seperti diliputi ketakutan. Juga ada kesan tergesa-gesa dalam suaranya<br />
yang terbata-bata. Tapi kabar terpenting bagi saya adalah keadaannya<br />
yang sehat dan tak<br />
kurang suatu apapun. Usai berbicara dengan Meutya saya berbicara<br />
dengan Budi, termasuk menanyakan soal perbekalan mereka selama<br />
perjalanan. Budi juga menjelaskan keadaan yang kurang aman<br />
sepanjang perjalanan.<br />
Saat itu juga Kedoya mengudarakan breaking news, langsung<br />
dengan Meutya dan Budiyanto. Kali ini, kegembiraan di ruang pengendali<br />
siaran luar biasa meriah.Tapi kemeriahan itu berlangsung sejenak.<br />
Ruang pengendali siaran kembali senyap.Sebab Meutya dan Budi<br />
mengabarkan mereka tidak diperkenankan melewati perbatasan Irak-<br />
Yordania. Pos perbatasan, malam itu, hingga keesokan harinya ditutup di<br />
bawah penjagaan ketat. Tidak boleh ada yang lalu lalang dari dan ke Irak,<br />
atau sebaliknya, karena menjelang hari raya Asyura. Meutya<br />
menggambarkan keadaan di perbatasan juga menakutkan. Keduanya<br />
tidak berani keluar dari mobil. Kontak dengan keduanya pun terputus.
Bersamaan dengan itu, Surya Paloh dan tim juga sudah sampai di<br />
perbatasan untuk menjemput Budi dan Meutya. Penasaran dengan<br />
terhadangnya kedua kru itu di perbatasan, saya meminta Surya Paloh<br />
melaporkan langsung keadaan di perbatasan untuk disiarkan di Metro TV<br />
malam itu juga. Begitu on air, penyiar dari studio Metro TV menanyakan<br />
Surya Paloh tentang langkah-langkah para diplomat Indonesia yang<br />
sudah ada diperbatasan. "Saya melihat mereka seperti tenang-tenang<br />
saja dan tidak berbuat apa-apa," kata Surya Paloh.<br />
Rupanya isi laporan Surya Paloh itu membuat<br />
Marty Natalegawa kecewa. Marty menelepon saya, mengingatkan<br />
komitmen bahwa Metro TV dan Deplu harus bekerjasama untuk<br />
membebaskan Budi dan Meutya. dia juga mengingatkan perlunya<br />
memahami tata krama diplomatik dalam urusan semacam ini. Saya tidak<br />
punya pilihan lain kecuali meminta maaf atas laporan yang mungkin<br />
mengabaikan kerja keras pemerintah atau Deplu dalam upaya<br />
pembebasan ini.<br />
Penantian keesokannya tak kalah panjang. Semula kami menduga,<br />
pukul 10 siang hari Selasa, 22 Februari, posko di Kedoya sudah akan<br />
mendapatkan kabar Budi dan Meutya melintasi perbatasan Irak-Yordania.<br />
Lewat pukul 3 sore, belum juga ada tan da-tanda Budi dan Meutya bisa<br />
melintasi perbatasan. Menjadi pertanyaan, kok proses ini susah dan lama<br />
benar jalannya?<br />
Pada malam hari, atau sore waktu Irak, barulah kabar itu benar-benar<br />
nyata. Budi dan Meutya baru bisa melintasi perbatasan. Begitu Surya<br />
Paloh mengabarkan Meutya dan Budi sudah dalam dekapannya, semua<br />
beban terasa terlepaskan. Sebagai pemimpin redaksi yang menugaskan<br />
keduanya ke Irak, langkah saya terasa sangat enteng malam itu. Suasana<br />
ruang redaksi dan ruang pengendali siaran pun ceria ketika Boy Noya<br />
mengantarkan breaking news tentang pembebasan ini.<br />
Ribuan ucapan selamat berdatangan melalui telepon, email, maupun<br />
sms. Jumlahnya hampir sama dengan ucapan simpati dan doa yang<br />
mengalir selama empat hari masa penyanderaan sebelumnya.<br />
Jelas, kabar ini benar-benar mengakhiri penantian 4 hari yang terasa<br />
amat sangat panjang dan melelahkan. "Saya ingin Meutya dan Budi<br />
menikmati malam pembebasan ini di Amman," kata Surya melalui telepon<br />
dengan suaraparau. Rupanya, penantian di tengah hawa dingin malam<br />
hari di perbatasan membuat kesehatan Surya Paloh agak terganggu.<br />
Dalam percakapan telepon itu saya mendengar Budi dan Meutya akan<br />
berangkat ke Jakarta bersama tim dari Metro TV keesokannya dengan<br />
Qatar Airways.<br />
"Mungkin saya akan menyusul ke Jakarta. Saya agak sakit," kata Surya<br />
Paloh.<br />
"Abang harus pulang bersama Budi dan Meutya. Abang kan tahu,<br />
Presiden akan menyambut kedatangan Meutya dan Budi di Istana. Apa<br />
jadinya kalau Abang tidak di sini," kata saya. "Okelah, Don."<br />
* * *<br />
KEDEKATAN Meutya dan Budi dengan awak pemberitaan Metro TV<br />
mengundang rasa rindu segera bertemu dengan keduanya. Begitu pun<br />
saya. Pemberitaan yang luas melalui media cetak dan elektronik di<br />
sini,dan juga media-media internasional, menambah rasa ingin tahu
agaimana keadaan keduanya setelah diculik hampir selama seminggu.<br />
Dan yang lebih menarik, bagaimana sesungguhnya kisah penyanderaan<br />
di kota Ramadi itu. Bagi saya, karena pemberitaan yang lua situ, jelas<br />
menempatkan Budi dan Meutya menjadi "bu-kan wartawan biasa" dan<br />
"bukan juru kamera biasa" lagi. Perasaan semacam<br />
itulah yang saya bawa sampai tiba waktunya menjemput mereka di<br />
Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 24 Februari siang.<br />
Bersama iring-iringan mobil yang cukup panjang yang membawa<br />
awak Metro TV, begitu tiba di bandara Soekarno Hatta, enam atau tujuh<br />
diplomat dari Departemen Luar Negeri sudah lebih dulu tiba. Sejumlah<br />
wartawan cetak dan elektronik hilir mudik di sana. Perasaan saya<br />
berdebar-debar menantikan ke duanya keluar dari garbarata di ruang<br />
tunggu khusus.<br />
Begitu wajah Meutya dan Budi muncul, dari jarak sekitar 15 meter,<br />
saya melompat kegirangan. Setelah itu saya merapat. Saya memeluk<br />
tubuh mungil Meutya dengan perasaan kasih yang tulus. Air mata saya<br />
menetes. Di dalam tubuh mungil ini, bertahta hati dan jiwa yang tegar,<br />
pikirku seraya menatap mata Meutya. "Kami semua bangga padamu, Mut,"<br />
kata saya. Tidak banyak kata lagi yang kami ucapkan ketika itu.Meutya<br />
mengucapkan terima kasih, dan saya menyampaikan permintaan maaf.<br />
Juga menyampaikan selamat tiba kembali ke pangkuan keluarga dan<br />
keluarga besar Metro TV.<br />
Usai memeluk Meutya, saya memeluk Budi. "Kami semua bangga<br />
pada Mas Budi," kata saya sambil menatap mata Budiyanto. Pada<br />
wajahnya yang murah senyum bertahta jiwa yang tegar. Usai memeluk<br />
keduanya, saya memeluk Surya, mengucapkan terima kasih karena telah<br />
memikul penuh tanggung jawab atas akibat keputusan saya.<br />
Iring-iringan perjalanan menuju istana, hari itu<br />
bak mengantar pahlawan yang telah memenangkan pertempuran.<br />
Sambutan di pendopo Istana pun meriah. Presiden Susilo Bambang<br />
Yudhoyono didampingi Menlu Hassan Wirajuda menyambut keduanya<br />
dengan antusias. Menikmati sambutan semeriah itu, saya pun merasa<br />
ikut memenangkan pertempuran batin. Tanpa ragu saya ikut berdiri di<br />
pendopo, menyaksikan Meutya dan Budi, yang tampak kikuk dengan<br />
penyambutan meriah ini.<br />
Usai di istana, penyambutan di Metro TV lebih meriah lagi. Begitu<br />
memasuki gerbang Metro TV sekitar pukul 5 sore, seluruh karyawan Media<br />
Grup memadati halaman depan kantor yang megah. Di tengah<br />
kerumunan itu, Budi dan Meutya dengan sabar melayani rekan-rekannya<br />
yang memeluk dan ber jabat tangan dengan keduanya. Di sana-sini saya<br />
mendengar seruan membahana, "Hidup Meutya. Hidup Budi". Di grand<br />
studio, saya menikmati pemandangan magis: semua orang menikmati<br />
kemenangan. Sebuah catatan kecil sejarah telah ditoreh Meutya dan Budi<br />
dalam karier jurnalistiknya. Sementara dari sebuah sudut studio itu saya,<br />
kali ini, merasa bukan lagi pemimpin redaksi yang bodoh. []<br />
Failure is not an Option<br />
Oleh Dr. R.M.Marty M.Natalegawa<br />
Mantan Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI<br />
SEBAGAI seorang Juru Bicara Departemen Luar Negeri, tidak ada hari<br />
yang saya lalui bersifat rutin. Tiap hari saya selalu siapkan diri
menghadapi tantangan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.<br />
Namun hari itu, Jumat, 18 Februari 2DD5, menjadi salah satu hari luar<br />
biasa buat saya.<br />
Menjelang press briefing yang rutin diselenggarakan di Deplu, kami<br />
menerima laporan dari KBRI Amman, Yordania, mengenai 'kehilangan<br />
kontak' dengan dua wartawan Metro TV, Meutya Hafid dan Budiyanto yang<br />
tengah berkunjung ke Irak. Menurut kabar yang masih perlu dikonfirmasi<br />
itu, kendaraan yang disewa kedua wartawan Metro TV dihadang<br />
sekelompok bersenjata berseragam militer, dan keduanya dilarikan ke<br />
tempat yang belum diketahui.<br />
Ketika saya kontak ke Amman, pihak KBRI mengonfirmasikan telah<br />
kehilangan kontak dengan kedua kru Metro TV sejak mereka<br />
menyeberangi perbatasan Yordania-Irak hari Selasa, 15 Februari. Mereka<br />
sampaikan pula bahwa sesungguhnya tanggal 30 Januari, kedua<br />
wartawan tersebut telah berkunjung<br />
ke Irak untuk meliput pemilihan umum. Keduanya masuk<br />
kembali ke Irak untuk meliput perayaan Asyura di Karbala.<br />
Sesuai arahan Menteri Luar Negeri, saya hubungi Pemimpin Redaksi<br />
Metro TV, Don Bosco Sela-mun, yang juga mengonfirmasikan bahwa<br />
pihaknya telah kehilangan kontak dengan kedua wartawan sejak Selasa<br />
sore, 15 Februari. Kami sepakat menggunakan momentum press briefing<br />
mingguan di Deplu untuk mengumumkan kabar 'kehilangan kontak'<br />
tersebut kepada media massa dan masyarakat. Istilah "kehilangan<br />
kontak" sengaja digunakan karena sampai detik tersebut belum ada<br />
kejelasan mengenai nasib Budiyanto dan Meutya Hafid, sehingga belum<br />
dapat diasumsikan bahwa keduanya telah diculik.<br />
Setelah pers briefing, sekitar pukul 12:00 WIB, didampingi Direktur<br />
Diplomasi Publik, Andri Hadi dan Kabag Infomed Badan Administrasi<br />
Menteri (BAM), Umar Hadi, saya bertemu dengan Pemred Metro TV, Don<br />
Bosco Selamun dan Koordinator Penyiar Metro TV, Usi Karundeng. Dalam<br />
pertemuan itu pihak Metro TV dan Deplu sepakat untuk menjalin<br />
koordinasi dan berbagai informasi, serta perlunya kehati-hati an karena<br />
menyangkut keselamatan dua WNI. Kami juga sepakat mengedepankan<br />
kepentingan keluarga kedua wartawan. Deplu dan Metro TV akan selalu<br />
menginformasikan kepada pihak keluarga perkembangan terakhir dan<br />
upaya-upaya pengembalian kedua wartawan tersebut ke Tanah Air.<br />
Sekitar pukul 17:00 WIB, laporan tertulis Menlu<br />
kepada Presiden mengenai hilangnya 2 Wartawan Metro TV<br />
disampaikan ke Istana Merdeka. Pada saat yang sama Menlu memimpin<br />
rapat koordinasi untuk membentuk Tim Penanggulangan Krisis (TPK)<br />
Deplu. Bapak Triyono Wibowo, Staf Ahli Menlu bidang Manajemen ditunjuk<br />
sebagai Ketua TPK dan saya sebagai Wakil Ketua, serta antara lain<br />
Direktur Timur Tengah, Gatot Abdullah Mansyur; Direktur Informasi dan<br />
Media, Luthfi Rauf; Direktur Konsuler, Harimawan Suyitno; Direktur<br />
Perlindungan WNI Deplu, Ferry Adamhar, dan Kabag Infomed BAM Umar<br />
Hadi sebagai anggota.<br />
Pertemuan pertama TPK membahas langkah-langkah yang perlu<br />
dilakukan, antara lain penyiapan konsep appeal dari keluarga untuk<br />
disiarkan melalui Ai-Jazeera di negara-negara Timur Tengah. Appeal<br />
menekankan aspek kemanusiaan dengan menegaskan bahwa
keberadaan kedua wartawan Metro TV di Irak hanya untuk menjalankan<br />
tugas jurnalistik. Tim TPK juga sepakat memfasilitasi rencana pengiriman<br />
tim khusus Metro TV ke Amman, serta pengguliran upaya intensif dan<br />
serentak dari Deplu dan Perwakilan RI di sekitar wilayah Irak(Amman,<br />
Damaskus, Beirut, Doha, Abu Dhabi, Riyadh dan Jeddah) guna<br />
menggalang kontak, baik secara formal maupun informal dengan pihakpihak<br />
yang dapat membantu, baik dari kalangan pemerintahan, organisasi<br />
Bulan Sabit Merah, Palang Merah (ICRC) dan tokoh serta ulama setempat.<br />
Pukul 19:00 WIB, di Istana Merdeka, Presiden menyampaikan<br />
'imbauan resmi' (appeal) atas hilangnya<br />
kedua wartawan di Irak. Himbauan tersebut disiarkan secara<br />
langsung oleh Metro TV, dan disiarkan juga oleh Al-Jazeera.<br />
Pukul 22:00 WIB, saya mendapat telepon dari Associated Press<br />
Television News (APTN) yang menyampaikan bahwa mereka mendapat<br />
rekaman penahanan kedua wartawan Metro TV oleh Tentara Mujahidin<br />
(Jaisy Al-Mujahidin). Dalam pernyataannya yang akan ditayangkan<br />
APTN,Jaisy Al-Mujahidin meminta konfirmasi dari Pemerintah Indonesia<br />
perihal status keberadaan kedua WNI di Irak dan menyatakan bahwa<br />
mereka tidak akan bertanggung jawab atas keselamatan mereka di Irak.<br />
APTN akan menyiarkan breaking new sini 1 jam mendatang.<br />
Sejumlah hal muncul di benak saya. Pertama, dengan adanya berita<br />
ini, diperoleh kejelasan bahwa Meutya dan Budiyanto telah menjadi<br />
tahanan Tentara Mujahidin. Kedua, Pemerintah Indonesia harus segera<br />
memberikan tanggapan awal terhadap kejadian yang menimpa kedua<br />
wartawan tersebut. Perkembangan ini saya laporkan kepada Menlu, yang<br />
juga memandang penting untuk segera melaporkan masalah ini kepada<br />
Presiden dan segera menyampaikan pandangan Pemerintah RI.<br />
Akhirnya, dini hari pukul 01:00 WIB, Presiden Vudhoyono<br />
menyampaikan imbauan untuk membebaskan kedua wartawan Metro TV,<br />
yang disiarkan secara langsung melalui APTN dan Al-Jazeera. Inti<br />
imbauan Presiden adalah bahwa kedua wartawan Metro TV hanya<br />
menjalankan tugas jurnalistik,tanpa misi politik tertentu.<br />
Pagi harinya, Menteri Luar Negeri memimpin rapat TPK untuk<br />
mengkaji perkembangan terakhir. Deplu pun menginstruksikan kepada<br />
perwakilan-perwa kilan RI diwilayah sekitar Irak untuk mengintensifkan<br />
kontak, baik melalui jalur formal melalui pemerintah setempat, maupun<br />
informal dengan kalangan ulama dan rohaniawan, mengintensifkan<br />
imbauan pembebasan melalui pernyataan Presiden RI yang telah<br />
disiarkan dan disebarluaskan oleh APTN dan Al-Jazee ra. TPK juga<br />
menyiapkan konsep imbauan yang akan dibacakan keluarga Meutya dan<br />
Budiyanto dan akan direlay APTN dan Al-Jazeera. Deplu juga<br />
memfasilitasi kunjungan ketua PMI, Drs. Mar'ie Muhammad ke Abu Dhabi<br />
untuk menjalin kontak dengan Bulan Sabit Merah Uni Emirat Arab.<br />
Sore hari, sesuai instruksi Menlu RI, saya memanggil Kuasa Usaha<br />
Ad Interim Irak di Jakarta, Mrs. Sudad. untuk menjelaskan keberadaan<br />
kedua wartawan Metro TV yang ditahan Jaisy Al-Mujahidin di Irak.<br />
Pada pukul 21:30 WIB, AFP Bagdad menginformasikan bahwa pihak<br />
penyandera telah menyerahkan kedua wartawan Metro TV kepada Mufti<br />
setempat di Ramadi. Kabar yang masih sumir ini saya konfirmasikan ke<br />
ketua TPK yang sudah berada di Amman. Menlu menginstruksikan
ilamana benar terjadi penyerahan kedua sandera agar segera<br />
dikoordinasikan dengan pihak Bulan Sabit Merah di UAE, sehingga<br />
mereka dapat membantu penjemputan dan pemulangan sandera apabila<br />
kedua wartawan dibawa ke kota Bagdad.<br />
Senin, 21 Februari, TPK menggelar rapat, men-jajagi skenario<br />
evakuasi kedua sandera. Skenario pertama, evakuasi dilakukan dengan<br />
bantuan organisasi Bulan Sabit Merah. Dan skenario kedua, apabila<br />
sandera pulang sendiri ke Amman melalui perbatasan, akan dijemput<br />
oleh KBRI Amman dan Ketua TPK di perbatasan Irak-Yordania.<br />
Tengah hari, pukul 12:30 WIB, kembali saya menerima info dari<br />
Associated Press (AP) bahwa kedua wartawan Metro TV telah dibebaskan<br />
oleh pihak Jaisy Al-Mujahidin. Setelah mendengar kabar ini, saya<br />
mendampingi Menlu ke Istana Merdeka guna menyampaikan<br />
perkembangan ini kepada Presiden, meskipun kabar tersebut masih<br />
harus dikonfirmasikan kembali. Menlu juga menyampaikan kabar tersebut<br />
dalam press briefing di Istana Merdeka. Disampaikan pula bahwa pihak<br />
penyandera,Jaisy Al-Muhajidin dalam pernyataannya menyatakan bahwa<br />
'memerhatikan niat baik kedua sandera dan menghormati rasa<br />
persaudaraan Islami antara kedua negara serta menghargai posisi<br />
Indonesia yang menentang invasi Irak', diputuskan untuk membebaskan<br />
para sandera, dan bahwa Bapak Presiden RI menyambut baik kabar ini.<br />
Setelah briefing dari Menlu, saya lanjutkan press briefing untuk<br />
menyampaikan detail perkembangan terakhir, bahwa Tim TPK telah<br />
melewati tahap konfirmasi pembebasan sandera dan lokasi mereka,<br />
hingga saat ini berada dalam tahap evakuasi. Namun Deplu tidak dapat<br />
memberikan informasi mengenai proses evakuasi karena dapat<br />
mengganggu<br />
proses itu sendiri, dan bahwa kebijakan Deplu yang konsisten<br />
terhadap invasi Irak oleh pihak koalisi terbukti telah menjadi faktor<br />
pertimbangan pembebasan sandera.<br />
Pukul 20:50 WIB saya mengontak Ketua TPK di-perbatasan Yordania-<br />
Irak. Bapak Triyono menyampaikan bahwa sampai saat ini belum berhasil<br />
mengontak telepon seluler Meutya Hafid. Satu jam kemudian, Bapak<br />
Triyono menginformasikan bahwa berdasarkan percakapan telepon<br />
antara Kabidpen KBRI Amman dengan Meutya Hafid, kedua sandera akan<br />
tiba diperbatasan dalam setengah jam.<br />
Pada saat yang sama di Tanah Air, Metro TV menayangkan Breaking<br />
News telewicara dengan Meutya Hafid dan Budiyanto, yang saat itu masih<br />
berada diwilayah Irak dan belum melintas ke wilayah Yordania. Menurut<br />
Meutya, ia dan Budiyanto dalam keadaan baik, sehat dan aman, serta<br />
diperlakukan dengan baik selama penyanderaan. Meutya dan Budiyanto<br />
juga berbicara dengan anggota keluarga ma sing-masing.Namun<br />
menjelang akhir telewicara, Meutya mengatakan bahwa ada kemungkinan<br />
rombongan mereka harus kembali ke Bagdad. Tentu kabar itu sangat<br />
mengkhawatirkan.<br />
Pukul 23.00 WIB, Bapak Triyono mengabarkan informasi dari petugas<br />
perbatasan Yordania, bahwa pihak Irak tidak mengizinkan Meutya dan<br />
Budi melintas perbatasan. Saya minta Bapak Triyono untuk terus<br />
mengusahakan agar perbatasan tetap dibuka bagi rombongan sandera.<br />
Saya juga menghubungi Pemimpin Redaksi Metro TV,dan mengingatkan
ahwa<br />
telewicara dengan kedua wartawan sebelum melintasi<br />
perbatasan dapat menghambat proses kepulangan karena tidak<br />
konsisten dengan upaya evakuasi yang bersifat low-key.<br />
Sekitar pukul 23:30 WIB, Bapak Triyono mengabarkan bahwa sangat<br />
sulit untuk mengusahakan dibukanya kembali perbatasan. Pihak Irak dan<br />
Yordan juga gusar karena rencana yang telah dirancang secara seksama<br />
tidak berhasil direalisasikan. Pihak Irak mengatakan bahwa perbatasan<br />
hanya akan dibuka kembali keesokan harinya. Padahal, semua dokumen<br />
resmi perjalanan sudah selesai diurus dan dilegalisasi, dan<br />
sesungguhnya rombongan hanya tinggal melewati perbatasan.<br />
Perkembangan ini saya teruskan kepada Menlu RI, yang<br />
menginstruksikan agar saya menelepon Dubes RI di Amman dan Abu<br />
Dhabi untuk juga menyiapkan pemulangan kedua wartawan Metro TV<br />
dengan menggunakan jasa Bulan Sabit Merah. Saya juga menelepon<br />
kakak kandung Meutya, Finny Hafid, memberikan penjelasan tentang<br />
situasi terakhir, sekaligus memintanya untuk sementara tidak mencoba<br />
menghubungi Meutya.<br />
Sepanjang Senin malam hingga Selasa dini hari, melalui hubungan<br />
telepon dengan sejumlah perwakilan RI dan instansi pemerintah terkait di<br />
wilayah sekitar Irak, Tim TPK melakukan upaya-upaya fasilitasi agar<br />
perbatasan Yordan-Irak dapat dibuka untuk kedua wartawan Metro TV.<br />
Perkembangan ini saya sampaikan kepada Juru Bicara<br />
Kepresidenan, Dino Patti Djalal, termasuk informasi<br />
bahwa sesungguhnya perbatasan Irak-Yor dania telah ditutup<br />
selama 4 hari terakhir karena perayaan Asyura. Namun, sesuai rencana<br />
awal, petugas perbatasan Irak-Yordania telah memberikan pengecualian<br />
bagi kedua wartawan Metro TV dengan membuka perbatasan.<br />
Berdasarkan perkembangan ini, Bapak Triyono dan saya menyimpulkan<br />
bahwa kedua wartawan Metro TV tampaknya baru dapat meninggalkan<br />
Irak Selasa pagi.<br />
Sekitar pukul 01:30 WIB, saya menghubungi Bapak Surya Paloh,<br />
Pemimpin Media Group, yang juga mengetahui adanya kesulitan di<br />
perbatasan. Saya ungkapkan harapan bahwa kesulitan ini hanya<br />
merupakan minorhick-ups yang dapat selesai selambatnya hari Selasa<br />
pagi. Selasa pagi pukul 11:00 WIB, di Deplu, Tim TPK kembali<br />
mengadakan rapat koordinasi, menyusun skenario untuk mengantisipasi<br />
pengembalian sandera. Dalam skenario tersebut, disepakati bahwa<br />
Direktur Timur Tengah Deplu, Gatot Abdullah Mansyur akan berkoordinasi<br />
dengan Dubes RI di Amman untuk persiapan keberangkatan kedua<br />
wartawan Metro TV beserta rombongan dari Amman ke Jakarta.<br />
Sementara persiapan di Bandara Soekarno Hatta dan penjemputan kedua<br />
wartawan akan dilakukan oleh Direktur Konsuler, Harimawan Suyitno, dan<br />
Lu-tfi Rauf, Direktur Infomed Deplu. Sementara prosesi penyerahan kedua<br />
wartawan Metro TV tersebut disiapkan oleh Direktur Protokol, Dienne<br />
Muharyo.<br />
Pukul 12:00 WIB saya menerima telepon dari KBRI Doha yang<br />
mengabarkan kedatangan Ketua<br />
PMI, Drs.Mar'ie Muhammad, dan pihak KBRI telah mengatur
pertemuan Ketua PMI dengan Bulan Sabit Merah di Qatar. Hal ini<br />
selanjutnya saya komunikasikan kepada Mrs. Sudad, KUAI Irak di Jakarta.<br />
Menanggapi hal ini Mrs. Sudad di Jakarta menjanjikan secara lisan bahwa<br />
pihaknya akan menghubungi Ke-menterian Dalam Negeri Irak di Bagdad<br />
untuk memfasilitasi pemulangan kedua wartawan.<br />
Kemudian saya kembali menghubungi Bapak Triyono untuk<br />
menanyakan perkembangan terakhir di-perbatasan Vordania-Irak.Bapak<br />
Triyono mengabarkan bahwa kedua warga Indonesia saat ini tidak<br />
diinterogasi oleh petugas perbatasan Irak, dan perbatasan akan dibuka<br />
pukul 13:00 WIB. Menurut ketua TPK, kedua wartawan telah memesan<br />
ruangan istirahat, namun karena kondisi ruangan di perbatasan tidak<br />
memungkinkan, maka mereka menginap di dalam kendaraan sewaan.<br />
Begitu pun, petugas perbatasan telah menyediakan makanan bagi kedua<br />
wartawan.<br />
Saya kembali menghubungi Mrs. Sudad, menyampaikan keprihatinan<br />
terhadap hambatan yang dialami diperbatasan. Dalam kapasitas pribadi,<br />
dengan tegas saya sampaikan bahwa akan sangat inhumane apabila<br />
kedua wartawan tersebut tinggal satu malam lagi di perbatasan Irak.<br />
Menanggapi hal ini, Mrs. Sudad mengaku telah mendapatkan konfirmasi<br />
dari Departemen Dalam Negeri Irak di Bagdad yang telah memerintahkan<br />
petugas perbatasan agar membuka akses bagi kepulangan kedua<br />
wartawan. Mrs. Sudad juga mengabarkan bahwa perbatasan<br />
Irak masih akan ditutup hingga 23 atau 24 Februari.<br />
Sekitar pukul 17:00 WIB, Bapak Triyono mengabarkan bahwa saat ini<br />
Meutya dan Budiyanto masih harus menjalani pertanyaan dari petugas<br />
perbatasan Irak karena keduanya telah mengalami penyanderaan. Pukul<br />
17:20 WIB saya berhasil mengontak handphone Meutya.<br />
Saya sampaikan kepada Meutya bahwa sejak tanggal 18 Februari,<br />
Deplu telah berupaya semaksimal mungkin untuk membebaskan kedua<br />
wartawan Metro TV. Meutya mengatakan bahwa dirinya bersama Budiyanto<br />
sangat prihatin karena tidak ada kontak dengan pihak perwakilan<br />
Indonesia di Yordania. Ia juga mengatakan bahwa petugas perbatasan<br />
Irak telah mendapat instruksi dari Bagdad untuk membuka perbatasan.<br />
Saya sampaikan agar Meutya menerima telepon dari KUAI Irak di Jakarta<br />
yang akan berbicara langsung dengan petugas perbatasan di Irak melalui<br />
saluran telepon milik Meutya. Selanjutnya saya minta kepada Meutya agar<br />
terus memberikan kabar ke Deplu setiap setengah jam.<br />
Selanjutnya kembali saya menelepon Mrs. Sudad, KUAI Irak di<br />
Jakarta. Saya sampaikan kepada Mrs. Sudad bahwa kedua wartawan<br />
Metro TV sangat depressed dan prihatin terhadap penanganan petugas<br />
perbatasan di Irak dan saya meminta kesediaannya untuk menghubungi<br />
Meutya di handpho ne-nya untuk kemudian berbicara dengan petugas<br />
perbatasan Irak.<br />
Pukul 18:20 WIB, saya mengontak Bapak Triyono untuk<br />
memberitahukan bahwa saat ini Meutya<br />
sedang berbicara dengan KUAI Irak di Jakarta. Saya tanyakan pula<br />
persiapan dan kesiapan contingency KBRI Amman apabila sandera telah<br />
menyeberangi perbatasan. Seluruh perkembangan ini secara terus<br />
menerus saya laporkan kepada Menlu RI yang memberikan pengarahan<br />
penanganan permasalahan as they unfold.
Akhirnya, berita yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sekitar pukul 19:00<br />
WIB, saya mendapatkan kabar dari Meutya bahwa dirinya dan Budiyanto<br />
dalam perjalanan menuju Yordania. Pukul 19.35 WIB, Meutya dan<br />
Budiyanto diantar oleh petugas Yordania tiba di wilayah Yordania,<br />
disambut Ketua TPK dan langsung menuju kantor Border Department.<br />
Bapak Triyono menelepon Menlu melaporkan bahwa kedua wartawan<br />
yang disandera telah berada bersama beliau dan selanjutnya Menlu<br />
berbicara langsung dengan Meutya dan Budi.<br />
Kamis, pukul 10:00 WIB, staf Deplu menjemput Keluarga Meutya<br />
Hafid dan Budiyanto dari rumah mereka ke Deplu dan Istana. Kedua<br />
wartawan Metro TV tiba di Bandara pukul 14:05 WIB. Pukul 15:15, kedua<br />
wartawan Metro TV beserta Triyono Wibowo, Surya Paloh dan saya tiba di<br />
Istana Merdeka melalui Pintu Utara, dan disambut oleh anggota keluarga.<br />
Kedatangan rombongan disiarkan secara langsung oleh Metro TV dan<br />
diliput berbagai media massa nasional maupun koresponden asing di<br />
Jakarta. Saya, dan tentu semua pihak yang terlibat dalam pembebasan<br />
Meutya dan Budiyanto, merasa lega dengan pulangnya mereka ke Tanah<br />
Air, dengan selamat.<br />
Satu hal yang selalu saya nomor satukan dalam menangani masalah<br />
ini adalah kontak dengan keluarga, dan mereka harus yang pertama<br />
mendapatkan informasi sebelum pihak lain, terlebih media massa.<br />
Sebagai seorang bapak, saya sangat memahami bahwa pihak keluarga<br />
pasti ingin tahu semua informasi, sekecil apapun informasi tersebut.<br />
Karena itulah selalu saya sampaikan kepada Finny, kakak Meutya, semua<br />
perkembangan informasi upaya pembebasan, sekecil apa pun.<br />
Terasa pilu mendengar respons dari keluarga Meutya yang berusaha<br />
tenang, walau kekhawatiran mendalam tetap terbaca dari nada suara<br />
Finny. Sebagai perwakilan dari pemerintah saya mempersiapkan diri<br />
untuk menerima tuntutan ataupun tekanan dari keluarga. Akan lebih<br />
mudah diterima jika reaksi keluarga lebih emosional. Tapi respons yang<br />
begitu sabar dan pengertian terhadap kebijakan Deplu, justru menjadi<br />
'beban' bagi saya. Ini berarti keluarga memercayakan penuh nasib anak<br />
kesayangannya di tangan Deplu. Setiap menutup telepon saya berulang<br />
kali berjanji dalam hati, saya akan lakukan apa pun semampu saya untuk<br />
membawa Meutya dan Budi kembali ke pangkuan keluarga. Bagi saya,<br />
Failure is not an option.<br />
Perasaan yang sama dirasakan semua anggota Tim<br />
Penanggulangan Krisis. Ruang TPK tidak pernah ditinggal selama 24<br />
jam. Lelah fisik dan mental tentu terasa.Namun kekhawatiran akan<br />
mengecewakan pihak keluarga begitu tinggi. Sehingga untuk beristirahat<br />
menikmati secangkir teh saja terasa sebagai<br />
kesalahan. Dalam keadaan genting seperti itu satu menit bahkan<br />
satu detik pun berharga. Tapi itulah pilihan Tim: to work with no pause,<br />
sampai Meutya dan Budi kembali dengan selamat.<br />
Menlu juga siaga 24 jam. Ia minta saya secara khusus untuk terus<br />
meng-update informasi sekecil apapun, jam berapa pun. Saya pernah<br />
menelepon Menlu jam 2 pagi, dan beliau tetap fokus mengikuti laporan.<br />
Saya memandang Menlu Hasan Wirayuda sebagai sosok yang dear<br />
headed. Saya sependapat dengan Menlu, terbawa perasaan akan<br />
semakin menyulitkan upaya kami. Saya yakin sebagai seorang bapak dan
seorang Menlu, ia pun mengalami kegundahan yang sama. Tapi beliau<br />
memilih mengutamakan pikiran jernih dan logis.Karenanya beliau<br />
menjadi orang pertama yang saya cari untuk mohon pertimbangan dan<br />
masukan setiap kali ada perkembangan.<br />
Di tengah upaya kerjasama yang kami sepakati bersama Metro TV,<br />
memang sempat ada hambatan kecil. Wajar, pendekatan Deplu dan Metro<br />
TV sebagai institusi media, tentunya tidak selalu sama, walaupun tujuan<br />
utamanya sama. Situasi sempat memburuk ketika Meutya dan Budi<br />
tertahan di perbatasan, tidak diizinkan keluar dari Irak. Saya dan Meutya<br />
beberapa kali berhubungan melalui ponsel, dan terdengar kepanikan dari<br />
suaranya. Tim Metro TV yang menunggu di perbatasan bersama dengan<br />
Ketua tim penanggulangan krisis, juga tidak sabar. Saya mengontak<br />
Pemred Metro TV Don Bosco untuk meminta mereka tenang. Pintu<br />
terakhir menuju<br />
pembebasan memang biasanya lebih sulit. Silang pendapat hanya<br />
akan membuat situasi semakin berbahaya bagi Meutya dan Budi.<br />
Ketegangan pun mereda setelah kami kembali saling mengingatkan<br />
bahwa tujuan yang hendak kita capai sama.<br />
Saya selalu menekankan bahwa upaya pembebasan membutuhkan<br />
kerja sama semua pihak, bukan hanya Deplu. Namun semua pihak perlu<br />
berjalan di atas track yang sama,demi keselamatan WNI. Hal lain, jangan<br />
pernah menyerah jika satu upaya mengalami kebuntuan. Harus selalu<br />
ada inisiatif dan alternatif upaya lain, sehingga counterpart kita tidak<br />
pernah mengatakan "tidak". Faiiure is not an option. Kita juga harus<br />
menjalani berbagai upaya ini dengan cool headed dan berpikiran jernih.<br />
Menjalani upaya ini seperti berjalan di atas roller coaster, karena itu jika<br />
dihadapi dengan gegabah, akan fatal akibatnya.<br />
Bagaimanapun, kembalinya Meutya dan Budi ke Tanah Air dengan<br />
selamat, adalah salah satu saat yang paling melegakan sepanjang hidup<br />
saya. Terlihat kelegaan di muka Bapak Menlu ketika saya sampaikan<br />
kabar kepulangan mereka. Dan reward terbesar untuk kita semua adalah<br />
ketika menyampaikan kabar inikepada keluarga Meutya dan Budi. Haru<br />
dan puas telah memenuhi janji terhadap keluarga, menyelimuti perasaan<br />
saya. Makan, minum, dan istirahat saya terasa menjadinikmat dan<br />
nyaman sekali. Teringat kembali ketika kabar mengejutkan itu datang satu<br />
pekan sebelumnya.Inilah salah satu journey yang memberi warna<br />
terhadap perjalanan tugas saya sebagai Juru Bicara Deplu.[]<br />
TENTANG PENULIS<br />
Meutya Viada Hafid lahir di Bandung, 3 Mei 1978.Anak keempat<br />
(bungsu) dari pasangan DR Anwar Hafid, Ph.D. dan Metty Hafid. Meutya<br />
menghabiskan masa kecilnya di Bogor dan Makassar, sementara masa<br />
sekolahnya di Jakarta dan Singapura. Setelah menyelesaikan SI di<br />
Manufacturing Engineering University of New South Wales, Australia, gadis<br />
mungil yang memiliki motto hidup kerja keras ini pun bergabung bersama<br />
Metro TV pada Februari 2001 sampai sekarang,sebagai reporter<br />
sekaligus presenter. Peliputan yang dipercayakan kepada Meutya tidak<br />
jarang mengharuskannya berkunjung ke daerah konflik,di antaranya ke<br />
Aceh dalam keadaan Darurat Militer (Mei 2003), ke Bali pasca bom kedua<br />
(2005) , ke Irakuntuk meliput Pemilu pertama (Januari-Februari 2005),dan<br />
ke Thailand ketika terjadi Kudeta Militer (2006),atau ke daerah bencana
(disaster zone), yaitu ke Aceh pasca tsunami (Desember<br />
2DD4 - Januari 2DD5). Pengalaman peliputan mancanegara<br />
lainnya adalah in depth report tentang kondisi TKI Malaysia (November<br />
2004), tentang pertemuan tokoh islam dunia di Rusia (2005), dan barubaru<br />
ini mengenai komunitas pergerakan Muslim di Thailand Selatan<br />
(2007).[]<br />
Meutya Viada Hafid lahir di Bandung, 3 Mei 1978. Anak keempat<br />
(bungsu) dari pasangan Anwar Hafid, Ph.D. dan Metty Hafid<br />
menghabiskan masa kecilnya di Bogor dan Makassar, sementara masa<br />
sekolahnya di Jakarta dan Singapura.<br />
Setelah menyelesaikan studi S1 di jurusan Manufacturing<br />
Engineering, University of New South Wales, Australia, gadis mungil yang<br />
memiliki motto hidup kerja keras ini pun bergabung bersama Metro TV<br />
pada Februari 2001 sebagai jurnalis.