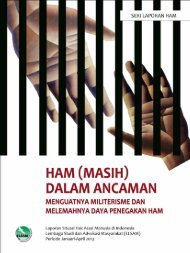Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
martabat manusia yang telah dinistakan oleh para<br />
penjahat kemanusiaan dunia itu sendiri. Mengapa<br />
‘mengembalikan’? Karena nilai-nilai asasi<br />
kemanusiaan, masih menurut Fuad, rusak akibat<br />
dipaksakannya ideologi kesatuan – ideologi yang<br />
menyeragamkan pluralitas bangsa dalam sebuah<br />
doktrin politik. Oleh karenanya tidak ada alasan<br />
bagi siapapun untuk menolaknya [hal. 105].<br />
Andi Widjajanto, ahli militer, menempatkan MPI<br />
dalam perspektif pengembangan sistem pertahanan<br />
keamanan nasional – yang menurut penulis<br />
harus didasarkan pada doktrin ius bellum. Persis<br />
karena itu maka MPI yang antara lain mengadili<br />
kejahatan perang merupakan konsekuensi logis<br />
dari penerapan doktrin tersebut. Karena peradilan<br />
ini akan memungkinkan adanya akuntabilitas dari<br />
sebuah tindakan militer.<br />
Dari banyak pengalaman, asal usul kekerasan<br />
bersumber pada doktrin ‘keamanan nasional’.<br />
Doktrin ini menempatkan supremasi militer atas<br />
sipil, mengembangkan aparat represif bagi<br />
penerapan ‘perang permanen’, dan menganggap<br />
kekuatan bersenjata sebagai satu-satunya institusi<br />
yang mampu menjaga kekuatan ideologis – sembari<br />
merusak sistem-sistem peradilan, politik, budaya<br />
maupun ekonomi. [Nunca Mas, hal. 442]. Bahaya<br />
penerapan doktrin ini harus dicegah dari awal.<br />
Doktrin yang harus menjadi dasar<br />
pengembangan strategi pertahanan keamanan<br />
Indonesia adalah ius ad bellum. Berbeda<br />
dengan doktrin ‘keamanan nasional’ doktrin<br />
ini mengharuskan negara menerapkan prinsip<br />
diskriminasi dan proporsional dalam strategi dan<br />
operasi militer. Diskriminasi karena sasaran,<br />
metode dan strategi bertempur hanya boleh<br />
terarah pada kelompok tempur dan bukan pada<br />
non tempur (prajurit terluka, pengungsi, unit medis,<br />
masyarakat sipil terutama perempuan dan anak)<br />
dan juga bukan pada zona imunitas (seperti fasilitas<br />
sipil, zona netral, zona demiliterisasi). Sedangkan<br />
prinsip proporsional mengharuskan semua biaya<br />
dan kerusakan yang timbul diperhitungkan dengan<br />
seksama, sedemikian sehingga ‘kebaikan’ yang<br />
muncul dari perang lebih besar daripada kerusakan<br />
dan biaya yang dikeluarkan. [hl. 128] Disamping itu<br />
doktrin ini memperlakukan tindakan militer sebagai<br />
pilihan terakhir. Semua upaya non perang harus<br />
dilakukan lebih dahulu dengan maksimal sebelum<br />
memutuskan untuk perang; juga jika harus<br />
berhadapan dengan kelompok separatis. Tindakan<br />
militer hanya bisa didasarkan pada maksud untuk<br />
mempertahankan diri dan menciptakan kembali<br />
perdamaian yang dilakukan pemerintah yang sah.<br />
Doktrin ius ad bellum ini sangat penting diterapkan<br />
persis karena besarnya potensi instrumen perang<br />
digunakan secara tidak bertanggung jawab atau<br />
imoral. Ketika itu terjadi jatuhnya korban sipil akan<br />
sangat besar, ruang untuk resolusi konfl ik alternatif<br />
semakin sempit. Sebaliknya dengan mendasarkan<br />
pada doktrin ini tindakan militer akan lebih terkendali<br />
dan dapat dipertanggungjawabkan [hal. 137-145].<br />
Pilihan ini membawa konsekuensi pembentukan<br />
peradilan kejahatan perang dengan kapasitas yang<br />
memadai.<br />
Ketika terdapat dua sistem yang bekerja untuk<br />
persoalan yang sama timbul kekhawatiran bahwa<br />
keduanya akan saling bertabrakan. Fadillah<br />
Agus mencoba meyakinkan bahwa antara MPI<br />
dengan Pengadilan Militer di Indonesia tidak terjadi<br />
yurisdiksi yang saling tumpang tindih dengan cara<br />
membandingkan keduanya. Perbandingan itu<br />
mencakup aspek legitimasi, struktur pengadilan,<br />
kompetensi auditor dan sebagainya. Penulis<br />
yang merupakan seorang ahli hukum militer juga<br />
mengulas persoalan yang paling sering diresahkan<br />
militer dalam misi perdamaian. Diingatkan bahwa<br />
MPI bersifat pelengkap dari pengadilan nasional.<br />
Abdulkadi Jailani, seorang diplomat senior,<br />
berupaya menjernihkan kekuatiran yang ada dengan<br />
mengupas kesalahpahaman-kesalahpahaman di<br />
benak mereka yang menolak ratifikasi. Sebagai<br />
contoh kesalahpahaman bahwa MPI mencakup pula<br />
wewenang mengadili pelanggaran HAM masa lalu,<br />
bahwa kewenangan MPI lebih ditentukan melalui<br />
proses politik daripada hukum, dan berkenaan<br />
dengan perlunya kesiapan hukum nasional. Ia<br />
menunjukan bahwa ratifikasi justru bermanfaat<br />
bagi kepentingan nasional baik dalam rangka<br />
mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia,<br />
mencegah terjadinya impunitas, dan meningkatkan<br />
citra Indonesia dalam perlindungan HAM.<br />
Keadilan Global<br />
Jika bicara mengenai keadilan global pada<br />
umumnya merujuk pada gerakan akan perlunya<br />
pluralisme dalam tatanan global yang sedang<br />
berlangsung. Lebih spesifi k lagi suatu gerakan<br />
untuk menciptakan alternatif dari perdagangan<br />
bebas dan pasar bebas. Perjuangan keadilan yang<br />
digerakkan oleh perlawanan terhadap penunggalan<br />
pola hubungan baik dalam hidup ekonomi, sosial,<br />
politik maupun budaya. Dalam hal ini sistem pasar<br />
yang hendak ‘dipaksakan’ untuk diterapkan bukan<br />
hanya di bidang ekonomi tapi juga di luar itu.<br />
Dalam buku ini bukan hal itu yang pembaca<br />
temukan. Menyimak tulisan-tulisan di buku ini,<br />
pembaca dibatasi pengertian ‘keadilan’ sebagai<br />
‘pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang<br />
dilakukan’. Segera terasa bahwa hal itu bukan hal<br />
baru. Namun, ‘hal yang tidak baru’ ini memang harus<br />
dikedepankan kembali persis karena hal tersebut<br />
tidak terjadi dalam kesetaraan. Prinsip ‘semua<br />
manusia sama di hadapan hukum’ disandera oleh<br />
sistem politik.<br />
Gejala seperti ini adalah gejala impunitas.<br />
Sub-Komisi HAM PBB mendefi nisikan impunitas<br />
sebagai: “the impossibility, de jure or de facto, of<br />
bringing the perpetrators of human rights violations to<br />
account - whether in criminal, civil, administrative or<br />
disciplinary proceedings - since they are not subject<br />
to any inquiry that might lead to their being accused,<br />
arrested, tried and, if found guilty, convicted, and to<br />
22 ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER MEI-JUNI 2012 2012